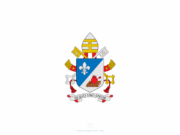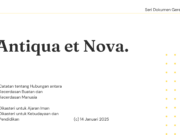| Judul | DIGNITAS INFINITA |
| Deskripsi | Deklarasi tentang Martabat Manusia |
| Tanggal Terbit | 8 April 2024 |
| Penerjemah | Th. Eddy Susanto, SCJ |
| Harga | Rp 30.000,- |
| Tebal Buku | 71 halaman |
| Ukuran Buku | 15 x 22 cm |
Daftar Isi
Pengantar …
Pendahuluan …
Martabat Manusia Tak Terbatas …
Klarifikasi Mendasar …
1. Tumbuhnya Kesadaran Akan Pentingnya Martabat Manusia …
Perspektif Alkitabiah …
Perkembangan Pemikiran Kristen …
Zaman Sekarang …
2. Gereja Mewartakan, Mempromosikan, dan Menjamin Martabat Manusia …
Gambar Allah yang Tak Terhapuskan …
Kristus Mengangkat Martabat Manusia …
Panggilan Menuju Kepenuhan Martabat …
Komitmen terhadap Kebebasannya Sendiri …
3. Martabat, Dasar dari Hak dan Kewajiban Manusia …
Penghormatan Tanpa Syarat pada Martabat Manusia
Dasar Objektif bagi Kebebasan Manusia …
Struktur Relasional Pribadi Manusia …
Membebaskan Pribadi Manusia dari Pengaruh Negatif dalam Bidang Moral dan Sosial …
4. Beberapa Pelanggaran Berat terhadap Martabat Manusia …
Drama Kemiskinan …
Perang …
Penderitaan Para Migran …
Perdagangan Manusia …
Pelecehan Seksual …
Kekerasan Terhadap Perempuan …
Aborsi …
Ibu Pengganti …
Eutanasia dan Bunuh Diri dengan Bantuan …
Marginalisasi Penyandang Disabilitas …
Teori Gender …
Perubahan Jenis Kelamin …
Kekerasan Digital …
Dikasteri Untuk Ajaran Iman
“DIGNITAS INFINITA”
Deklarasi
Tentang Martabat Manusia
8 April 2024
Pada Kongres tanggal 15 Maret 2019, Kongregasi Ajaran Iman memutuskan untuk memulai “penyusunan sebuah teks yang menyoroti pentingnya konsep martabat pribadi manusia dalam antropologi Kristen dan mengilustrasikan ruang lingkup dan implikasi bermanfaat di bidang sosial, politik, dan ekonomi—sambil juga mempertimbangkan perkembangan terkini dalam bidang akademis dan cara-cara ambivalen (bercabang dan saling bertentangan) dalam memahami konsep tersebut saat ini.” Draf awal teks tersebut disiapkan dengan bantuan beberapa ahli pada tahun 2019 tetapi Konsultasi Terbatas dari Kongregasi, yang diadakan pada tanggal 8 Oktober tahun yang sama, menganggapnya tidak memuaskan.
Kantor Ajaran kemudian menyiapkan draf yang baru lainnya, berdasarkan kontribusi berbagai ahli, yang dipresentasikan dan dibahas dalam Konsultasi Terbatas yang diadakan pada tanggal 4 Oktober 2021. Pada bulan Januari 2022, draf baru tersebut dipresentasikan pada Sidang Pleno Kongregasi, di mana para Anggota mengambil langkah-langkah untuk mempersingkat dan menyederhanakan teks.
Setelah itu, pada tanggal 6 Februari 2023, versi perubahan dari draf baru tersebut ditinjau oleh Konsultasi Terbatas, yang mengusulkan beberapa perubahan tambahan. Versi yang telah diperbarui kemudian diserahkan untuk dipertimbangkan oleh Anggota pada Sidang Biasa Dikasteri (Feria IV) pada tanggal 3 Mei 2023, di mana Anggota menyetujui bahwa dokumen tersebut, dengan beberapa penyesuaian, dapat dipublikasikan. Selanjutnya, Paus Fransiskus menyetujui pembahasan sesi tersebut pada Audiensi yang diberikan kepada saya (prefek dikasteri) pada tanggal 13 November 2023. Pada kesempatan tersebut, beliau juga meminta agar dokumen tersebut menyoroti topik-topik yang berkaitan erat dengan tema martabat manusia, seperti kemiskinan, situasi migran, kekerasan terhadap perempuan, perdagangan manusia, perang, dan tema lainnya. Untuk menghormati arahan Bapa Suci, Bagian Ajaran Dikasteri mendedikasikan Kongres untuk melakukan studi mendalam terhadap Ensiklik Fratelli Tutti, yang menawarkan analisis orisinal dan pertimbangan lebih lanjut mengenai tema martabat manusia “melampaui segala keadaan.”
Versi baru dan perubahan signifikan dari teks ini dikirimkan kepada Anggota Dikasteri pada tanggal 2 Februari 2024, menjelang Sidang Biasa (Feria IV) pada tanggal 28 Februari 2024. Surat yang menyertai draf tersebut memuat klarifikasi sebagai berikut: “Draft tambahan ini diperlukan untuk memenuhi permintaan yang khusus dari Bapa Suci: yaitu, beliau secara eksplisit mendesak agar perhatian pada pelanggaran berat terhadap martabat manusia di zaman kita mendapatkan perhatian yang lebih banyak, khususnya sehubungan dengan Ensiklik Fratelli Tutti. Dengan ini, Kantor Ajaran mengambil langkah-langkah untuk mengurangi bagian awal […] dan mengembangkan secara lebih rinci apa yang ditunjukkan oleh Bapa Suci.” Teks Deklarasi saat ini akhirnya disetujui pada Feria IV tanggal 28 Februari 2024 yang disebutkan di atas. Kemudian, dalam Audiensi yang diberikan kepada saya dan kepada Monsinyur Armando Matteo, Sekretaris Bagian Ajaran, pada tanggal 25 Maret 2024, Bapa Suci menyetujui Deklarasi ini dan memerintahkan penerbitannya.
Elaborasi teks yang berlangsung selama lima tahun ini, membantu kita memahami bahwa kita dihadapkan pada sebuah dokumen yang, karena keseriusan dan sentralitas persoalan martabat dalam cara pandang Kristiani, memerlukan proses pematangan yang cukup lama untuk sampai pada versi final yang telah kami publikasikan hari ini.
Dalam tiga bagian awalnya, Deklarasi ini mengingatkan kembali prinsip-prinsip dasar dan premis teoritis, dengan tujuan memberikan klarifikasi penting yang dapat membantu menghindari kebingungan yang sering terjadi seputar penggunaan istilah “martabat manusia.” Bagian keempat menyajikan beberapa situasi terkini dan persoalan-persoalan di mana martabat setiap manusia yang sangat besar dan tidak dapat dicabut kurang diakui secara memadai. Kecaman terhadap pelanggaran-pelanggaran berat dan aktual terhadap martabat manusia merupakan tindakan yang perlu dilakukan, karena Gereja memupuk keyakinan mendalam bahwa iman tidak dapat dipisahkan dari pembelaan martabat manusia, evangelisasi untuk mempromosikan kehidupan yang bermartabat, dan spiritualitas dari komitmen terhadap martabat setiap umat manusia.
Martabat setiap manusia ini dapat dipahami sebagai sesuatu yang “tidak terbatas” (dignitas infinita), sebagaimana ditegaskan Paus Santo Yohanes Paulus II dalam pertemuan bagi orang-orang yang hidup dengan berbagai keterbatasan atau disabilitas.[1] Beliau mengatakan hal ini untuk menunjukkan bagaimana martabat manusia melampaui semua penampilan luar dan aspek-aspek tertentu dari kehidupan masyarakat.
Dalam Fratelli Tutti, Paus Fransiskus ingin menggarisbawahi bahwa martabat ini ada “melampaui segala keadaan.” Dengan demikian, Bapa Paus mengajak semua orang untuk membela martabat manusia dalam setiap konteks budaya dan setiap momen keberadaan manusia, terlepas dari kekurangan fisik, psikologis, sosial, atau bahkan moral. Deklarasi ini berupaya untuk menunjukkan bahwa ini adalah kebenaran universal yang memanggil kita semua untuk mengakuinya sebagai kondisi mendasar bagi masyarakat kita untuk menjadi masyarakat yang benar-benar adil, damai, sehat, dan manusiawi.
Meskipun tidak komprehensif, topik-topik yang dibahas dalam Deklarasi ini dipilih untuk menjelaskan berbagai aspek martabat manusia yang mungkin tersembunyi dalam kesadaran banyak orang. Beberapa topik mungkin lebih disukai oleh beberapa kelompok masyarakat dibandingkan yang lain. Namun demikian, semua hal tersebut menurut kami penting karena, jika digabungkan, hal-hal tersebut membantu kita mengenali keselarasan dan kekayaan pemikiran tentang martabat manusia yang mengalir dari Injil.
Deklarasi ini tidak bertujuan untuk membahas topik yang begitu kaya dan krusial. Sebaliknya, tujuannya adalah untuk menawarkan beberapa poin refleksi yang dapat membantu kita mempertahankan kesadaran akan martabat manusia di tengah momen sejarah yang kompleks yang kita jalani. Hal ini agar kita tidak tersesat, sebaliknya agar kita membuka diri terhadap lebih banyak luka dan penderitaan yang mendalam di tengah banyaknya kekhawatiran dan kegelisahan di zaman kita.
Kardinal Víctor Manuel Fernández
Prefek
1. Dignitas Infinita (Martabat yang Tak Terbatas), yang secara inheren tertanam dalam diri seseorang, dimiliki setiap pribadi manusia, melampaui segala keadaan dan status atau situasi apa pun yang dialami seseorang. Prinsip ini, yang sepenuhnya dapat dikenali bahkan hanya dengan akal budi, menjadi landasan keutamaan pribadi manusia dan perlindungan hak asasinya. Gereja, dalam terang Wahyu, secara mutlak menegaskan kembali dan meneguhkan martabat ontologis pribadi manusia, yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah dan ditebus dalam Kristus Yesus. Dari kebenaran ini, Gereja memaparkan alasan-alasan atas komitmennya terhadap kaum lemah dan mereka yang kurang mempunyai kekuasaan, dengan selalu menekankan «keutamaan pribadi manusia dan pembelaan martabatnya melampaui semua keadaan».”[2]
2. Martabat ontologis serta nilai unik dan unggul setiap pria dan wanita di dunia ini ditegaskan kembali secara otoritatif dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang dikeluarkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948.[3] Saat kita memperingati 75 tahun dokumen tersebut, Gereja melihat peluang untuk menyatakan kembali keyakinannya bahwa semua umat manusia— yang diciptakan oleh Allah dan ditebus oleh Kristus— harus diakui dan diperlakukan dengan hormat dan cinta karena martabat mereka yang tidak dapat dicabut. Peringatan ini juga memberikan kesempatan bagi Gereja untuk mengklarifikasi beberapa kesalahpahaman yang sering terjadi mengenai martabat manusia dan untuk mengatasi beberapa masalah yang serius dan mendesak berkaitan dengannya.
3. Sejak awal misinya dan didorong oleh Injil, Gereja telah berupaya untuk menegaskan kebebasan manusia dan memajukan hak-hak semua orang.[4] Belakangan ini, berkat suara para Paus, Gereja dengan sengaja telah melakukan upaya untuk merumuskan komitmen ini secara lebih eksplisit melalui seruan baru untuk mengakui martabat fundamental yang melekat pada setiap orang. Dalam hal ini, Paus Santo Paulus VI menegaskan bahwa “tidak ada antropologi yang menandingi antropologi Gereja mengenai pribadi manusia—khususnya mengenai orisinalitas, martabat, sifat tidak berwujud dan kekayaan hak-hak dasar, kesakralan, kapasitas pendidikan, aspirasi seseorang untuk mencapai perkembangan yang utuh, dan keabadian.”[5]
4. Paus Santo Yohanes Paulus II, pada Konferensi Umum Ketiga Para Uskup Amerika Latin dan Karibia di Puebla pada tahun 1979, menegaskan bahwa martabat manusia adalah “nilai Injil yang tidak dapat diremehkan tanpa sangat menghina Sang Pencipta. Martabat ini dilanggar pada tingkat individu ketika nilai-nilai seperti kebebasan, hak untuk menganut agama, integritas fisik dan mental, hak atas barang-barang penting, dan hak untuk hidup tidak dihargai. Hal ini dilanggar pada tingkat sosial dan politik ketika seseorang tidak dapat menggunakan haknya untuk berpartisipasi, atau ketika ia menjadi sasaran pemaksaan yang tidak adil dan melanggar hukum, atau disiksa secara fisik atau mental, dan lain-lain. […] Jika Gereja hadir untuk membela atau memajukan martabat manusia, maka Gereja melakukan hal tersebut sesuai dengan misinya, yang meskipun bersifat keagamaan dan bukan sosial atau politik, mau tidak mau harus mempertimbangkan manusia dalam keberadaan integralnya”[6]
5. Pada tahun 2010, di Akademi Kepausan untuk Kehidupan, Paus Benediktus XVI menyatakan bahwa martabat pribadi manusia adalah “sebuah prinsip fundamental yang oleh iman kepada Yesus Kristus yang bangkit selalu dibela, terutama ketika hal ini diabaikan terhadap orang-orang yang paling sederhana dan paling tidak berdaya”[7] Pada kesempatan lain, ketika berbicara kepada para ekonom, Paus Benediktus XVI mengatakan bahwa «ekonomi dan keuangan tidak ada demi kepentingannya sendiri, mereka tidak lebih dari sebuah instrumen, sebuah sarana. Tujuan ekonomi dan keuangan semata-mata untuk pribadi manusia dan realisasi penuh martabat manusia. Inilah satu-satunya modal yang harus dilindungi.”[8]
6. Sejak awal masa kepausannya, Paus Fransiskus telah mengajak Gereja untuk “percaya kepada Bapa yang mengasihi semua pria dan wanita dengan kasih yang tak terbatas, menyadari bahwa ‘dengan demikian Ia menganugerahkan kepada mereka martabat yang tak terbatas.”[9] Dengan tegas Paus menekankan bahwa martabat yang begitu besar merupakan suatu anugerah asali yang dengan setia harus diakui dan disambut penuh rasa syukur. Hidup berdampingan yang baru di antara manusia dapat dibangun berdasarkan pengakuan dan penerimaan martabat manusia ini, yang mengembangkan hubungan sosial dalam konteks persaudaraan sejati. Memang benar, hanya dengan “mengakui martabat setiap pribadi manusia” kita dapat “berkontribusi pada lahirnya kembali cita-cita universal menuju persaudaraan.”[10] Paus Fransiskus menegaskan bahwa “sumber martabat dan persaudaraan manusia ada di dalam Injil Yesus Kristus,”[11] namun, bahkan melalui refleksi dan dialog, akal manusia pun dapat sampai pada keyakinan ini, karena “martabat orang-orang lain harus dihormati dalam setiap situasi, itu bukan karena kita menemukan atau mengandaikan martabat itu, tetapi karena di dalam diri manusia memang ada nilai yang melebihi benda-benda materiil dan keadaan-keadaan yang tak tentu; dan itu menuntut agar mereka diperlakukan secara berbeda. Bahwa setiap manusia memiliki martabat yang tak dapat diganggu gugat adalah kebenaran yang sesuai dengan kodrat manusia melampaui perubahan budaya apa pun.”[12] Paus Fransiskus menyimpulkan, “manusia memiliki martabat sama yang tidak dapat diganggu gugat dalam masa sejarah mana pun; dan tidak seorang pun dapat merasa diberi wewenang oleh situasi tertentu untuk menyangkal keyakinan ini atau tidak bertindak sesuai dengannya.”[13] Dari sudut pandang ini, ensiklik Paus Fransiskus, Fratelli Tutti, merupakan semacam “Magna Carta” dari tugas kita saat ini untuk melindungi dan meningkatkan martabat manusia.
7. Saat ini terdapat kesepakatan luas mengenai pentingnya dan ruang lingkup normatif martabat manusia serta nilai unik dan transenden setiap manusia.[14] Namun, frasa “martabat pribadi manusia” berisiko menimbulkan beragam penafsiran yang dapat menimbulkan potensi ambiguitas[15] dan “kontradiksi yang membuat kita bertanya-tanya apakah persamaan martabat seluruh umat manusia […] benar-benar diakui, dihormati, dilindungi dan dipromosikan dalam setiap situasi.”[16] Hal ini membawa kita pada kemungkinan adanya empat perbedaan dalam konsep martabat: martabat ontologis, martabat moral, martabat sosial, dan martabat eksistensial. Yang paling penting di antara semua ini adalah martabat ontologis yang dimiliki seseorang karena dia ada dan dikehendaki, diciptakan, dan dicintai oleh Allah. Martabat ontologis tidak dapat dihapuskan dan tetap berlaku melampaui keadaan apa pun yang dialami orang tersebut. Ketika kita berbicara tentang martabat moral, yang kita maksud adalah bagaimana orang menjalankan kebebasannya. Meskipun manusia mempunyai hati nurani, mereka selalu dapat bertindak melawannya. Namun jika mereka melakukan hal tersebut maka mereka akan berperilaku “tidak bermartabat” terhadap kodratnya sebagai makhluk yang dicintai Allah dan terpanggil untuk mencintai sesamanya. Namun, kemungkinan ini selalu ada dalam kebebasan manusia, dan sejarah menggambarkan bagaimana individu—ketika menjalankan kebebasan mereka melawan hukum kasih yang diungkapkan oleh Injil—dapat melakukan tindakan kejahatan yang sangat besar terhadap orang lain. Mereka yang bertindak seperti ini tampaknya telah kehilangan rasa kemanusiaan dan martabat. Di sinilah pembedaan yang ada saat ini dapat membantu kita membedakan antara martabat moral yang secara de facto bisa “hilang” dan martabat ontologis yang tidak akan pernah bisa dihilangkan. Dan justru karena poin terakhir inilah kita harus bekerja sekuat tenaga agar semua orang yang melakukan kejahatan dapat menyesal dan bertobat.
8. Masih ada dua aspek martabat lainnya yang perlu dipertimbangkan: martabat sosial dan martabat eksistensial. Ketika kita berbicara tentang martabat sosial, yang kita maksud adalah kualitas kondisi kehidupan seseorang. Misalnya, dalam kasus kemiskinan ekstrem, di mana individu bahkan tidak memiliki apa pun yang diperlukan untuk hidup sesuai dengan martabat ontologisnya, dikatakan bahwa masyarakat miskin tersebut hidup dalam cara yang “tidak bermartabat”. Ungkapan ini tidak menyiratkan penghakiman terhadap individu-individu tersebut namun menyoroti bagaimana situasi di mana mereka terpaksa hidup bertentangan dengan martabat mereka yang tidak dapat dicabut. Makna yang terakhir adalah martabat eksistensial, yakni jenis martabat yang tersirat dalam diskusi yang semakin meningkat mengenai kehidupan yang “bermartabat” dan kehidupan yang “tidak bermartabat”. Misalnya, meskipun beberapa orang mungkin tampak tidak kekurangan apa pun yang diperlukan dalam hidup, karena berbagai alasan, mereka mungkin masih berjuang untuk hidup damai, gembira, dan penuh harapan. Dalam situasi lain, adanya penyakit serius, lingkungan keluarga yang penuh kekerasan, kecanduan patologis, dan kesulitan lainnya dapat mendorong orang untuk mengalami kondisi kehidupan mereka sebagai “tidak bermartabat” dibandingkan dengan persepsi mereka tentang martabat ontologis yang tidak pernah bisa dikaburkan. Pembedaan ini mengingatkan kita akan nilai martabat ontologis yang tidak dapat dicabut, yang berakar pada keberadaan pribadi manusia dalam segala keadaan.
8. Terakhir, perlu disebutkan bahwa definisi klasik tentang seseorang sebagai “substansi individu yang memiliki kodrat rasional”[17] memperjelas landasan martabat manusia. Sebagai “substansi individual”, pribadi memiliki martabat ontologis (yaitu, pada tingkat metafisik dari keberadaan itu sendiri). Karena menerima eksistensi dari Allah, manusia adalah subjek yang “bertahan hidup”—yakni, mereka menjalankan eksistensinya secara mandiri. Istilah “rasional” mencakup seluruh kapasitas pribadi manusia, termasuk kapasitas mengetahui dan memahami, serta kapasitas menginginkan, mencintai, memilih, dan berhasrat; itu juga mencakup semua fungsi jasmani yang berkaitan erat dengan kemampuan ini. Istilah “kodrat” mengacu pada kondisi khusus kita sebagai manusia, yang memungkinkan kita melakukan berbagai aktivitas dan pengalaman yang menjadi cirinya; dalam pengertian ini, kodrat adalah “prinsip tindakan”. Kita tidak menciptakan kodrat kita; kita menganggapnya sebagai anugerah dan kita dapat memelihara, mengembangkan, dan meningkatkan kemampuan kita. Dengan menggunakan kebebasan untuk mengolah kekayaan kodratnya, pribadi manusia bertumbuh seiring berjalannya waktu. Sekalipun seseorang tidak mampu menjalankan kemampuannya karena berbagai keterbatasan atau kondisi, namun orang tersebut selalu hidup sebagai “substansi individu” dengan martabat yang utuh dan tidak dapat dicabut. Hal ini berlaku, misalnya, pada bayi yang belum lahir, orang yang tidak sadarkan diri, atau orang lanjut usia yang berada dalam kesusahan.
1.
Tumbuhnya Kesadaran Akan Pentingnya Martabat Manusia
10. Sudah di zaman dulu,[18] intuisi tentang martabat manusia muncul dari perspektif sosial yang memandang setiap orang mempunyai martabat tertentu berdasarkan pangkat dan status mereka dalam tatanan yang sudah mapan. Dari asal usulnya dalam bidang sosial, maka kata “martabat” kemudian digunakan untuk menggambarkan keberbedaan martabat makhluk-makhluk di alam semesta. Dalam pandangan ini, semua makhluk memiliki “martabat” masing-masing sesuai dengan tempatnya dalam keselarasan keseluruhan. Beberapa poin penting dari pemikiran kuno mulai mengakui tempat unik bagi manusia sebagai makhluk yang dianugerahi akal-budi sehingga mampu mengambil tanggung jawab terhadap diri mereka sendiri dan orang lain di dunia.[19] Namun demikian, cara berpikir yang mampu membumikan penghormatan terhadap martabat setiap manusia dalam segala keadaan masih jauh dari harapan.
11. Perwahyuan Biblis mengajarkan bahwa semua umat manusia memiliki martabat yang melekat karena mereka diciptakan menurut gambar dan rupa Allah: “Allah berfirman, ‘Baiklah Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Kita’ […] Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia; laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka” (Kejadian 1:26-27). Dengan demikian, umat manusia memiliki kualitas tertentu yang berarti tidak dapat direduksi menjadi unsur-unsur material belaka. Terlebih lagi, “gambar” tidak mendefinisikan jiwa atau kemampuan intelektualnya, melainkan martabat sebagai laki-laki dan perempuan. Dalam hubungan kesetaraan dan cinta timbal balik, baik pria maupun wanita mewakili Allah di dunia dan juga dipanggil untuk menghargai dan memelihara dunia. Oleh karena itu, diciptakan menurut gambar Allah berarti memiliki nilai sakral yang melampaui segala perbedaan yang bersifat seksual, sosial, politik, budaya, dan agama. Martabat kita dianugerahkan kepada kita oleh Allah; itu tidak dapat diklaim atau dianggap sebagai hak. Setiap manusia dicintai dan dikehendaki oleh Allah, sehingga manusia mempunyai martabat yang tidak dapat diganggu gugat. Dalam Kitab Keluaran, yang menjadi inti Perjanjian Lama, Allah menunjukkan diri-Nya sebagai Dia yang mendengar jeritan orang-orang miskin, melihat kesengsaraan umat-Nya, dan peduli terhadap mereka yang paling kecil dan tertindas (bdk. Kel 3:7; 22:20-26). Pengajaran yang sama dapat ditemukan dalam Kitab Ulangan (bdk. Ulangan 12-26); di sini, ajaran tentang hak diubah menjadi sebuah manifesto martabat manusia, khususnya yang mendukung tiga kategori yaitu: anak yatim, janda, dan orang asing (bdk. Ul 24:17). Ajaran leluhur dalam Kitab Keluaran diingat dan diterapkan pada saat ini dalam khotbah para nabi, yang mewakili hati nurani Israel yang kritis. Nabi Amos, Hosea, Yesaya, Mikha, dan Yeremia memiliki seluruh pasal yang mengecam ketidakadilan. Amos dengan getir mengecam penindasan terhadap kaum miskin dan kegagalan para pendengarnya untuk mengakui martabat kemanusiaan mendasar kaum miskin (bdk. Am 2:6-7; 4:1; 5:11-12). Yesaya mengucapkan kutukan terhadap mereka yang menginjak-injak hak-hak orang miskin, dengan mengabaikan keadilan bagi mereka: “Celakalah mereka yang menentukan ketetapan-ketetapan yang tidak adil, dan mereka yang mengeluarkan keputusan-keputusan kelaliman, untuk menghalang-halangi orang-orang lemah mendapat keadilan” (Yes. 10: 1-2). Ajaran profetik ini digaungkan dalam Sastra Kebijaksanaan. Misalnya, Sirakh menyamakan penindasan terhadap orang miskin dengan pembunuhan: “Merampas penghidupan tetangga berarti membunuhnya; mencabut upah seorang pekerja berarti menumpahkan darah” (Sir. 34:22). Dalam Mazmur, hubungan keagamaan dengan Allah muncul melalui pembelaan terhadap yang lemah dan membutuhkan: “Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim, belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan! Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin, lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik!” (Mzm. 82:3-4).
12. Dilahirkan dan dibesarkan dalam kondisi yang sederhana, Yesus mengungkapkan martabat orang yang membutuhkan dan mereka yang bekerja keras.[20] Kemudian, sepanjang pelayanan publik-Nya, Yesus meneguhkan nilai dan martabat semua orang yang memiliki gambar Allah, tanpa memandang status sosial dan keadaan eksternal mereka. Yesus meruntuhkan penghalang budaya dan aliran sesat, memulihkan martabat mereka yang “ditolak” atau dianggap terpinggirkan dalam masyarakat, seperti pemungut pajak (bdk. Mat 9:10-11), perempuan (bdk. Yoh. 4:1-42), anak-anak (bdk. Mrk 10:14-15), penderita kusta (bdk. Mat 8:2-3), orang sakit (bdk. Mrk 1:29-34), orang asing (bdk. Mat 25:35), dan para janda (bdk. Luk 7:11-15). Dia menyembuhkan, memberi makan, membela, membebaskan, dan menyelamatkan. Ia digambarkan sebagai seorang Gembala yang prihatin terhadap satu dombaNya yang hilang (bdk. Mat 18:12-14). Dia mengidentifikasi diri dengan saudara-saudaranya yang paling hina: “Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudara-Ku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk Aku“ (Mat. 25:40). Dalam bahasa Alkitab, “orang kecil” bukan hanya anak-anak, tetapi juga mereka yang rentan, yang paling tidak berarti, yang terbuang, yang tertindas, yang ditolak, yang miskin, yang terpinggirkan, yang tidak terpelajar, yang sakit, dan mereka yang ditindas oleh pihak yang berkuasa. Kristus yang mulia akan menghakimi melalui kasih terhadap sesama yang terdiri dari pelayanan kepada mereka yang lapar, haus, orang asing, orang telanjang, orang sakit, dan orang yang dipenjarakan, kepada mereka ini Dia sendiri mengidentifikasi Diri-Nya (bdk. Mat 25:34-36). Bagi Yesus, kebaikan yang dilakukan kepada setiap umat manusia, tanpa memandang hubungan darah atau agama, merupakan satu-satunya kriteria penghakiman. Rasul Paulus menegaskan bahwa setiap orang Kristen harus hidup sesuai dengan persyaratan martabat dan penghormatan terhadap hak-hak semua orang (lih. Rom 13:8-10) sesuai dengan perintah baru cintakasih (bdk. 1 Kor 13:1 -13).
Perkembangan Pemikiran Kristen
13. Seiring berkembangnya pemikiran Kristen, hal ini juga mendorong dan menyertai kemajuan refleksi umat manusia mengenai konsep martabat. Berangkat dari kekayaan tradisi para Bapa Gereja, antropologi Kristen klasik menekankan doktrin manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah serta peran unik pribadi manusia dalam penciptaan.[21] Dengan menyaring secara kritis warisan yang diterima dari filsafat kuno, pemikiran Kristen Abad Pertengahan sampai pada sintesis gagasan “pribadi” yang mengakui landasan metafisik martabat manusia. Santo Thomas Aquinas membuktikan hal ini ketika ia menegaskan bahwa “’pribadi’ menandakan apa yang paling sempurna dalam seluruh alam—yaitu, individu subsisten yang memiliki kodrat rasional.”[22] Humanisme Kristen pada zaman Renaisans kemudian menekankan martabat ontologis ini dan manifestasi utamanya dalam tindakan manusia yang bebas.[23] Bahkan dalam tulisan-tulisan para pemikir modern seperti Descartes dan Kant, yang menantang beberapa dasar antropologi Kristen tradisional, kita masih dapat melihat dengan jelas gaung dari Kitab Wahyu. Berdasarkan beberapa refleksi filosofis terkini mengenai status subjektivitas teoretis dan praktis, refleksi Kristiani kemudian semakin menekankan kedalaman konsep martabat. Pada abad kedua puluh, hal ini mencapai perspektif orisinal (seperti yang terlihat dalam Personalisme) yang mempertimbangkan kembali pertanyaan tentang subjektivitas dan memperluasnya hingga mencakup intersubjektivitas dan hubungan yang mengikat pribadi manusia satu sama lain.[24] Pemikiran yang mengalir dari pandangan ini telah memperkaya antropologi Kristen kontemporer.[25]
14. Saat ini, istilah “martabat” terutama digunakan untuk menekankan keunikan pribadi manusia, yang tidak dapat dibandingkan dengan semua makhluk lain di alam semesta. Dari perspektif ini, kita dapat memahami bagaimana kata “martabat” digunakan dalam Deklarasi PBB tahun 1948, yang berbicara tentang “martabat yang melekat dan hak-hak yang setara dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga umat manusia.” Hanya karakter martabat manusia yang tidak dapat dicabut inilah yang memungkinkan kita berbicara tentang hak asasi manusia.[26]
15. Untuk lebih memperjelas konsep martabat, perlu ditegaskan bahwa martabat bukanlah sesuatu yang diberikan kepada seseorang oleh orang lain sebagai hadiah atau karena kualitasnya, sehingga martabat tersebut dapat ditarik kembali. Jika martabat tersebut diberikan, maka martabat tersebut akan diberikan dengan cara yang bersyarat dan dapat dialihkan, dan kemudian makna martabat (betapapun layaknya dihormati) akan tetap terkena risiko dihapuskan. Sebaliknya, martabat adalah sesuatu yang intrinsik dalam diri seseorang: martabat tidak diberikan setelahnya (a posteriori), martabat mendahului pengakuan, dan martabat tidak dapat hilang. Semua umat manusia memiliki martabat intrinsik yang sama, terlepas dari apakah mereka dapat mengekspresikannya dengan cara yang pantas atau tidak.
16. Oleh karena itu, Konsili Vatikan II berbicara tentang “keluhuran martabat pribadi manusia, karena melampaui segala sesuatu, lagi pula hak-hak maupun kewajiban-kewajibannya bersifat universal dan tidak dapat diganggu-gugat.”[27] Sebagai kalimat pembuka Deklarasi Dignitatis Humanae dari konsili mengenang, “manusia masa kini semakin sadar akan martabat pribadi manusia; semakin banyak orang yang menuntut agar manusia sepenuhnya menerapkan penilaiannya sendiri dan kebebasan yang bertanggung jawab dalam tindakannya dan tidak boleh berada di bawah tekanan paksaan namun didorong oleh rasa kewajiban.”[28] Kebebasan berpikir dan hati nurani tersebut, baik secara individu maupun komunal, didasarkan pada pengakuan terhadap martabat manusia “sebagaimana yang diketahui melalui Sabda Allah yang diwahyukan dan melalui akal budi itu sendiri.”[29] Magisterium Gereja secara progresif mengembangkan pemahaman yang semakin besar mengenai makna martabat manusia, seiring dengan perkembangan zaman dengan tuntutan-tuntutan dan konsekuensi-konsekuensinya, hingga sampai pada pengakuan bahwa martabat setiap umat manusia melampaui segala situasi.
2.
Gereja Mewartakan, Mempromosikan, dan Menjamin Martabat Manusia
17. Gereja mewartakan martabat yang sama bagi semua orang, apa pun kondisi atau kualitas hidup mereka. Pernyataan ini bertumpu pada tiga keyakinan, yang —menurut iman Kristiani— memberikan kepada martabat manusia suatu nilai yang tidak terukur dan memperkuat tuntutan-tuntutan intrinsiknya.
Gambar Allah yang Tak Terhapuskan
18. Keyakinan pertama, yang diambil dari Kitab Wahyu, menyatakan bahwa martabat pribadi manusia berasal dari cinta kasih Sang Pencipta, yang telah menanamkan ciri-ciri gambar-Nya yang tak terhapuskan pada setiap orang (bdk. Kej 1:26). Sang Pencipta memanggil setiap orang untuk mengenal Dia, untuk mencintai Dia, dan untuk hidup dalam hubungan perjanjian dengan Dia, sekaligus memanggil orang tersebut untuk hidup dalam persaudaraan, keadilan, dan perdamaian dengan semua orang. Dalam perspektif ini, martabat tidak hanya mengacu pada jiwa tetapi juga pribadi sebagai satu kesatuan tubuh dan jiwa yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, martabat juga melekat dalam tubuh setiap orang, yang dengan caranya sendiri ikut serta dalam imago Dei (menurut gambar Allah) dan juga dipanggil untuk ikut ambil bagian dalam kemuliaan jiwa dalam kebahagiaan Ilahi.
Kristus Mengangkat Martabat Manusia
19. Keyakinan kedua berasal dari fakta bahwa martabat pribadi manusia terungkap sepenuhnya ketika Bapa mengutus Putra-Nya, yang mengambil keberadaan manusia sepenuhnya: “Dalam misteri Inkarnasi, Putra Allah meneguhkan martabat tubuh dan jiwa yang membentuk umat manusia.”[30] Dengan menyatukan diri-Nya dengan setiap umat manusia melalui Inkarnasi-Nya, Yesus Kristus menegaskan bahwa setiap orang memiliki martabat yang tak ternilai hanya dengan menjadi bagian dari komunitas manusia; terlebih lagi, Yesus Kristus menegaskan bahwa martabat ini tidak akan pernah hilang.[31] Dengan mewartakan bahwa Kerajaan Allah adalah milik orang-orang miskin, orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang hina, dan orang-orang yang menderita baik jasmani maupun rohani; dengan menyembuhkan segala macam penyakit dan kelemahan, bahkan yang paling parah sekalipun, seperti penyakit kusta; dengan menegaskan bahwa apa pun yang dilakukan terhadap individu-individu ini juga dilakukan terhadap Dia karena Dia hadir di dalam mereka: dengan semua cara ini, Yesus membawa hal baru dalam mengakui martabat setiap orang, terutama mereka yang dianggap “tidak layak.” Prinsip baru dalam sejarah umat manusia ini—yang menekankan bahwa individu bahkan lebih “layak” untuk kita hormati dan cintai ketika mereka lemah, terhina, atau menderita, bahkan sampai kehilangan “sosok” manusianya—telah mengubah wajah dunia. Hal ini telah memberikan kehidupan bagi lembaga-lembaga yang merawat mereka yang berada dalam kondisi yang kurang beruntung, seperti bayi terlantar, anak yatim piatu, orang lanjut usia yang tidak mendapat bantuan, orang yang sakit jiwa, orang dengan penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau cacat parah, dan mereka yang hidup di jalanan.
Panggilan Menuju Kepenuhan Martabat
20. Keyakinan ketiga menyangkut tujuan akhir umat manusia. Setelah Penciptaan dan Inkarnasi, Kebangkitan Kristus menyingkapkan aspek lebih lanjut dari martabat manusia. Memang benar, “martabat manusia terletak terutama pada kenyataan bahwa ia dipanggil untuk bersekutu dengan Allah,”[32] yang ditakdirkan untuk bertahan selamanya. Oleh karena itu, “martabat kehidupan ini tidak hanya terkait dengan permulaannya, dengan fakta bahwa kehidupan ini berasal dari Allah, namun juga dengan tujuan akhirnya, yang ditakdirkan untuk bersekutu dengan Allah dalam pengetahuan dan cinta akan Dia. Dalam terang kebenaran ini, Santo Irenaeus memenuhi syarat dan melengkapi pujiannya terhadap manusia: ‘kemuliaan Allah’ memang ‘manusia yang hidup’, tetapi “hidup manusia berupa memandang Allah’”[33]
21. Oleh karena itu, Gereja percaya dan menegaskan bahwa seluruh umat manusia—dengan diciptakan segambar dan serupa dengan Allah dan diciptakan kembali[34] dalam diri Putra, yang menjadi manusia, disalibkan, dan bangkit kembali— dipanggil untuk bertumbuh dalam bimbingan dan tindakan Roh Kudus untuk mencerminkan kemuliaan Bapa dalam gambar yang sama dan untuk mengambil bagian dalam kehidupan kekal (bdk. Yoh 10:15-16, 17:22-24; 2 Kor 3:18; Ef 1:3- 14). Memang benar, “Wahyu […] memaparkan martabat pribadi manusia dalam arti yang sepenuhnya.”[35]
Komitmen terhadap Kebebasannya Sendiri
22. Setiap individu memiliki martabat yang tidak dapat dicabut dan hakiki sejak awal keberadaannya sebagai anugerah yang tidak dapat ditarik kembali. Namun, pilihan untuk mengungkapkan martabat itu dan mewujudkannya secara penuh atau mengaburkannya bergantung pada keputusan masing-masing orang yang bebas dan bertanggung jawab. Beberapa Bapa Gereja, seperti Santo Irenaeus dan Santo Yohanes dari Damaskus, membedakan antara “gambar” dan “rupa” yang disebutkan dalam Kejadian (bdk Kej 1:26). Hal ini memungkinkan adanya perspektif dinamis mengenai martabat manusia yang memahami bahwa citra Allah dipercayakan kepada kebebasan manusia sehingga—di bawah bimbingan dan tindakan Roh Kudus—keserupaan seseorang dengan Allah dapat bertumbuh dan setiap orang dapat mencapai martabat tertingginya.[36] Semua orang dipanggil untuk mewujudkan ruang lingkup ontologis martabat mereka pada tingkat eksistensial dan moral ketika mereka, melalui kebebasan mereka, mengarahkan diri mereka menuju kebaikan yang sejati sebagai tanggapan terhadap kasih Allah. Oleh karena itu, sebagai makhluk yang diciptakan menurut citra Allah, pribadi manusia tidak pernah kehilangan martabatnya dan tidak pernah berhenti terpanggil untuk meraih kebaikan dengan leluasa. Pada saat yang sama, sejauh individu memberikan tanggapan terhadap kebaikan, martabat individu dapat terwujud secara bebas, dinamis, dan progresif; dengan itu, ia juga bisa tumbuh dan menjadi dewasa. Oleh karena itu, setiap orang juga harus berusaha untuk memenuhi martabatnya dengan sepenuhnya. Dengan demikian kita dapat memahami bagaimana dosa dapat melukai dan mengaburkan martabat manusia, karena dosa merupakan tindakan yang bertentangan dengan martabat tersebut; namun, dosa tidak pernah dapat membatalkan fakta bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dengan cara ini, iman memainkan peran yang menentukan dalam membantu akal budi memahami martabat manusia dan dalam menerima, mengkonsolidasikan, dan memperjelas ciri-ciri esensialnya, seperti yang dikatakan Benediktus XVI: “Namun, tanpa perbaikan yang diberikan oleh agama, akal budi juga bisa menjadi mangsa distorsi, seperti ketika hal tersebut dimanipulasi oleh ideologi, atau diterapkan secara parsial sehingga tidak sepenuhnya mempertimbangkan martabat pribadi manusia. Penyalahgunaan akal budi inilah yang pertama-tama memunculkan perdagangan budak dan banyak kejahatan sosial lainnya, termasuk ideologi totaliter di abad ke-20.”[37]
3.
Martabat, Dasar dan Hak dan Kewajiban Manusia
23. Sebagaimana diingatkan oleh Paus Fransiskus, “Dalam kebudayaan modern, referensi terdekat terhadap prinsip martabat manusia yang tidak dapat dicabut adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang didefinisikan oleh Santo Yohanes Paulus II sebagai ‘tonggak sejarah dalam perjalanan umat manusia yang panjang dan sulit,’ dan sebagai ‘salah satu ekspresi tertinggi dari hati nurani manusia.’”[38] Untuk menangkal upaya mengubah atau menghilangkan makna mendalam Deklarasi tersebut, ada baiknya mengingat beberapa prinsip penting yang harus selalu dihormati.
Penghormatan Tanpa Syarat pada Martabat Manusia
24. Pertama, kendatipun kesadaran akan martabat manusia telah meningkat, namun ada banyak kesalahpahaman mengenai konsep tersebut yang masih menyimpang dari maknanya. Beberapa orang berpendapat bahwa lebih baik menggunakan ungkapan “martabat pribadi” (dan hak-hak “pribadi”) daripada “martabat manusia” (dan hak-hak “manusia”) karena mereka memahami bahwa seorang “pribadi” sajalah “orang yang mampu berpikir.” Mereka kemudian berpendapat bahwa martabat dan hak-hak disimpulkan dari kapasitas individu atas pengetahuan dan kebebasan, yang tidak dimiliki semua manusia. Oleh karena itu, menurut mereka, anak yang belum lahir tidak akan memiliki martabat pribadi, begitu pula orang lanjut usia yang bergantung pada orang lain, dan individu dengan disabilitas mental juga tidak akan memilikinya.[39] Sebaliknya, Gereja menegaskan bahwa martabat setiap pribadi manusia, justru karena martabat itu bersifat intrinsik, tetap dipertahankan “dalam segala keadaan.” Pengakuan atas martabat ini tidak dapat bergantung pada penilaian mengenai kemampuan seseorang untuk memahami dan bertindak secara bebas; jika tidak, hal tersebut tidak akan melekat pada diri seseorang, terlepas dari situasi individu tersebut, dan dengan demikian patut dihormati tanpa syarat. Hanya dengan mengakui martabat yang intrinsik dan tidak dapat dicabut dalam diri setiap manusia, kita dapat menjamin landasan yang aman dan tidak dapat diganggu gugat bagi kualitas tersebut. Tanpa landasan ontologis apa pun, pengakuan terhadap martabat manusia akan terombang-ambing karena adanya penilaian yang berbeda-beda dan sewenang-wenang. Satu-satunya prasyarat untuk berbicara tentang martabat yang melekat pada diri seseorang adalah keanggotaannya dalam spesies manusia, yang mana “hak-hak pribadi adalah hak-hak manusia.”[40]
Dasar Objektif bagi Kebebasan Manusia
25. Kedua, konsep martabat manusia juga kadang-kadang disalahgunakan untuk membenarkan perluasan hak-hak baru secara sewenang-wenang, yang banyak di antaranya bertentangan dengan definisi awal dan seringkali bertentangan dengan hak dasar untuk hidup.[41] Seolah-olah kemampuan untuk mengekspresikan dan mewujudkan setiap preferensi atau keinginan subjektif individu harus dijamin. Perspektif ini mengidentifikasi martabat dengan kebebasan yang terisolasi dan individualistis yang mengklaim memaksakan keinginan dan kecenderungan subjektif tertentu sebagai “hak” yang harus dijamin dan didanai oleh komunitas. Namun, martabat manusia tidak bisa hanya didasarkan pada standar individualistis, juga tidak bisa diidentifikasikan dengan kesejahteraan psiko-fisik individu. Sebaliknya, pembelaan terhadap martabat manusia didasarkan pada tuntutan konstitutif dari sifat manusia, yang tidak bergantung pada kemauan individu atau pengakuan sosial. Oleh karena itu, kewajiban yang timbul dari pengakuan martabat orang lain dan hak-hak terkait yang timbul darinya mempunyai isi yang konkret dan objektif berdasarkan sifat kemanusiaan kita bersama. Tanpa landasan objektif seperti itu, konsep martabat secara de facto akan tunduk pada berbagai bentuk kesewenang-wenangan dan kepentingan kekuasaan.
Struktur Relasional Pribadi Manusia
26. Dilihat dari sudut pandang sifat relasional seseorang, martabat manusia membantu mengatasi perspektif sempit tentang kebebasan yang mengacu pada diri sendiri dan individualistis yang mengklaim dapat menciptakan nilai-nilainya sendiri terlepas dari norma-norma objektif kebaikan dan hubungan kita dengan makhluk hidup lainnya. Memang benar, terdapat risiko yang semakin besar yaitu menurunkan martabat manusia pada kemampuan untuk menentukan identitas dan masa depan seseorang secara mandiri, tanpa memperhatikan keanggotaan seseorang dalam komunitas manusia. Dalam pemahaman yang salah tentang kebebasan ini, pengakuan timbal balik atas tugas dan hak yang memungkinkan kita untuk peduli satu sama lain menjadi mustahil. Faktanya, seperti yang diingatkan oleh Paus St. Yohanes Paulus II, kebebasan ditempatkan “untuk melayani pribadi dan pemenuhannya melalui pemberian diri dan keterbukaan terhadap orang lain; namun ketika kebebasan dijadikan mutlak secara individualistis, maka kebebasan tersebut menjadi kosong dari isi aslinya, dan makna serta martabatnya menjadi bertentangan.”[42]
27. Martabat manusia juga mencakup kemampuan yang melekat pada kodrat manusia untuk memikul kewajiban terhadap orang lain.
28. Perbedaan manusia dengan seluruh makhluk hidup lainnya yang menonjol karena konsep harkat dan martabatnya, hendaknya tidak membuat kita melupakan kebaikan makhluk lain. Makhluk-makhluk itu memang diciptakan bagi manusia tetapi (mereka) juga memiliki nilai tersendiri; mereka seperti anugerah yang dipercayakan kepada umat manusia untuk dihargai dan dikembangkan. Oleh karena itu, walaupun konsep martabat diperuntukkan bagi manusia, pada saat yang sama, kebaikan ciptaan seluruh kosmos harus ditegaskan. Seperti yang Paus Fransiskus tunjukkan, “Berdasarkan martabat kita yang unik dan karunia kecerdasan yang kita miliki, kita dipanggil untuk menghormati ciptaan dan hukum-hukum yang melekat di dalamnya […], ‘Setiap makhluk memiliki kebaikan dan kesempurnaannya masing-masing… Masing-masing dari berbagai makhluk, dikehendaki dalam wujudnya sendiri, dengan caranya sendiri mencerminkan pancaran kebijaksanaan dan kebaikan Allah yang tak terbatas. Oleh karena itu, manusia harus menghormati kebaikan khusus dari setiap makhluk, untuk menghindari penggunaan makhluk hidup yang tidak teratur.’”[43] Lebih jauh lagi, “saat ini kita melihat diri kita dipaksa untuk menyadari bahwa hanya mungkin untuk mempertahankan ‘antropo-sentrisme yang ada’. Untuk mengakui, dengan kata lain, kehidupan manusia tidak dapat dipahami dan tidak dapat dipertahankan tanpa makhluk lain.”[44] Dalam perspektif ini, “bukanlah soal ketidakpedulian bagi kita bahwa begitu banyak spesies yang punah dan bahwa krisis iklim membahayakan kehidupan banyak makhluk hidup lainnya.”[45] Sungguhlah tanggung jawab martabat manusia untuk menjaga lingkungan, dengan mempertimbangkan secara khusus ekologi manusia yang melestarikan keberadaan mereka.
Membebaskan Pribadi Manusia dari Pengaruh Negatif dalam Bidang Moral dan Sosial
29. Persyaratan mendasar ini, betapapun penting, tidak menjamin pertumbuhan seseorang sesuai dengan martabatnya. Meskipun “Allah menciptakan manusia sebagai makhluk rasional, menganugerahkan kepadanya martabat sebagai orang yang dapat memulai dan mengendalikan tindakannya sendiri,”[46] dengan tujuan untuk kebaikan, kehendak bebas kita sering kali lebih memilih kejahatan daripada kebaikan. Oleh karena itu, kebebasan manusia pada gilirannya perlu dibebaskan. Dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, Santo Paulus menegaskan bahwa “supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita” (Gal. 5:1), mengingat tugas yang patut bagi setiap umat Kristiani, yang di pundaknya terdapat tanggung jawab pembebasan yang mencakup seluruh seluruh dunia (bdk. Rom 8:19 dst). Ini adalah sebuah pembebasan yang, dimulai dari hati setiap orang, dipanggil untuk menyebarkan dan mewujudkan kekuatan kemanusiaannya ke dalam semua hubungan.
30. Kebebasan adalah anugerah luar biasa dari Allah. Bahkan ketika Allah menarik kita kepada-Nya dengan kasih karunia-Nya, Dia melakukannya dengan cara yang tidak pernah melanggar kebebasan kita. Oleh karena itu, merupakan kesalahan besar jika kita berpikir bahwa dengan menjauhkan diri dari Allah dan bantuan-Nya, kita bisa menjadi lebih bebas dan merasa lebih bermartabat. Sebaliknya, jika kita terlepas dari Sang Pencipta, kebebasan kita hanya akan melemah dan menjadi kabur. Hal yang sama terjadi jika kebebasan membayangkan dirinya tidak bergantung pada referensi eksternal dan menganggap hubungan apa pun dengan kebenaran sebelumnya sebagai ancaman; akibatnya, rasa hormat terhadap kebebasan dan martabat orang lain juga akan berkurang. Sebagaimana dijelaskan oleh Paus Benediktus XVI, “Suatu wasiat yang meyakini dirinya secara radikal tidak mampu mencari kebenaran dan kebaikan tidak memiliki alasan atau motif objektif untuk bertindak kecuali hal-hal yang dipaksakan oleh kepentingan sesaat dan tidak terduga; ia tidak memiliki ‘identitas’ untuk dilindungi dan dibangun melalui keputusan yang benar-benar bebas dan sadar. Akibatnya, masyarakat tidak bisa menuntut rasa hormat dari ‘kehendak’ orang lain, yang tidak terikat pada keberadaan mereka yang terdalam sehingga mampu memaksakan ‘alasan’ lain atau, dalam hal ini, tidak ada ‘alasan’ sama sekali. Ilusi bahwa relativisme moral memberikan kunci bagi hidup berdampingan secara damai sebenarnya adalah asal mula perpecahan dan pengingkaran terhadap martabat umat manusia.”[47]
31. Selain itu, tidaklah realistis untuk menganggap kebebasan abstrak tanpa pengaruh, konteks, atau batasan apa pun. Sebaliknya, “pelaksanaan kebebasan pribadi yang tepat memerlukan kondisi khusus dalam tatanan ekonomi, sosial, hukum, politik dan budaya,”[48] yang sering kali tidak terpenuhi. Dalam pengertian ini, kita dapat mengatakan bahwa beberapa individu menikmati lebih banyak “kebebasan” dibandingkan yang lain. Paus Fransiskus memberikan perhatian khusus pada hal ini: “Beberapa orang dilahirkan dalam keluarga yang stabil secara ekonomi, menerima pendidikan yang baik, tumbuh dengan gizi yang baik, atau secara alami memiliki bakat yang luar biasa. Mereka tentu saja tidak membutuhkan negara yang proaktif; mereka hanya perlu mendapatkan kebebasan mereka. Namun, peraturan yang sama jelas tidak berlaku bagi penyandang disabilitas, bagi mereka yang lahir dalam kemiskinan parah, bagi mereka yang tidak memiliki pendidikan yang baik dan memiliki sedikit akses terhadap layanan kesehatan yang memadai. Jika suatu masyarakat terutama diatur berdasarkan kriteria kebebasan pasar dan efisiensi, tidak ada tempat bagi orang-orang seperti itu, dan persaudaraan akan tetap menjadi cita-cita yang samar-samar.”[49] Oleh karena itu, penting untuk dipahami bahwa “menghapus ketidakadilan akan mendorong kebebasan manusia dan martabat”[50] di setiap tingkat usaha manusia. Untuk mewujudkan kebebasan sejati, “kita harus mengembalikan martabat manusia sebagai prioritas utama dan, pada pilar tersebut, membangun struktur sosial alternatif yang kita perlukan.”[51] Demikian pula, kebebasan sering kali dikaburkan oleh berbagai aspek psikologis, sejarah, sosial, dan pendidikan, dan pengaruh budaya. Kebebasan yang nyata dan historis selalu perlu “dibebaskan.” Terlebih lagi, kita harus menegaskan kembali hak fundamental atas kebebasan beragama.
32. Pada saat yang sama, sejarah umat manusia menunjukkan kemajuan yang jelas dalam memahami martabat dan kebebasan manusia, meskipun bukan tanpa bayang-bayang dan risiko kemunduran. Kemajuan dalam pemahaman martabat manusia ini ditunjukkan oleh meningkatnya keinginan untuk memberantas rasisme, perbudakan, dan marginalisasi perempuan, anak-anak, orang sakit, dan penyandang disabilitas. Aspirasi ini diperkuat oleh pengaruh iman Kristen, yang terus bergejolak, bahkan di masyarakat yang semakin sekuler. Namun, perjalanan yang sulit untuk memajukan martabat manusia masih jauh dari selesai.
33. Mengingat refleksi sebelumnya mengenai pentingnya martabat manusia, bagian akhir Deklarasi ini membahas beberapa pelanggaran spesifik dan berat terhadap martabat manusia. Hal ini dilakukan sesuai dengan semangat magisterium Gereja, yang telah diungkapkan sepenuhnya dalam ajaran para Paus baru-baru ini, sebagaimana disebutkan sebelumnya. Misalnya, Paus Fransiskus, di satu sisi, tanpa kenal lelah mengingatkan kita akan perlunya menghormati martabat manusia: “Setiap manusia mempunyai hak untuk hidup bermartabat dan berkembang secara integral; hak mendasar ini tidak dapat disangkal oleh negara mana pun. Setiap orang mempunyai hak ini, meskipun mereka tidak produktif atau dilahirkan dengan atau mengembangkan keterbatasan. Hal ini tidak mengurangi martabat mereka yang agung sebagai pribadi manusia, suatu martabat yang tidak didasarkan pada keadaan tetapi pada nilai intrinsik dari keberadaan mereka. Jika prinsip dasar ini tidak ditegakkan, tidak akan ada masa depan, baik bagi persaudaraan maupun kelangsungan hidup umat manusia.”[52] Di sisi lain, beliau tidak pernah berhenti menunjukkan pelanggaran nyata terhadap martabat manusia di zaman kita, dengan memanggil kita masing-masing untuk menyadari tanggung jawab kita dan perlunya terlibat dalam komitmen nyata dalam hal ini.
34. Dalam menyikapi beberapa pelanggaran berat terhadap martabat manusia saat ini, kita dapat mengacu pada ajaran Konsili Vatikan Kedua, yang menekankan bahwa “semua pelanggaran terhadap kehidupan itu sendiri, seperti pembunuhan, genosida, aborsi, euthanasia, dan bunuh diri yang disengaja” harus dianggap bertentangan dengan martabat manusia.[53] Lebih lanjut, Dewan menegaskan bahwa “semua pelanggaran terhadap integritas pribadi manusia, seperti mutilasi, penyiksaan fisik dan mental, tekanan psikologis yang tidak semestinya,” juga melanggar martabat kita.[54] Pada akhirnya, Konvensi ini mengecam “semua pelanggaran terhadap martabat manusia, seperti kondisi kehidupan yang tidak manusiawi, pemenjaraan sewenang-wenang, deportasi, perbudakan, prostitusi, penjualan perempuan dan anak-anak, kondisi kerja yang merendahkan martabat dimana individu diperlakukan hanya sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan, bukan sebagai orang yang bebas dan bertanggungjawab.”[55] Di sini, hukuman mati juga harus disebutkan, karena hukuman mati juga melanggar martabat setiap orang, apa pun kondisinya.[56] Dalam hal ini, kita harus mengakui bahwa “penolakan tegas terhadap hukuman mati menunjukkan sejauh mana kita bisa mengakui martabat setiap umat manusia dan menerima bahwa ia mempunyai tempat di alam semesta ini. Jika saya mengakui martabat penjahat paling keji, maka saya juga akan mengakui martabat setiap orang. Saya akan memberi semua orang kemungkinan untuk berbagi planet ini dengan saya, terlepas dari semua perbedaan kita.”[57] Juga patut untuk menegaskan kembali martabat mereka yang dipenjara, yang seringkali harus hidup dalam kondisi yang tidak bermartabat. Yang terakhir, harus dinyatakan bahwa—bahkan jika seseorang bersalah atas kejahatan berat—praktik penyiksaan sepenuhnya bertentangan dengan martabat yang pantas bagi setiap umat manusia.
35. Meskipun tidak menjelaskan secara lengkap, paragraf-paragraf berikut ini menarik perhatian pada beberapa pelanggaran berat terhadap martabat manusia yang sangat relevan.
36. Salah satu fenomena yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pengingkaran martabat begitu banyak umat manusia adalah kemiskinan ekstrem, yang terkait dengan distribusi kekayaan yang tidak merata. Sebagaimana ditekankan oleh Paus Santo Yohanes Paulus II, “Salah satu ketidakadilan terbesar dalam dunia masa kini justru terletak pada hal ini: bahwa mereka yang mempunyai banyak jumlahnya relatif sedikit dan mereka yang hampir tidak punya apa-apa jumlahnya banyak. Ini adalah ketidakadilan dalam distribusi barang dan jasa yang buruk, yang awalnya ditujukan untuk semua orang.”[58] Terlebih lagi, akan menyesatkan jika kita hanya membedakan secara sepintas antara negara-negara “kaya” dan “negara-negara miskin”, karena Benediktus XVI mengakui bahwa “kekayaan dunia meningkat secara absolut, namun kesenjangan semakin meningkat. Di negara-negara kaya, sektor-sektor baru dalam masyarakat mengalami kemiskinan dan muncul bentuk-bentuk baru kemiskinan. Di wilayah yang lebih miskin, beberapa kelompok menikmati semacam ‘perkembangan luar biasa’ yang boros dan konsumeris, yang sangat kontras dengan perampasan yang tidak manusiawi.” “‘Skandal kesenjangan yang mencolok’ terus berlanjut,”[59] di mana martabat masyarakat miskin diremehkan karena kurangnya sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan ketidakpedulian yang ditunjukkan oleh tetangga mereka.
37. Oleh karena itu, bersama dengan Paus Fransiskus, kita harus menyimpulkan bahwa “kekayaan telah meningkat, namun bersamaan dengan kesenjangan, yang mengakibatkan ‘bentuk-bentuk kemiskinan baru bermunculan’. Pernyataan bahwa dunia modern telah mengurangi kemiskinan dibuat dengan mengukur kemiskinan dengan kriteria dari masa lalu yang tidak sesuai dengan kenyataan saat ini.”[60] Akibatnya, kemiskinan “dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti obsesi untuk mengurangi biaya tenaga kerja tanpa mempedulikan dampak buruknya, sejak pengangguran yang secara langsung menghasilkan perluasan kemiskinan.”[61] Di antara “dampak destruktif dari kerajaan uang” ini,[62] harus diakui bahwa “tidak ada kemiskinan yang lebih buruk daripada kemiskinan yang menghilangkan pekerjaan dan martabat pekerjaan.”[63] Selain itu, jika ada orang yang dilahirkan di negara atau keluarga di mana mereka memiliki lebih sedikit kesempatan untuk berkembang, kita harus mengakui bahwa hal ini bertentangan dengan martabat mereka, yang merupakan martabat yang sama dengan mereka yang lahir di keluarga atau negara yang kaya. Kita semua bertanggung jawab atas kesenjangan yang mencolok ini, meskipun pada tingkat yang berbeda-beda.
38. Tragedi lain yang bertentangan dengan martabat manusia, baik di masa lalu maupun di masa kini, adalah perang: “Perang, serangan teroris, persekusi rasial atau agama, dan banyak penghinaan lainnya terhadap martabat manusia […] ‘telah menjadi hal yang biasa sehingga merupakan sebuah tragedi nyata ‘perang dunia ketiga’ terjadi sedikit demi sedikit.’”[64] Dengan jejak kehancuran dan penderitaannya, perang menyerang martabat manusia baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang: “Sambil menegaskan kembali hak yang tidak dapat dicabut untuk membela diri dan tanggung jawab untuk melindungi mereka yang kehidupan terancam, kita harus mengakui bahwa perang selalu merupakan ‘kekalahan kemanusiaan.’ Tidak ada perang yang sebanding dengan air mata seorang ibu yang melihat anaknya dimutilasi atau dibunuh; tidak ada perang yang sebanding dengan hilangnya nyawa satu manusia pun, makhluk suci yang diciptakan menurut gambar dan rupa Sang Pencipta; tidak ada perang yang sebanding dengan keracunan rumah kita bersama; dan tidak ada perang yang sebanding dengan keputusasaan mereka yang terpaksa meninggalkan tanah air mereka dan, dari satu saat ke saat berikutnya, kehilangan rumah mereka dan semua ikatan keluarga, persahabatan, sosial dan budaya yang telah dibangun, terkadang dari generasi ke generasi. .”[65] Semua perang, karena bertentangan dengan martabat manusia, adalah “konflik yang tidak akan menyelesaikan masalah namun hanya akan menambah masalah.”[66] Hal ini bahkan menjadi lebih penting lagi di zaman kita, ketika sudah menjadi hal biasa bagi begitu banyak warga sipil yang tidak bersalah untuk binasa di luar batas medan perang.
39. Oleh karena itu, bahkan saat ini, Gereja harus tetap menggunakan kata-kata Paus, yang mengulangi bersama Paus Santo Paulus VI: “jamais plus la guerre, jamais plus la guerre!” [“jangan ada lagi perang, jangan ada lagi perang!”].[67] Terlebih lagi, bersama dengan Paus Santo Yohanes Paulus II, Gereja memohon “dalam nama Allah dan dalam nama manusia: Jangan membunuh! Jangan mempersiapkan kehancuran dan pemusnahan bagi manusia! Pikirkanlah saudara-saudaramu yang menderita kelaparan dan kesengsaraan! Hormatilah martabat dan kebebasan setiap orang!”[68] Saat ini, hal ini merupakan seruan Gereja dan seluruh umat manusia. Paus Fransiskus menggarisbawahi hal ini dengan menyatakan, “Kita tidak bisa lagi menganggap perang sebagai solusi karena risikonya mungkin selalu lebih besar daripada manfaat yang diharapkan. Mengingat hal ini, saat ini sangat sulit untuk menggunakan kriteria rasional yang diuraikan pada abad-abad sebelumnya untuk berbicara tentang kemungkinan terjadinya ‘perang yang adil’. Jangan pernah lagi berperang!”[69] Karena umat manusia sering kali terjatuh ke dalam kesalahan yang sama seperti di masa lalu, “untuk mewujudkan perdamaian, kita harus menjauh dari logika legitimasi perang.”[70] Hubungan yang erat antara iman dan martabat manusia berarti akan menjadi kontradiktif jika perang didasarkan pada keyakinan agama: “Mereka yang menyebut nama Allah untuk membenarkan terorisme, kekerasan, dan perang, tidak mengikuti jalan Allah. Perang atas nama agama menjadi perang melawan agama itu sendiri.”[71]
40. Para migran merupakan korban pertama dari berbagai bentuk kemiskinan. Martabat mereka tidak hanya diremehkan di negara asal mereka,[72] namun kehidupan mereka juga terancam karena mereka tidak lagi mempunyai sarana untuk berkeluarga, bekerja, atau menghidupi diri mereka sendiri.[73] Begitu mereka tiba di negara-negara yang seharusnya dapat menerima mereka, “para migran tidak dipandang mempunyai hak seperti orang lain untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, dan dilupakan bahwa mereka memiliki martabat intrinsik yang sama dengan orang lain. […] Tidak seorang pun akan secara terbuka menyangkal bahwa mereka adalah manusia; namun dalam praktiknya, melalui keputusan dan cara kita memperlakukan mereka, kita dapat menunjukkan bahwa kita menganggap mereka kurang berharga, kurang penting, kurang manusiawi.”[74] Oleh karena itu, penting untuk diingat bahwa “setiap migran adalah manusia yang, dengan demikian, memiliki hak-hak mendasar dan tidak dapat dicabut yang harus dihormati oleh semua orang dan dalam keadaan apa pun.”[75] Menerima migran adalah cara yang penting dan bermakna untuk membela “martabat setiap manusia yang tidak dapat dicabut tanpa memandang asal usul, ras, atau agama. ”[76]
41. Perdagangan manusia juga harus dimasukkan dalam pelanggaran berat terhadap martabat manusia.[77] Walaupun ini bukan sebuah fenomena baru, namun hal ini telah mencapai dimensi yang tragis di depan mata kita, itulah sebabnya Paus Fransiskus mengecamnya dengan tegas: “Saya tegaskan kembali di sini bahwa ‘perdagangan manusia’ adalah kegiatan yang keji, memalukan bagi semua masyarakat kita yang mengaku beradab! Para pengeksploitasi dan klien di semua tingkatan harus melakukan pemeriksaan hati nurani yang serius baik secara langsung maupun di hadapan Allah! Saat ini Gereja memperbarui seruannya yang mendesak agar martabat dan sentralitas setiap individu selalu dijaga, dengan menghormati hak-hak dasar, sebagaimana ditekankan oleh ajaran sosialnya. Beliau meminta agar hak-hak ini benar-benar diberikan kepada jutaan pria dan wanita di setiap benua, dimanapun mereka tidak diakui. Di dunia yang banyak dibicarakan tentang hak asasi manusia, betapa seringnya martabat manusia diinjak-injak! Di dunia yang banyak dibicarakan tentang hak, nampaknya satu-satunya hal yang memiliki hak adalah uang.”[78]
42. Karena alasan-alasan ini, Gereja dan umat manusia tidak boleh berhenti berjuang melawan fenomena seperti “jual beli organ dan jaringan tubuh manusia, eksploitasi seksual terhadap anak laki-laki dan perempuan, kerja paksa, termasuk prostitusi, perdagangan narkoba dan senjata, terorisme, dan kejahatan terorganisir internasional. Begitu besarnya situasi ini, dan dampaknya terhadap kehidupan orang-orang yang tidak bersalah, sehingga kita harus menghindari setiap godaan untuk jatuh ke dalam nominalisme deklarasi (deklarasi sebatas kata-kata) yang akan menenangkan hati nurani kita. Kita perlu memastikan bahwa lembaga-lembaga kita benar-benar efektif dalam melawan semua teror ini.”[79] Dihadapkan dengan beragam dan brutalnya penolakan terhadap martabat manusia, kita perlu semakin menyadari bahwa “perdagangan manusia adalah kejahatan terhadap kemanusiaan.”[80] Hal ini pada dasarnya menyangkal martabat manusia setidaknya dalam dua hal: “Perdagangan manusia sangat merusak kemanusiaan korban, melanggar kebebasan dan martabatnya. Namun, pada saat yang sama, merusak kemanusiaan mereka yang melakukannya.”[81]
43. Martabat mendalam yang melekat pada diri manusia secara keseluruhan baik jiwa maupun raganya juga memungkinkan kita memahami mengapa semua pelecehan seksual meninggalkan luka yang dalam di hati orang-orang yang mengalaminya. Memang benar, mereka yang mengalami pelecehan seksual mengalami luka nyata dalam martabat kemanusiaan mereka. Ini adalah “penderitaan yang dapat berlangsung seumur hidup dan tidak dapat disembuhkan dengan pertobatan. Fenomena ini tersebar luas di masyarakat dan juga berdampak pada Gereja serta merupakan hambatan serius bagi misinya.”[82] Dari sinilah muncul upaya Gereja yang tak henti-hentinya untuk mengakhiri segala bentuk pelecehan, dimulai dari dalam.
44. Kekerasan terhadap perempuan merupakan skandal global yang semakin disadari. Meskipun kesetaraan martabat perempuan diakui secara kasat mata, namun kesenjangan antara perempuan dan laki-laki di beberapa negara masih sangat serius. Bahkan di negara-negara paling maju dan demokratis sekalipun, realitas sosial yang konkret menunjukkan fakta bahwa perempuan seringkali tidak diberikan martabat yang sama dengan laki-laki. Paus Fransiskus menggarisbawahi hal ini ketika ia menegaskan bahwa “organisasi masyarakat di seluruh dunia masih jauh dari mencerminkan dengan jelas bahwa perempuan memiliki martabat dan hak yang sama dengan laki-laki. Kita mengatakan satu hal dengan kata-kata, namun keputusan dan kenyataan kita menceritakan hal lain. Memang benar, ‘yang termasuk dalam kelompok miskin ganda adalah perempuan yang mengalami situasi pengucilan, penganiayaan, dan kekerasan, karena mereka sering kali tidak mampu mempertahankan hak-hak mereka.’”[83]
45. Paus Santo Yohanes Paulus II mengakui bahwa “masih banyak yang harus dilakukan untuk mencegah diskriminasi terhadap mereka yang telah memilih menjadi istri dan ibu. […] Ada kebutuhan mendesak untuk mencapai kesetaraan nyata di setiap bidang: upah yang setara untuk pekerjaan yang setara, perlindungan bagi ibu yang bekerja, keadilan dalam kemajuan karir, kesetaraan pasangan dalam hal hak-hak keluarga dan pengakuan atas segala sesuatu yang ada. bagian dari hak dan kewajiban warga negara di negara demokratis.”[84] Memang benar, kesenjangan di bidang-bidang ini juga merupakan bentuk kekerasan. Santo Yohanes Paulus II juga mengingatkan bahwa “sudah tiba waktunya untuk mengutuk keras jenis-jenis kekerasan seksual yang sering kali menjadikan perempuan sebagai sasarannya dan untuk mengeluarkan undang-undang yang secara efektif membela mereka dari kekerasan tersebut. Kita juga tidak boleh gagal, atas nama penghormatan terhadap pribadi manusia, untuk mengecam meluasnya budaya hedonistik dan komersial yang mendorong eksploitasi seksualitas secara sistematis dan merusak bahkan gadis-gadis yang masih sangat muda sehingga membiarkan tubuh mereka digunakan demi keuntungan.”[85] Di antara bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan, bagaimana kita tidak menyebutkan aborsi paksa, yang berdampak pada ibu dan anak, seringkali untuk memuaskan keegoisan laki-laki? Dan bagaimana kita tidak juga menyebut praktik poligami? Sebagaimana diingatkan oleh Katekismus Gereja Katolik, poligami bertentangan dengan kesetaraan martabat perempuan dan laki-laki; hal ini juga “bertentangan dengan cinta suami-istri yang tidak terbagi dan eksklusif.”[86]
46. Dalam pertimbangan mengenai kekerasan terhadap perempuan, kita tidak bisa hanya mengutuk fenomena femicide (pembunuhan kaum perempuan karena ia perempuan). Dalam hal ini, seluruh komunitas internasional harus memiliki komitmen yang terkoordinasi dan konkret, sebagaimana ditegaskan kembali oleh Paus Fransiskus, “Cinta kita kepada Maria harus membantu kita merasakan penghargaan dan rasa syukur terhadap perempuan, terhadap ibu dan nenek kita, yang merupakan benteng dalam kehidupan di kota-kota kita. Hampir selalu dalam keheningan, mereka membawa kehidupan ke depan. Itu adalah keheningan dan kekuatan harapan. Terima kasih atas kesaksian Anda. […] Namun mengingat ibu dan nenek kita, saya ingin mengajak Anda untuk memerangi momok yang menimpa benua Amerika: banyaknya kasus pembunuhan terhadap perempuan. Dan banyaknya situasi kekerasan yang dirahasiakan di balik begitu banyak tembok. Saya meminta Anda untuk melawan sumber penderitaan ini dengan mengusahakan undang-undang dan budaya yang menolak segala bentuk kekerasan.”[87]
47. Gereja secara konsisten mengingatkan kita bahwa “martabat setiap manusia mempunyai karakter intrinsik dan berlaku sejak saat pembuahan hingga kematian alaminya. Penegasan martabat itulah yang merupakan prasyarat yang tidak dapat dicabut untuk melindungi keberadaan pribadi dan sosial, dan juga syarat yang diperlukan agar persaudaraan dan persahabatan sosial dapat terwujud di antara semua bangsa di bumi.”[88] Karenanya mengenai nilai tak berwujud dari kehidupan manusia, magisterium Gereja selalu menentang aborsi. Sehubungan dengan hal ini, Paus Santo Yohanes Paulus II menulis: “Di antara semua kejahatan yang dapat dilakukan terhadap kehidupan, aborsi yang dilakukan secara terencana memiliki karakteristik yang menjadikannya sangat serius dan menyedihkan. […] Namun saat ini, dalam hati nurani banyak orang, persepsi akan pentingnya hal ini semakin kabur. Diterimanya aborsi dalam pikiran masyarakat, dalam perilaku, dan bahkan dalam hukum itu sendiri merupakan tanda krisis moral yang sangat berbahaya, yang semakin tidak mampu membedakan antara yang baik dan yang jahat, bahkan ketika hak asasi manusia sudah tidak ada lagi nyawa sedang dipertaruhkan. Mengingat situasi yang begitu sulit, kita sekarang perlu lebih dari sebelumnya untuk memiliki keberanian untuk memandang kebenaran dan menganggap segala sesuatunya sesuai dengan namanya, tanpa menyerah pada kompromi atau godaan untuk menipu diri sendiri. Dalam hal ini, celaan Nabi sangat jelas: ‘Celakalah mereka yang menyebut kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang menjadikan kegelapan sebagai terang dan terang sebagai kegelapan’ (Yes. 5:20). Khususnya dalam kasus aborsi, terdapat banyak penggunaan terminologi yang ambigu, seperti ‘interupsi kehamilan’, yang cenderung menyembunyikan sifat sebenarnya dari aborsi dan melemahkan keseriusan aborsi dalam opini publik. Barangkali fenomena linguistik ini sendiri merupakan gejala kegelisahan hati nurani. Namun tidak ada kata yang mampu mengubah realitas yang ada: aborsi yang dilakukan adalah pembunuhan yang disengaja dan langsung, dengan cara apa pun dilakukan, terhadap seorang manusia pada tahap awal keberadaannya, mulai dari pembuahan hingga kelahiran. ”[89] Oleh karena itu, anak-anak yang belum lahir adalah “yang paling tidak berdaya dan tidak bersalah di antara kita. Saat ini, berbagai upaya dilakukan untuk mengabaikan martabat kemanusiaan mereka dan memperlakukan mereka sesuka hati, mengambil nyawa mereka dan mengeluarkan undang-undang yang mencegah siapa pun menghalangi hal ini.”[90] Oleh karena itu, harus dinyatakan dengan segala kekuatan dan kejelasan, bahkan di zaman kita, bahwa “pembelaan terhadap kehidupan yang belum dilahirkan ini terkait erat dengan pembelaan terhadap setiap hak asasi manusia lainnya. Hal ini mencakup keyakinan bahwa manusia selalu suci dan tidak dapat diganggu gugat, dalam situasi apa pun dan pada setiap tahap perkembangan. Manusia adalah tujuan dalam dirinya sendiri dan tidak pernah menjadi alat untuk menyelesaikan masalah lain. Ketika keyakinan ini hilang, maka landasan yang kokoh dan tahan lama bagi pembelaan hak asasi manusia pun akan hilang, yang akan selalu bergantung pada keinginan pihak-pihak yang berkuasa. Nalar saja sudah cukup untuk mengakui nilai yang tidak dapat diganggu gugat dari setiap kehidupan manusia, namun jika kita juga melihat permasalahan ini dari sudut pandang keimanan, ‘setiap pelanggaran terhadap martabat pribadi manusia merupakan bentuk balas dendam terhadap Allah dan merupakan sebuah serangan melawan Pencipta individu.’”[91] Dalam konteks ini, patut diingat kembali komitmen Santa Teresa dari Kalkuta yang murah hati dan berani untuk membela setiap orang yang ada dalam kandungan.
48. Gereja juga menentang praktik ibu pengganti, yang menjadikan anak yang sangat berharga hanya menjadi objek belaka. Dalam hal ini, kata-kata Paus Fransiskus memiliki kejelasan yang luar biasa: “Jalan menuju perdamaian menuntut penghormatan terhadap kehidupan, terhadap setiap kehidupan manusia, dimulai dengan kehidupan anak yang belum lahir dalam rahim ibu, yang tidak dapat ditekan atau diubah menjadi sebuah objek perdagangan. Dalam hal ini, saya memandang menyedihkan praktik yang disebut sebagai ibu pengganti, yang merupakan pelanggaran berat terhadap martabat perempuan dan anak, berdasarkan eksploitasi situasi kebutuhan materi ibu. Seorang anak selalu merupakan anugerah dan tidak pernah menjadi dasar kontrak komersial. Oleh karena itu, saya menyampaikan harapan saya terhadap upaya komunitas internasional untuk melarang praktik ini secara universal.”[92]
49. Yang pertama dan terpenting, praktik ibu pengganti melanggar martabat anak. Memang benar, setiap anak memiliki martabat tak berwujud yang diungkapkan dengan jelas—walaupun dengan cara yang unik dan berbeda—di setiap tahap kehidupannya: sejak saat pembuahan, saat lahir, tumbuh sebagai laki-laki atau perempuan, dan menjadi seorang dewasa. Karena martabat yang tidak dapat dicabut ini, anak mempunyai hak untuk mempunyai asal usul yang sepenuhnya manusiawi (dan bukan karena penyebab artifisial) dan untuk menerima anugerah kehidupan yang mewujudkan martabat pemberi dan penerima. Selain itu, mengakui martabat pribadi manusia juga berarti mengakui setiap dimensi martabat persatuan suami-istri dan martabat prokreasi manusia. Mengingat hal ini, keinginan sah untuk memiliki anak tidak dapat diubah menjadi “hak atas anak” yang tidak menghormati martabat anak tersebut sebagai penerima anugerah kehidupan.[93]
50. Ibu pengganti juga melanggar martabat perempuan, baik dia dipaksa atau memilih untuk tunduk secara bebas. Sebab, dalam praktik ini, perempuan terlepas dari anak yang tumbuh dalam dirinya dan hanya menjadi alat yang tunduk pada keuntungan atau keinginan sewenang-wenang orang lain. Hal ini bertentangan dengan martabat fundamental setiap umat manusia dan hak setiap orang untuk selalu diakui secara individu dan tidak pernah sebagai instrumen bagi orang lain.
Eutanasia dan Bunuh Diri dengan Bantuan
51. Terdapat kasus khusus pelanggaran martabat manusia yang lebih tenang namun dengan cepat meluas. Hal ini unik dalam cara mereka memanfaatkan pemahaman yang salah tentang martabat manusia untuk mengubah konsep martabat melawan kehidupan itu sendiri. Kebingungan ini terlihat jelas saat ini dalam diskusi seputar euthanasia. Misalnya, undang-undang yang memperbolehkan euthanasia atau bunuh diri dengan bantuan kadang-kadang disebut “kematian dengan tindakan yang bermartabat.” Oleh karena itu, terdapat anggapan luas bahwa euthanasia atau bunuh diri yang dibantu adalah hal yang konsisten dengan penghormatan terhadap martabat pribadi manusia. Namun, dalam menanggapi hal ini, harus ditegaskan kembali bahwa penderitaan tidak menyebabkan orang sakit kehilangan martabatnya, yang pada hakikatnya merupakan martabat mereka sendiri. Sebaliknya, penderitaan bisa menjadi kesempatan untuk memperkuat ikatan rasa saling memiliki dan memperoleh kesadaran yang lebih besar akan nilai berharga setiap orang bagi seluruh keluarga umat manusia.
52. Tentu saja, martabat mereka yang sakit kritis atau mematikan memerlukan segala upaya yang sesuai dan diperlukan untuk meringankan penderitaan mereka melalui perawatan paliatif yang tepat dan dengan menghindari perawatan yang agresif atau prosedur medis yang tidak proporsional. Pendekatan ini sejalan dengan “tanggung jawab abadi untuk menghargai kebutuhan orang yang sakit: kebutuhan perawatan, pereda nyeri, dan kebutuhan afektif dan spiritual.”[94] Namun, upaya seperti ini sama sekali berbeda dari—dan tentu saja bertentangan dengan pendekatan ini —keputusan untuk mengakhiri hidup sendiri atau orang lain yang terbebani oleh penderitaan. Sekalipun dalam keadaan yang menyedihkan, kehidupan manusia membawa martabat yang harus selalu dijunjung tinggi, tidak boleh hilang, dan menuntut penghormatan tanpa syarat. Sesungguhnya, tidak ada keadaan di mana kehidupan manusia tidak lagi bermartabat dan, sebagai akibatnya, dapat diakhiri: “Setiap kehidupan mempunyai nilai dan martabat yang sama bagi setiap orang: rasa hormat terhadap nyawa orang lain sama dengan rasa hormat terhadap nyawa sendiri.”[95] Oleh karena itu, membantu orang yang ingin bunuh diri untuk mengakhiri hidupnya merupakan pelanggaran objektif terhadap martabat orang yang memintanya, meskipun dengan melakukan hal tersebut keinginan orang tersebut akan terpenuhi. “Kita harus mendampingi orang-orang menuju kematian, namun tidak memprovokasi kematian atau memfasilitasi segala bentuk bunuh diri. Ingatlah bahwa hak atas perawatan dan pengobatan bagi semua orang harus selalu diutamakan agar pihak yang paling lemah, khususnya orang lanjut usia dan orang sakit, tidak pernah ditolak. Hidup adalah hak, bukan kematian, yang harus disambut, bukan dikelola. Dan prinsip etika ini menyangkut semua orang, bukan hanya umat Kristiani atau penganutnya.”[96] Seperti disebutkan di atas, martabat setiap orang, tidak peduli seberapa lemah atau terbebani oleh penderitaan, menyiratkan martabat kita semua.
Marginalisasi Penyandang Disabilitas
53. Salah satu kriteria untuk memverifikasi perhatian nyata yang diberikan terhadap martabat setiap individu dalam masyarakat adalah bantuan yang diberikan kepada kelompok yang paling tidak beruntung. Sayangnya, zaman kita tidak dikenal dengan perhatian seperti itu; sebaliknya, “budaya membuang” semakin menguat.[97] Untuk mengatasi tren tersebut, kondisi mereka yang mengalami keterbatasan fisik dan mental perlu mendapatkan perhatian khusus. Kondisi kerentanan akut seperti ini [98] —yang banyak disebutkan dalam Injil—menimbulkan pertanyaan universal tentang apa artinya menjadi manusia, terutama jika dimulai dari kondisi disabilitas atau kecacatan. Pertanyaan mengenai ketidaksempurnaan manusia juga membawa implikasi sosio-kultural yang jelas karena beberapa budaya cenderung meminggirkan atau bahkan menindas penyandang disabilitas, memperlakukan mereka sebagai “orang yang ditolak”. Namun kenyataannya setiap manusia, terlepas dari kelemahannya, menerima martabatnya karena ia dikehendaki dan dicintai oleh Allah. Oleh karena itu, segala upaya harus dilakukan untuk mendorong inklusi dan partisipasi aktif mereka yang terkena dampak kelemahan atau disabilitas dalam kehidupan bermasyarakat dan Gereja.[99]
54. Dalam perspektif yang lebih luas, harus diingat bahwa “kemurahan hati ini, yang merupakan jantung spiritual politik, selalu merupakan kasih yang utama yang ditunjukkan kepada mereka yang paling membutuhkan; hal ini mendasari semua yang kami lakukan atas nama mereka. […] ‘Untuk merawat mereka yang membutuhkan diperlukan kekuatan dan kelembutan, usaha, dan kemurahan hati di tengah pola pikir fungsionalis dan privatisasi yang mau tidak mau mengarah pada ‘budaya membuang’ […]. Hal ini mencakup pengambilan tanggung jawab atas situasi saat ini yang penuh dengan marginalisasi dan penderitaan, serta kemampuan untuk memberikan martabat padanya.’ Hal ini juga akan menginspirasi upaya yang intens untuk memastikan bahwa ‘segala sesuatu dilakukan untuk melindungi status dan martabat pribadi manusia.’”[100]
55. Gereja ingin, lebih dari segalanya, “menegaskan kembali bahwa setiap orang, apapun orientasi seksualnya, harus dihormati martabatnya dan diperlakukan dengan penuh pertimbangan, sementara ‘setiap tanda diskriminasi yang tidak adil’ harus dihindari dengan hati-hati, khususnya segala bentuk agresi dan kekerasan.”[101] Oleh karena itu, segala bentuk diskriminasi harus dikecam karena bertentangan dengan martabat manusia mengingat fakta bahwa, di beberapa tempat, tidak sedikit orang yang dipenjarakan, disiksa, dan bahkan dirampas hak hidupnya semata-mata karena orientasi seksual mereka.
56. Pada saat yang sama, Gereja menyoroti isu-isu kritis yang ada dalam teori gender. Dalam hal ini, Paus Fransiskus telah mengingatkan kita bahwa “jalan menuju perdamaian membutuhkan penghormatan terhadap hak asasi manusia, sesuai dengan rumusan sederhana namun jelas yang terkandung dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang ulang tahunnya yang ke tujuh puluh lima baru-baru ini kita rayakan. Prinsip-prinsip ini sudah jelas dan diterima secara umum. Sayangnya, dalam beberapa dekade terakhir, berbagai upaya telah dilakukan untuk memperkenalkan hak-hak baru yang tidak sepenuhnya konsisten dengan definisi awal dan tidak selalu dapat diterima. Hal ini telah menyebabkan terjadinya penjajahan ideologis, yang mana teori gender memainkan peran sentral; yang terakhir ini sangat berbahaya karena menghilangkan perbedaan dalam klaimnya untuk membuat semua orang setara.”[102]
57. Mengenai teori gender, yang keterpaduan ilmiahnya menjadi pokok perdebatan di kalangan para ahli, Gereja mengingatkan bahwa kehidupan manusia dalam segala dimensinya, baik jasmani maupun rohani, adalah anugerah dari Allah. Karunia ini harus diterima dengan rasa syukur dan digunakan untuk melayani kebaikan. Menginginkan penentuan nasib sendiri secara pribadi, sebagaimana ditegaskan dalam teori gender, terlepas dari kebenaran mendasar bahwa kehidupan manusia adalah sebuah anugerah, sama saja dengan menyerah pada godaan kuno untuk menjadikan diri sendiri sebagai Allah, memasuki persaingan dengan Allah kasih sejati yang diwahyukan kepada kita dalam Injil.
58. Aspek menonjol lainnya dari teori gender adalah bahwa teori ini bermaksud untuk menyangkal kemungkinan perbedaan terbesar yang ada di antara makhluk hidup: perbedaan seksual. Perbedaan mendasar ini bukan hanya perbedaan terbesar yang dapat dibayangkan, namun juga merupakan perbedaan yang paling indah dan paling kuat. Pada pasangan pria-wanita, perbedaan ini menghasilkan timbal balik yang paling menakjubkan. Hal demikian menjadi sumber keajaiban yang tak henti-hentinya membuat kita kagum: kedatangan manusia baru ke dunia.
59. Dalam hal ini, rasa hormat terhadap tubuh sendiri dan tubuh orang lain sangatlah penting mengingat semakin banyaknya klaim terhadap hak-hak baru yang dikemukakan oleh teori gender. Ideologi ini “membayangkan sebuah masyarakat tanpa perbedaan seksual, sehingga menghilangkan dasar antropologis keluarga.”[103] Oleh karena itu, menjadi tidak dapat diterima jika “beberapa ideologi semacam ini, yang berusaha menanggapi aspirasi yang kadang-kadang dapat dimengerti, berhasil menyatakan dirinya sebagai ideologi yang mutlak dan tidak dapat dipertanyakan, bahkan mendikte bagaimana anak-anak harus dibesarkan. Perlu ditekankan bahwa ‘seks biologis dan peran sosio-kultural dari seks (gender) dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan.”[104] Oleh karena itu, semua upaya untuk mengaburkan acuan terhadap perbedaan seksual, yang tidak dapat dihilangkan antara laki-laki dan perempuan, haruslah ditolak: “Kita tidak dapat memisahkan maskulin dan feminin dari karya penciptaan Allah, yang terjadi sebelum semua keputusan dan pengalaman kita, dan di mana terdapat unsur-unsur biologis yang tidak mungkin diabaikan.”[105] Hanya dengan mengakui dan menerima secara timbal balik perbedaan ini, setiap orang dapat sepenuhnya menemukan diri mereka sendiri, martabat mereka, dan identitas mereka.
60. Martabat suatu tubuh tidak dapat dianggap lebih rendah daripada martabat seseorang. Katekismus Gereja Katolik secara tegas mengajak kita untuk mengakui bahwa “tubuh manusia mempunyai martabat ‘gambar Allah’.”[106] Kebenaran seperti ini patut untuk diingat, terutama dalam hal perubahan jenis kelamin, karena manusia tidak dapat dipisahkan dari tubuh dan jiwa. Dalam hal ini, tubuh berfungsi sebagai konteks hidup di mana interioritas jiwa terungkap dan memanifestasikan dirinya, seperti halnya melalui jaringan hubungan antarmanusia. Sebagai wujud manusia, jiwa dan raga sama-sama ikut serta dalam harkat dan martabat yang menjadi ciri khas setiap manusia.[107] Terlebih lagi, tubuh ikut serta dalam martabat tersebut karena ia diberkahi dengan makna-makna pribadi, khususnya dalam kondisi gendernya.[108] Di dalam tubuhlah setiap orang mengenali dirinya sebagai yang dihasilkan oleh orang lain, dan melalui tubuh itulah laki-laki dan perempuan dapat membangun hubungan cinta yang mampu melahirkan orang lain. Untuk mengajarkan perlunya menghormati tatanan kodrat pribadi manusia, Paus Fransiskus menegaskan bahwa “ciptaan ada sebelum kita dan harus diterima sebagai anugerah. Pada saat yang sama, kita dipanggil untuk melindungi kemanusiaan kita, dan ini pertama-tama berarti menerimanya dan menghormati kemanusiaan sebagaimana ia diciptakan.”[109] Oleh karena itu, setiap intervensi perubahan jenis kelamin, pada umumnya, berisiko mengancam martabat unik yang diterima seseorang sejak saat pembuahan. Namun demikian tetap ada kemungkinan bahwa seseorang dengan kelainan genital yang sudah terlihat sejak lahir atau berkembang di kemudian hari dapat memilih untuk menerima bantuan profesional kesehatan untuk mengatasi kelainan tersebut. Namun, dalam kasus ini, prosedur medis tersebut bukan merupakan perubahan jenis kelamin sebagaimana dimaksud di sini.
61. Meskipun kemajuan teknologi digital menawarkan banyak kemungkinan untuk meningkatkan martabat manusia, namun kemajuan tersebut juga semakin cenderung mengarah pada terciptanya dunia di mana eksploitasi, pengucilan, dan kekerasan semakin meningkat, bahkan sampai pada titik yang merugikan martabat pribadi manusia. Misalnya, betapa mudahnya membahayakan nama baik seseorang dengan berita palsu dan fitnah melalui cara-cara tersebut. Dalam hal ini, Paus Fransiskus menekankan bahwa “tidaklah sehat jika kita mengacaukan komunikasi dengan sekadar kontak virtual. Sesungguhnya, lingkungan digital juga penuh dengan kesepian, manipulasi, eksploitasi, dan kekerasan, bahkan hingga kasus ekstrem ‘jaringan gelap’. Media digital dapat membuat orang terpapar pada risiko kecanduan, isolasi, dan kehilangan kontak secara bertahap dengan realitas konkret, menghalangi perkembangan hubungan interpersonal yang autentik. Bentuk-bentuk kekerasan baru menyebar melalui media sosial, misalnya cyberbullying (perundungan siber). Internet juga merupakan saluran untuk menyebarkan pornografi dan eksploitasi orang untuk tujuan seksual atau melalui perjudian’.”[110] Dengan cara ini, secara paradoks, semakin besar peluang untuk menjalin hubungan di dunia ini, semakin banyak orang yang merasa terisolasi dan miskin dalam hubungan interpersonal: “Komunikasi digital ingin mengungkapkan segalanya; kehidupan orang-orang disisir, ditelanjangi, dan diperbincangkan, sering kali tanpa nama. Rasa hormat terhadap orang lain akan hancur, dan bahkan ketika menghilangkan, mengabaikan, atau menjauhkan orang lain, kita tanpa malu-malu mengintip setiap detail kehidupan mereka.”[111] Kecenderungan seperti itu mewakili sisi gelap kemajuan digital.
62. Dalam perspektif ini, jika teknologi bertujuan untuk mengabdi pada martabat manusia dan tidak merugikannya, dan jika teknologi bertujuan untuk memajukan perdamaian dibandingkan kekerasan, maka komunitas manusia harus proaktif dalam mengatasi kecenderungan-kecenderungan ini sehubungan dengan martabat manusia dan promosi kebaikan: “Dalam dunia global saat ini, ‘media dapat membantu kita untuk merasa lebih dekat satu sama lain, menciptakan rasa persatuan sebagai keluarga umat manusia yang pada gilirannya dapat menginspirasi solidaritas dan upaya serius untuk menjamin kehidupan yang lebih bermartabat bagi semua orang. […] Media dapat sangat membantu kita dalam hal ini, terutama saat ini, ketika jaringan komunikasi manusia telah mencapai kemajuan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Internet, khususnya, menawarkan kemungkinan besar untuk perjumpaan dan solidaritas. Ini adalah sesuatu yang benar-benar baik, sebuah anugerah dari Allah.’ Kita perlu terus-menerus memastikan bahwa bentuk-bentuk komunikasi masa kini benar-benar membimbing kita menuju pertemuan yang penuh kemurahan hati dengan orang lain, pada pencarian kebenaran yang jujur, pada pelayanan, pada kedekatan dengan orang yang kurang mampu dan untuk memajukan kesejahteraan umum.”[112]
63. Pada peringatan 75 tahun diundangkannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948), Paus Fransiskus menegaskan kembali bahwa dokumen ini “seperti sebuah rencana induk, yang darinya banyak langkah telah diambil, namun banyak pula yang masih perlu dilakukan, dan sayangnya, terkadang ada langkah mundur yang diambil. Komitmen terhadap hak asasi manusia tidak pernah selesai! Dalam hal ini, saya bersama dengan semua orang yang, tanpa gembar-gembor, dalam kehidupan nyata sehari-hari, berjuang dan secara pribadi membayar harga untuk membela hak-hak mereka yang tidak diperhitungkan.”[113]
64. Dalam semangat ini, Gereja, melalui Deklarasi ini, dengan sungguh-sungguh mendesak agar penghormatan terhadap martabat pribadi manusia apapun keadaannya harus ditempatkan pada pusat komitmen terhadap kesejahteraan umum dan pada pusat setiap sistem hukum. Memang benar, penghormatan terhadap martabat setiap orang merupakan dasar yang sangat diperlukan bagi keberadaan masyarakat mana pun yang mengklaim diri mereka didasarkan pada hukum yang adil dan bukan pada kekuatan kekuasaan. Pengakuan martabat manusia merupakan dasar untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia, yang mendahului dan mendasari hidup berdampingan semua masyarakat sipil.[114]
65. Setiap individu dan juga setiap komunitas manusia bertanggung jawab atas perwujudan harkat dan martabat manusia yang konkret dan aktual. Sementara itu, negara mempunyai kewajiban untuk tidak hanya melindungi martabat manusia namun juga menjamin kondisi yang diperlukan agar dapat berkembang dalam upaya memajukan pribadi manusia secara integral: “Dalam kegiatan politik, kita harus ingat bahwa ‘meskipun terlihat seperti itu, setiap orang sangatlah suci dan layak mendapatkan cinta dan dedikasi kita.’”[115]
66. Bahkan saat ini, berhadapan dengan begitu banyak pelanggaran martabat manusia yang secara serius mengancam masa depan keluarga umat manusia, Gereja mendorong peningkatan martabat setiap pribadi manusia, tanpa memandang fisik, mental, budaya, sosial, dan karakteristik agama mereka. Gereja melakukan hal ini dengan harapan dan keyakinan akan kuasa yang mengalir dari Kristus yang Bangkit, yang telah sepenuhnya mengungkapkan martabat integral setiap pria dan wanita. Kepastian ini menjadi seruan dalam kata-kata Paus Fransiskus yang ditujukan kepada kita masing-masing: “Saya mengimbau semua orang di seluruh dunia untuk tidak melupakan martabat yang merupakan milik kita ini. Tak seorang pun berhak mengambilnya dari kita.”[116]
Paus Fransiskus, pada Audiensi yang diberikan kepada Prefek Dikasteri untuk Ajaran Iman yang bertanda-tangan di bawah ini, bersama Sekretaris Bagian Ajaran Dikasteri, pada tanggal 25 Maret 2024, menyetujui Deklarasi ini, yang diputuskan dalam Rapat Biasa Sidang Dikasteri ini pada tanggal 28 Februari 2024, dan beliau memerintahkan penerbitannya.
Diberikan di Roma, pada Dikasteri untuk Ajaran Iman, pada tanggal 2 April 2024, bertepatan dengan peringatan sembilan belas tahun wafatnya Paus St. Yohanes Paulus II.
Kardinal Víctor Manuel Fernandez
Prefek
Mgr. Armando Matteo
Sekretaris Bagian Ajaran
[1] Yohanes Paulus II, Angelus di Katedral Osnabrück (16 November 1980): Insegnamenti III/2 (1980), 1232.
[2] Fransiskus, Anjuran Apostolik Laudate Deum (4 Oktober 2023), no. 39: L’Osservatore Romano (4 Oktober 2023), III.
[3] Pada tahun 1948, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang terdiri dari tiga puluh pasal. Kata “martabat” muncul lima kali di sana, di tempat-tempat strategis: pada kata pertama Pembukaan dan pada kalimat pertama Pasal Satu. Martabat ini dinyatakan “melekat pada seluruh anggota keluarga umat manusia” (Pembukaan) dan “semua umat manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama” (Pasal 1).
[4] Dengan hanya memperhatikan era modern, kita melihat bagaimana Gereja semakin menekankan pentingnya martabat manusia. Tema ini khususnya dikembangkan dalam Ensiklik Rerum Novarum (1891) karya Paus Leo XIII, Ensiklik Quadragesimo Anno (1931) karya Paus Pius XI, dan Pidato Paus Pius XII di hadapan Kongres Persatuan Bidan Katolik Italia (1951). Konsili Vatikan Kedua kemudian mengembangkan isu ini, mendedikasikan seluruh dokumen untuk membahas masalah ini melalui Deklarasi Dignitatis Humanae (1965) dan membahas kebebasan manusia dalam Konstitusi Pastoral Gaudium et Spes (1965).
[5] Paulus VI, Audiensi Umum (4 September 1968): Insegnamenti VI (1968), 886.
[6] Yohanes Paulus II, Pidato pada Konferensi Umum Ketiga Keuskupan Amerika Latin (28 Januari 1979), III.1-2: Insegnamenti II/1 (1979), 202-203.
[7] Benediktus XVI, Pidato kepada Peserta Sidang Umum Akademi Kepausan untuk Kehidupan (13 Februari 2010): Insegnamenti VI/1 (2011), 218.
[8] Benediktus XVI, Pidato kepada Peserta Pertemuan Bank Pembangunan Dewan Eropa (12 Juni 2010): Insegnamenti VI/1 (2011), 912-913.
[9] Fransiskus, Anjuran Apostolik Evangelii Gaudium (24 November 2013), no. 178: AAS 105 (2013), 1094; mengutip Yohanes Paulus II, Angelus di Katedral Osnabrück (16 November 1980): Insegnamenti III/2 (1980), 1232.
[10] Fransiskus, Surat Ensiklik Fratelli Tutti (3 Oktober 2020), no. 8: AAS 112 (2020), 971.
[11] Ibid., no. 277: AAS 112 (2020), 1069.
[12] Ibid., no. 213: AAS 112 (2020), 1045.
[13] Ibid., no. 213: AAS 112 (2020), 1045; mengutip Id., Pesan kepada Peserta Konferensi Internasional “Human Rights in the Contemporary World: Achievements, Omissions, Negations” (10 Desember 2018): L’Osservatore Romano, (10-11 Desember 2018), 8.
[14] Deklarasi PBB tahun 1948 diikuti dan diuraikan lebih lanjut oleh Kovenan Internasional PBB tentang Hak-Hak Sipil dan Politik tahun 1966 dan Undang-Undang Akhir Konferensi Keamanan dan Kerja Sama di Eropa tahun 1975 di Helsinki.
[15] Lih. International Theological Commission, Dignity and Rights of the Human Person (1983), Pendahuluan, 3. Ringkasan ajaran Katolik tentang martabat manusia dapat ditemukan dalam Katekismus Gereja Katolik, dalam bab yang berjudul, “Martabat Pribadi Manusia, ” no. 1700-1876.
[16] Fransiskus, Surat Ensiklik Fratelli Tutti (3 Oktober 2020), no. 22: AAS 112 (2020), 976.
[17] Boethius, Contra Eutychen et Nestorium, kr. 3: PL 64, 1344: “persona est rasionalis naturae individua substantia.” Lih. Bonaventure, In I Sent., d. 25, a. 1, q. 2; Thomas Aquinas, Summa Theologiae I, q. 29, a. 1, resp.
[18] Karena Deklarasi ini tidak bertujuan untuk menyusun sebuah risalah yang lengkap mengenai pengertian martabat, maka demi singkatnya, hanya budaya Yunani dan Romawi klasik yang disebutkan di sini sebagai contoh, sebagai intinya. referensi untuk refleksi filosofis dan teologis Kristen awal.
[19] Misalnya, lihat Cicero, De Officiis I, 105-106: “Sed pertinet ad omnem officii quaestionem semper in promptu habere, quantum natura hominis pecudibus reliquisque beluis antecedat […] Atque etiam si thoughtare volumus, quae sit in natura Excellentia et dignitas, intellegemus, quam sit turpe diffluere luxuria et halus ac molliter vivere quamque kejujuranum parce, benua, parah, sobrie” (Id., Scriptorum Latinorum Bibliotheca Oxoniensis, ed. M. Winterbottom, Oxford 1994, 43). Dalam terjemahan bahasa Inggris: “Tetapi penting untuk setiap penyelidikan tentang tugas yang kita perhatikan seberapa jauh manusia lebih unggul secara alami dibandingkan ternak dan hewan lainnya […] Dan jika kita hanya mengingat superioritas dan martabat sifat kita , kita akan menyadari betapa salahnya membiarkan diri kita berlebihan dan hidup dalam kemewahan dan kegairahan, dan betapa benarnya hidup dalam penghematan, penyangkalan diri, kesederhanaan, dan ketenangan” (Id., On Duties, tr. W .Miller, Perpustakaan Klasik Loeb 30, Harvard University Press, Cambridge 1913, 107-109).
[20] Lih. Paulus VI, Pidato Ziarah ke Tanah Suci: Kunjungan ke Basilika Kabar Sukacita di Nazareth (5 Januari 1964): AAS 56 (1964), 166-170.
[21] Misalnya, Klemenn dari Roma, 1 Clem. 33, 4f: PG 1, 273; Theophilus dari Antiokia, Ad Aut. I, 4: PG 6, 1029; Klemen dari Alexandria, Strom. III, 42, 5-6: PG 8, 1145; Ibid., VI, 72, 2: PG 9, 293; Irenaeus dari Lyons, Adv. Haer. V, 6, 1: PG 7, 1137-1138; Origen, De princ. III, 6, 1: PG 11, 333; Augustine, De Gen. ad litt. VI, 12: PL 34, 348; De Trinitate XIV, 8, 11: PL 42, 1044-1045.
[22] Thomas Aquinas, Summa Theologiae, I, q. 29, a. 3, resp.: «persona significat id, quod est perfectissimum in tota natura, scilicet subsistens in rationali natura»
[23] Lih. Giovanni Pico della Mirandola dan teksnya yang terkenal, Orartio de Hominis Dignitate (1486).
[24] Bagi seorang pemikir Yahudi, seperti E. Levinas (1906-1995), manusia dikualifikasikan berdasarkan kebebasannya sejauh ia menemukan dirinya bertanggung jawab tanpa batas terhadap manusia lain.
[25] Beberapa pemikir besar Kristen pada abad kesembilan belas dan kedua puluh—seperti St. J.H. Newman, Bl. A. Rosmini, J. Maritain, E. Mounier, K. Rahner, H. U. von Balthasar, dan lain-lain—telah berhasil mengajukan visi tentang pribadi manusia yang secara valid dapat berdialog dengan seluruh arus pemikiran yang ada di awal abad ke-21. abad, apapun inspirasinya, bahkan Postmodernisme.
[26] Inilah sebabnya mengapa “Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia […] secara implisit menyatakan bahwa sumber hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut terletak pada martabat setiap pribadi manusia” (Komisi Teologi Internasional, In Search of a Universal Ethics: A New Look at the Natural Law [2009], no.115)
[27] Konsili Ekumenis Vatikan Kedua, Konstitusi Pastoral Gaudium et Spes (7 Desember 1965), no. 26: AAS 58 (1966), 1046. Seluruh bab pertama dari bagian pertama Konstitusi Pastoral (nos. 11-22) dikhususkan untuk “Martabat Pribadi Manusia.”
[28] Konsili Ekumenis Vatikan Kedua, Deklarasi Dignitatis Humanae (7 Desember 1965), no. 1: AAS 58 (1966), 929
[29] Ibid., no. 2: AAS 58 (1966), 931
[30] Lih. Kongregasi Ajaran Iman, Instruksi Dignitas Personae (8 September 2008), no. 7: AAS 100 (2008), 863. Bdk. juga Irenaeus dari Lyons, Adv. Haer. V, 16, 2: PG 7, 1167-1168
[31] Karena “melalui Inkarnasi-Nya, Putra Allah telah menyatukan diri-Nya dengan cara tertentu dengan setiap manusia,” martabat setiap manusia diungkapkan kepada kita oleh Kristus dalam kepenuhannya (Konsili Ekumenis Vatikan Kedua, Konstitusi Pastoral Gaudium et Spes (7 Desember 1965), no.22: AAS 58 [1966], 1042)
[32] Konsili Ekumenis Vatikan Kedua, Konstitusi Pastoral Gaudium et Spes (7 Desember 1965), no. 19: AAS 58 (1966), 1038.
[33] Yohanes Paulus II, Surat Ensiklik Evangelium Vitae (25 Maret 1995), no. 38: AAS 87 (1995), 443, mengutip Irenaeus dari Lyons, Adv. Haer. IV, 20, 7: PG 7, 1037-1038.
[34] Memang benar, Kristus telah memberikan martabat baru kepada mereka yang dibaptis, yaitu menjadi “anak-anak Allah”: lih. Katekismus Gereja Katolik, no. 1213, 1265, 1270, 1279.
[35] Konsili Ekumenis Vatikan Kedua, Deklarasi Dignitatis Humanae (7 Desember 1965), no. 9: AAS 58 (1966), 935.
[36] Lih. Irenaeus dari Lyons, Adv. Haer. V, 6, 1.V, 8, 1.V, 16, 2: PG 7, 1136-1138. 1141-1142. 1167-1168; John Damaskus, De fide orth. 2, 12: PG 94, 917-930.
[37] Benediktus XVI, Pidato di Westminster Hall (17 September 2010): Insegnamenti VI/2 (2011), 240.
[38] Fransiskus, Audiensi Umum (12 Agustus 2020): L’Osservatore Romano (13 Agustus 2020), 8; mengutip Yohanes Paulus II, Pidato pada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (2 Oktober 1979), 7 dan Id., Pidato pada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (5 Oktober 1995), 2.
[39] Lih. Kongregasi Ajaran Iman, Instruksi Dignitas Personae (8 September 2008), no. 8: AAS 100 (2008), 863-864.
[40] Komisi Teologi Internasional, Kebebasan Beragama untuk Kebaikan Semua (2019), no. 38.
[41] Lih. Fransiskus, Pidato kepada Anggota Korps Diplomatik yang Terakreditasi Tahta Suci untuk Penyampaian Ucapan Selamat Tahun Baru (8 Januari 2024): L’Osservatore Romano (8 Januari 2024), 3.
[42] Yohanes Paulus II, Surat Ensiklik Evangelium Vitae (25 Maret 1995), no. 19: AAS 87 (1995), 422.
[43] Fransiskus, Surat Ensiklik Laudato Si’ (24 Mei 2015), no. 69: AAS 107 (2015), 875; mengutip Katekismus Gereja Katolik, no. 339.
[44] Fransiskus, Anjuran Apostolik Laudate Deum (4 Oktober 2023), no. 67: L’Osservatore Romano (4 Oktober 2023), IV.
[45] Ibid., tidak. 63: L’Osservatore Romano (4 Oktober 2023), IV.
[46] Katekismus Gereja Katolik, no. 1730.
[47] Benediktus XVI, Pesan untuk Perayaan Hari Perdamaian Sedunia ke-44 (1 Januari 2011), no. 3: Insegnamenti VI/2 (2011), 979.
[48] Dewan Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian, Ringkasan Ajaran Sosial Gereja, no. 137.
[49] Fransiskus, Surat Ensiklik Fratelli Tutti (3 Oktober 2020), no. 109: AAS 112 (2020), 1006.
[50] Dewan Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian, Ringkasan Ajaran Sosial Gereja, no. 137.
[51] Fransiskus, Pidato kepada Peserta Pertemuan Gerakan Populer Sedunia (28 Oktober 2014): AAS 106 (2014), 858.
[52] Fransiskus, Surat Ensiklik Fratelli Tutti (3 Oktober 2020), no. 107: AAS 112 (2020), 1005-1006.
[53] Konsili Ekumenis Vatikan Kedua, Konstitusi Pastoral Gaudium et Spes (7 Desember 1965), no. 27: AAS 58 (1966), 1047.
[54] Ibid.
[55] Ibid.
[56] Bdk. Katekismus Gereja Katolik, no. 2267, dan Kongregasi Ajaran Iman, Surat kepada Para Uskup Mengenai Revisi Baru Nomor 2267 Katekismus Gereja Katolik tentang Hukuman Mati (1 Agustus 2018), nos. 7-8.
[57] Fransiskus, Surat Ensiklik Fratelli Tutti (3 Oktober 2020), no. 269: AAS 112 (2020), 1065.
[58] Yohanes Paulus II, Surat Ensiklik Sollicitudo Rei Socialis (30 Desember 1987), no. 28: AAS 80 (1988), 549.
[59] Benediktus XVI, Surat Ensiklik Caritas in Veritate (29 Juni 2009), no. 22: AAS 101 (2009), 657, mengutip Paulus VI, Surat Ensiklik Populorum Progressio (26 Maret 1967), no. 9: AAS 59 (1967), 261-262.
[60] Fransiskus, Surat Ensiklik Fratelli Tutti (3 Oktober 2020), no. 21: AAS 112 (2020), 976; mengutip Benediktus XVI, Surat Ensiklik Caritas in Veritate (29 Juni 2009), no. 22: AAS 101 (2009), 657.
[61] Fransiskus, Surat Ensiklik Fratelli Tutti (3 Oktober 2020), no. 20: AAS 112 (2020), 975-976. Lih. juga “Doa kepada Sang Pencipta” di akhir ensiklik ini.
[62] Ibid., no. 116: AAS 112 (2020), 1009; mengutip Paus Fransiskus, Pidato kepada Peserta Pertemuan Gerakan Populer Sedunia (28 Oktober 2014): AAS 106 (2014), 851-852.
[63] Fransiskus, Surat Ensiklik Fratelli Tutti (3 Oktober 2020), no. 162: AAS 112 (2020), 1025; mengutip Paus Fransiskus, Pidato kepada Anggota Korps Diplomatik yang Terakreditasi Takhta Suci (12 Januari 2015): AAS 107 (2015), 165.
[64] Fransiskus, Surat Ensiklik Fratelli Tutti (3 Oktober 2020), no. 25: AAS 112 (2020), 978; mengutip Fransiskus, Pesan untuk Hari Perdamaian Sedunia 2016 (1 Januari 2016): AAS 108 (2016), 49.
[65] Fransiskus, Pesan kepada Peserta “Forum de Paris sur la Paix” Edisi Keenam (10 November 2023): L’Osservatore Romano (10 November 2023), 7; mengutip Id., Audiensi Umum (23 Maret 2022): L’Osservatore Romano (23 Maret 2022), 3.
[66] Paus Fransiskus, Pidato pada Konferensi Para Pihak pada Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (COP 28) (2 Desember 2023): L’Osservatore Romano (2 Desember 2023), 2.
[67] Lih. Paulus VI, Pidato di PBB (4 Oktober 1965): AAS 57 (1965), 881.
[68] Yohanes Paulus II, Surat Ensiklik Redemptor Hominis (4 Maret 1979), no. 16: AAS 71 (1979), 295.
[69] Fransiskus, Surat Ensiklik Fratelli Tutti (3 Oktober 2020), no. 258: AAS 112 (2020), 1061.
[70] Paus Fransiskus, Pidato kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (14 Juni 2023): L’Osservatore Romano (15 Juni 2023), 8.
[71] Fransiskus, Pidato pada Hari Doa Sedunia untuk Perdamaian (20 September 2016): L’Osservatore Romano (22 September 2016), 5.
[72] Lih. Fransiskus, Surat Ensiklik Fratelli Tutti (3 Oktober 2020), no. 38: AAS 112 (2020), 983: “Oleh karena itu, ‘ada juga kebutuhan untuk menegaskan kembali hak untuk tidak beremigrasi, yaitu untuk tetap tinggal di tanah air seseorang’”; mengutip Benediktus XVI, Pesan untuk Hari Migran dan Pengungsi Sedunia ke-99 (12 Oktober 2012): AAS 104 (2012), 908.
[73] Lih. Fransiskus, Surat Ensiklik Fratelli Tutti (3 Oktober 2020), no. 38: AAS 112 (2020), 982-983.
[74] Ibid., no. 39: AAS 112 (2020), 983.
[75] Benediktus XVI, Surat Ensiklik Caritas in Veritate (29 Juni 2009), no. 62: AAS 101 (2009), 697.
[76] Fransiskus, Surat Ensiklik Fratelli Tutti (3 Oktober 2020), no. 39: AAS 112 (2020), 983.
[77] Di sini kita dapat mengingat deklarasi Paus Paulus III tentang martabat orang-orang yang ditemukan di negeri-negeri “Dunia Baru” dalam Bulla Pastorale Officium (29 Mei 1537), yang mana Bapa Suci menetapkan—dengan hukuman ekskomunikasi—bahwa penduduk wilayah tersebut, “meskipun berada di luar Gereja, tidak boleh […] dirampas kebebasannya atau kepemilikan harta bendanya, karena mereka adalah laki-laki dan, oleh karena itu, mampu beriman dan keselamatan” ( «licet extra gremium Ecclesiae ada, non tamen sua libertate, aut rerum suarum dominio […] privandos esse, et cum homines, ideoque fidei et salutis capaces sint»): DH 1495.
[78] Fransiskus, Pidato kepada Peserta Pleno Dewan Kepausan untuk Pelayanan Pastoral Migran dan Perantau (24 Mei 2013): AAS 105 (2013), 470-471.
[79] Fransiskus, Pidato kepada Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York (25 September 2015): AAS 107 (2015), 1039.
[80] Fransiskus, Pidato kepada Duta Besar Baru untuk Takhta Suci pada Acara Penyerahan Surat Kepercayaan (12 Desember 2013): L’Osservatore Romano (13 Desember 2013), 8.
[81] Fransiskus, Pidato kepada Peserta Konferensi Internasional tentang Perdagangan Manusia (11 April 2019): AAS 111 (2019), 700.
[82] Sidang Umum Biasa Sinode Para Uskup XV, Dokumen Akhir (27 Oktober 2018), no. 29.
[83] Fransiskus, Surat Ensiklik Fratelli Tutti (3 Oktober 2020), no. 23: AAS 112 (2020), 977, mengutip Fransiskus, Anjuran Apostolik Evangelii Gaudium (24 November 2013), no. 212: AAS 105 (2013), 1108.
[84] Yohanes Paulus II, Surat kepada Wanita (29 Juni 1995), no. 4: Insegnamenti XVIII/1 (1997), 1874.
[85] Ibid., no. 5: Insegnamenti XVIII/1 (1997), 1875.
[86] Katekismus Gereja Katolik, no. 1645.
[87] Fransiskus, Pidato pada Perayaan Maria – Bunda Maria dari Gerbang Fajar (20 Januari 2018): AAS 110 (2018), 329.
[88] Fransiskus, Pidato kepada Para Peserta Sidang Pleno Kongregasi Ajaran Iman (21 Januari 2022): L’Osservatore Romano (21 Januari 2022), 8.
[89] Yohanes Paulus II, Surat Ensiklik Evangelium Vitae (25 Maret 1995), no. 58: AAS 87 (1995) 466-467. Mengenai penghormatan terhadap embrio manusia, lihat Kongregasi Ajaran Iman, Instruksi Donum Vitae (22 Februari 1987): “Praktik menjaga embrio manusia tetap hidup secara in vivo atau in vitro untuk tujuan percobaan atau komersial sangat ditentang demi martabat manusia” (I, 4): AAS 80 (1988), 82.
[90] Fransiskus, Anjuran Apostolik Evangelii Gaudium (24 November 2013), no. 213: AAS 105 (2013), 1108.
[91] Ibid.
[92] Fransiskus, Pidato kepada Anggota Korps Diplomatik yang Terakreditasi Takhta Suci (8 Januari 2024): L’Osservatore Romano (8 Januari 2024), 3.
[93] Lih. Kongregasi Ajaran Iman, Instruksi Dignitas Personae (8 September 2008), no. 16: AAS 100 (2008), 868-869. Semua aspek ini diingat dalam Instruksi Donum Vitae Kongregasi saat itu (22 Februari 1987): AAS 80 (1988), 71-102.
[94] Kongregasi Ajaran Iman, Surat Samaritanus Bonus (14 Juli 2020), V, no. 4: AAS 112 (2020), 925
[95] Bdk. Ibid., V, no. 1: AAS 112 (2020), 919.
[96] Fransiskus, Audiensi Umum (9 Februari 2022): L’Osservatore Romano (9 Februari 2022), 3.
[97] Lihat khususnya Fransiskus, Surat Ensiklik Fratelli Tutti (3 Oktober 2020), no. 18-21: AAS 112 (2020), 975-976: “Dunia yang ‘Sekali Pakai’.” 188 dari Ensiklik yang sama bahkan lebih jauh lagi mengidentifikasi “budaya membuang”.
[98] Bdk. Fransiskus, Pidato kepada Peserta Konferensi yang Diselenggarakan oleh Dewan Kepausan untuk Mempromosikan Evangelisasi Baru (21 Oktober 2017): L’Osservatore Romano (22 Oktober 2017), 8: “Kerentanan merupakan hal yang intrinsik dalam hakikat esensial pribadi manusia.”
[99] Lih. Fransiskus, Pesan untuk Hari Penyandang Disabilitas Internasional (3 Desember 2020): AAS 112 (2020), 1185-1188.
[100] Fransiskus, Surat Ensiklik Fratelli Tutti (3 Oktober 2020), no. 187-188: AAS 112 (2020), 1035-1036; lih. Id., Pidato kepada Parlemen Eropa, Strasbourg (25 November 2014): AAS 106 (2014), 999, dan Id., Pidato pada Pertemuan dengan Pihak Berwenang dan Korps Diplomatik di Republik Afrika Tengah, Bangui (29 November 2015) : AAS 107 (2015), 1320.
[101] Fransiskus, Anjuran Apostolik Pasca Sinode Amoris Laetitia (19 Maret 2016), no. 250: AAS 108 (2016), 412-413; mengutip Katekismus Gereja Katolik, no. 2358.
[102] Fransiskus, Pidato kepada Anggota Korps Diplomatik yang Terakreditasi Takhta Suci untuk Penyampaian Ucapan Selamat Tahun Baru (8 Januari 2024): L’Osservatore Romano (8 Januari 2024), 3.
[103] Fransiskus, Anjuran Apostolik Amoris Laetitia (19 Maret 2016), no. 56: AAS 108 (2016), 334.
[104] Ibid.; mengutip Sidang Umum Biasa Keempat Belas Sinode Para Uskup, Relatio Finalis (24 Oktober 2015), 58.
[105] Ibid., tidak. 286: AAS 108 (2016), 425.
[106] Katekismus Gereja Katolik, no. 364.
[107] Hal ini juga berlaku pada penghormatan terhadap jenazah orang yang meninggal; misalnya, lihat Kongregasi Ajaran Iman, Instruksi Ad Resurgendum cum Christo (15 Agustus 2016), no. 3: AAS 108 (2016), 1290: “Dengan menguburkan jenazah umat beriman, Gereja meneguhkan imannya akan kebangkitan tubuh, dan bermaksud untuk menunjukkan martabat agung tubuh manusia sebagai bagian integral dari pribadi manusia. yang tubuhnya merupakan bagian dari identitas mereka.” Secara lebih umum, lihat juga International Theological Commission, Current Problems of Eschatology (1990), no. 5: “Orang-orang yang Dipanggil untuk Kebangkitan.”
[108] Lih. Fransiskus, Surat Ensiklik Laudato si’ (24 Mei 2015), no. 155: AAS 107 (2015), 909.
[109] Fransiskus, Anjuran Apostolik Amoris Laetitia (19 Maret 2016), no. 56: AAS 108 (2016), 344.
[110] Fransiskus, Anjuran Apostolik Pasca Sinode Christus Vivit (25 Maret 2019), no. 88: AAS 111 (2019), 413, mengutip Sidang Umum Biasa XV Sinode Para Uskup, Dokumen Akhir (27 Oktober 2018), no. 23.
[111] Fransiskus, Surat Ensiklik Fratelli Tutti (3 Oktober 2020), no. 42: AAS 112 (2020), 984.
[112] Fransiskus, Surat Ensiklik Fratelli Tutti (3 Oktober 2020), no. 205: AAS 112 (2020), 1042; mengutip Id., Pesan Hari Komunikasi Sedunia ke-48 (24 Januari 2014): AAS 106 (2014), 113.
[113] Fransiskus, Angelus (10 Desember 2023): L’Osservatore Romano (11 Desember 2023), 12.
[114] Lih. Komisi Teologi Internasional, Proposisi tentang Martabat dan Hak Pribadi Manusia (1983), no. 2.
[115] Fransiskus, Surat Ensiklik Fratelli Tutti (3 Oktober 2020), no. 195: AAS 112 (2020), 1038, mengutip Id., Anjuran Apostolik Evangelii Gaudium (24 November 2013), no. 274: AAS 105 (2013), 1130.
[116] Fransiskus, Surat Ensiklik Laudato si’ (24 Mei 2015), no. 205: AAS 107 (2015), 928