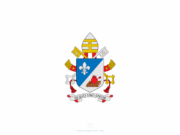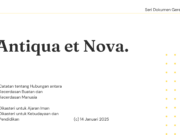| Judul | FRATELLI TUTTI — Saudara Sekalian |
| Deskripsi | Ensiklik Paus Fransiskus tentang Persaudaraan dan Persahabatan Sosial. |
| Tanggal Terbit | 3 Oktober 2020 |
| Harga | Rp 35.000,- |
| Tebal Buku | 178 halaman |
| Ukuran Buku | 15 x 22 cm |
FRATELLI TUTTI
ENSIKLIK PAUS FRANSISKUS
TENTANG PERSAUDARAAN DAN PERSAHABATAN SOSIAL
1. “Fratelli tutti.”[1] Dengan kata-kata itu Santo Fransiskus dari Asisi menyapa semua saudara dan saudarinya dan menawarkan kepada mereka cara hidup yang memiliki cita rasa Injil. Di antara petuah-petuahnya, saya ingin menyoroti satu yang dengannya ia mengundang orang kepada cinta kasih yang melampaui batas-batas geografis dan jarak jauh. Di sini Fransiskus menyatakan berbahagialah orang yang mengasihi saudaranya “ketika ia berada jauh darinya, sama seperti kalau saudara itu berada di sampingnya.”[2] Dengan kata-kata singkat dan sederhana itu ia menjelaskan hakikat persaudaraan yang terbuka dan yang memungkinkan kita untuk mengakui, menghargai, dan mengasihi setiap orang, terlepas dari kedekatan fisiknya, terlepas dari tempat mereka dilahirkan atau tinggal.
2. Orang kudus yang ditandai kasih persaudaraan, kesederhanaan, dan sukacita ini telah mengilhami saya untuk menulis Ensiklik Laudato Si´. Sekali lagi ia mendorong saya untuk mempersembahkan Ensiklik baru ini tentang persaudaraan dan persahabatan sosial. Kenyataannya, Santo Fransiskus yang merasa diri sebagai saudara matahari, laut, dan angin, tahu bahwa ia lebih bersatu lagi dengan mereka yang sedaging dengan dirinya. Di mana-mana ia menabur kedamaian dan berjalan bersama mereka yang miskin, yang diabaikan, yang sakit, yang tersingkir, yang paling hina.
Tanpa batas
3. Ada sebuah episode dalam hidup Santo Fransiskus yang menunjukkan kepada kita hatinya yang tidak mengenal batas-batas, yang mampu melampaui perbedaan-perbedaan asal-usul, kebangsaan, warna kulit, atau agama. Itu adalah kunjungannya kepada Sultan Malik-el-Kamil di Mesir, kunjungan yang menuntut usaha besar darinya mengingat kemiskinannya, sumber dayanya yang minim, jarak yang jauh, dan perbedaan bahasa, budaya, dan agama. Perjalanan ini, yang dalam saat sejarah ditandai dengan Perang Salib, lebih jauh menunjukkan keagungan kasih yang ingin ia hayati dalam keinginan untuk merangkul semua orang. Kesetiaan Fransiskus kepada Tuhannya sebanding dengan kasihnya kepada para saudara dan saudarinya. Tanpa mengabaikan aneka kesulitan dan bahaya, Santo Fransiskus pergi menemui Sultan dengan sikap yang sama yang ia tuntut dari pengikut-pengikutnya: mereka yang, tanpa menyangkal identitas mereka sendiri, “mau pergi ke tengah kaum muslim dan orang tak beriman, hendaknya […] tidak menimbulkan perselisihan dan pertengkaran, tetapi hendaklah mereka tunduk kepada setiap makhluk insani karena Allah.”[3] Dalam konteks saat itu, ini adalah permintaan luar biasa. Sungguh mengejutkan kita bahwa delapan ratus tahun lalu Santo Fransiskus menyarankan untuk menghindari segala bentuk “perselisihan dan pertengkaran” dan untuk menghidupi “ketundukan” yang rendah hati dan penuh persaudaraan, juga terhadap mereka yang tidak seiman.
4. Fransiskus tidak mengobarkan perang kata-kata untuk memaksakan ajarannya, tetapi menyebarkan kasih Allah. Ia memahami bahwa “Allah adalah kasih, dan barangsiapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia” (1Yoh. 4:16). Dengan cara ini dia menjadi seorang bapa yang berhasil membangkitkan impian tentang suatu masyarakat yang bersaudara, karena “hanya seorang yang mau mendekati orang-orang lain dalam gerakan mereka sendiri, bukan untuk mempertahankan mereka bagi dirinya, tetapi untuk membantu mereka semakin menjadi diri mereka sendiri, dia benar-benar seorang bapa.”[4] Di dunia yang saat itu penuh dengan menara pengawas dan tembok pertahanan, kota-kota mengalami peperangan berdarah antara keluarga-keluarga yang kuat, sementara tumbuh kawasan-kawasan kumuh di daerah pinggiran kota yang terkucilkan. Di situ Fransiskus menerima kedamaian sejati dalam dirinya, membebaskan dirinya dari setiap keinginan untuk menguasai orang lain, menjadikan dirinya salah seorang dariyang terkecil dan berusaha untuk hidup harmonis dengan semua orang. Fransiskus telah mengilhami halaman-halaman ini.
5. Masalah-masalah yang terkait dengan persaudaraan dan persahabatan sosial sudah selalu menjadi perhatian saya. Selama beberapa tahun terakhir, saya telah membicarakannya berulang kali dan di berbagai tempat. Dalam Ensiklik ini, saya ingin mengumpulkan banyak dari pernyataan itu dengan menempatkannya dalam konteks refleksi yang lebih luas. Selain itu, bilamana dalam penulisan Laudato Si’, saya telah menemukan sumber inspirasi pada saudaraku Bartolomeus, Patriarkh Ortodoks, yang sangat gencar menganjurkan pemeliharaan alam ciptaan, dalam penulisan Ensiklik baru ini saya merasa didorong secara khusus oleh Iman Besar Ahmad Al-Tayyeb yang saya temui di Abu Dhabi untuk mengingat bahwa Allah “menciptakan semua manusia setara dalam hak, kewajiban, dan martabat, dan memanggil mereka untuk hidup berdampingan sebagai saudara dan saudari.”[5] Ini bukan sekadar tindakan diplomatik, tetapi merupakan refleksi yang lahir dari dialog dan komitmen bersama. Ensiklik ini mengumpulkan dan mengembangkan beberapa tema penting yang dibahas dalam Dokumen yang kami tandatangani bersama. Saya juga telah memasukkan di sini, dengan gaya bahasa saya sendiri, banyak dokumen dan surat yang telah saya terima dari banyak orang dan kelompok di seluruh dunia.
6. Halaman-halaman berikut tidak berpretensi merangkum ajaran tentang kasih persaudaraan, tetapi lebih berfokus pada dimensi universal, pada keterbukaannya kepada semua manusia. Saya menawarkan Ensiklik sosial ini sebagai sumbangan sederhana untuk refleksi, agar di hadapan pelbagai cara sekarang ini untuk menyingkirkan atau mengabaikan orang lain, kita mampu menanggapinya dengan mimpi baru tentang persaudaraan dan persahabatan sosial yang tidak terbatas pada kata-kata. Meskipun saya menulisnya berangkat dari keyakinan Kristiani yang mengilhami dan memelihara saya, saya telah berusaha melakukannya sedemikian rupa sehingga refleksi ini terbuka untuk dialog dengan semua orang yang berkehendak baik.
7. Tepat ketika saya sedang menulis Ensiklik ini, tiba-tiba meledaklah pandemi Covid-19 dan membongkar kepastian-kepastian palsu kita. Terlepas dari berbagai tanggapan yang diberikan oleh berbagai negara, telah tampak nyata ketidakmampuan untuk bertindak bersama. Meskipun negara-negara sangat terhubung, terjadi perpecahan yang membuatnya lebih sulit untuk menyelesaikan masalah-masalah yang melanda kita semua. Jika orang berpikir bahwa itu hanyalah soal membuat apa yang sudah kita lakukan berjalan dengan lebih baik, atau bahwa satu-satunya pesan adalah bahwa kita harus memperbaiki berbagai sistem dan peraturan yang sudah ada, mereka sedang mengingkari kenyataan.
8. Saya berkeinginan kuat agar, di zaman hidup kita ini, dengan mengakui martabat setiap pribadi manusia, kita dapat menghidupkan kembali di antara kita semua aspirasi universal akan persaudaraan. Di antara kita semua! “Ini adalah rahasia sangat indah untuk bermimpi dan menjadikan hidup kita sebagai petualangan yang indah. Tak seorang pun dapat menghadapi hidup dalam pengasingan […] Kita membutuhkan komunitas yang mendukung dan membantu kita, di mana kita dapat saling membantu untuk terus melihat ke depan. Betapa pentingnya bermimpi bersama […] Sendirian, kita berisiko melihat fatamorgana, melihat apa yang tidak ada. Mimpi dibangun bersama.”[6] Marilah kita bermimpi sebagai satu umat manusia, sebagai sesama pengembara yang memiliki raga manusiawi yang sama, sebagai anak-anak dari bumi yang sama yang menjadi tempat tinggal kita semua, masing-masing dengan kekayaan iman dan keyakinannya, masing-masing dengan suaranya sendiri, semuanya saudara dan saudari.
BAB SATU
BAYANG-BAYANG GELAP DUNIA YANG TERTUTUP
9. Tanpa mengklaim melakukan analisis yang lengkap atau mempertimbangkan semua aspek realitas kehidupan kita, saya hanya mengusulkan untuk memusatkan perhatian kita pada beberapa tren di dunia saat ini yang menghambat perkembangan persaudaraan universal.
Impian-impian yang hancur
10. Selama beberapa dekade, tampaknya dunia telah belajar dari banyak peperangan dan kegagalan, dan perlahan-lahan bergerak menuju berbagai bentuk integrasi. Misalnya, telah berkembang impian Eropa yang bersatu, yang mampu mengakui akar-akar kebersamaannya dan bersukacita atas keberagaman yang ada di situ. Mari kita ingat “keyakinan teguh para pendiri Uni Eropa, yang menginginkan masa depan berdasarkan kemampuan kerja sama untuk mengatasi perpecahan dan mendorong perdamaian dan persekutuan antara semua bangsa di benua ini.”[7] Demikian pula, aspirasi untuk integrasi Amerika Latin semakin kuat dan beberapa langkah telah mulai diambil. Di beberapa negara dan wilayah lain pun telah muncul upaya-upaya menuju pendamaian dan pendekatan yang telah membuahkan hasil; dan ada upaya-upaya lainnya yang tampak menjanjikan.
11. Tapi sejarah saat ini sedang memperlihatkan tanda-tanda kemunduran. Konflik-konflik lama yang dianggap sudah diatasi tersulut kembali, dan membangkitkan kembali nasionalisme yang tertutup, penuh kemarahan, kekesalan, dan agresif. Di beberapa negara, suatu paham kesatuan bangsa dan negara yang dipengaruhi oleh pelbagai ideologi menciptakan bentuk-bentuk baru keegoisan dan hilangnya rasa sosial yang berkedok membela kepentingan-kepentingan nasional. Ini mengingatkan kita bahwa “setiap generasi harus menjadikan perjuangan dan pencapaian generasi sebelumnya sebagai miliknya dan membawanya kepada tujuan yang lebih tinggi. Itulah jalannya. Kebaikan, demikian juga kasih, keadilan, dan solidaritas, tidak dicapai sekali untuk selamanya; tetapi harus dimenangkan kembali setiap hari. Tidak mungkin untuk berpuas diri dengan apa yang telah dicapai di masa lampaudanberhenti, lalu menikmatinya, seolah-olah situasi itu membuat kita mengabaikan bahwa banyak saudara kita masih menderita situasi ketidakadilan yang menantang kita semua.[8]
12. “Membuka diri terhadap dunia” adalah ungkapan yang saat ini digunakan oleh bidang ekonomi dan keuangan. Ini merujuk secara eksklusif kepada keterbukaan terhadap kepentingan asing atau kebebasan bagi kekuatan-kekuatan ekonomi untuk berinvestasi tanpa hambatan atau kesulitan di semua negara. Konflik-konflik lokal dan kurangnya perhatian pada kebaikan bersama dimanfaatkan oleh ekonomi global untuk memaksakan model budaya tunggal. Budaya ini menyatukan dunia, tetapi memecah-belah pribadi-pribadi dan bangsa-bangsa, karena “masyarakat yang semakin mengglobal membuat kita lebih dekat, tetapi tidak membuat kita bersaudara.”[9] Lebih daripada sebelumnya, kita semakin sendirian dalam dunia yang diseragamkan yang mendukung kepentingan individu, dan melemahkan dimensi komunal keberadaan kita. Sebaliknya, ada peningkatanpasar di mana manusia berperan sebagai konsumen atau penonton. Kemajuan globalisme ini biasanya mendukung identitas mereka yang terkuat yang dapat melindungi dirinya sendiri, tetapi berupaya mengaburkan identitas wilayah-wilayah yang lebih lemah dan miskin, dengan membuatnya lebih rapuh dan bergantung. Dengan demikian, politik semakin rapuh berhadapan dengan kekuatan-kekuatan ekonomi transnasional yang menerapkan prinsip “bagilah dan kuasai (divide et impera).”
Akhir kesadaran historis
13. Dengan alasan yang sama ini rasa kesejarahan juga hilang, hal mana menyebabkan disintegrasi lebih jauh. Kita melihat tersebarnya budaya seperti “dekonstruksionisme”, di mana kebebasan manusia mengklaim membangun segala sesuatu dari nol. Yang tetap tinggal hanyalah kebutuhan untuk mengonsumsi tanpa batas dan penekanan pada aneka bentuk individualisme kosong. Dalam konteks ini saya pernah memberikan nasihat ini kepada orang-orang muda: “jika seseorang mengajukan usul dan berkata pada kalian untuk mengabaikan sejarah, untuk tidak menghargai pengalaman orang-orang tua, untuk memandang rendah masa lalu dan hanya melihat masa depan yang ia tawarkan kepada kalian, bukankah ini sebuah cara mudah untuk menarik kalian dengan usulannya itu, untuk membuat kalian melakukan hanya apa yang ia katakan? Orang itu ingin membuat kalian menjadi kosong, tercabut dan curiga terhadap semua sehingga kalian hanya bisa percaya pada janji-janjinya dan menyerah pada rencananya. Inilah cara kerja berbagai ideologi: mereka menghancurkan (atau mendekonstruksi) semua yang berbeda sehingga mereka dapat berkuasa tanpa perlawanan. Untuk tujuan ini, mereka membutuhkan orang-orang muda yang meremehkan sejarah, yang menolak kekayaan spiritual dan manusiawi yang telah diwarisi dari generasi sebelumnya, dan mengabaikan segala hal yang mendahului mereka.”[10]
14. Inilah bentuk-bentuk baru penjajahan budaya. Janganlah kita lupa bahwa “bangsa-bangsa yang meninggalkan tradisi mereka dan yang membiarkan jiwa mereka dirampas, entah karena gila meniru, atau karena dipaksa dengan kekerasan, atau karena kelalaian atau sikap apatis yang tak termaafkan, bahwa bangsa-bangsa itu kehilangan bukan hanya identitas spiritual mereka, tetapi serentak juga kehilangan konsistensi moral mereka dan pada akhirnya juga kemerdekaan ideologis, ekonomis, dan politik mereka.”[11] Salah satu cara efektif untuk melemahkan kesadaran historis, pemikiran kritis, komitmen terhadap keadilan, dan proses-proses integrasi adalah dengan meniadakan atau mengubah makna kata-kata luhur. Saat ini, apakah arti beberapa ungkapan seperti demokrasi, kebebasan, keadilan, persatuan? Semuanya telah dimanipulasi dan diputarbalikkan untuk dimanfaatkan sebagai alat dominasi, sebagai slogan-slogan kosong yang dapat dipakai untuk membenarkan tindakan apa pun.
Tanpa program untuk semua orang
15. Cara terbaik untuk mendominasi dan bergerak maju tanpa batas adalah dengan menebarkan keputusasaan dan menimbulkan ketidakpercayaan terus-menerus, meskipun dengan kedok mempertahankan nilai-nilai tertentu. Saat ini di banyak negara mekanisme politik digunakan untuk menjengkelkan, memperburuk, dan mempolarisasi. Dengan berbagai cara, orang lain diingkari haknya untuk hidup dan berpikir, dan untuk tujuan itu dipakai strategi mengejek mereka, mencurigai mereka, mengepung mereka. Sumbangan mereka tentang kebenaran dan nilai-nilai mereka tidak diterima, dan dengan cara itu masyarakat dimiskinkan dan direndahkan dalam kesombongan dari mereka yang sangat kuat. Dengan demikian, politik tidak lagi menjadi debat-debat sehat tentang program-program jangka panjang untuk pengembangan semua orang dan kebaikan bersama, tetapi hanya menawarkan resep-resep pemasaran sekilas yang menemukan sumber dayanya yang paling efektif dalam penghancuran pihak lain. Dalam permainan diskualifikasi picik ini, debat dimanipulasi menjadi sarana perbantahan dan pertentangan permanen.
16. Dalam konflik kepentingan yang membuat kita semua melawan semua, di mana menang identik dengan menghancurkan, bagaimana mungkin mengangkat kepala untuk mengenali sesamanya atau membantu mereka yang telah jatuh di sepanjang jalan? Sebuah program dengan tujuan-tujuan mulia demi pengembangan seluruh umat manusia saat ini terdengar seperti khayalan. Jarak di antara kita semakin jauh, dan perjalanan yang sulit dan lambat menuju dunia yang bersatu dan lebih adil sedang mengalami kemunduran baru dan drastis.
17. Merawat dunia yang mengelilingi dan mendukung kita berarti merawat diri kita sendiri. Tapi kita harus membentuk diri menjadi suatu “kita” yang mendiami rumah bersama. Perawatan seperti itu tidak menarik bagi kekuatan-kekuatan ekonomi yang membutuhkan keuntungan cepat. Seringkali suara-suara yang diangkat untuk membela lingkungan hidup dibungkam atau diejek, disamarkan dengan rasionalitas yang hanya untuk kepentingan tertentu. Dalam budaya yang sedang kita bangun –kosong, terobsesi dengan hasil segera dan tanpa program bersama– “dapat diduga bahwa, berhadapan dengan menipisnya beberapa sumber daya, secara bertahap diciptakan skenario yang mengarah ke peperangan baru, meskipun di bawah kedok klaim-klaim yang mulia.”[12]
Dunia yang membuang
18. Bagian-bagian tertentu umat manusia tampaknya dapat dikorbankan untuk kepentingan sekelompok orang pilihan yang dianggap layak untuk hidup tanpa batas. Akhirnya, “pribadi manusia tidak lagi dirasa sebagai nilai utama yang perlu dihormati dan dilindungi, terutama jika mereka miskin atau difabel, jika mereka “belum berguna” –seperti mereka yang belum lahir– atau “tidak lagi berguna” –seperti orang lansia. Kita tidak lagi peka terhadap segala jenis buangan, mulai dari buanganmakanan, yang termasuk di antara yang paling patut dicela.”[13]
19. Kurangnya anak-anak, yang menyebabkan penuaan populasi, bersama dengan para lansia yang ditinggalkan dalam kesendirian yang menyedihkan, secara implisit menyatakan bahwa segala sesuatu berakhir pada diri kita, bahwa hanya kepentingan pribadi kita saja yang penting. Jadi, “objek yang dibuang bukan hanya makanan atau barang yang berlebihan, tetapi seringkali juga manusia sendiri.”[14] Kita telah melihat apa yang terjadi pada para lansia di beberapa bagian dunia akibat virus korona. Seharusnya mereka tidak meninggal seperti itu. Namun dalam kenyataannya, hal serupa sudah terjadi juga karena beberapa gelombang cuaca panas dan dalam keadaan lain: secara kejam dibuang. Kita gagal menyadari bahwa mengasingkan orang lansia dan membiarkan mereka dirawat oleh orang lain tanpa pendampingan yang memadai dan cukup perhatian dari keluarga, merusak dan memiskinkan keluarga itu sendiri. Selain itu, hal itu akhirnya merampas orang muda dari kontak yang diperlukan dengan akar-akar mereka dan dengan suatu hikmat yang tidak dapat dicapai oleh orang muda sendiri saja.
20. Tindakan membuang ini mewujud dalam banyak cara, seperti dalam obsesi untuk mengurangi biaya tenaga kerja, tanpa memperhitungkan konsekuensinya yang serius, sebab pengangguran yang terjadi berdampak langsung pada perluasan duniakemiskinan.[15] Selain itu, tindakan membuang tersebut mengambil bentuk-bentuk tercela yang kita yakini sudah berlalu, seperti rasisme, yang bersembunyi dan selalu muncul kembali. Ungkapan-ungkapan rasisme kembali mempermalukan kita karena menunjukkan bahwa kemajuan masyarakat yang diharapkan belum begitu nyata dan tidak selamanya terjamin.
21. Ada aneka aturan ekonomi yang terbukti efektif untuk pertumbuhan, tetapi tidak untuk perkembangan manusia seutuhnya.[16] Kekayaan telah meningkat, tetapi tanpa keseimbangan, dan yang terjadi adalah “munculnya bentuk-bentuk baru kemiskinan.”[17] Ketika dikatakan bahwa dunia modern telah mengurangi kemiskinan, itu dilakukan dengan mengukurnya dengan kriteria zaman lain yang tidak sesuai dengan kenyataan saat ini. Pada kenyataannya di lain zaman, misalnya, tidak adanya akses listrik tidak dianggap sebagai tanda kemiskinan dan bukan penyebab ketidaknyamanan besar. Kemiskinan selalu dianalisis dan dipahami dalam konteks peluang nyata dari suatu momen sejarah konkret.
Hak-hak asasi manusia yang tidak cukup universal
22. Banyak kali kita lihat bahwa pada kenyataannya hak-hak asasi manusia tidaklah sama untuk semua orang. Rasa hormat atas hak-hak ini “merupakan prasyarat bagi pembangunan masyarakat dan ekonomi sebuah negara. Ketika martabat manusia dihormati dan hak-haknya diakui dan dijamin, kreativitas dan kemampuan berinovasijuga tumbuh subur dan kepribadian manusia dapat menyebarkan banyak inisiatif demi kebaikan bersama.”[18] Tetapi “dengan mengamati secara cermat masyarakat zaman ini, kita menemukan banyak kontradiksi yang membuat kita bertanya-tanya apakah kesetaraan martabat semua manusia, yang dengan sungguh-sungguh diproklamasikan 70 tahun yang lalu, benar-benar diakui, dihormati, dilindungi dan dikembangkan dalam segala keadaan. Di dunia saat ini masih ada banyak bentuk ketidakadilan, yang disuburkan oleh visi antropologis yang reduktif dan model ekonomi yang didasarkan pada keuntungan, yang tidak segan-segan mengeksploitasi, membuang, dan bahkan membunuh orang. Sementara sebagian umat manusia hidup dalam kemewahan, sebagian lain melihat martabatnya dinista, dihina atau diinjak-injak, dan hak-hak asasinya diabaikan atau dilanggar.”[19] Apa yang dikatakan di sini tentang persamaan hak berdasarkan martabat manusia yang sama?
23. Demikian pula, “pengaturan” masyarakat di seluruh dunia masih jauh dari mencerminkan secara jelas bahwa perempuan memiliki martabat dan hak yang persis sama dengan laki-laki. Kita menegaskan satu hal dengan kata-kata, tetapi keputusan dan kenyataan kita dengan lantang menceritakan kisah lain. Faktanya, “yang menderita kemalangan ganda adalah para perempuan yang menanggung situasi pengasingan, pelecehan dan kekerasan, karena mereka seringkali tidak mampu membela hak-hak mereka.”[20]
24. Kita mengakui pula bahwa, “meskipun masyarakat internasional telah membuat banyak kesepakatan untuk mengakhiri perbudakan dalam segala bentuknya dan menerapkan berbagai strategi untuk memerangi fenomena ini, sampai saat ini masih jutaan orang –anak-anak, laki-laki, dan perempuan dari segala usia– dirampas kebebasan mereka dan dipaksa untuk hidup dalam kondisi-kondisi yang mirip dengan perbudakan. […] Hari ini seperti kemarin, akar perbudakan itu terletak pada pemahaman tentang pribadi manusia yang memungkinkan untuk memperlakukannya sebagai objek. […] Pribadi manusia, yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dengan paksaan, penipuan, atau tekanan fisik atau psikologis dirampas kebebasannya, diperdagangkan, dan direduksi menjadi milik orang lain; ia diperlakukan sebagai sarana dan bukan sebagai tujuan. Jaringan-jaringan kriminal dengan lihai menggunakan teknologi informasi modern untuk menjerat orang muda dan orang yang masih sangat muda di seluruh dunia.”[21] Penyimpangan ini tidak mengenal batas ketika perempuan direndahkan, kemudian dipaksa untuk melakukan aborsi. Tindakan keji itu bahkan sampai pada penculikan orang dengan tujuan menjual organ-organ tubuh mereka. Semua ini membuat perdagangan manusia dan bentuk-bentuk perbudakan lainnya menjadi masalah global, yang menuntut tanggapan serius dari umat manusia secara keseluruhan, karena “sebagaimana organisasi kriminal menggunakan jaringan global untuk mencapai tujuannya, begitu pula tindakan untuk mengatasi fenomena ini membutuhkan upaya bersama dan juga global dari berbagai pemangku kepentingan yang membentuk masyarakat.”[22]
Konflik dan ketakutan
25. Peperangan, serangan teroris, penganiayaan karena alasan ras atau agama, dan begitu banyak penyalahgunaan kekuasaan terhadap martabat manusia dinilai dengan cara yang berbeda tergantung apakah hal itu sesuai atau tidak dengan kepentingan-kepentingan tertentu, terutama kepentingan ekonomis. Apa yang benar selama cocok bagi orang yang berkuasa tidak lagi benar bila itu bukan untuk kepentingannya. Situasi kekerasan seperti itu “bertambah banyak secara menyedihkan di banyak wilayah dunia, hingga mengambil ciri-ciri dari apa yang bisa disebut ‘perang dunia ketiga secara bertahap’.”[23]
26. Hal ini tidak mengherankan jika kita memperhatikan kurang adanya cakrawala yang mampu mempersatukan kita, karena korban pertama setiap perang adalah “program persaudaraan itu sendiri yang terukir dalam panggilan keluarga manusia”; sehingga “setiap situasi yang mengancam menimbulkan ketidakpercayaan dan penarikan diri.”[24] Dunia kita terjebak dalam dikotomi yang tak masuk akal, dengan mengklaim dapat “memastikan stabilitas dan perdamaian atas dasar keamanan palsu yang dipertahankan dengan mentalitas ketakutan dan ketidakpercayaan.”[25]
27. Paradoksnya, ada ketakutan turun-temurun yang belum teratasi oleh kemajuan teknologi; sebaliknya, ketakutan itu telah mampu bersembunyi dan bertambah kuat di balik teknologi baru. Saat sekarang pun, di luar tembok kota tua ada jurang yang dalam, wilayah yang tidak dikenal, wilayah tak berpenghuni. Apa yang datang dari sana tidak dapat dipercayai, karena tidak diketahui, tidak dikenal, bukan bagian dari wilayah kita. Itu adalah wilayah “barbar”; terhadapnya kita harus mempertahankan diri dengan cara apa pun. Akibatnya, dibuat barikade-barikade baru untuk pertahanan diri, sehingga tak ada lagi dunia; yang ada hanya dunia “saya,” hingga banyak orang tidak lagi dianggap sebagai manusia dengan martabat yang tak dapat dicabut, tetapi hanya menjadi “mereka.” Muncul kembali “godaan untuk menciptakan budaya tembok, untuk meninggikan tembok, tembok dalam hati, tembok di bumi untuk mencegah perjumpaan dengan budaya lain, dengan orang lain. Dan siapa pun yang meninggikan tembok, membangun tembok, pada akhirnya akan menjadi budak di dalam tembok yang telah ia bangun, tanpa wawasan. Karena ia kehilangan pertukaran dengan yang lain.”[26]
28. Kesendirian, ketakutan, dan rasa tidak aman yang dialami begitu banyak orang yang merasa diri disingkirkan oleh sistem, menciptakan lahan subur bagi para mafia. Bahkan, mereka menegaskan diri dengan tampil sebagai “pelindung” dari mereka yang terlupakan, seringkali dengan memberi aneka macam bantuan, sambil mengejar kepentingan kriminal mereka. Ada pedagogi khas mafia yang, dengan semangat komunal yang palsu, menciptakan ikatan ketergantungan dan loyalitas yang sangat sulit untuk dilepaskan.
Globalisasi dan kemajuan tanpa peta jalan bersama
29. Bersama Imam Besar Ahmad Al-Tayyeb, kami mengakui kemajuan positif yang telah terjadi di bidang sains, teknologi, kedokteran, industri, dan kesejahteraan, terutama di negara-negara maju. Meskipun demikian, “kami ingin menekankan bahwa, terkait dengan kemajuan bersejarah seperti itu, betapa pun hebat dan bernilainya hal-hal tersebut, terdapat kemerosotan moral yang mempengaruhi tindakan internasional dan pelemahan nilai-nilai dan tanggung jawab rohani. Semua ini berkontribusi pada perasaan frustrasi umum, keterasingan, dan keputusasaan.” […] “Sarang-sarang ketegangan muncul serta senjata dan amunisi menumpuk, dan semua ini dalam konteks global yang dibayang-bayangi oleh ketidakpastian, kekecewaan, ketakutan akan masa depan, dan dikendalikan oleh kepentingan ekonomi yang berpikiran sempit.” Kami juga dapat menunjukkan “krisis politik besar, situasi ketidakadilan, dan kurangnya distribusi sumber daya alam yang adil.[…] Dalam menghadapi krisis seperti itu yang mengakibatkan kematian jutaan anak-anak akibat kemiskinan dan kelaparan, ada kebungkaman yang tidak dapat diterima, di tingkat internasional.”[27] Berhadapan dengan panorama ini, meskipun kita tertarik oleh banyak kemajuan, kita tidak menemukan trayek yang benar-benar manusiawi.
30. Di dunia saat ini, rasa memiliki sebagai satu keluarga umat manusia yang sama semakin memudar, sementara impian untuk bersama-sama membangun keadilan dan perdamaian tampak seperti utopia dari zaman lain. Kita melihat bagaimana ketidakpedulian yang nyaman, dingin, dan mengglobal menjadi dominan, lahir dari kekecewaan mendalam yang bersembunyi di balik tipu daya ilusi: percaya bahwa kita bisa menjadi mahakuasa dan melupakan bahwa kita semua berada dalam perahu yang sama. Kekecewaan yang meninggalkan nilai-nilai luhur persaudaraan, mengarah pada “semacam sinisme. Inilah godaan yang kita hadapi jika kita mengambil jalan kekecewaan atau ketidakpuasan ini. […] Pengasingan dan ketertutupan diri ke dalam kepentingannya sendiri tidak pernah menjadi jalan untuk memulihkan harapan dan membawa pembaruan. Sebaliknya, itu dibawa oleh kedekatan, oleh budaya perjumpaan. Pengasingan, tidak; kedekatan, ya! Budaya konfrontasi, tidak; budaya perjumpaan, ya!”[28]
31. Di dunia yang berjalan tanpa peta jalan bersama, ada suasana di mana “jarak antara obsesi akan kesejahteraannya sendiri dan kebahagiaan bersama untuk seluruh umat manusia tampaknya melebar, sampai menunjukkan bahwa sekarang sedang berlangsung perpecahan yang nyata antara individu dan komunitas manusia. […] Karena itu, merasa harus hidup bersama adalah satu hal, hal lain adalah menghargai kekayaan dan keindahan benih-benih kehidupan bersama yang harus ditemukan dan dikembangkan bersama.”[29] Teknologi terus mengalami kemajuan, tetapi “alangkah indahnya jika perkembangan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi juga disertai dengan semakin meningkatnya kesetaraan dan inklusi sosial! Alangkah indahnya bila, ketika kita menemukan planet-planet baru yang jauh, kita jugamenemukan kembali apa yang dibutuhkan oleh saudara dan saudari yang mengelilingi saya!”[30]
Pandemi dan bencana lain dalam sejarah
32. Tragedi global seperti pandemi Covid-19 sebenarnya untuk sementara waktu telah membangkitkan kesadaran bahwa kita adalah suatu komunitas global yang berlayar di perahu yang sama, di mana kemalangan seseorang membawa kerugian bagi semua. Kita diingatkan bahwa tidak ada yang diselamatkan sendirian, bahwa kita hanya dapat diselamatkan secara bersama-sama. Karena itu, saya pernah mengatakan bahwa “badai menyingkapkan kerentanan kita dan menelanjangi kepastian palsu dan berlebihan, yang dengannya kita telah menyusun agenda, program, kebiasaan, dan prioritas kita. […] Berkat badai itu, telah jatuh topeng klise yang kita gunakan untuk menyembunyikan ego kita yang selalu disibukkan dengan citranya; sekali lagi terungkap kesadaran berahmat yang tak bisa kita hindari bahwa kita adalah bagian dari satu sama lain: kita semua adalah saudara satu sama lain.”[31]
33. Dunia bergerak tanpa hentinya menuju suatu ekonomi yang, dengan menggunakan kemajuan teknologi, berusaha mengurangi “biaya manusia”, dan beberapa orang membuat kita percaya bahwa kebebasan pasar sudah cukup untuk membuat segala sesuatu dianggap aman. Tetapi pukulan keras dan tak terduga dari pandemi yang tak terkendali ini memaksa kita untuk berpikir kembali tentang manusia, tentang mereka semua, daripada tentang keuntungan untuk segelintir orang saja. Hari ini kita dapat mengenali bahwa “kita telah memuaskan diri dengan impian-impian kemegahan dan keagungan dan akhirnya menelan gangguan, keterasingan dan kesepian; kita menikmati jaringan dunia maya tetapi kita kehilangan selera untuk persaudaraan. Kita telah mencari hasil-hasil yang cepat dan aman, dan kita menjadi tertekan oleh ketidaksabaran dan kecemasan. Sebagai tawanan dunia virtual, kita telah kehilangan cita rasa dan selera untuk realitas nyata.”[32] Rasa sakit, ketidakpastian, ketakutan, dan kesadaran akan keterbatasan diri yang telah ditimbulkan oleh pandemi, menggemakan kembali seruan untuk memikirkan kembali gaya hidup kita, hubungan kita, pengaturan masyarakat kita, dan terutama, makna keberadaan kita.
34. Jika semuanya terhubung, sulit untuk membayangkan bahwa malapetaka global ini tidak terkait dengan cara kita menghadapi kenyataan, dengan mengklaim bahwa kita adalah tuan mutlak atas hidup kita dan segala sesuatu yang ada. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa itu semacam hukuman ilahi. Juga tidak akan cukup untuk mengatakan bahwa kerusakan yang terjadi pada alam akhirnya meminta pertanggungjawaban atas pelanggaran kita. Realitas sendirilah yang mengeluh dan memberontak. Terlintas di benak syair-syair puisi Vergilius yang membangkitkan kisah-kisah manusia yang penuh air mata.[33]
35. Akan tetapi, kita cepat melupakan pelajaran sejarah, “guru kehidupan.”[34] Setelah krisis kesehatan berakhir, reaksi terburuk kita adalah terjerumus lebih dalam lagi ke dalam demam konsumerisme dan bentuk-bentuk baru pertahanan diri yang egois. Semoga pada akhirnya tidak ada lagi “yang lain”, melainkan hanya “kita.” Semoga ini bukanlah peristiwa serius kesekian dalam sejarah yang darinya kita belum mampu belajar. Jangan kita melupakan para lansia yang meninggal karena kekurangan alat pernafasan, sebagian sebagai akibat sistem perawatan kesehatan yang dilemahkan dari tahun ke tahun. Semoga penderitaan yang begitu besar tidak sia-sia, tetapi kita mengambil langkah besar menuju cara hidup baru dan menemukan sekali dan untuk semua bahwa kita saling membutuhkan dan saling berutang budi, sehingga umat manusia terlahir kembali dengan semua wajahnya, semua tangannya, dan semua suaranya, melampaui batas-batas yang telah kita buat.
36. Jika kita gagal mendapatkan kembali hasrat bersama akan sebuah komunitas di mana kita saling memiliki dan setia kawan, dan mengalokasikan waktu, tenaga, dan sarana untuk itu, ilusi global yang menipu kita akan berantakan dan runtuh dan meninggalkan banyak orang dalam cengkeraman penderitaan dan kehampaan. Selain itu, tidak boleh diabaikan secara naif bahwa “obsesi gaya hidup konsumtif hanya akan menimbulkan kekerasan dan tindakan saling menghancurkan, terutama ketika hanya sedikit orang dapat menikmati gaya hidup itu.”[35] Semboyan “setiap orang menyelamatkan diri sendiri” akan dengan cepat mengakibatkan “semua melawan semua”, dan hal itu akan menjadi lebih buruk daripada suatu pandemi.
Tiadanya martabat manusia di perbatasan
37. Baik beberapa rezim politik populis maupun pendekatan ekonomi liberal menyatakan bahwa kedatangan migran harus dicegah dengan segala cara. Pada saat yang sama, dikatakan bahwa bantuan kepada negara-negara miskin sebaiknya dibatasi, sampai mereka mencapai titik terendah dan memutuskan untuk mengambil langkah-langkah penghematan. Tidak disadari bahwa di balik pernyataan-pernyataan abstrak yang sulit didukung ini, kehidupan banyak orang dihancurkan. Banyak migran telah melarikan diri dari perang, penganiayaan, atau bencana alam. Orang-orang lain, dengan segala hak, “mencari kesempatan bagi dirinya sendiri dan keluarga mereka. Mereka memimpikan masa depan yang lebih baik dan berharap dapat menciptakan kondisi untuk mewujudkannya.”[36]
38. Sayangnya, ada orang yang “tertarik oleh budaya Barat, terkadang dengan ekspektasi yang tidak realistis, yang membuat mereka sangat kecewa. Para pedagang ilegal tanpa rasa salah, sering terkait dengan kartel narkoba dan kartel senjata, mengeksploitasi kelemahan para migran yang sepanjang perjalanan sangat sering mengalami kekerasan, perdagangan manusia, pelecehan psikologis dan bahkan fisik, serta penderitaan-penderitaan yang tak terkatakan.”[37] Mereka yang beremigrasi “mengalami keterpisahan dari tempat asalnya dan seringkali juga tercabut dari budaya dan agama mereka. Keretakan juga berdampak pada komunitas asal mereka, yang kehilangan unsur terkuat dan terpenting, dan keluarga, terutama ketika salah satu atau kedua orangtua bermigrasi dan meninggalkan anak-anak mereka di negara asal.”[38] Karena itu, harus juga “ditegaskan kembali hak untuk tidak beremigrasi, artinya tetap tinggal di tanahnya sendiri.”[39]
39. Lebih lanjut, “di beberapa negara tujuan, fenomena migrasi menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan, yang sering dipicu dan dieksploitasi untuk tujuan politik. Karena itu, mentalitas xenofobia yang menutup diri dan menarik diri, menyebar.”[40]Para migran dipandang tidakselayak orang lain untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial; dan dilupakan bahwa mereka memiliki martabat hakiki yang sama seperti pada orang lain. Karena itu, mereka harus menjadi “pelaku utama pembebasan mereka sendiri.”[41] Tidak akan pernah dikatakan bahwa mereka bukan manusia, tetapi dalam praktiknya, dengan pilihan-pilihan dan cara memperlakukan mereka, terlihat jelas bahwa mereka dipandang kurang berharga, kurang penting, kurang manusiawi. Tidak dapat diterima bahwa orang Kristen memiliki mentalitas dan sikap seperti itu; dalam hal ini mereka kadang-kadang menempatkan preferensi politik tertentu di atas keyakinan iman yang paling mendasar, yakni: martabat yang tak tercabut dari setiap manusia terlepas dari asal, warna kulit atau agama, dan hukum tertinggi kasih persaudaraan.
40. “Migrasi akan menjadi unsur sangat penting di masa depan dunia.”[42] Tetapi, saat ini, migrasi terdampak oleh “hilangnya rasa tanggung jawab persaudaraan yang menjadi dasar setiap masyarakat sipil.”[43] Eropa, misalnya, sangat berisiko mengambil jalan itu. Namun, “dibantu oleh warisan budaya dan religiusnya yang agung, benua itu mempunyai sarana untuk mempertahankan sentralitas pribadi manusia dan untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara kewajiban moral rangkap: baik melindungi hak-hak warga negaranya maupun menjamin bantuan dan penerimaan bagi para migran.”[44]
41. Saya mengerti bahwa ketika berhadapan dengan para migran, beberapa orang memiliki keraguan atau ketakutan. Saya memahami hal ini sebagai bagian dari naluri alami untuk mempertahankan diri. Namun, juga benar bahwa seseorang dan suatu bangsa akan berhasil hanya jika mereka tahu bagaimana secara kreatif mengintegrasikan ke dalam dirinya keterbukaan terhadap orang lain. Saya mengajak Anda untuk melampaui reaksi spontan, karena “masalahnya adalah bahwa keraguan dan ketakutan mengondisikan cara berpikir dan bertindak kita sedemikian rupa sehingga membuat kita intoleran, tertutup, bahkan mungkin –tanpa disadari– rasis. Dan dengan demikian, rasa takut membuat kita kehilangan keinginan dan kemampuan untuk bertemu dengan yang lain.”[45]
Ilusi komunikasi
42. Sementara sikap tertutup dan intoleran yang menjauhkan kita dari orang lain meningkat, secara paradoksal jarak berkurang atau menghilang sampai ke titik hilangnya hak atas privasi. Segala sesuatu menjadi semacam tontonan yang bisa dimata-matai, diawasi, dan kehidupan berada di bawah pengawasan terus menerus. Dalam komunikasi digital kita ingin menampilkan segalanya dan setiap individu dijadikan objek perhatian yang dibongkar-bongkar, ditelanjangi dan disingkapkan, seringkali secara anonim. Rasa hormat terhadap orang lain runtuh dan dengan cara ini, justru pada saat saya menyingkirkan mereka, mengabaikan mereka dan menjauhkan mereka, tanpa rasa malu saya dapat menerobos ke dalam hidup mereka secara ekstrem.
43. Di sisi lain, gerakan-gerakan digital untuk menyebarkan kebencian dan penghancuran bukanlah –seperti diyakini sebagian orang– bentuk terbaik untuk saling mendukung, tetapi hanya persekutuan melawan seorang musuh. Lebih jauh lagi, “media-media digital dapat mengarah kepada risiko kecanduan, isolasi diri, dan kehilangan kontak dengan kenyataan konkret secara bertahap, dengan menghalangi perkembangan relasi-relasi personal yang autentik.”[46] Diperlukan gestur fisik, ekspresi wajah, saat-saat hening, bahasa tubuh, bahkan bau harum, tangan yang gemetar, pipi yang memerah, keringat, karena semua ini berbicara dan merupakan bagian dari komunikasi manusia. Hubungan digital yang tidak menuntut upaya membina persahabatan timbal balik yang stabil, atau pun membangun konsensus yang semakin matang seiring waktu, bisa menampilkan kesan keramahan, tetapihubungan seperti itu tidak benar-benar membangun suatu “kita”, sebaliknya biasanya menyembunyikan dan memperkuat individualisme yang sama yang terungkap juga dalam ketakutan terhadap yang asing (xenofobia) dan penghinaan terhadap yang lemah. Konektivitas digital tidak cukup untuk membangun jembatan dan tidak mampu mempersatukan umat manusia.
Agresi tanpa tahu malu
44. Pada saat yang sama ketika orang mempertahankan isolasinya yang konsumeris dan nyaman, mereka memilih untuk terikat secara terus menerus dan obsesif. Hal ini mendorong munculnya bentuk-bentuk luar biasa agresivitas, penghinaan, pelecehan, pencemaran nama baik, kekerasan verbal yang menghancurkan sosok lain, dengan sikap tak terkendali yang tak mungkin ada dalam kontak fisik karena pada akhirnya kita akan saling menghancurkan. Agresivitas sosial itu menemukan dalam perangkat seluler dan komputer suatu ruang penyebaran yang tiada taranya.
45. Ini telah memungkinkan berbagai ideologi kehilangan segala rasa malu. Apa yang sampai beberapa tahun lalu tidak bisa dikatakan oleh seseorang tanpa risiko kehilangan respek dari semua orang, saat ini bisa dikatakan dengan sangat kasar, bahkan oleh beberapa tokoh politik, tanpa dapat dipersalahkan. Tidak boleh dilupakan bahwa “kepentingan ekonomi raksasa beraksi di dunia digital, yang mampu membuat bentuk-bentuk pengendalian halus karena bersifat invasif, dengan menciptakan mekanisme untuk memanipulasi hati nurani dan proses demokrasi. Banyak platform beroperasi sedemikian sehingga akhirnya hanyaorang-orang yang berpikiran sama bertemu, dan mereka terlindung dari konfrontasi dengan hal-hal yang berbeda. Lingkungan tertutup seperti itu memudahkan penyebaran informasi dan berita-berita palsu (fake news), yang berakibat meningkatnya prasangka dan kebencian.”[47]
46. Harus diakui bahwa fanatisme yang mengarah pada penghancuran orang lain juga ditemukan di antara umat beragama, tidak terkecuali umat Kristiani, yang “dapat ikut serta dalam jaringan kekerasan verbal melalui internet dan berbagai forum komunikasi digital. Bahkan di dalam media Katolik, batas-batas dapat dilampaui, fitnah dan umpatan bisa ditoleransi, dan segala etika dan rasa hormat terhadap nama baik sesama dapat diabaikan.”[48] Dengan melakukan itu, kontribusi apa yang diberikan kepada persaudaraan yang ditawarkan kepada kita oleh Bapa kita bersama?
Informasi tanpa kebijaksanaan
47. Kebijaksanaan sejati mengandaikan perjumpaan dengan kenyataan. Tetapi saat ini semuanya dapat diciptakan, disamarkan, diubah. Dengan demikian, perjumpaan langsung dengan realitas yang marjinal menjadi tidak tertahankan. Maka, dibuat mekanisme “seleksi” dan diciptakan kebiasaan untuk segera memisahkan apa yang saya suka dari apa yang tidak saya suka, apa yang menarik dari apa yang tidak menyenangkan. Dengan cara yang sama kita memilih orang yang dengannya kita putuskan untuk berbagi dunia. Orang atau keadaan yang telah melukai perasaan kita atau tidak diinginkan, disingkirkan saja dari jaringan virtual saat ini, dengan membangun lingkaran virtual yang memisahkan kita dari dunia di mana kita hidup.
48. Duduk mendengarkan orang lain, ciri khas perjumpaan manusia, adalah paradigma sikap menyambut, sifat orang yang melampaui narsisme dan menerima yang lain, memperhatikannya, memberi ruang baginya dalam lingkarannya sendiri. Namun, “dunia saat ini sebagian besar adalah dunia yang tuli […]. Terkadang kecepatan dunia modern, hiruk-pikuk, menghalangi kita mendengarkan dengan baik apa yang dikatakan orang lain. Ketika ia tengah berbicara, kita sudah menyela dan ingin menjawabnya sementara ia belum selesai berbicara. Jangan kita kehilangan kemampuan untuk mendengarkan.” Santo Fransiskus dari Asisi “mendengarkan suara Allah, ia mendengarkan suara orang miskin, ia mendengarkan suara orang sakit, ia mendengarkan suara alam. Dan semua itu mengubahnya menjadi gaya hidup. Saya berharap agar benih dari Santo Fransiskus bisa tumbuh di hati banyak orang.”[49]
49. Dengan hilangnya keheningan dan sikap mendengarkan, dan semuanya diubah menjadi ketikan dan pesan singkat yang tidak sabar, struktur dasar komunikasi manusia yang bijak terancam. Tercipta gaya hidup baru di mana kita membangun apa yang mau kita hadapi, dengan menyingkirkan segala sesuatu yang tidak dapat kita kendalikan atau ketahui secara instan dan dangkal saja. Dinamika ini, dengan logikanya tersendiri, menghalangi refleksi tenang yang dapat mengantar kita pada kebijaksanaan bersama.
50. Bersama-sama, kita dapat mencari kebenaran dalam dialog, entah dalam percakapan yang tenang atau debat yang sengit. Ini adalah perjalanan yang membutuhkan ketekunan, juga ditandai dengan keheningan dan penderitaan, yang mampu dengan sabar mengumpulkan pengalaman luas individu dan bangsa-bangsa. Akumulasi informasi yang melimpah yang membanjiri kita tidak berarti lebih banyak kebijaksanaan. Kebijaksanaan tidak lahir dari pencarian bersemangat di internet, atau dari setumpuk informasi yang tidak terjamin kebenarannya. Dengan cara itu seseorang tidak menjadi matang berhadapan dengan kebenaran. Percakapan akhirnya hanya berkisar pada data terbaru, yang hanya bersifat datar dan kumulatif. Sebaliknya, orang tidak memberi perhatian yang lama dan masuk kepada esensi kehidupan; tidak mengenali apa yang penting untuk memberi makna pada keberadaan kita. Dengan demikian, kebebasan menjadi ilusi yang dijual kepada kita dan yang dikacaukan dengan kebebasan untuk berselancar di depan layar. Masalahnya ialah bahwa jalan persaudaraan, baik lokal maupun universal, hanya dapat ditempuh oleh jiwa-jiwa bebas yang bersedia untuk berjumpa secara nyata.
Ketundukan dan kehinaan diri
51. Beberapa negara yang ekonominya kuat digambarkan sebagai model budaya bagi negara-negara yang kurang berkembang, alih-alih berusaha agar tiap-tiap negara tumbuh dengan gaya khasnya sendiri, dengan mengembangkan kemampuan berinovasi yang dimulai dari nilai-nilai budayanya sendiri. Nostalgia dangkal dan menyedihkan yang mendorong untuk menyalin dan membeli, alih-alih untuk menciptakan, menimbulkan harga diri nasional yang sangat rendah. Di kalangan orang berada di banyak negara miskin, dan terkadang pada mereka yang berhasil keluar dari kemiskinan, ditemukan ketidakmampuan untuk menerima kekhasan dan proses mereka sendiri; mereka jatuh ke dalam penghinaan terhadap identitas budaya mereka sendiri, seolah-olah itu menjadi penyebab dari segala yang buruk.
52. Menghancurkan harga diri orang adalah cara mudah untuk mendominasinya. Di balik kecenderungan untuk membuat dunia menjadi seragam, muncul kepentingan kekuasaan yang memanfaatkan harga diri yang rendah, sambil mencoba, melalui media dan jaringan, menciptakan budaya baru untuk melayani yang paling kuat. Hal ini dimanfaatkan oleh oportunisme spekulasi keuangan dan eksploitasi, di mana kaum miskin selalu menjadi pihak yang kalah. Namun, mengabaikan budaya sebuah bangsa menyebabkan banyak pemimpin politik tidak lagi mampu mengembangkan program efektif yang dapat diterima dan dipertahankan secara bebas dari waktu ke waktu.
53. Kita lupa bahwa “tidak ada bentuk keterasingan yang lebih buruk daripada merasa tidak memiliki akar dan tidak dimiliki siapa pun. Suatu tanah akan subur, dan bangsanya akan berbuah dan melahirkan masa depan, hanya sejauh bangsa itu dapat menumbuhkan hubungan saling memiliki di antara para anggotanya, menciptakan ikatan integrasi antar generasi dan antar pelbagai komunitas yang membentuknya, dan menghindari segala hal yang membuat kita tidak peka dan terus menjauhkan kita yang satu dari yang lain.”[50]
Harapan
54. Terlepas dari bayang-bayang pekat yang tidak boleh diabaikan ini, di halaman-halaman berikut saya ingin berbicara tentang banyak jalan pengharapan. Memang, Allah terus menabur benih-benih kebaikan di antara umat manusia. Pandemi baru-baru ini telah memungkinkan kita untuk menemukan kembali dan menghargai banyak teman seperjalanan yang dalam situasi yang menakutkan telah bertindak dengan memberikan nyawa mereka. Kita bisa mengakui bahwa hidup kita terjalin dan ditopang oleh orang-orang biasa yang tanpa ragu-ragu telah menggoreskan peristiwa-peristiwa penting pada sejarah kita bersama: para dokter, perawat, apoteker, pekerja supermarket, petugas kebersihan, tenaga pengasuh, pekerja transportasi, laki-laki dan perempuan yang berupaya menyediakan layanan dan keamanan penting, relawan, imam, biarawati,… mereka telah memahami bahwa tidak ada yang dapat diselamatkan sendirian.”[51]
55. Saya mengundang kepada pengharapan yang “berbicara kepada kita tentang realitas yang berakar dalam hati manusia, terlepas dari situasi konkret dan kondisi historis di mana ia hidup. Harapan berbicara kepada kita tentang kehausan, aspirasi, kerinduan akan kepenuhan, akan kehidupan yang terpenuhi, keinginan untuk mencapai hal-hal besar, yang memenuhi hati kita dan membangkitkan gairah kita kepada hal-hal yang luhur, seperti kebenaran, kebaikan dan keindahan, keadilan dan kasih. […] Harapan itu berani, mampu melihat melampaui kenyamanan pribadi, jaminan dan imbalan kecil yang mempersempit cakrawala kita, untuk terbuka pada cita-cita besar yang membuat hidup lebih indah dan bermartabat.”[52] Marilah kita berjalan dalam pengharapan.
BAB DUA
SEORANG ASING DI JALAN
56. Semua yang saya sebutkan dalam bab sebelumnya lebih dari sekadar deskripsi yang lepas dari realitas, karena “kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin, dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga. Tiada sesuatu yang sungguh manusiawi yang tidak bergema di hati mereka.”[53] Dalam upaya untuk mencari terang di tengah-tengah apa yang sedang kita alami, dan sebelum mengajukan beberapa garis tindakan, saya bermaksud mempersembahkan satu bab bagi suatu perumpamaan yang diceritakan Yesus dua ribu tahun yang lalu. Sesungguhnya, meskipun Ensiklik ini ditujukan kepada semua orang yang berkehendak baik, terlepas dari keyakinan agamanya, perumpamaan itu disajikan sedemikian rupa sehingga siapa pun di antara kita dapat membiarkan diri ditantang olehnya.
Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya: “Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?”26Jawab Yesus kepadanya: “Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kaubaca di sana?”27 Jawab orang itu: “Kasihilah Allah, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.”28 Kata Yesus kepadanya: “Jawabmu itu benar; perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup.”29Tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus: “Dan siapakah sesamaku manusia?”30 Jawab Yesus: “Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yerikho; ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati.31Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu; ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan.32 Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu; ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan.33 Lalu datang seorang Samaria, yang sedang dalam perjalanan, ke tempat itu; dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan.34 Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya.35 Keesokan harinya ia menyerahkan dua dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya: ‘Rawatlah dia dan jika kaubelanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya, waktu aku kembali.’36 Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?”37 Jawab orang itu: “Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya.” Kata Yesus kepadanya: “Pergilah, dan perbuatlah demikian!” (Lukas 10:25-37)
Latar belakang
57. Perumpamaan ini mencerminkan latar belakang berabad-abad. Tak lama setelah kisah tentang penciptaan dunia dan manusia, Alkitab menyajikan masalah hubungan antara kita. Kain membunuh saudaranya Habel, lalu bergemalah pertanyaan Allah: “Di mana Habel, adikmu itu?” (Kejadian 4:9). Jawabannya sama seperti yang sering kita berikan: “Apakah aku penjaga adikku?” (ibid.). Dengan pertanyaan-Nya itu, Allah mempertanyakan segala jenis determinisme atau fatalisme yang beranggapan menjadi pembenaran atas ketidakpedulian sebagai satu-satunya jawaban yang mungkin. Sebaliknya, pertanyaan itu memungkinkan kita untuk menciptakan budaya yang berbeda, yang mengarahkan kita untuk mengatasi permusuhan dan untuk memperhatikan satu sama lain.
58. Kitab Ayub mengacu pada fakta bahwa kita memiliki Pencipta yang sama sebagai dasar untuk mempertahankan beberapa hak bersama: “Bukankah Ia, yang membuat aku dalam kandungan, membuat orang itu juga? Bukankah satu juga yang membentuk kita dalam rahim? (31:15). Berabad-abad kemudian, Santo Ireneus akan mengungkapkannya dengan cara lain melalui kiasan melodi: “Maka, siapa pun yang mencintai kebenaran tidak boleh membiarkan dirinya terbawa oleh perbedaan setiap nada dan membayangkan bahwa nada yang satu dibuat dan digubah oleh orang yang satu, nada yang lain oleh orang yang lain […], tetapi ia harus berpikir bahwa hanya satu orang saja yang melakukannya.”[54]
59. Dalam tradisi Yahudi, perintah untuk mengasihi dan memperhatikan orang lain tampaknya terbatas pada hubungan antara anggota sebangsa. Perintah kuno “kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri” (Imamat 19:18) biasanya dipahami sebagai merujuk pada sesama warga negara. Namun, khususnya dalam Yudaisme yang berkembang di luar tanah Israel, batas-batasnya diperlebar. Orang diajak untuk tidak melakukan kepada siapa pun apa yang tidak ia sukai dilakukan terhadap dirinya (lih. Tobit 4:15). Rabi Hillel (abad ke-1 SM) berkata tentang hal itu: “Inilah Hukum dan Para Nabi. Selebihnya adalah penjelasan.”[55] Keinginan untuk meneladani sikap ilahi mendorong orang mengatasi kecenderungan untuk membatasi diri pada mereka yang paling dekat: “Belas kasih manusia ditujukan kepada sesamanya, sedangkan belas kasih Allah kepada segala makhluk” (Sirakh 18:13).
60. Dalam Perjanjian Baru, ajaran Hillel mendapat ungkapan positif: “Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi” (Mat. 7:12). Seruan ini bersifat universal, cenderungmerangkul semua orang bukan hanya karena kondisi manusiawi mereka, tetapi karena Allah Yang Mahatinggi, Bapa surgawi “menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik” (Matius 5:45). Karena itu dituntut: “Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati” (Luk. 6:36).
61. Motivasi untuk melapangkan hati sehingga tidak mengecualikan orang asing, sudah dapat ditemukan dalam teks-teks tertua di Alkitab. Ini berasal dari ingatan tetap orang-orang Yahudi bahwa mereka pernah hidup sebagai orang asing di Mesir:
“Janganlah kautindas atau kautekan seorang orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir” (Kel. 22:21).
“Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir” (Kel. 23:9).
“Apabila seorang asing tinggal padamu di negerimu, janganlah kamu menindas dia. 34 Orang asing yang tinggal padamu harus sama bagimu seperti orang Israel asli dari antaramu, kasihilah dia seperti dirimu sendiri, karena kamu juga orang asing dahulu di tanah Mesir” (Im. 19:33-34).
“Apabila engkau mengumpulkan hasil kebun anggurmu, janganlah engkau mengadakan pemetikan sekali lagi; itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda.22 Haruslah kauingat, bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir; itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal in” (Ul. 24:21-22).
Seruan kepada kasih persaudaraan bergema dengan kuat dalam Perjanjian Baru:
“Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu: “Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri!” (Gal. 5:14).
“Barangsiapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barangsiapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan” (1Yoh. 2:10-11).
“Kita tahu, bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barangsiapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut” (1Yoh. 3:14).
“Barangsiapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah, yang tidak dilihatnya” (1Yoh. 4:20).
62. Ajakan untuk mengasihi ini dapat juga disalahpahami. Bukan tanpa alasan, ketika Santo Paulus menghadapi godaan dari komunitas-komunitas Kristen awal untuk membentuk kelompok-kelompok yang tertutup dan terasing, ia menyerukan kepada murid-muridnya untuk “berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang” (1Tes. 3:12); dan dalam komunitas Yohanes diminta untuk menyambut dengan baik “saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing” (3Yoh. 5). Konteks ini membantu kita untuk memahami nilai perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati: kasih tidak peduli apakah saudara yang terluka itu berasal dari sini atau dari sana. Karena “kasihlah yang mematahkan belenggu yang membuat kita terasing dan terpisah, dengan membangun jembatan; kasihlah yang memungkinkan kita membangun keluarga besar di mana kita semua bisa merasa kerasan …. Kasih yang mengenal bela rasa dan martabat.”[56]
Orang yang ditinggalkan
63. Yesus menceritakan kisah tentang seseorang yang telah dirampok dan terluka, tergeletak di pinggir jalan. Ada beberapa orang yang melintasi jalan itu, tetapi mereka berjalan terus tanpa berhenti. Mereka adalah orang yang memegang posisi penting dalam masyarakat, tetapi di hati mereka tidak ada kasih untuk kebaikan bersama. Mereka tidak dapat meluangkan beberapa menit untuk membantu orang yang terluka atau setidaknya mencari bantuan. Hanya satu orang yang berhenti, mendekatinya, merawatnya dengan tangannya sendiri, membayarinya dari sakunya sendiri, dan menjaganya. Terlebih-lebih, ia memberinya sesuatu yang sangat kita hemat di dunia yang tergesa-gesa ini: ia memberinya waktunya sendiri. Tentunya dia mempunyai rencananya sendiri untuk menggunakan hari itu, sesuai dengan keperluan, komitmen, atau keinginannya sendiri. Tapi dia bisa mengesampingkan semuanya itu ketika berhadapan dengan orang yang terluka itu. Meskipun tidak mengenalnya, ia menganggapnya layak untuk menerima pemberian waktunya.
64. Dengan siapa Anda mengidentifikasi diri? Pertanyaan ini sulit, langsung, dan tegas. Anda serupa dengan siapa dari antara mereka? Kita harus mengakui godaan di sekitar kita untuk mengabaikan orang lain, terutama yang paling lemah. Katakanlah, kita telah maju dalam banyak hal, tetapi kita buta huruf dalam hal mendampingi, memedulikan, dan mendukung yang paling rapuh dan lemah di masyarakat kita yang sudah maju. Kita sudah terbiasa memalingkan wajah, melewati, mengabaikan aneka situasi sampai hal itu mengenai kita secara langsung.
65. Seseorang diserang di jalan dan banyak orang bergegas berlalu seolah-olah tidak melihat apa pun. Seringkali ada orang yang menabrak seseorang dengan mobilnya dan melarikan diri. Mereka hanya memikirkan bagaimana menghindari masalah, tidak peduli jika seorang manusia mati karena kesalahan mereka. Semuanya ini adalah tanda suatu gaya hidup umum yang terungkap dengan berbagai cara, bisa juga dengan cara-cara lebih halus. Selain itu, karena kita semua sangat terpusat pada kebutuhan kita sendiri, melihat saja seseorang yang menderita sudah mengganggu kita, merisaukan kita, karena kita tidak ingin membuang-buang waktu dengan masalah orang lain. Ini adalah gejala suatu masyarakat yang sakit karena berusaha mengembangkan dirinya dengan mengabaikan penderitaan.
66. Lebih baik kita tidak jatuh ke dalam kemalangan seperti itu. Marilah kita memperhatikan contoh orang Samaria yang murah hati. Nas ini mengundang kita untuk menghidupkan kembali panggilan kita sebagai warga dari negara kita masing-masing dan dari seluruh dunia, sebagai para pembangun ikatan sosial baru. Inilah panggilan yang selalu baru, meskipun telah tertulis sebagai hukum dasar keberadaan kita: bahwa masyarakat harus bergerak maju untuk mengejar kebaikan bersama dan, mulai dari tujuan ini, selalu membangun kembali tatanan politik dan sosialnya, tatanan relasi-relasinya, proyek kemanusiaannya. Dengan tindakan-tindakannya, orang Samaria yang murah hati itu menunjukkan bahwa “keberadaan kita masing-masing terkait dengan keberadaan orang-orang lain: hidup bukanlah sekadar waktu yang berlalu, melainkan waktu perjumpaan.”[57]
67. Perumpamaan ini menjadi gambaran yang mencerahkan, yang mampu menyoroti pilihan dasar yang perlu kita buat untuk membangun kembali dunia yang menyakiti kita ini. Dalam menghadapi begitu banyak penderitaan dan luka-luka, satu-satunya jalan keluar adalah menjadi seperti orang Samaria yang murah hati. Pilihan lain apa pun akan menuntun kita entah ke sisi para perampok atau ke sisi mereka yang lewat tanpa memiliki bela rasa atas penderitaan orang yang terluka di pinggir jalan. Perumpamaan ini menunjukkan kepada kita inisiatif mana yang mampu membangun kembali sebuah komunitas, mulai dari laki-laki dan perempuan yang menjadikan kerapuhan orang lain sebagai kerapuhannya sendiri, yang menolak pembangunan masyarakat yang ditandai dengan pengucilan, tetapi menjadi sesama manusia dari orang yang jatuh, dan mengangkat serta memulihkannya, sehingga kebaikan itu menjadi kebaikan bersama. Pada saat yang sama, perumpamaan ini memperingatkan kita terhadap sikap tertentu dari mereka yang hanya peduli pada dirinya sendiri dan tidak mau menanggung tuntutan-tuntutan yang tak terhindarkan dari realitas manusia.
68. Mari kita katakan dengan jelas, cerita ini tidak hanya menyampaikan ajaran tentang cita-cita abstrak, juga tidak membatasi dirinya hanya pada fungsi moralitas sosial-etis. Cerita ini berbicara kepada kita tentang ciri khas esensial kemanusiaan, yang sering dilupakan: kita diciptakan untuk kepenuhan yang hanya dapatdicapai dalam kasih. Hidup acuh tak acuh terhadap penderitaan tidak dapat menjadi pilihan; kita tidak bisa membiarkan seseorang tetap “hidup di pinggiran.” Ini harus membuat kita geram, hingga membuat kita keluar dari ketenangan kita karena terganggu oleh penderitaan manusia. Itulah martabat!
Sebuah kisah yang terulang kembali
69. Kisah ini sederhana dan lurus, namun mengandung seluruh dinamika pergulatan batin yang terjadi dalam penjabaran jati diri kita, dalam setiap keberadaan yang dirancang dalam perjalanan untuk mewujudkan persaudaraan manusia. Begitu berada dalam perjalanan, kita pasti bertemu dengan orang yang terluka. Saat ini semakin banyak orang yang terluka. Penerimaan atau penyingkiran terhadap orang-orang yang menderita di sepanjang jalan menentukan setiap perencanaan ekonomi, politik, sosial atau agama. Setiap hari kita dihadapkan pada pilihan menjadi orang Samaria yang murah hati atau pejalan kaki yang melintas acuh tak acuh dari seberang jalan. Dan jika kita memperluas pandangan kita ke seluruh sejarah hidup kita dan ke sejarah dunia secara keseluruhan, kita semua saat ini atau pernah menjadi seperti tokoh-tokoh itu: dalam diri kita, kita semua memiliki sesuatu dari orang yang terluka, sesuatu dari perampok, sesuatu dari orang yang melintasdari seberang jalan, dan sesuatu dari orang Samaria yang murah hati.
70. Sungguh menarik bagaimana pelbagai perbedaan antara tokoh-tokoh dalam cerita itu berubah sepenuhnya ketika mereka dihadapkan dengan pemandangan menyakitkan seorang manusia yang terjatuh dan terhina. Tidak ada lagi perbedaan antara penduduk Yudea dan penduduk Samaria, tidak ada imam atau pedagang; hanya ada dua jenis orang: mereka yang peduli terhadap penderitaan orang lain dan mereka yang lewat dari seberang jalan; mereka yang membungkuk untuk memperhatikan orang yang jatuh dan mereka yang memalingkan muka dan mempercepat langkahnya. Sungguh, semua topeng kita, label kita, dan penyamaran kita jatuh: ini adalah momen kebenaran. Akankah kita membungkuk untuk menyentuh dan merawat luka orang lain? Akankah kita membungkuk untuk saling bahu membahu? Itulah tantangan saat ini, yang tidak perlu membuat kita takut. Di saat-saat krisis, pilihan menjadi mendesak: bisa dikatakan bahwa siapa pun, yang pada saat seperti itu bukan perampok dan bukan orang yang lewat dari jauh, adalah entah sendiri terluka atau sedang memanggul orang yang terluka di pundaknya.
71. Kisah orang Samaria yang murah hati terulang kembali: semakin nyata bahwa ketidakpedulian sosial dan politik mengubah banyak bagian dunia ini menjadi jalan-jalan terpencil di mana konflik-konflik dalam negeri dan internasional serta perampasan peluang membuat banyak orang tersingkirkan, telantar di pinggir jalan. Dalam perumpamaannya, Yesus tidak menawarkan jalan-jalan alternatif, misalnya: apa yang akan terjadi dengan orang yang terluka parah itu atau orang yang membantunya seandainya kemarahan atau rasa haus akan balas dendam mendapat ruang di hati mereka? Yesus percaya pada sisi terbaik jiwa manusia dan dengan perumpamaan ini Dia mendorongnya untuk berpaut pada kasih, memulihkan orang yang menderita dan membangun suatu masyarakat yang layak menyandang sebutan itu.
Tokoh-tokoh dalam kisah
72. Perumpamaan dimulai dengan para perampok. Titik tolak yang Yesus pilih adalah sebuah perampokan yang telah terjadi. Ia tidak membiarkan kita berhenti untuk meratapi peristiwa itu, Ia tidak mengarahkan pandangan kita pada para perampok. Kita mengenal mereka. Kita telah melihat bayang-bayang gelap penelantaran, penggunaan kekerasan untuk kepentingan sempit pemegang kekuasaan, juga keserakahan, dan perpecahan yang berkembang pesat di dunia kita. Pertanyaannya mungkin demikian: akankah kita meninggalkan orang yang terluka tergeletak di tanah dan lari untuk melindungi diri dari kekerasan itu atau untuk mengejar para perampok? Apakah orang yang terluka itu akan menjadi pembenaran diri kita atas segala perpecahan kita yang tidak dapat didamaikan, segala ketidakpedulian kita yang kejam, dan segala konflik internal kita?
73. Selanjutnya, perumpamaan ini dengan jelas mengarahkan pandangan kita pada orang-orang yang melewati dari seberang jalan. Ketidakpedulian yang berbahaya untuk melanjutkan perjalanan tanpa berhenti sejenak, –secara bersalah atau tidak, akibat pandangan hina atau kebingungan yang menyedihkan– membuat sosok imam dan orang Lewi itu menjadi cerminan yang tak kalah menyedihkan dari jarak yang memisahkan kita dari realitas. Ada banyak cara untuk melewati dari seberang jalan, yang saling melengkapi. Salah satunya adalah menarik diri ke dalam dunianya sendiri, tanpa minat pada orang lain, acuh tak acuh. Cara yang lain, mengalihkan pandangan ke luar. Berkenaan dengan cara melewati dari seberang jalan yang terakhir ini, di beberapa negara, atau di kalangan tertentu ada pandangan hina terhadap orang miskin dan budaya mereka; ada suatu kehidupan dengan pandangan yang diarahkan keluar, seolah-olah rencana pembangunan yang diimpor dari luar dapat mengambil tempat orang miskin. Dengan demikian, ketidakpedulian beberapa orang dapat dibenarkan, karena permintaan bantuan orang-orang miskin yang sesungguhnya dapat menyentuh hati mereka, sama sekali tidak ada; orang-orang itu berada di luar jangkauan minat mereka.
74. Pada mereka yang melewati dari seberang jalan ada detail yang tidak boleh kita abaikan: mereka adalah orang-orang religius. Terlebih lagi, mereka mempersembahkan diri untuk beribadat kepada Allah: seorang imam dan seorang Lewi. Ini patut diperhatikan: ini menunjukkan bahwa percaya kepada Allah dan menyembah-Nya tidak menjamin hidup sesuai dengan kehendak Allah. Seseorang yang beriman bisa tidak setia pada semua yang dituntut oleh imannya itu, namun mungkin merasa dekat dengan Allah dan merasa dirinya lebih pantas daripada yang lain. Akan tetapi, ada juga cara menghayati iman yang membantu keterbukaan hati kepada sesama saudara, dan itulah yang menjadi jaminan keterbukaan autentik kepada Allah. Santo Yohanes Krisostomus mengungkapkan tantangan ini bagi umat Kristen dengan sangat jelas: “Apakah Anda benar-benar ingin menghormati tubuh Kristus? Jangan meremehkan-Nya saat Dia telanjang. Jangan menghormati-Nya di gereja dengan jubah sutra, sementara Anda membiarkan Dia di luar menderita kedinginan dan ketelanjangan.”[58] Paradoksnya adalah bahwa, kadang-kadang, mereka yang mengatakan tidak beriman dapat menghayati kehendak Allah dengan lebih baik daripada orang beriman.
75. “Para perampok di jalan” biasanya memiliki sekutu-sekutu rahasia dalam mereka yang “melewati jalan itu sambil melihat ke arah lain.” Ada lingkaran tertutup di antara mereka yang memperalat dan menipu masyarakat untuk merampoknya dan mereka yang beranggapan mereka menjaga kemurnian dalam fungsi kritis mereka, tetapi pada saat yang sama hidup dari sistem dan sumber dayanya itu. Ada kemunafikan yang menyedihkan ketika impunitas atas kejahatan, atas penggunaan institusi demi keuntungan pribadi atau perusahaan, dan kejahatan-kejahatan lain yang belum dapat kita berantas, disertai dengan kritikan terus menerus terhadap apa pun, dengan kecurigaan yang terus ditaburkan, yang mengakibatkan ketidakpercayaan serta kebingungan. Tipuan “segalanya berjalan salah” dijawab dengan “tidak ada yang bisa memperbaikinya”, “apa yang bisa saya lakukan?” Dengan demikian, dipupuk kekecewaan dan keputusasaan, yang tidak mendorong semangat solidaritas dan kemurahan hati. Menjerumuskan suatu bangsa ke dalam keputusasaan adalah menutupi lingkaran setan secara sempurna: demikianlah bekerja kediktatoran tak terlihat dari kepentingan tersembunyi yang sebenarnya, yang menguasai baik sumber-sumber daya maupun kecakapan untuk beropini dan berpikir.
76. Akhirnya, mari kita memperhatikan orang yang terluka itu. Terkadang kita merasa seperti dia, terluka parah dan tergeletak di pinggir jalan. Kita pun merasa ditinggalkan oleh lembaga-lembaga kita yang terabaikan dan kurang sumber daya, atau yang diarahkan untuk melayani kepentingan beberapa orang saja, di dalam dan dari luar. Memang, “masyarakat global saat ini memiliki cara yang elegan untuk mengalihkan pandangannya: yang biasanya dilakukan dengan kedok kebenaran politik atau model ideologis, mereka memandang orang yang menderita tanpa menyentuhnya, lalu menayangkannya secara langsung di televisi, bahkan dengan memakai ujaran yang tampaknya toleran dan penuh eufemisme.”[59]
Memulai kembali
77. Setiap hari kita ditawari kesempatan baru, tahap baru. Kita tidak boleh mengharapkan semuanya dari mereka yang memerintah kita, sebab itu akan kekanak-kanakan. Kita memiliki ruang untuk tanggung jawab bersama, yang mampu memulai dan mengembangkan proses-proses dan perubahan-perubahan baru. Kita hendaknya berperan aktif dalam membangun kembali dan membantu masyarakat yang terluka. Hari ini kita diberi kesempatan istimewa untuk mengungkapkan keberadaan kita sebagai saudara, untuk menjadi orang Samaria lain yang murah hati yang menanggung rasa sakit kegagalan-kegagalan, alih-alih membangkitkan kebencian dan dendam. Sama seperti musafir yang kebetulan lewat dalam cerita kita, kita hanya perlu memiliki keinginan yang tulus, murni, dan sederhana, untuk menjadi suatu bangsa, untuk terus menerus dan tanpa kenal lelah berkomitmen untuk melibatkan, mengintegrasikan, dan membangunkan orang yang telah jatuh; bahkan jika kita berkali-kali terjerumus dan terkutuk untuk mengulangi logika kekerasan, logika dari mereka yang hanya mementingkan diri sendiri dan menyebarkan kebingungan dan kebohongan. Sementara orang lain mungkin terus memikirkan politik atau ekonomi untuk permainan kekuasaan mereka, marilah kita memupuk apa yang baik dan mendedikasikan diri kita untuk melayani kebaikan itu.
78. Kita dapat mulai dari bawah, kasus per kasus, untuk memperjuangkan yang paling konkret dan di tingkat lokal, hingga mencapai sudut terjauh tanah air kita dan seluruh dunia, dengan perhatian yang sama seperti yang dimiliki oleh pejalan dari Samaria bagi segala cedera orang yang terluka. Marilah kita mencari orang-orang lain dan merengkuh realitas apa adanya, tanpa takut akan rasa sakit atau ketidakberdayaan, karena di situ ditemukan semua kebaikan yang telah ditaburkan Allah dalam hati manusia. Kesulitan yang tampak sangat besar merupakan kesempatan untuk bertumbuh, bukan alasan untuk bersedih tanpa daya yang cenderung mendukung kepasrahan. Tapi jangan mengerjakannya sendiri, secara individual. Orang Samaria mencari seorang pemilik penginapan yang bisa merawat orang terluka itu; kita pun dipanggil untuk mengajak orang lain dan berjumpa dalam suatu “kita” yang lebih kuat daripada sekadar sejumlah individu yang kecil; mari kita ingat bahwa “keseluruhan melebihi bagian, dan juga melebihi jumlah total bagian-bagiannya.”[60] Mari kita singkirkan kepicikan dan kebencian dari partikularisme mandul dan dari konfrontasi tanpa akhir. Mari kita berhenti menyembunyikan rasa sakit karena kehilangan dan bertanggung jawab atas kejahatan kita, kemalasan kita, dan kebohongan kita. Rekonsiliasi yang memulihkan akan membangkitkan kita dan membebaskan kita dan orang lain dari rasa takut.
79. Orang Samaria itu melanjutkan perjalanannya tanpa menantikan pengakuan atau ucapan terima kasih. Dedikasi untuk melayani memberinya kebahagiaan besar dalam hidupnya di hadapan Allahnya, dan karena itu menjadi kewajiban. Kita semua memiliki tanggung jawab terhadap orang yang terluka, ialah bangsa kita sendiri dan semua bangsa di bumi. Marilah kita merawat kerapuhan setiap laki-laki, setiap perempuan, setiap anak, dan setiap orang lanjut usia, dengan sikap solidaritas dan perhatian, dengan sikap kedekatan yang ada pada orang Samaria yang murah hati.
Sesama manusia tanpa batas-batas
80. Yesus menyampaikan perumpamaan ini untuk menjawab pertanyaan: siapakah sesamaku manusia? Kata “sesama” dalam masyarakat zaman Yesus biasanya menunjukkansiapayang paling dekat, tetangga. Maksudnya, bantuan harus diberikan terutama kepada mereka yang termasuk dalam kelompoknya sendiri, suku bangsanya sendiri. Seorang Samaria, bagi sebagian orang Yahudi pada zaman itu, dianggap sebagai orang yang hina dan najis, dan oleh karena itu tidak termasuk di antara sesama yang perlu dibantu. Yesus, seorang Yahudi, sepenuhnya memutarbalikkan pendekatan itu: Ia tidak memanggil kita untuk bertanya siapa yang dekat dengan kita, tetapi untuk menjadikan diri kita dekat, menjadi sesama manusia.
81. Anjuran Yesus itu ialah untuk hadir bagi orang yang membutuhkan bantuan, tanpa melihat apakah ia termasuk anggota kelompok kita. Dalam kasus ini, orang Samaria menjadikan dirinya sesama dari orang Yahudi yang terluka. Untuk membuat dirinya dekat dan hadir, ia telah mengatasi segala hambatan budaya dan sejarah. Yesus menyimpulkannya dengan sebuah permintaan: “Pergi dan berbuatlah demikian” (Luk. 10:37). Artinya, Ia menantang kita untuk mengesampingkan segala perbedaan dan, berhadapan dengan penderitaan, menjadi dekat dengan siapa saja yang mengalaminya. Oleh karena itu, saya tidak lagi mengatakan bahwa saya mempunyai “sesama” yang harus dibantu, tetapi saya merasa terpanggil untuk menjadi sesama bagi orang lain.
82. Masalahnya adalah, Yesus dengan tegas menyoroti bahwa orang yang terluka itu adalah seorang Yahudi, seorang penduduk Yudea, sedangkan orang yang berhenti dan menolongnya adalah seorang Samaria, seorang penduduk Samaria. Detail ini sangat penting untuk merenungkan cinta kasih yang terbuka untuk semua orang. Orang-orang Samaria mendiami suatu wilayah yang telah dicemari oleh ritus kafir, dan bagi orang-orang Yahudi hal ini membuat mereka najis, menjijikkan, berbahaya. Pada kenyataannya, suatu teks Yahudi kuno yang menyebutkan beberapa bangsa yang dipandang hina, mengacu pada Samaria, dengan menyatakan bahwa mereka “bukan suatu bangsa” (Sir. 50:25), dan menambahkan bahwa itulah “bangsa bodoh yang menetap di Sikhem” (ay. 26).
83. Hal ini menjelaskan mengapa seorang perempuan Samaria, ketika Yesus minta dia untuk memberinya minum, menjawab dengan tegas: “Masakan Engkau, seorang Yahudi, minta minum kepadaku, seorang perempuan Samaria?” (Yoh. 4:9). Tuduhan paling buruk yang ditemukan oleh mereka yang berusaha untuk mendiskreditkan Yesus, adalah mencapnya sebagai “orang Samaria” dan “kerasukan setan” (Yoh. 8:48). Oleh karena itu, perjumpaan penuh belas kasihan antara seorang Samaria dan seorang Yahudi ini merupakan sebuah provokasi kuat, yang membantah setiap manipulasi ideologis, sehingga kita dapat memperluas lingkaran kita, dengan memberikan suatu dimensi universal kepada kemampuan kita untuk mencintai, mampu mengatasi semua prasangka, semua hambatan sejarah dan budaya, semua kepentingan sempit.
Seruan orang asing
84. Akhirnya, saya ingat bahwa Yesus dalam perikop lain Injil berkata: “ketika Aku seorang asing, kamu memberi Aku tumpangan” (Mat. 25:35). Yesus dapat mengucapkan kata-kata itu karena Ia memiliki hati terbuka yang menjadikan derita orang lain milik-Nya sendiri. Santo Paulus menyerukan: “Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis!” (Rom. 12:15). Ketika hati kita mengambil sikap demikian ini, ia mampu mengidentifikasi diri dengan yang lain, terlepas dari lahir di mana atau berasal dari mana. Dengan masuk ke dalam dinamika itu, ia akhirnya mengalami bahwa orang lain adalah “dagingnya sendiri” (Yes. 58:7.
85. Bagi umat Kristen, perkataan Yesus juga memiliki dimensi lain, yang transenden. Perkataan itu menyiratkan bahwa Kristus sendiri dapat dikenali dalam setiap saudara yang ditinggalkan atau dikucilkan (lih. Mat. 25:40, 45). Sesungguhnya, iman memberi motivasi-motivasi tak terkira untuk mengakui orang lain, karena orang beriman dapat mengakui bahwa Allah mencintai setiap manusia dengan kasih yang tak terbatas dan bahwa “dengan demikian Ia menganugerahkan martabat yang tak terbatas kepadanya.”[61] Tambahan lagi, kita percaya bahwa Kristus menumpahkan darahnya untuk semua, untuk setiap orang, dan karena itu tak seorang pun dikecualikan dari kasihnya yang universal. Dan jika kita melangkah menuju sumber utama, yaitu kehidupan Allah yang terdalam, kita menjumpai persekutuan tiga Pribadi, asal mula dan model sempurna dari setiap kehidupan bersama. Teologi terus memperkaya dirinya dengan merenungkan kebenaran agung ini.
86. Kadang-kadang saya sedih dengan kenyataan bahwa Gereja, meskipun memiliki motivasi seperti itu, membutuhkan waktu lama untuk secara tegas mengutuk perbudakan dan berbagai bentuk kekerasan. Saat ini, dengan perkembangan spiritualitas dan teologi, kita tidak punya dalih lagi. Namun, masih ada yang merasa bahwa keyakinan iman mereka mendorong atau setidaknya memungkinkan mereka untuk mendukung berbagai bentuk nasionalisme yang tertutup dan penuh kekerasan, sikap-sikap xenofobia, penghinaan dan bahkan penganiayaan terhadap mereka yang berbeda. Untuk menghadapi kecenderungan-kecenderungan seperti itu, keyakinan iman, bersama dengan humanisme yang diilhaminya, harus menjaga supaya kesadaran kritis kita tetap hidup dan membantu untuk bereaksi dengan cepat pada saat kecenderungan itu mulai menyusupi. Oleh karena itu, penting bahwa katekese dan khotbah secara tegas dan jelas berbicara juga tentang makna sosial keberadaan kita, dimensi spiritualitas persaudaraan, keyakinan akan martabat yang tak dapat dicabut dari setiap pribadi, dan dorongan untuk mengasihi dan menerima semua orang.
BAB TIGA
MEMIKIRKAN DAN MENCIPTAKAN DUNIA YANG TERBUKA
87. Manusia diciptakan sedemikian rupa sehingga ia tidak dapat mewujudkan dirinya, berkembang, dan menemukan kepenuhannya “tanpa dengan tulus memberikan dirinya.”[62] Dan ia juga tidak sepenuhnya mengenali kebenarannya sendiri kecuali dalam perjumpaan dengan orang lain: “Saya berkomunikasi secara efektif dengan diri saya sendiri hanya sejauh saya berkomunikasi dengan orang lain.”[63] Ini menjelaskan mengapa tak seorang pun bisa menghayati nilai hidup tanpa wajah-wajah nyata untuk dicintai. Di sinilah terletak rahasia keberadaan manusia yang sejati, karena “hidup ada di mana ada ikatan, persekutuan, persaudaraan; dan hidup itu lebih kuat daripada kematian bila dibangun di atas hubungan yang benar dan ikatan kesetiaan. Sebaliknya, tidak ada hidup di mana seseorang beranggapan hanya menjadi milik dirinya sendiri dan hidup sebagai pulau: dalam sikap seperti itu kematian menang.”[64]
Keluar dari diri sendiri
88. Dari kedalaman setiap hati, kasih menciptakan ikatan dan memperluas keberadaan ketika ia membawa orang keluar dari dirinya sendiri menuju orang lain.[65] Kita diciptakan untuk kasih dan di dalam diri kita masing-masing ada “semacam hukum ‘ekstasis’: bergerak keluar dari diri sendiri untuk menemukan dalam diri orang lain perkembangan keberadaannya.”[66] Oleh karena itu “bagaimanapun, manusia sendiri harus sesekali berani melompat keluar dari dirinya sendiri.”[67]
89. Di sisi lain, saya juga tidak dapat mempersempit kehidupan saya pada hubungan dengan kelompok kecil atau bahkan dengan keluarga saya saja karena tidak mungkin memahami diri saya sendiri tanpa jalinan hubungan yang lebih luas: bukan hanya hubungan yang sekarang, melainkan juga yang telah mendahului saya dan membentuk saya sepanjang hidup saya. Hubungan saya dengan seseorang yang saya hargai tidak boleh melupakan bahwa orang ini tidak hidup hanya untuk hubungannya dengan saya, saya juga tidak hidup hanya untuk berhubungan dengan dia. Hubungan kita, bila sehat dan autentik, membuka kita kepada orang-orang lain yang membuat kita tumbuh dan memperkaya kita. Saat ini naluri-naluri sosial yang paling mulia dengan mudah menghilang di balik keakraban yang egois yang memberi kesan hubungan yang intens. Sebaliknya, kasih autentik, yang membantu kita untuk tumbuh, dan bentuk-bentuk persahabatan yang paling mulia mendiami hati yang membiarkan dirinya disempurnakan. Ikatan pasangan dan persahabatan diarahkan untuk membuka hati kepada sekitar kita, sehingga memungkinkan kita bergerak keluar dari diri sendiri untuk menyambut semua orang. Kelompok tertutup dan pasangan yang mengacu pada diri sendiri, yang membentuk diri sebagai “kami” yang berlawanan dengan seluruh dunia, biasanya merupakan bentuk-bentuk egoisme yang diidealkan dan perlindungan diri sendiri belaka.
90. Bukan kebetulan bahwa banyak masyarakat kecil yang hidup di daerah gurun mengembangkan kemampuan bermurah hati untuk menyambut para peziarah yang lewat, dan dengan demikian memberikan suatu tanda keteladanan dari tugas suci keramahtamahan. Komunitas para rahib abad pertengahan juga menghayati hal itu, seperti dapat dilihat dalam Regula Santo Benediktus. Meski itu dapat mengganggu keteraturan dan keheningan biara, Benediktus menuntut agar orang miskin dan para peziarah diperlakukan “dengan segala rasa hormat dan perhatian yang mungkin.”[68] Keramahtamahan adalah cara konkret untuk tidak kehilangan tantangan dan anugerah yang ditemukan dalam perjumpaan dengan manusia dari luar kelompoknya sendiri. Orang-orang seperti itu menyadari bahwa segala nilai yang dapat mereka kembangkan harus disertai dengan kemampuan untuk melampaui diri sendiri dalam keterbukaan kepada orang lain.
Nilai unik cinta kasih
91. Orang dapat mengembangkan sikap-sikap tertentu yang menghadirkan nilai-nilai moral: ketabahan, keugaharian, kerja keras, dan keutamaan-keutamaan lainnya. Namun, untuk mengarahkan tindakan berbagai keutamaan moral secara tepat, orang harus juga mempertimbangkan sejauh mana tindakan tersebut sungguh mencapai dinamisme keterbukaan dan persatuan terhadap orang lain. Dinamisme seperti itu adalah kasih yang ditanamkan Allah. Tanpa itu, kita mungkin hanya terkesan memiliki kebajikan yang tidak mampu membangun kehidupan bersama. Karena itu Santo Tomas Aquinas –mengutip Santo Agustinus– mengatakan bahwa kesederhanaan orang pelit malah bukan kebajikan.[69] Santo Bonaventura, dengan kata lain, menjelaskan bahwa tanpa kasih, keutamaan-keutamaan lain secara tegas tidak memenuhi perintah-perintah “seperti yang dimaksudkan oleh Allah.” [70]
92. Tingkat spiritual hidup manusia ditentukan oleh kasih, yang pada akhirnya menjadi “kriteria untuk keputusan definitif tentang bernilai atau tidaknya hidup manusia.”[71] Namun, ada orang beriman yang berpikir bahwa kebesaran mereka terletak dalam memaksakan ideologi mereka kepada orang lain, atau dalam membela kebenaran dengan kekerasan, atau dalam menunjukkan kekuatan yang besar. Kita, orang beriman, semuanya harus menyadari ini: yang terpenting adalah kasih yang tidak boleh dipertaruhkan; bahaya terbesar adalah tidak mengasihi (lih. 1Kor. 13:1-13).
93. Dalam upaya untuk menjabarkan apa yang termasuk dalam pengalaman mengasihi yang dimungkinkan dengan rahmat Allah, Santo Tomas Aquinas menjelaskannya sebagai gerakan yang memusatkan perhatian kepada yang lain “dengan menganggapnya sebagai satu dengan dirinya sendiri.”[72] Perhatian afektif yang diberikan kepada orang lain membangkitkan keinginan untuk mengupayakan kebaikannya dengan murah hati. Semuanya ini bertolak dari sebuah penghargaan, dari sebuah apresiasi, yang pada akhirnya adalah apa yang ada di balik kata “caritas”: orang yang dikasihi bagi saya adalah ”terkasih” (caro), artinya saya menganggapnya sangat berharga.[73] Dan “dari kasih yang membuat seseorang menyukai orang lain mengalirlah kemurahan-kemurahan terhadapnya.”[74]
94. Karena itu, kasih melibatkan lebih dari sekadar serangkaian tindakan kebajikan. Tindakan-tindakan itu bersumber dari persatuan yang semakin terarahkepada yang lain, karena menganggapnya berharga, layak, menyenangkan, dan indah, terlepas dari penampilan fisik atau moral. Kasih untuk orang lain, sebagaimana adanya dirinya, mendorong kita untuk mengusahakan yang terbaik bagi hidupnya. Hanya dengan mengembangkan cara berelasi seperti ini kita akan memungkinkan persahabatan sosial yang tidak mengecualikan siapa pun dan persaudaraan yang terbuka terhadap semua.
Kasih yang semakin terbuka
95. Kasih akhirnya mendorong kita menuju persekutuan universal. Tidak seorang pun yang menjadi dewasa atau mencapai kepenuhan dengan mengasingkan diri. Dengan dinamikanya sendiri, kasih menuntut keterbukaan yang makin berkembang, kemampuan makin besar untuk menerima orang-orang lain, dalam petualangan tanpa akhir yang membuat semua pinggiran bertemu dalam rasa saling memiliki sepenuhnya. Yesus berkata kepada kita: “Kamu semua adalah saudara” (Mat. 23:8).
96. Kebutuhan untuk melampaui batas-batas kita sendiri juga berlaku untuk berbagai wilayah dan negara. Nyatanya, “terus meningkatnya jumlah interkoneksi dan komunikasi yang meliputi seluruh planet kita membuat kesadaran kita akan persatuan dan berbagi nasib bersama di antara segala bangsa di bumi menjadi lebih nyata. Dalam dinamisme sejarah, terlepas dari keragaman suku bangsa, masyarakat, dan budaya, kita melihat benih panggilan untuk membentuk suatu komunitas yang terdiri dari saudara-saudara yang saling menerima dan peduli satu sama lain.”[75]
Masyarakat terbuka yang mengintegrasikan semua orang
97. Ada beberapa pinggiran yang dekat dengan kita, di tengah kota atau dalam keluarga kita. Ada juga aspek keterbukaan universal dalam kasih yang tidak bersifat geografis tetapi eksistensial. Ini menyangkut kemampuan sehari-hari untuk memperluas lingkaran saya, untuk menjangkau mereka yang secara spontan tidak saya rasakan sebagai bagian dari dunia perhatian saya, meskipun mereka dekat dengan saya. Selain itu, setiap saudara atau saudari yang menderita, ditinggalkan atau diabaikan oleh masyarakat saya adalah orang asing yang eksistensial, meskipun lahir di negara yang sama. Ia mungkin adalah warga negara dengan semua dokumennya, tetapi diperlakukan seperti orang asing di negerinya sendiri. Rasisme adalah virus yang mudah bermutasi dan, bukannya menghilang, bersembunyi, tetapi selalu siap menyerang.
98. Saya ingin menyebutkan beberapa dari “orang-orang buangan tersembunyi” yang diperlakukan sebagai sekumpulan orang asing di masyarakat.[76] Banyak penyandang disabilitas “merasa hidup tanpa turut memiliki dan tanpa berpartisipasi.” Masih banyak hal yang “menghalangi mereka untuk menikmati kewarganegaraan penuh.” Tujuannya bukan hanya bantuan bagi mereka, tetapi “partisipasi aktif mereka dalam komunitas sipil dan gerejawi. Inilah suatu perjalanan yang menuntut banyak dan juga melelahkan, tetapi perjalanan itu akan selalu memberikan sumbangan makin besar kepada pembentukan hati nurani yang mampu mengakui setiap orang sebagai pribadi yang unik dan tak terulang.” Saya juga berpikir tentang para lansia “yang, juga karena disabilitas mereka, terkadang dianggap sebagai beban.” Namun, mereka semua dapat memberikan “kontribusi unik kepada kebaikan bersama melalui kisah hidup mereka yang sungguh asli.” Saya ingin menegaskan: kita harus “berani bersuara bagi mereka yang didiskriminasi karena kondisi disabilitas mereka, karena sayangnya di beberapa negara, bahkan saat ini, masih ada kesulitan untuk mengakui mereka sebagai orang yang bermartabat sama.”[77]
Pemahaman yang tidak memadai tentang kasih universal
99. Cinta kasih yang melampaui segala batas didasarkan pada apa yang kita sebut sebagai “persahabatan sosial” di setiap kota dan di setiap negara. Persahabatan sosial murni dalam suatu masyarakat memungkinkan keterbukaan universal sejati. Ini bukanlah universalisme palsu dari mereka yang terus menerus harus bepergian karena tidak tahan dan tidak mencintai bangsanya sendiri. Siapa pun yang memandang rendah bangsanya sendiri akan menetapkan dalam masyarakatnya kategori kelas satu dan kelas dua, orang-orang dengan martabat dan hak-hak yang lebih atau yang kurang. Dengan cara itu, mereka menyangkal bahwa ada ruang untuk setiap orang.
100. Saya juga tidak mengusulkan universalisme yang otoriter dan abstrak, yang didikte atau dirancang oleh beberapa orang dan ditampilkan sebagai ideal yang seharusnya, dengan maksud untuk menyeragamkan, mendominasi dan menjarah. Ada suatu model globalisasi yang “secara sadar mengupayakan suatu keseragaman satu dimensi dan mencoba menghilangkan semua perbedaan dan aneka tradisi dalam pencarian dangkal untuk persatuan. […] Jika globalisasi beranggapan bisa membuat semua orang sama, seolah-olah itu sebuah bola, globalisasi itu menghancurkan anugerah-anugerah yang kaya dan kekhasan setiap pribadi dan setiap bangsa.”[78] Mimpi universalisme palsu itu berakhir dengan merampas dunia dari keragaman warnanya, keindahannya, dan akhirnya kemanusiaannya. Karena “masa depan bukanlah monokromatik (satu-warna). Jika kita memiliki keberanian, kita dapat melihat masa depan dalam keanekaragaman dan keberbedaan yang dapat disumbangkan masing-masing. Betapa banyak yang harus dipelajari oleh keluarga manusia untuk hidup berdampingan dalam harmoni dan damai tanpa perlu kita semua menjadi sama!”[79]
Melampaui dunia rekan-rekannya
101. Mari kita kembali ke perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati, karena itu masih mempunyai banyak hal untuk ditawarkan kepada kita. Seorang yang terluka tergeletak di jalan. Tokoh-tokoh yang melewatinya tidak berfokus pada panggilan batin mereka untuk menjadi sesama manusia, tetapi lebih pada jabatan mereka, posisi sosial yang mereka pegang, profesi bergengsi di masyarakat. Mereka merasa dirinya penting bagi masyarakat saat itu dan mengutamakan peran yang harus mereka mainkan. Orang yang terluka dan ditinggalkan di pinggir jalan merupakan gangguan bagi rencana itu, interupsi, dan terlebih lagi dia adalah seorang yang tidak memiliki fungsi. Dia “bukanlah siapa-siapa”, ia tidak termasuk kelompok yang layak diperhitungkan, ia tidak punya peran dalam membangun sejarah. Sedangkan orang Samaria yang murah hati menolak klasifikasi sempit seperti itu. Dia sendiri pun tidak termasuk semua kategori itu dan hanyalah seorang asing yang tidak memiliki tempatnya sendiri di masyarakat. Dengan demikian, bebas dari gelar dan struktur apa pun, ia dapat menghentikan perjalanannya, mengubah rencananya, siap sedia untuk membuka diri terhadap kejutan dari orang terluka yang membutuhkannya.
102. Reaksi apa yang dapat ditimbulkan oleh cerita itu pada saat ini, di dunia yang tiada hentinya menyaksikan kemunculan dan berkembangnya kelompok-kelompok sosial yang melekat pada identitas yang memisahkan mereka dari orang lain? Bagaimana cerita itu dapat menggerakkan mereka yang cenderung mengatur dunianya sedemikian rupa sehingga mencegah kehadiran segala yang asing yang dapat mengganggu identitas dan organisasi mereka yang membela diri dan merujuk pada diri sendirisaja? Dalam kerangka itu kemungkinan untuk menjadi sesama ditiadakan, dan dimungkinkan hanya bagi mereka yang bisa memperkuat keuntungan pribadi. Dengan demikian kata “sesama” kehilangan segala makna; hanya kata “rekan” mempunyai makna, dia yang menjadi rekan kerja untuk kepentingan tertentu.[80]
Kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan
103. Persaudaraan bukan hanya hasil dari kondisi penghormatan terhadap kebebasan individu, bukan juga dari kesetaraan tertentu yang diatur. Walaupun semuanya itu merupakan kondisi yang memungkinkan persaudaraan, tetapi tidak cukup untuk memunculkannya sebagai hasil yang mutlak. Persaudaraan dapat menawarkan hal yang positif pada kebebasan dan kesetaraan. Apa yang terjadi tanpa persaudaraan yang dibina secara sadar, tanpa kemauan politik untuk persaudaraan, yang diterjemahkan ke dalam pendidikan untuk persaudaraan, dialog, penemuan relasi timbal balik dan saling memperkaya sebagai hal-hal yang bernilai? Yang terjadi adalah bahwa kebebasan melemah, sehingga menghasilkan keadaan kesendirian, sepenuhnya bebas untuk memilih menjadi milik siapa atau apa, atau hanya untuk memiliki dan menikmati saja.Ini sama sekali tidak menguras kekayaan kebebasan, yang terutama berorientasi pada cinta kasih.
104. Kesetaraan juga tidak dicapai dengan merumuskan secara abstrak bahwa “semua manusia adalah setara”, tetapi adalah hasil pengolahan yang disadari dan pedagogis akan persaudaraan. Mereka yang hanya mampu menjadi rekan menciptakan dunia tertutup. Dalam kerangka itu, makna apa yang bisa diperoleh seseorang yang tidak termasuk dalam lingkaran rekan-rekan itu dan datang dengan memimpikan suatu kehidupan yang lebih baik bagi dirinya dan keluarganya?
105. Individualisme tidak membuat kita lebih bebas, lebih setara, lebih bersaudara. Jumlah kepentingan individual belaka tidak mampu menciptakan dunia yang lebih baik bagi seluruh umat manusia. Juga tidak dapat melindungi kita dari begitu banyak kejahatan yang semakin mengglobal. Tetapi, individualisme radikal adalah virus yang paling sulit dikalahkan. Individualisme menipu; membuat kita percaya bahwa segalanya terdiri dari memberi kebebasan kendali pada ambisinya sendiri, seolah-olah dengan menimbun ambisi dan keamanan individual kita dapat membangun kebaikan bersama.
Kasih universal yang memajukan pribadi-pribadi
106. Untuk berjalan menuju persahabatan sosial dan persaudaraan universal, diperlukan pengakuan yang mendasar dan penting ini: menyadari betapa berharganya seorang manusia, betapa berharganya seorang pribadi, selalu dan dalam keadaan apa pun. Jika setiap orang begitu berharga, harus dinyatakan dengan jelas dan tegas bahwa “fakta belaka bahwa beberapa orang dilahirkan di tempat-tempat yang memiliki sumber daya yang lebih sedikit atau perkembangan yang kurang tidak membenarkan bahwa mereka hidup secara kurang bermartabat.”[81] Ini adalah prinsip dasar kehidupan sosial, yang biasanya dan dengan berbagai cara diabaikan oleh mereka yang melihat bahwa hal itu tidak sesuai dengan pandangan dunia mereka atau tidak melayani tujuan mereka.
107. Setiap manusia berhak untuk hidup bermartabat dan berkembang seutuhnya, dan tidak ada negara yang dapat menyangkal hak asasi ini. Setiap orang memilikinya, meskipun ia kurang berdaya guna, meskipun ia lahir atau dibesarkan dengan keterbatasan; sebab hal itu tidak mengurangi martabatnya yang luhur sebagai pribadi manusia, yang tidak didasarkan pada keadaan tetapi pada nilai keberadaannya. Jika prinsip dasar ini tidak dijaga, tidak akan ada masa depan, baik untuk persaudaraan maupun untuk kelangsungan hidup umat manusia.
108. Beberapa masyarakat menerima prinsip ini sebagian saja. Mereka menerima bahwa setiap orang memiliki peluang, tetapi mereka mengatakan bahwa selanjutnya semuanya bergantung pada masing-masing. Dalam perspektif parsial ini, tidak masuk akal untuk “mendukung investasi dalam upaya-upaya membantu mereka yang tertinggal, yang lemah atau yang kurang berbakat untuk dapat menemukan peluang-peluang dalam hidup.”[82] Berinvestasi untuk orang-orang yang rentan barangkali tidak menguntungkan, dan dapat menyebabkan kurang efisiensi. Di sini kita membutuhkan negara yang hadir dan aktif, dan lembaga-lembaga masyarakat sipil yang melampaui kebebasan berbagai mekanisme efisiensi dari sistem ekonomi, politik atau ideologi tertentu, karena benar-benar berorientasi pertama-tama kepada rakyat dan kebaikan bersama.
109. Beberapa orang dilahirkan dalam keluarga kaya, menerima pendidikan yang baik, tumbuh dengan gizi yang baik, atau memiliki bakat bawaan yang luar biasa. Mereka tentu tidak membutuhkan negara yang aktif dan hanya akan menuntut kebebasan. Tapi jelas hal yang sama tidak berlaku bagi penyandang disabilitas, bagi mereka yang lahir di keluarga miskin, bagi mereka yang tumbuh dengan pendidikan berkualitas rendah dan kurang akses ke perawatan kesehatan yang semestinya. Jika masyarakat ditata menurut kriteria kebebasan pasar dan efisiensi, maka tidak ada tempat bagi mereka, dan persaudaraan hanya menjadi ekspresi romantis lain.
110. Memang, “berbicara tentang kebebasan ekonomi, sementara kondisi riil yang sebenarnya menghalangi banyak orang untuk mendapat akses nyata kepadanya dan juga akses ke lapangan kerja memburuk, menjadi wacana kontradiktif.”[83] Kata-kata seperti kebebasan, demokrasi, atau persaudaraan menjadi tidak berarti. Sebab, kenyataannya, “selama sistem sosial ekonomi kita masih menghasilkan satu korban dan masih ada satu orang yang disingkirkan, tidak mungkin ada pesta persaudaraan universal.”[84] Suatu masyarakat manusiawi dan bersaudara mampu memastikan secara efisien dan stabil bahwa semua orang didampingi dalam perjalanan hidupnya, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi agar mereka dapat memberikan yang terbaik dari dirinya, meskipun kinerja mereka bukanlah yang terbaik, gerak mereka lambat, dan kedayagunaan mereka kurang berarti.
111. Pribadi manusia, dengan hak-haknya yang tidak dapat dicabut, secara kodrati terbuka terhadap ikatan. Panggilan untuk melampaui diri sendiri dalam perjumpaan dengan orang lain berakar dari dalam dirinya. Karena itu, “orang harus berhati-hati agar tidak jatuh ke dalam kesalahpahaman yang dapat timbul dari kesalahpahaman tentang konsep hak-hak asasi manusia dan penyalahgunaannya yang bertolak belakang dengan maksudnya. Kenyataannya, saat ini ada kecenderungan untuk menuntut hak-hak individual yang semakin luas –saya tergoda untuk mengatakan individualistis–yang bersembunyi di baliksuatu konsep tentang pribadi manusia yang terlepas dari konteks sosial dan antropologis, hampir seperti “monad” (Yun.: monás, unit), yang semakin tidak peka terhadap yang lain […]. Jika hak setiap orang tidak diatur secara harmonis untuk kebaikan yang lebih besar, hak itu akhirnya dianggap tak terbatas dan dengan demikian menjadi sumber konflik dan kekerasan.”[85]
Mengembangkan kebaikan moral
112. Kita tidak boleh lupa menyebutkan bahwa keinginan dan upaya untuk kebaikan orang lain dan seluruh umat manusia juga berarti mengusahakan pendewasaan pribadi dan masyarakat dalam berbagai nilai moral yang mengarah pada perkembangan manusia seutuhnya. Dalam Perjanjian Baru, salah satu buah Roh Kudus disebutkan dengan istilah Yunani agathosyne (bdk. Gal. 5:22). Ini menunjukkan keterikatan pada yang baik, pencarian akan yang baik. Terlebih lagi, ini berarti menyediakan apa yang paling berharga, yang terbaik bagi orang lain: pendewasaan mereka, pertumbuhan mereka dalam kehidupan yang sehat, praktik nilai-nilai, dan bukan hanya kesejahteraan materi. Ada ungkapan Latin serupa: bene-volentia, yaitu sikap menginginkan kebaikan orang lain. Inilah suatu dambaan kuat akan kebaikan, kecenderungan terhadap semua yang baik dan sangat baik, yang mendorong kita untuk melimpahi kehidupan orang lain dengan hal-hal yang indah, luhur, dan membangun.
113. Dalam konteks ini, saya dengan rasa sedih kembali menekankan bahwa “kita sudah terlalu lama mengalami kemerosotan moral, kita mencemooh etika, kebaikan, iman, kejujuran. Waktunya telah datang untuk menyadari bahwa kedangkalan yang riang itu kurang bermanfaat bagi kita. Kehancuran seluruh landasan kehidupan sosial ini akhirnya membuat kita berbenturan satu sama lain, sementara masing-masing berusaha untuk menyelamatkan kepentingannya sendiri.”[86] Mari kita berbalik untuk meningkatkan kebaikan, untuk diri kita sendiri dan untuk seluruh umat manusia, dan dengan demikian kita akan maju bersama menuju pertumbuhan yang sejati dan utuh. Setiap masyarakat harus memastikan penerusan nilai-nilai, karena jika ini tidak terjadi, yang akan diteruskan adalah keegoisan, kekerasan, korupsi dalam berbagai bentuknya, ketidakpedulian dan, pada akhirnya, kehidupan yang tertutup untuk segala transendensi dan mengakar dalam kepentingan individu.
Nilai solidaritas
114. Saya ingin menggarisbawahi solidaritas, yang “sebagai kebajikan moral dan sikap sosial, buah dari pertobatan pribadi, membutuhkan komitmen dari banyak orang yang memiliki tanggung jawab di bidang pendidikan dan pembinaan. Saya memikirkan pertama-tama semua keluarga yang dipanggil kepada misi pendidikan yang pertama dan esensial. Keluarga merupakan tempat pertama di mana nilai-nilai kasih dan persaudaraan, hidup bersama dan berbagi, perhatian dan kepedulian terhadap sesama dihidupi dan diteruskan. Keluarga juga merupakan lingkungan istimewa untuk meneruskan iman, mulai dari sikap-sikap kesalehan pertama yang sederhana yang diajarkan para ibu kepada anak-anak mereka. Para pendidik dan pembina yang memiliki tugas berat untuk mendidik dan membina anak-anak dan remaja di sekolah atau di berbagai pusat anak dan remaja, dipanggil untuk menyadari bahwa tanggung jawab mereka menyangkut dimensi moral, spiritual dan sosial pribadi-pribadi tersebut. Nilai-nilai kebebasan, saling menghormati dan solidaritas dapat diteruskan sejak usia dini. […] Mereka yang bekerja di dunia budaya dan media sosial juga memiliki tanggung jawab dalam bidang pendidikan dan pembinaan, terutama dalam masyarakat kontemporer, di mana akses ke sarana informasi dan komunikasi semakin tersebar luas.”[87]
115. Pada saat ini ketika segala sesuatu tampak terpecah-pecah dan kehilangan konsistensi, ada baiknya kita berpaling kepada soliditas,[88] yang berasal dari pemahaman bahwa kita bertanggung jawab atas kerapuhan orang lain, saat kita berusaha membangun masa depan bersama. Solidaritas ditunjukkan secara konkret dalam pelayanan, yang dapat mengambil aneka bentuk dalam cara kita bertanggung jawab terhadap orang lain. Pelayanan adalah “sebagian besar, menjaga kerapuhan orang. Melayani berarti merawat mereka yang lemah di dalam keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita.” Dalam komitmen ini, masing-masing mampu “mengesampingkan kebutuhan, harapan, keinginannya untuk berkuasa di hadapan tatapan nyata orang-orang yang paling rapuh. […] Pelayanan selalu memandang wajah saudara itu, menyentuh dagingnya, merasakan kedekatannya sampai pada titik ‘merasakan sakitnya’, dan mengusahakan kemajuan saudara itu. Karena itu, pelayanan tidak pernah ideologis, karena yang dilayani bukan ide melainkan pribadi.”[89]
116. Orang-orang paling sederhana umumnya “mempraktikkan solidaritas khususyang ditemukan di antara mereka yang menderita, miskin, dan yang tampaknya telah dilupakan oleh peradaban kita, atau setidaknya sangat ingin dilupakan. Solidaritas adalah kata yang tidak selalu disukai; saya mau mengatakan bahwa kadang-kadang kita telah mengubahnya menjadi kata buruk yang tidak boleh diucapkan. Akan tetapi, kata ini mengungkapkan lebih dari sekadar beberapa tindakan kemurahan hati yang tidak tentu. Kata ini berarti berpikir dan bertindak dalam semangat komunitas, memprioritaskan kehidupan semua orang di atas perampasan barang oleh beberapa orang. Kata ini berarti juga memerangi penyebab struktural dari kemiskinan, ketimpangan, kurangnya pekerjaan, tanah dan perumahan, pengingkaran hak-hak sosial dan ketenagakerjaan. Artinya, menghadapi dampak merusak dari kerajaan uang […]. Solidaritas, dipahami dalam arti yang paling dalam, adalah suatu cara mencipta sejarah, dan itulah yang dilakukan oleh gerakan-gerakan populer.”[90]
117. Ketika kita berbicara tentang perawatan rumah kita bersama, yaitu planet ini, kita mengharapkan sedikit kesadaran universal dan kepedulian timbal balik yang mungkin masih tersisa di hati manusia. Sesungguhnya, jika seseorang berkelimpahan air, namun menghematnya dengan memikirkan kebutuhan seluruh umat manusia, itu karena ia telah mencapai tingkat moral yang memungkinkannya untuk melampaui dirinya sendiri dan kelompoknya sendiri. Itulah betapa luar biasa manusiawi! Sikap yang sama ini dibutuhkan untuk mengakui hak-hak semua manusia, bahkan jika mereka lahir di seberang batas-batas kita sendiri.
Menyarankan kembali fungsi sosial harta milik
118. Dunia ada untuk semua orang, karena kita manusia semuanya lahir di bumi ini dengan martabat yang sama. Perbedaan warna, agama, kemampuan, tempat asal, tempat tinggal, dan banyak lainnya tidak dapat diprioritaskan atau digunakan untuk membenarkan hak-hak istimewa beberapa orang hingga merugikan hak-hak semua orang. Karenanya, sebagai komunitas kita berkewajiban untuk memastikan bahwa setiap orang hidup bermartabat dan memiliki kesempatan yang cukup untuk perkembangannya yang utuh.
119. Pada abad-abad pertama iman Kekristenan, berbagai orang bijak pandai mengembangkan suatu kesadaran universal dalam permenungan mereka tentang tujuan umum dari barang-barang ciptaan.[91] Hal itu menimbulkan pemikiran bahwa jika seseorang tidak memiliki apa yang diperlukan untuk hidup bermartabat, itu karena orang lain telah merampasnya. Santo Yohanes Krisostomus menyimpulkannya dengan mengatakan sebagai berikut: “tidak memberikan kepada orang miskin sebagian dari harta milik kita adalah mencuri dari orang miskin; itu berarti merampas hidup mereka sendiri; apa yang kita miliki bukanlah milik kita, tetapi milik mereka.”[92] Seperti juga dalam kata-kata Santo Gregorius Agung: “Ketika kita memberikan kepada orang miskin hal-hal penting yang mereka butuhkan, kita tidak memberikan barang milik kita sendiri, tetapi kita mengembalikan apa yang menjadi milik mereka.”[93]
120. Sekali lagi saya menjadikan sebagai milik saya sendiri dan menganjurkan kepada setiap orang beberapa pernyataan dari Santo Yohanes Paulus II, yang kekuatannya mungkin belum dipahami: “Allah menganugerahkan bumi kepada seluruh umat manusia, supaya bumi menjadi sumber kehidupan bagi semua anggotanya, tanpa mengecualikan atau mengutamakan siapa pun juga.”[94] Sejalan dengan itu saya mengingatkan bahwa “tradisi Kristen tidak pernah mengakui hak milik pribadi sebagai hak mutlak yang tak dapat diganggu gugat, dan telah menekankan fungsi sosial setiap bentuk milik pribadi.”[95] Prinsip penggunaan bersama barang-barang ciptaan bagi semua adalah “prinsip pertama dari seluruh tatanan sosial-etis”,[96] dan merupakan hak kodrati, asali dan prioritas.[97] Semua hak lain atas barang-barang yang diperlukan untuk pemenuhan pribadi seutuhnya, termasuk hak milik pribadi dan hak lainnya, dengan demikian, “sama sekali tidak boleh menghalangi-halanginya. Malahan harus secara aktif melancarkan pelaksanaannya,”[98] sebagaimana ditegaskan Santo Paulus VI. Hak milik pribadi hanya dapat dianggap sebagai hak kodrati sekunder yang berasal dari prinsip tujuan universal barang-barang ciptaan, dan hal ini memiliki konsekuensi yang sangat konkret, yang harus tercermin dalam cara kerja masyarakat. Namun, seringkali terjadi bahwa hak-hak sekunder ditempatkan di atas hak-hak primer dan asali, dengan merampasnya dari kepentingan praktisnya.
Hak-hak tanpa batas-batas
121. Maka, tidak seorang pun bisa tetap disingkirkan karena tempat kelahirannya, apalagi karena hak istimewa yang dinikmati orang lain yang lahir di tempat dengan peluang lebih besar. Segala batas dan perbatasan negara-negara tidak dapat menghalangi terwujudnya hal itu. Sama seperti tidak dapat diterima bahwa seseorang memiliki hak yang lebih sedikit karena ia seorang perempuan, demikian juga tidak dapat diterima bahwa tempat kelahiran atau tempat tinggal mengakibatkan kurangnya kesempatan untuk hidup bermartabat dan mengembangkan diri.
122. Pembangunan tidak boleh berorientasi pada penumpukan harta dari beberapa orang, tetapi harus menjamin “hak-hak asasi manusia, pribadi dan sosial, ekonomis dan politis, termasuk hak-hak dari negara-negara dan bangsa-bangsa.”[99] Hak beberapa orang atas kebebasan berusaha atau berdagang tidak bisa berdiri di atas hak rakyat dan martabat orang miskin; dan bahkan tidak di atas penghormatan terhadap lingkungan hidup, karena “jika orang memiliki sesuatu, hal itu hanya untuk dikelolanya demi kesejahteraan semua.”[100]
123. Kegiatan wirausaha benar-benar “merupakan panggilan mulia untuk menghasilkan kekayaan dan memperbaiki dunia untuk semua.”[101] Allah mendorong kita dan mengharapkan kita mengembangkan kemampuan yang telah diberikan-Nya kepada kita dan Ia telah memenuhi alam semesta dengan banyak potensi. Dalam rencana Allah, setiap manusia dipanggil untuk meningkatkan pengembangan dirinya,[102] termasuk mengembangkan kemampuan ekonomi dan teknologi untuk menumbuhkan aset dan meningkatkan kekayaan. Tetapi bagaimanapun juga, keterampilan para wirausaha yang merupakan anugerah dari Allah, harus secara jelas diarahkan kepada kemajuan orang lain dan pemberantasan kemiskinan, terutama dengan menciptakan kesempatan kerja yang beragam. Bersama dengan hak milik pribadi, selalu disertai prinsip utama dan pertama bahwa segala milik pribadi tunduk pada tujuan universal segala harta benda, dan karena itu semua berhak untuk menggunakannya.[103]
Hak-hak bangsa-bangsa
124. Keyakinan kokoh akan tujuan umum harta benda bumi saat ini menuntut agar prinsip itu juga diterapkan kepada negara-negara, kepada wilayah-wilayah mereka dan sumber-sumber daya mereka. Jika kita memandangnya dengan bertolak bukan hanya dari keabsahan milik pribadi dan hak-hak para warga dari suatu negara tertentu, melainkan juga dari prinsip pertama tujuan umum harta benda, maka kita dapat mengatakan bahwa setiap negara adalah milik orang asing juga karena harta benda suatu wilayah tidak boleh ditolak bagi orang yang membutuhkannya yang datang dari tempat lain. Memang, seperti yang diajarkan oleh para Uskup Amerika Serikat, ada hak-hak mendasar yang “mendahului masyarakat mana pun karena mengalir dari martabat yang dianugerahkan kepada setiap pribadi sebagaimana diciptakan oleh Allah.[104]
125. Ini juga mengandaikan cara lain dalam memahami hubungan dan pertukaran antarnegara. Jika setiap orang memiliki martabat yang tidak dapat dicabut, jika setiap manusia adalah saudara atau saudari saya, dan jika dunia benar-benar milik semua orang, tidak menjadi masalah apakah seseorang lahir di sini atau tinggal di luar wilayah negerinya. Bangsa saya juga ikut bertanggung jawab atas perkembangan mereka, meskipun dapat memenuhi tanggung jawab ini dengan berbagai cara: dengan menyambut mereka dengan murah hati ketika mengalami keadaan mendesak, dengan mendukung mereka di negaranya sendiri, dengan tidak menggunakan dan menguras sumber daya alam negara-negara mereka, dengan tidak mendukung sistem korup yang menghalangi pembangunan yang layak bagi rakyat. Apa yang berlaku untuk negara-negara, berlaku juga untuk pelbagai wilayah dalam setiap negara, di mana sering terjadi ketimpangan besar. Namun, ketidakmampuan untuk mengakui martabat manusia yang sama kadang-kadang menyebabkan wilayah-wilayah yang lebih maju di negara tertentu ingin membebaskan diri dari “beban” wilayah-wilayah yang lebih miskin agar dapat semakin meningkatkan tingkat konsumsi mereka.
126. Kita berbicara tentang suatu jaringan baru dalam hubungan internasional, karena tidak ada cara untuk menyelesaikan masalah-masalah serius dunia dengan hanya berpikir mengenai bantuan timbal balik antar-individu atau kelompok-kelompok kecil. Mari kita ingat bahwa “ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada negara-negara seluruhnya; hal itu memaksa kita untuk memikirkan suatu etika hubungan internasional.”[105] Keadilan menuntut pengakuan dan penghormatan tidak hanya terhadap hak-hak individu, tetapi juga hak-hak sosial dan hak-hak bangsa-bangsa.[106] Apa yang sedang kita katakan menyiratkan bahwa “hak asasi bangsa-bangsa atas penghidupan dan kemajuannya” dijamin,[107] hal mana terkadang sangat terhambat oleh tekanan utang luar negeri. Pembayaran utang dalam banyak kasus tidak hanya gagal mendukung pembangunan, tetapi juga amat membatasinya dan sangat mempengaruhinya. Meskipun dipertahankan prinsip bahwa setiap utang yang diperoleh secara sah harus dibayar, cara memenuhi kewajiban ini bagi banyak negara miskin terhadap negara-negara kaya, tidak boleh berakhir dengan membahayakan penghidupan dan pertumbuhan mereka.
127. Tentu saja, ini membutuhkan cara berpikir yang berbeda. Jika tidak mencoba masuk ke cara berpikir itu, kata-kata saya akan terdengar seperti khayalan. Tetapi, jika kita menerima prinsip luhur bahwa ada hak-hak yang lahir dari martabat manusia yang tak dapat dicabut, kita dapat menerima tantangan untuk memimpikan dan memikirkan kemanusiaan lain. Adalah mungkin untuk menginginkan suatu planet yang menjamin tanah, rumah, dan pekerjaan untuk semua. Inilah jalan senyatanya menuju perdamaian, dan bukan strategi bodoh dan picik untuk menebarkan ketakutan dan ketidakpercayaan berhadapan dengan ancaman dari luar. Karena perdamaian yang nyata dan langgeng hanya mungkin “berdasarkan etika global tentang solidaritas dan kerja sama dalam melayani masa depan yang dibentuk oleh saling ketergantungan dan tanggung jawab bersama dalam seluruh keluarga manusia.”[108]
BAB EMPAT
HATI YANG TERBUKA KE SELURUH DUNIA
128. Jika penegasan bahwa sebagai manusia kita semua adalah saudara dan saudari, bukan hanya suatu gagasan abstrak tetapi mewujud dan menjadi nyata, timbullah serangkaian tantangan yang menggerakkan dan memaksa kita untuk melihat segalanya dari sudut pandang baru dan mengembangkan tanggapan baru.
Batas dari perbatasan
129. Ketika tetangga adalah seorang migran, bertambahlah tantangan yang kompleks.[109] Tentu saja, yang ideal adalah menghindari migrasi yang tidak perlu. Untuk tujuan ini, caranya adalah menciptakan kemungkinan nyata untuk hidup dan bertumbuh kembang secara bermartabat di negara asal, sehingga keadaan untuk perkembangan seutuhnya bagi seseorang dapat ditemukan di sana. Tetapi, selama tidak ada kemajuan nyata ke arah itu, kita wajib menghormati hak setiap manusia untuk menemukan tempat di mana mereka tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka sendiri dan keluarga mereka, tetapi juga dapat mewujudkan diri mereka sepenuhnya sebagai pribadi. Upaya-upaya kita terhadap para migran yang tiba dapat diringkas dalam empat kata kerja: menyambut, melindungi, memajukan, dan mengintegrasikan. Sesungguhnya, “ini bukan soal menyelenggarakan program bantuan dari atas, tetapi mengadakan perjalanan bersama melalui empat tindakan tersebut, untuk membangun kota dan negara yang, sembari mempertahankan jati diri budaya dan agama masing-masing, terbuka kepada perbedaan dan tahu bagaimana menghargainya atas nama persaudaraan manusia.”[110]
130. Ini berarti mengambil beberapa tanggapan yang sangat diperlukan, terutama dalam menghadapi mereka yang melarikan diri dari krisis kemanusiaan yang berat. Misalnya: meningkatkan dan mempermudah pemberian visa; menerima program-program sponsor pribadi dan komunitas; membuka koridor kemanusiaan untuk para pengungsi yang paling rentan; menawarkan akomodasi yang memadai dan layak; menjamin keamanan pribadi dan akses ke layanan penting; menjamin bantuan konsuler yang memadai, hak untuk selalu sendiri menyimpan dokumen identitas pribadi, akses ke pengadilan yang tidak memihak, kemungkinan membuka rekening bank;menjamin pemenuhan kebutuhan hidupyang penting; memberi kebebasan bergerak dan kesempatan untuk bekerja; melindungi anak-anak di bawah umur dan menjamin bagi mereka akses teratur ke pendidikan; menyediakan program pengasuhan atau penampungan sementara; menjamin kebebasan beragama; meningkatkan integrasi ke dalam masyarakat; membantu reunifikasi keluarga; dan menyiapkan masyarakat lokal untuk proses integrasi.[111]
131. Bagi mereka yang sudah cukup lama datang dan sudah masuk ke dalam tatanan sosial, penting untuk menerapkan konsep “kewarganegaraan”, yang “berlandaskan pada kesetaraan hak dan kewajiban, di mana semua menikmati keadilan. Karena itu, perlu upaya untuk membentuk dalam masyarakat kita konsep kewarganegaraan penuh dan menolak penggunaan istilah minoritas secara diskriminatif yang menimbulkan perasaan terisolasi dan inferioritas. Penyalahgunaannya melicinkan jalan bagi permusuhan dan perselisihan; hal itu mengurangi setiap keberhasilan dan merampas hak-hak keagamaan dan sipil dari beberapa warga negara yang terdiskriminasi karenanya.”[112]
132. Di samping berbagai tindakan yang sangat diperlukan itu, negara-negara tidak dapat mengembangkan solusi yang memadai sendirian “karena konsekuensi dari pilihan setiap negara pasti mempengaruhi seluruh komunitas internasional.” Oleh karena itu, “jawaban hanya bisa menjadi hasil dari upaya bersama”[113] dengan mengembangkan suatu bentuk tata pemerintahan global untuk migrasi. Bagaimanapun, perlu “ditetapkan rencana-rencana jangka menengah dan panjang yang melampaui tanggapan darurat. Di satu sisi, rencana-rencana itu harus secara efektif membantu integrasi para migran di negara penerima dan, pada saat yang sama, mendukung pembangunan negara asal dengan kebijakan solidaritas, namun yang tidak menghubungkan bantuan-bantuan dengan strategi dan praktik yang secara ideologis asing atau bertentangan dengan budaya masyarakat yang dibantu.”[114]
Pemberian timbal balik
133. Kedatangan orang-orang yang berbeda, yang berasal dari konteks kehidupan dan budaya yang berbeda, bisa menjadi anugerah, karena “para migran juga menjadi kisah perjumpaan antarpribadi dan antarbudaya: bagi komunitas-komunitas dan masyarakat yang didatangi, mereka adalah sebuah peluang pengayaan dan pengembangan manusia seutuhnya bagi mereka semua.”[115] Oleh karena itu, “secara khusus saya meminta orang muda untuk tidak jatuh ke tangan orang-orang yang ingin membuat mereka melawan orang-orang muda lain yang datang ke negara mereka, dengan menganggap orang-orang muda lain itu sebagai subjek berbahaya dan seolah-olah tidak memiliki martabat yang sama yang tidak dapat diganggu gugat dari setiap manusia.”[116]
134. Di sisi lain, ketika menyambut orang-orang yang berbeda dengan sepenuh hati, kita mengizinkan mereka untuk tetap menjadi diri mereka sendiri, sambil memberi mereka kemungkinan berkembang secara baru. Aneka budaya yang telah menghasilkan kekayaan mereka selama berabad-abad, harus dilestarikan agar dunia tidak dimiskinkan. Pada saat yang sama, budaya-budaya itu harus didorong untuk membiarkan sesuatu yang baru muncul dari dirinya dalam perjumpaan dengan realitas lain. Risiko menjadi korban sklerosis budaya tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, “kita perlu berkomunikasi, menemukan kekayaan masing-masing, menghargai apa yang menyatukan kita dan melihat perbedaan sebagai peluang untuk bertumbuh dengan saling menghormati. Dibutuhkan dialog yang sabar dan penuh kepercayaan agar setiap orang, keluarga, dan komunitas dapat meneruskan nilai-nilai budaya mereka sendiri dan menerima hal-hal baik yang datang dari pengalaman orang lain.”[117]
135. Saya ingin membahas kembali beberapa contoh yang saya sebutkan beberapa waktu lalu: budaya Amerika Latin adalah “suatu peragian nilai-nilai dan kemungkinan yang dapat membawa banyak berkah bagi Amerika Serikat […]. Imigrasi yang kuat selalu berakhir dengan mewarnai dan mengubah budaya lokal. […] Di Argentina, imigrasi kuat orang-orang Italia telah mewarnai budaya masyarakat, dan dalam corak budaya Buenos Aires kehadiran sekitar dua ratus ribu orang Yahudi sangat mudah terlihat. Para imigran, jika dibantu berintegrasi, adalah berkah, kekayaan, dan anugerah baru yang mengundang masyarakat untuk berkembang.”[118]
136. Dengan memperluas pandangan, bersama Imam Besar Ahmad Al-Tayyeb kami telah mengingatkan bahwa “hubungan baik antara Timur dan Barat tidak dapat disangkal diperlukan bagi keduanya. Keduanya tidak boleh diabaikan, sehingga masing-masing dapat diperkaya oleh budaya yang lain melalui pertukaran dan dialog yang bermanfaat. Barat dapat menemukan di Timur obat bagi penyakit rohani dan agama yang disebabkan oleh materialisme yang tersebar luas. Dan Timur dapat menemukan banyak unsur di Barat yang dapat membantu membebaskannya dari kelemahan, perpecahan, konflik dan kemunduran ilmu pengetahuan, teknik dan budaya. Pentinglah memperhatikan perbedaan agama, budaya dan sejarah yang merupakan unsur vital dalam membentuk karakter, budaya, dan peradaban Timur. Juga penting untuk memperkuat ikatan hak asasi manusia mendasar demi membantu menjamin hidup yang bermartabat bagi semua perempuan dan laki-laki di Timur dan Barat, dengan menghindari politik standar ganda.”[119]
Pertukaran yang bermanfaat
137. Saling membantu antarnegara pada akhirnya menguntungkan semua. Sebuah negara yang berkembang dengan berpijak pada lapisan dasar budaya aslinya adalah harta pusaka bagi seluruh umat manusia. Kita perlu meningkatkan kesadaran bahwa saat ini kita semua entah diselamatkan bersama-sama atau tidak ada yang diselamatkan. Kemiskinan, kemerosotan, penderitaan di satu wilayah di bumi secara diam-diam menjadi tempat pembiakan masalah-masalah yang pada akhirnya akan berdampak pada seluruh planet. Jika kita prihatin dengan kepunahan beberapa spesies, kita harus lebih terusik lagi dengan pikiran bahwa di mana-mana ada orang dan bangsa-bangsa yang tidak dapat mengembangkan potensi dan keindahan mereka karena kemiskinan atau keterbatasan struktural lainnya. Pada akhirnya, kenyataan ini akan memiskinkan kita semua.
138. Bila hal ini telah selalu benar, saat ini hal itu menjadi lebih nyata lagi daripada sebelumnya karena realitas dunia yang begitu saling terhubung oleh globalisasi. Kita membutuhkan tatanan hukum, politik, dan ekonomi mondial yang “berkembang dan mengarah pada kerja sama internasional menuju perkembangan solidaritas bagi bangsa-bangsa.”[120] Hal ini pada akhirnya akan bermanfaat bagi seluruh planet, karena “bantuan untuk pembangunan negara-negara miskin” berarti “menciptakan kesejahteraan bagi semua.”[121] Dari sudut pandang perkembangan integral, ini mengandaikan bahwa “negara-negara miskin diberi hak suara dalam pengambilan keputusan bersama”[122] dan bahwa upaya dilakukan untuk “memperlancar akses ke pasar internasional untuk negara-negara yang dirundung kemiskinan dan keterbelakangan.”[123]
Menyambut dengan kemurahan hati
139. Namun, saya tidak ingin mereduksi pendekatan ini menjadi semacam bentuk utilitarianisme. Ada suatu faktor kemurahan hati, pemberian secara cuma-cuma. Inilah kemampuan untuk melakukan beberapa hal hanya karena hal itu baik dalam dirinya, tanpa berharap mendapatkan hasil apa pun atau tanpa segera mengharapkan sesuatu sebagai imbalannya. Hal ini memungkinkan untuk menyambut orang asing, meskipun pada saat itu tidak membawa manfaat nyata. Namun, ada negara-negara yang menyatakan hanya menerima para ilmuwan dan para investor.
140. Siapa yang tidak menghayati kemurahan hati persaudaraan menjadikan hidupnya sebagai suatu perdagangan yang sibuk, selalu mengukur apa yang ia berikan dan apa yang ia terima sebagai imbalan. Sebaliknya, Allah memberi secara cuma-cuma, bahkan sampai menolong mereka yang tidak setia, dan “menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik” (Mat. 5:45). Karena itu Yesus menganjurkan: “jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi” (Mat. 6:3-4). Kita telah menerima hidup kita secara cuma-cuma, kita tidak pernah membayarnya. Oleh karena itu, kita semua bisa memberi tanpa mengharapkan sesuatu, berbuat baik tanpa menuntut hal yang sama dari orang yang kita bantu. Seperti yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya: “Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma” (Mat. 10:8).
141. Kualitas sebenarnya dari aneka negara di dunia diukur dari kemampuannya untuk berpikir tidak hanya sebagai sebuah negara, tetapi juga sebagai bagian dari keluarga manusia yang lebih besar, dan ini ditunjukkan terutama pada masa-masa kritis. Nasionalisme tertutup pada akhirnya menampakkan ketidakmampuan untuk memberi dengan cuma-cuma dan keyakinan keliru bahwa mereka dapat berkembang di sela-sela kehancuran orang lain dan bahwa dengan menutup diri terhadap yang lain, mereka akan lebih terlindung. Para imigran dipandang sebagai perampok yang tidak menyumbang apa pun. Dengan demikian, orang secara naif mulai berpikir bahwa orang miskin berbahaya atau tidak berguna dan bahwa yang berkuasa adalah dermawan yang murah hati. Hanya budaya sosial dan politik yang mampu menyambut yang lain dengan murah hati bisa memiliki masa depan.
Lokal dan universal
142. Harus diingat bahwa “juga ada tegangan antara keglobalan dan kelokalan. Kita perlu memperhatikan dimensi global agar tidak jatuh ke dalam kepicikan sehari-hari. Namun, kita juga tidak boleh lupa melihat yang lokal, untuk menjaga kaki kita tetap menapak di tanah. Bersama-sama, keduanya mencegah kita jatuh ke dalam dua ekstrem. Yang pertama, orang terjebak dalam universalisme yang abstrak dan mengglobal, yang hanya mengikuti langkah orang lain, mengagumi gemerlapnya dunia orang lain, dengan mulut ternganga memberikan tepuk tangan untuk program-programnya.[…]; Pada ekstrem yang lain, mereka berubah menjadi museum cerita rakyat setempat, terpisah dari dunia, dihukum untuk berulang-ulang melakukan hal yang sama, dan tidak mampu menghadapi tantangan hal-hal baru dan menghargai keindahan yang dianugerahkan Allah di luar batas-batas mereka.”[124] Kita perlu memiliki pandangan global, yang membebaskan kita dari kepicikan kedaerahan. Ketika rumah kita bukan lagi sebuah keluarga, tetapi sebuah kurungan, penjara, maka yang global membebaskan kita karena seperti penyebab akhir yang menarik kita menuju kepenuhan. Pada saat yang sama, dimensi lokal perlu dirangkul dengan sepenuh hati, karena itu memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh yang global: menjadi ragi, memperkaya, menggerakkan mekanisme subsidiaritas. Oleh karena itu, persaudaraan universal dan persahabatan sosial merupakan dua kutub yang tidak terpisahkan dan sama penting dalam setiap masyarakat. Memisahkan keduanya menyebabkan deformasi dan polarisasi yang berbahaya.
Cita rasa lokal
143. Solusinya bukanlah keterbukaan yang menyerahkan harta pusakanya sendiri. Seperti halnya tidak ada dialog dengan orang lain tanpa identitas pribadi, demikian juga tidak ada keterbukaan antarbangsa jika tidak dimulai dari cinta akan negerinya, bangsanya, dan ciri khas budayanya sendiri. Saya tidak dapat bertemu dengan yang lain jika saya tidak memiliki landasan dasar di mana saya berakar dan berdiri dengan kokoh, karena atas dasar itu saya dapat menerima apa yang diberikan orang lain dan menawarkan kepadanya sesuatu yang autentik. Adalah mungkin untuk menerima orang yang berbeda dan mengakui sumbangannya yang unik hanya jika saya berakar kuat pada bangsa saya dan budayanya. Setiap orang mencintai dan merawat tanahnya dengan tanggung jawab khusus dan peduli terhadap negaranya, sama seperti setiap orang harus mencintai dan menjaga rumahnya agar tidak runtuh, karena tetangga tidak akan melakukannya. Kesejahteraan dunia juga menuntut setiap orang untuk melindungi dan mencintai tanah airnya sendiri. Sebaliknya, akibat bencana di satu negara akan berdampak pada seluruh planet. Hal ini berlandaskan pada makna positif dari hak milik: Saya menjaga dan mengelola sesuatu yang saya miliki, sehingga itu dapat menjadi sumbangan untuk kebaikan semua.
144. Selain itu, ini juga merupakan prasyarat untuk pertukaran yang sehat dan memperkaya. Pengalaman hidup di tempat tertentu dan dalam budaya tertentu adalah dasar yang memampukan kita untuk memahami aspek-aspek realitas yang tidak dapat ditangkap dengan mudah oleh mereka yang tidak memiliki pengalaman seperti itu. Yang universal tidak boleh menjadi wilayah kekuasaan yang homogen, seragam, dan terstandarisasi dari satu bentuk budaya dominan, yang pada akhirnya akan kehilangan warna-warni polihedron (banyak bidang) dan kemudian tampak menjijikkan. Godaan inilah yang terungkap dalam kisah kuno Menara Babel: pembangunan menara yang menjulang ke langit tidak mengungkapkan persatuan antara aneka bangsa yang dapat berkomunikasi sesuai dengan keberagaman mereka. Sebaliknya, upaya itu menyesatkan, yang lahir dari kesombongan dan ambisi manusia untuk menciptakan suatu kesatuan yang berbeda dengan yang dikehendaki Allah dalam rencana pemeliharaan-Nya bagi bangsa-bangsa (bdk. Kej. 11:1-9).
145. Ada keterbukaan palsu terhadap yang universal, yang berasal dari kedangkalan kosong orang yang tidak mampu sepenuhnya menembus realitas tanah airnya, atau yang menyimpan dendam yang belum terselesaikan terhadap bangsanya. Bagaimanapun, “Kita senantiasa harus memperluas cakrawala kita dan memandang kebaikan yang lebih besar yang bermanfaat bagi kita semua. Tetapi hal ini harus dilakukan tanpa menjadi pelarian atau kehilangan akar. Kita perlu menanam akar-akar kita lebih dalam ke tanah yang subur dan sejarah tempat asal kita, yang merupakan anugerah Allah. Kita dapat bekerja pada skala kecil di lingkungan kita sendiri, tetapi dengan perspektif yang lebih luas. […] Yang global tidak perlu melenyapkan, dan yang khusus pun tak perlu memandulkan;”[125] itu adalah polihedron di mana masing-masing dihargai nilainya, dan pada saat yang sama “keseluruhan melebihi bagian, dan juga melebihi jumlah bagian-bagiannya.”[126]
Wawasan universal
146. Ada narsisme kedaerahan yang tidak mencerminkan cinta yang sehat kepada bangsa dan budayanya sendiri. Narsisme itu menyembunyikan semangat tertutup yang, karena rasa tak aman dan ketakutan tertentu terhadap orang lain, lebih suka membuat tembok pertahanan untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, tidak mungkin menjadi lokal secara sehat tanpa keterbukaan yang tulus dan ramah terhadap yang universal, tanpa membiarkan diri ditantang oleh apa yang terjadi di tempat lain, tanpa membiarkan diri diperkaya oleh budaya lain dan tanpa menunjukkan solidaritas terhadap tragedi bangsa-bangsa lain. Narsisme kedaerahan ini secara obsesif menutup diri pada beberapa gagasan, adat kebiasaan, dan keamanan, tanpa kemampuan untuk mengagumi banyak kemungkinan dan keindahan yang ditawarkan oleh seluruh dunia dan tanpa solidaritas yang autentik dan murah hati. Dengan demikian, kehidupan lokal tidak lagi benar-benar bersikap menerima, tidak lagi membiarkan dirinya disempurnakan oleh yang lain; karena itu, ia mempersempit kesempatannya untuk berkembang, menjadi statis dan sakit. Sebab, pada kenyataannya, setiap budaya yang sehat secara alamiah terbuka dan ramah, sehingga “suatu budaya tanpa nilai-nilai universal bukanlah budaya yang sejati.”[127]
147. Hendaknya kita menyadari bahwa semakin sempit pikiran dan hati seseorang, semakin ia akan kurang mampu menafsirkan realitas terdekat yang melingkupinya. Tanpa relasi dan perjumpaan dengan orang yang berbeda, sulit untuk memperoleh pengetahuan yang jelas dan lengkap tentang diri sendiri dan negerinya sendiri, karena budaya lain bukanlah musuh yang darinya kita harus mempertahankan diri, tetapi merupakan cerminan yang berbeda dari kekayaan hidup manusia yang tak habis-habisnya. Dengan melihat dirinya dari sudut pandang orang lain, dari orang yang berbeda, setiap orang dapat mengenali keunikan pribadi dan budayanya sendiri dengan lebih baik: kekayaan, kesempatan, dan keterbatasannya. Pengalaman yang terjadi di suatu tempat harus dikembangkan “secara berbeda” dan “selaras” dengan pengalaman orang lain yang hidup dalam aneka konteks budaya.[128]
148. Pada kenyataannya, keterbukaan yang sehat tidak pernah bertentangan dengan identitas. Sesungguhnya, ketika diperkaya dengan unsur-unsur dari anekasumber, suatu budaya yang hidup tidak menyalin atau mengulang begitu saja, tetapi menyatukan yang baru dengan caranya sendiri. Dari situ lahir suatu sintesis baru yang pada akhirnya bermanfaat bagi semua, karena budaya asal dari sumbangan baru ini sebaliknya juga dikembangkan. Oleh karena itu, saya telah mendesak masyarakat adat untuk melestarikan akar-akar dan budaya leluhur mereka, tetapi sekaligus saya telah menjelaskan bahwa bukanlah “maksud saya mengusulkan suatu “indigenismo” (pemribumian) yang sama sekali tertutup, a-historis, statis, yang menolak bentuk persilangan (mestizaje) apa pun,” karena “identitas budaya sendiri diperdalam dan diperkaya dalam dialog dengan mereka yang berbeda, dan cara autentik untuk menjaganya bukan suatu isolasi yang memiskinkan.”[129] Dunia berkembang dan dipenuhi dengan keindahan baru berkat sintesis-sintesis yang berturut-turut terjadi di antara budaya-budaya yang terbuka, bebas dari pemaksaan budaya apa pun.
149. Untuk mendorong hubungan yang sehat antara cinta tanah air dan keikutsertaan tulus dalam seluruh kemanusiaan, perlu diingat bahwa masyarakat dunia bukanlah totaljumlahberbagai negara, melainkan persekutuan itu sendiri yang ada di antara mereka, penerimaan timbal balik, yang mendahului munculnya kelompok-kelompok tertentu. Setiap kelompok manusia terintegrasi dalam jalinan persekutuan universal ini dan menemukan keindahannya di situ. Oleh karena itu, setiap orang yang lahir dalam konteks tertentu tahu bahwa ia termasuk dalam keluarga yang lebih besar; tanpa itu tidak mungkin untuk memahami dirinya sendiri sepenuhnya.
150. Pada akhirnya, pendekatan ini meminta kita dengan senang hati menerima bahwa tidak ada bangsa, tidak ada budaya atau orang yang dapat memperoleh segalanya dari dirinya sendiri. Yang lain sungguh diperlukan untuk membangun kehidupan yang penuh. Kesadaran akan keterbatasan dan ketidaklengkapan kita, jauh dari menjadi ancaman, justru menjadi kunci untuk memimpikan dan mengembangkan program bersama. Karena “manusia adalah makhluk berbatas yang tidak memiliki batas.”[130]
Mulai dari wilayahnya sendiri
151. Pertukaran dalam wilayah sebagai titik tolak bagi negara-negara terlemah untuk membuka diri kepada seluruh dunia, memungkinkan bahwa kekhususan mereka tidak segera larut ke dalam universalitas. Keterbukaan yang tepat dan autentik terhadap dunia mengandaikan kemampuan untuk terbuka terhadap tetanggadalam keluarga bangsa-bangsa. Integrasi budaya, ekonomi, dan politik dengan bangsa-bangsa sekitar harus disertai dengan proses pendidikan yang memajukan nilai kasih untuk tetangga, praktik pertama yang amat diperlukan untuk mencapai integrasi universal yang sehat.
152. Di beberapa lingkungan perkampungan, semangat “bertetangga” masih hidup, di mana setiap orang secara spontan merasakan kewajiban untuk mendampingi dan membantu tetangganya. Di tempat-tempat ini yang melestarikan nilai-nilai komunitas tersebut, hubungan kedekatan dihayati dengan ciri-ciri kemurahan hati, solidaritas, dan pertukaran timbal balik, berawal dari perasaan sebagai “kita” yang sekampung.[131] Semoga hal ini juga dapat dialami oleh negara-negara yang bertetangga, disertai kemampuan untuk membangun kedekatan yang tulus di antara rakyat mereka! Namun, visi individualistis telah berdampak pada hubungan antarnegara. Bahaya menjalani hidup dengan melindungi diri terhadap yang lain, dengan melihat yang lain sebagai pesaing atau musuh yang berbahaya, diterapkan ke dalam hubungan dengan bangsa-bangsa di wilayah tersebut. Mungkin kita telah dididik dalam ketakutan dan ketidakpercayaan seperti itu.
153. Ada negara kuat dan perusahaan besar yang mengambil keuntungan dari isolasi ini dan lebih suka bernegosiasi dengan setiap negara secara terpisah. Sebaliknya, bagi negara-negara kecil atau miskin terbukalah kemungkinan untuk mencapai kesepakatan regional dengan para tetangga mereka, yang memungkinkan mereka untuk bernegosiasi sebagai blok dan menghindari menjadi bagian-bagian marjinal yang bergantung pada kekuatan-kekuatan besar. Saat ini, tidak ada negara nasional yang mampu menjamin kesejahteraan umum penduduknya sendiri jika ia tetap terisolasi.
BAB LIMA
POLITIK YANG LEBIH BAIK
154. Untuk memungkinkan perkembangan komunitas mondial yang mampu mewujudkan persaudaraan yang dimulai dari bangsa-bangsa dan negara-negara yang menghayati persahabatan sosial, diperlukan kebijakan politik yang lebih baik dan benar-benar melayani kebaikan bersama. Namun sayangnya, politik saat ini sebaliknya sering mengambil bentuk-bentuk yang menghambat perjalanan menuju suatu dunia yang berbeda.
Populisme dan liberalisme
155. Penghinaan terhadap yang lemah dapat bersembunyi di balik bentuk-bentuk populisme yang digunakan dengan menghasut untuk kepentingannya sendiri, atau di balik bentuk-bentuk liberalisme yang melayani kepentingan ekonomi mereka yang berkuasa. Dalam kedua kasus tersebut, sulit untuk membayangkan suatu dunia terbuka di mana ada tempat untuk semua orang, termasuk yang paling lemah, dan di mana budaya-budaya yang berbeda dihormati.
Populer atau populis
156. Selama beberapa tahun terakhir, istilah “populisme” atau “populis” telah menyerbu media komunikasi dan pembicaraan secara umum. Akibatnya, istilah itu kehilangan nilai yang dimiliki sesungguhnya; dan menjadi salah satu polaritas dalam masyarakat yang terpecah. Pada akhirnya, orang menganggap dapat menggolong-golongkan semua orang, kelompok, masyarakat, dan pemerintah berdasarkan pembagian “populis” atau “non-populis.” Tidak mungkin lagi bagi seseorang untuk mengungkapkan pendapatnya tentang masalah apa pun tanpa orang mencoba menggolongkannya dalam salah satu dari dua kutub ini, baik untuk mendiskreditkannya secara tidak adil atau mengagungkannya secara berlebihan.
157. Anggapan untuk menempatkan populisme sebagai kunci untuk menafsirkan realitas sosial, mengandung kelemahan lain: fakta bahwa itu mengabaikan legitimitas arti kata bangsa atau rakyat (populus, people). Upaya untuk menghapus konsep ini dari bahasa dapat menyebabkan penghapusan kata “demokrasi” (“pemerintahan oleh rakyat”). Namun demikian, untuk menegaskan bahwa masyarakat lebih dari sekadar sekumpulan individu, istilah “rakyat” diperlukan. Dalam kenyataan, ada fenomena-fenomena sosial yang membentuk mayoritas; ada beberapa megatren dan aspirasi komunitarian; selain itu, dapat disebutkan tujuan-tujuan bersama, melampaui segala perbedaan, untuk mewujudkan suatu usaha/program bersama. Akhirnya, akan sangat sulit untuk merencanakan sesuatu yang besar dalam jangka panjang jika tidak berhasil untuk menjadikannya sebagai mimpi bersama. Semua ini terungkap dalam kata benda “rakyat” dan kata sifat “populer” (merakyat). Jika tidak lagi digunakan –bersamaan dengan suatu kritik kuat terhadap demagogi–, suatu aspek mendasar dari realitas sosial akan ditinggalkan.
158. Di sini ada kesalahpahaman. “Bangsa bukanlah kategori logis, juga bukan kategori mistik, bila kita memahaminya dalam arti bahwa segala sesuatu yang dilakukan bangsa itu baik, atau dalam arti bahwa bangsa termasuk kategori malaikat. Tidak! Bangsa adalah kategori mitos […]. Ketika Anda menjelaskan apa itu bangsa, Anda menggunakan kategori logis karena Anda harus menjelaskannya: sungguh, itu perlu. Namun demikian, ini bukan cara Anda menjelaskan makna menjadi bagian suatu bangsa. Kata bangsa memiliki makna yang lebih dalam yang tidak dapat dijelaskan secara logis. Menjadi bagian dari suatu bangsa adalah menjadi bagian dari identitas bersama yang dibangun dari ikatan sosial dan budaya. Dan ini bukan sesuatu yang otomatis, sebaliknya: ini merupakan proses yang lambat dan sulit… menuju proyek bersama.”[132]
159. Ada pemimpin ‘populer’, yang merakyat, yang mampu menafsirkan perasaan bangsa, dinamika budayanya dan tren-tren besar masyarakat. Layanan yang mereka berikan, dengan menyatukan dan membimbing, dapat menjadi landasan untuk proyek perubahan dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Ini juga berarti kemampuan untuk memberi ruang kepada orang lain dalam mencari kebaikan bersama. Tapi layanan itu bisa merosot menjadi populisme yang tidak sehat ketika berubah menjadi kemampuan seseorang untuk menarik kesepakatan yang bertujuan mengeksploitasi budaya bangsa secara politis, dengan bendera ideologis apa pun, guna melayani proyek pribadinya dan kelangsungan kekuasaannya. Di lain waktu ini bertujuan untuk mendapatkan popularitas, dengan mengobarkan kecenderungan terendah dan egois dari beberapa sektor penduduk. Populisme ini menjadi lebih buruk ketika, dalam bentuk kasar atau halus, menjadi perampasan kekuasaan atas institusi-institusi dan hukum.
160. Kelompok populis yang tertutup mendistorsi kata “bangsa”, karena pada kenyataannya yang mereka bicarakan bukanlah bangsa yang sesungguhnya. Sebenarnya, konsep “bangsa” itu terbuka. Bangsa yang hidup dan dinamis dengan masa depan adalah bangsa yang selalu tetap terbuka terhadap sintesis-sintesis baru, dengan menerima apa yang berbeda. Itu dilakukannya bukan dengan menyangkal dirinya sendiri, melainkan dengan kerelaan untuk digerakkan, dipertanyakan, diperluas, diperkaya oleh orang lain, dan dengan demikian bisa berkembang.
161. Tanda lain kemerosotan kepemimpinan populer adalah mengejar kepentingan segera. Kebutuhan rakyat dipenuhi untuk menjamin suara atau dukungan, tetapi tanpa meningkatkan komitmen yang kuat dan berkesinambungan untuk menyediakan sumber daya bagi perkembangan masyarakat, agar mereka dapat mencari nafkah dengan upaya dan kreativitas mereka sendiri. Dalam arti ini saya pernah menyatakan dengan jelas bahwa “saya tidak bermaksud sama sekali mengusulkan populisme yang tidak bertanggung jawab.”[133] Di satu sisi, mengatasi ketimpangan membutuhkan pengembangan ekonomi dengan memanfaatkan potensi tiap-tiap wilayah dan dengan demikian memastikan pemerataan yang berkelanjutan.[134] Di sisi lain, “program-program bantuan untuk mengatasi beberapa kebutuhan yang mendesak, hendaknya dipertimbangkan hanya sebagai jawaban sementara.”[135]
162. Persoalan besar adalah pekerjaan. Apa yang benar-benar populer –karena meningkatkan kesejahteraan bangsa–adalah memastikan bahwa semua orang mendapat kesempatan untuk menumbuhkan benih yang telah ditanam Allah pada setiap orang, bakatnya, inisiatifnya, sumber-dayanya. Ini adalah bantuan terbaik untuk orang miskin, jalan terbaik menuju kehidupan yang bermartabat. Oleh karena itu, saya menekankan bahwa “membantu orang miskin dengan uang harus selalu menjadi solusi sementara untuk mengatasi keadaan darurat. Tujuan utama seharusnya selalu memungkinkan mereka hidup bermartabat melalui pekerjaan.”[136] Sistem produksi dapat berubah, tetapi politik tidak pernah boleh mengabaikan tujuan untuk memastikan agar organisasi masyarakat menjamin bahwa setiap orang dapat berkontribusi dengan bakat dan usahanya sendiri. Memang, “tidak ada kemiskinan yang lebih buruk daripada kemiskinan berupa kehilangan pekerjaan dan martabat pekerjaan.”[137] Dalam masyarakat yang benar-benar maju, pekerjaan merupakan dimensi kehidupan sosial yang hakiki, karena pekerjaan bukan hanya sarana mencari nafkah, tetapi juga sarana untuk pengembangan pribadi, untuk membangun hubungan yang sehat, untuk mengekspresikan diri, untuk berbagi anugerah, untuk merasa turut bertanggung jawab dalam mengembangkan dunia dan, pada akhirnya, untuk hidup sebagai bangsa.
Nilai dan batasan pandangan liberal
163. Konsep tentang bangsa, yang memuat penilaian positif terhadap ikatan komunal dan budaya, biasanya ditolak oleh pandangan liberal yang individualistis, yang memandang masyarakat hanya sebagai sekumpulan kepentingan yang berdampingan. Mereka berbicara tentang penghormatan terhadap kebebasan, tetapi tanpa akar dalam narasi bersama. Dalam beberapa konteks tertentu, semua orang yang membela hak-hak para anggota yang terlemah dalam masyarakat sering dituduh sebagai populis. Untuk pandangan liberal ini, kategori bangsa merupakan mitologisasi dari sesuatu yang sesungguhnya tidak ada. Namun, hal ini menciptakan polarisasi yang tidak perlu, karena baik bangsa maupun sesama bukanlah sekadar kategori mitos atau romantisme yang menyingkirkan atau memandang rendah organisasi sosial, ilmu pengetahuan dan lembaga-lembaga masyarakat sipil.[138]
164. Kasih menyatukan kedua dimensi –mitos dan kelembagaan– karena menyiratkan jalan efektif untuk perubahan sejarah yang harus menyatukan segala sesuatu: lembaga, hukum, teknologi, pengalaman, sumbangan profesional, analisis ilmiah, prosedur administratif, dan sebagainya. Karena “memang tidak ada kehidupan pribadi jika tidak dilindungi aturan umum; rumah tangga tidak memiliki keakrabanbila tidak dilindungi hukum, keadaan tenang berdasarkan hukum dan penegakannya, dan disertai keadaan kesejahteraan minimal yang dijamin oleh pembagian kerja, perdagangan, keadilan sosial, dan kewarganegaraan politik.”[139]
165. Kasih sejati mampu mencakup semua itu dalam dedikasinya. Bila kasih harus menyatakan dirinya dalam perjumpaan dari orang-ke-orang, ia juga mampu menjangkau saudara-saudari yang jauh dan bahkan yang terabaikan, melalui berbagai sumber yang dapat dihasilkan oleh lembaga-lembaga masyarakat yang teratur, bebas, dan kreatif. Dalam kasus ini, juga orang Samaria yang murah hati membutuhkan suatu penginapan yang dapat memberi bantuan yang secara pribadi tidak mampu ia tawarkan. Kasih terhadap sesama itu realistis dan tidak menyia-nyiakan apa pun yang diperlukan untuk suatu perubahan sejarah demi kebaikan orang-orang yang paling kecil. Di sisi lain, terkadang ada ideologi-ideologi haluan kiri atau doktrin-doktrin sosial yang sejalan dengan kebiasaan individualistis dan cara kerja yang tidak efektif yang hanya menguntungkan sedikit orang. Sementara itu, mayoritas orang yang tersingkir tetap bergantung pada niat baik beberapa orang. Ini menunjukkan bahwa penting untuk memupuk tidak hanya spiritualitas persaudaraan, tetapi pada saat yang sama juga organisasi dunia yang lebih efisien, untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah mendesak orang-orang tersingkir yang menderita dan sekarat di negara-negara miskin. Hal ini pada gilirannya menyiratkan bahwa tidak hanya ada satu jalan keluar yang mungkin, hanya satu metodologi yang dapat diterima, hanya satu resep ekonomi yang dapat diterapkan sama untuk semua. Studi ilmiah yang paling teliti pun dapat mengusulkan jalan-jalan yang berbeda.
166. Semuanya ini akan menjadi tak tentu jika kita kehilangan kemampuan untuk mengakui perlunya perubahan hati, kebiasaan, dan gaya hidup manusia. Itulah yang terjadi ketika propaganda politik, media dan pembuat opini publik bersikeras mengobarkan budaya yang individualistis dan naif berhadapan dengan kepentingan-kepentingan ekonomis yang tanpa aturan dan terhadap organisasi masyarakat yang melayani mereka yang sudah memiliki terlalu banyak kekuasaan. Oleh karena itu, kritik saya terhadap paradigma teknokratis tidak berarti bahwa kita bisa aman hanya dengan mencoba mengendalikan ekses-eksesnya, karena bahaya terbesar tidak terletak pada benda-benda, pada realitas material, pada organisasi, tetapi pada cara orang menggunakannya. Masalahnya adalah kelemahan manusiawi, kecenderungannya untuk selalu mementingkan dirinya, hal mana merupakan bagian dari apa yang oleh tradisi Kristen disebut “concupiscentia”: kecenderungan manusia untuk menutup diri dalam imanensi dirinya sendiri, dalam kelompoknya sendiri, dalam kepentingan kecilnya sendiri. Gairah ini bukanlah cacat khas zaman kita. Itu sudah ada sejak manusia menjadi manusia; dan hanya berubah-ubah serta mengambil bentuk-bentuk yang berbeda selama berabad-abad, dengan menggunakan sarana-sarana yang disediakan baginya oleh momen sejarah. Namun, adalah mungkin untuk mengontrol gairah itu dengan bantuan Allah.
167. Komitmen pada pendidikan, pengembangan sikap solidaritas, kemampuan memahami kehidupan manusia secara lebih utuh, dan kedalaman spiritual, semuanya itu diperlukan untuk memberikan kualitas pada hubungan antarmanusia, sehingga masyarakat sendiri mengambil tindakan terhadap ketidakadilan, penyimpangan, dan penyalahgunaan kekuasaan di dunia ekonomi, teknologi, politik, dan media. Beberapa pandangan liberal mengabaikan faktor kelemahan manusiawi dan membayangkan sebuah dunia yang mengikuti tatanan tertentu dan dengan sendirinya mampu menjamin masa depan dan menyelesaikan semua masalah.
168. Pasar saja tidak menyelesaikan segala masalah, meskipun terkadang kita diminta untuk mempercayai dogma kepercayaan neoliberal ini. Ini merupakan cara berpikir yang miskin dan berulang-ulang, yang selalu menawarkan resep yang sama dalam menghadapi segala tantangan yang muncul. Neoliberalisme sekadar mereproduksi dirinya dengan cara yang sama, dengan menggunakan teori keramat “spillover” (tumpahan) atau “trickle” (tetesan ke bawah) –tanpa menyebut namanya– sebagai satu-satunya cara untuk memecahkan masalah-masalah sosial. Tidak disadari bahwa “tumpahan yang menetes ke bawah” yang diperkirakan, tidak menyelesaikan ketimpangan yang menjadi sumber bentuk-bentuk kekerasan baru yang mengancam tatanan sosial. Di satu sisi, sangat diperlukan kebijakan ekonomi aktif, yang bertujuan “memajukan suatu ekonomi yang mendorong keragaman produksi dan kreativitas kewirausahaan,”[140] sehingga dapat menambah lapangan kerja, alih-alih menguranginya. Spekulasi keuangan dengan tujuan dasar untuk mendapat hasil dengan mudah, terus mendatangkan malapetaka. Di sisi lain, “tanpa bentuk-bentuk internal solidaritas dan kepercayaan timbal-balik, pasar tidak dapat sepenuhnya melaksanakan fungsi ekonomis yang tepat. Dewasa ini kepercayaan inilah yang telah hilang.”[141] Cerita tidak berhenti di situ; rumusan-rumusan dogmatis dari teori ekonomi yang kini berlaku terbukti tidak sempurna. Kerapuhan sistem dunia dalam menghadapi pandemi telah menunjukkan bahwa tidak semuanya dapat diselesaikan dengan kebebasan pasar dan bahwa, selain merehabilitasi politik yang sehat yang tidak tunduk pada perintah dunia keuangan, “kita harus menempatkan kembali martabat manusia di pusat dan di atas pilar itu membangun struktur sosial alternatif yang kita butuhkan.”[142]
169. Dalam beberapa visi ekonomi tertutup dan tanpa nuansa, tampaknya tidak ada tempat bagi, misalnya, gerakan populer yang mengumpulkan para penganggur, pekerja tidak tetap dan informal, dan banyak lainnya yang tidak mudah masuk ke dalam struktur yang sudah mapan. Pada kenyataannya, mereka menghasilkan berbagai bentuk ekonomi kerakyatan dan produksi komunitas. Penting untuk memikirkan partisipasi sosial, politik, dan ekonomi sedemikian rupa sehingga “mencakup gerakan populer dan menjiwai struktur pemerintah lokal, nasional dan internasional dengan semburan energi moral yang muncul dari keterlibatan mereka yang tersisih dalam pembangunan nasib bersama.” Pada saat yang sama, sebaiknya diusahakan agar “gerakan-gerakan ini, pengalaman solidaritas yang tumbuh dari bawah, dari bawah tanah, menyatu, lebih terkoordinasi, dan saling bertemu.”[143] Namun, ini harus dilakukan tanpa mengkhianati gaya khas mereka, karena mereka adalah “penabur-penabur perubahan, pendukung proses di mana jutaan tindakan kecil dan besar bertemu secara kreatif, seperti dalam puisi.”[144] Dalam pengertian ini mereka adalah “penyair sosial” yang bekerja, mengusulkan, membawa kemajuan, dan membebaskan dengan cara mereka sendiri. Bersama mereka, pengembangan manusia seutuhnya akan menjadi mungkin. Ini meminta kita untuk melampaui “gagasan kebijakan sosial yang dipahami sebagai kebijakan terhadap orang miskin, tetapi tidak pernah bersama orang miskin, tidak pernah milik dari orang miskin; apalagi tidak disertakan dalam sebuah proyek yang menyatukan kembali bangsa-bangsa.”[145] Meskipun orang-orang miskin merepotkan, meskipun beberapa “pemikir” tidak tahu bagaimana menggolongkan mereka, namun kita harus berani mengakui bahwa tanpa mereka “demokrasi berhenti berkembang, menjadi kata-kata belaka, formalitas, kehilangan keterwakilan, berjalan tanpa wujud karena meninggalkan rakyat dalam perjuangannya setiap hari untuk martabatnya, dalam pembangunan masa depannya.”[146]
Kekuatan internasional
170. Saya ingin mengulangi bahwa “krisis keuangan 2007-2008 telah menjadi suatu kesempatan bagi pengembangan ekonomi baru yang lebih memperhatikan prinsip-prinsip etika, dan bagi cara-cara baru untuk mengatur praktik keuangan yang spekulatif dan kekayaan semu. Tetapi krisis itu tidak ditanggapi dengan memikirkan kembali kriteria usang yang terus menguasai dunia.”[147]Sebaliknya, strategi-strategi nyata yang kemudian dikembangkan di dunia, tampaknya berorientasi pada individualisme yang lebih besar, pelibatan yang lebih sedikit, kebebasan lebih banyak bagi mereka yang benar-benar berkuasa, yang selalu menemukan jalan keluar tanpa rugi.
171. Saya ingin menegaskan bahwa “memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, menurut definisi klasik keadilan, berarti bahwa tidak ada individu atau kelompok manusia yang dapat menganggap dirinya mahakuasa, berhak untuk melanggar martabat dan hak individu atau kelompok sosial lain. Pembagian kekuasaan faktual –politik, ekonomi, militer, teknologi, dan sebagainya– di antara beragam subjek dan penciptaan sistem hukum untuk mengatur klaim dan kepentingan, merealisasi pembatasan kekuasaan. Namun, saat ini panorama dunia memperlihatkan kepada kita banyak hak palsu, dan –pada saat yang sama– sektor-sektor luas yang tanpa perlindungan, yang menjadi korban terutama dari pelaksanaan kekuasaan yang buruk.”[148]
172. Abad kedua puluh satu “menyaksikan melemahnya kekuatan negara nasional, terutama karena sektor ekonomi dan keuangan yang bersifat transnasional, cenderung mendominasi politik. Dalam konteks ini, sangat diperlukan pengembangan lembaga-lembaga internasional yang harus terorganisasi lebih kuat dan efisien, yang mempunyai wewenang yang ditetapkan secara adil melalui kesepakatan di antara pemerintah-pemerintah nasional, dan memiliki kekuasaan untuk menjatuhkan sanksi.”[149] Ketika berbicara tentang kemungkinan suatu bentuk otoritas dunia yang diatur oleh hukum,[150]tidak perlu berpikir tentang suatu otoritas pribadi. Namun, setidaknya otoritas itu harus mencakup pembentukan organisasi dunia yang lebih efektif, yang diberi wewenang untuk menjamin kebaikan bersama secara global, pemberantasan kelaparan dan kesengsaraan, dan pembelaan kuat terhadap hak-hak asasi manusia.
173. Dalam konteks ini, saya ingat bahwa diperlukan reformasi “baik Perserikatan Bangsa-Bangsa maupun rancang bangun ekonomi dan keuangan internasional, sehingga kita dapat mewujudkan konsep keluarga bangsa-bangsa secara nyata.”[151] Tidak diragukan lagi bahwa ini mengandaikan pembatasan hukum yang jelas, untuk menghindari bahwa otoritas itu diambil alih oleh hanya beberapa negara dan, pada saat yang sama, untuk mencegah pemaksaan budaya atau pengurangan kebebasan dasar bagi negara-negara yang lebih lemah atas dasar perbedaan ideologis. Memang, “masyarakat internasional adalah sebuah masyarakat hukum yang didirikan di atas kedaulatan tiap-tiap negara anggota, tanpa ikatan-ikatan subordinasi yang mengingkari atau membatasi kemerdekaannya.”[152] Namun, “tugas Perserikatan Bangsa-Bangsa, mulai dari asas-asas Pembukaan dan pasal-pasal pertama dari Piagam Konstitusionalnya, dapat dipandang sebagai pengembangan dan peningkatan kedaulatan hukum, karena sadar bahwa keadilan adalah syarat yang sangat diperlukan untuk mewujudkan cita-cita persaudaraan universal. […] Kita harus memastikan supremasi hukum yang tidak terbantahkan dan jalan negosiasi yang tak kenal lelah, mediasi dan arbitrase, seperti yang diusulkan oleh Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, norma hukum mendasar yang sejati.”[153] Organisasi ini harus dihindarkan dari kehilangan legitimitas, karena berbagai masalah dan kekurangannya dapat dihadapi dan diselesaikan bersama.
174. Dibutuhkan keberanian dan kemurahan hati untuk secara bebas menetapkan tujuan-tujuan bersama dan memastikan bahwa norma-norma esensial tertentu di seluruh dunia dipenuhi. Agar ini benar-benar berguna, perlu dijunjung tinggi tuntutan “untuk setia kepada perjanjian-perjanjian yang telah dibuat (pacta sunt servanda),”[154] untuk menghindari “godaan untuk bersandar pada hukum rimba alih-alih pada kekuatan hukum”[155] Hal ini membutuhkan konsolidasi “instrumen-instrumen normatif untuk penyelesaian sengketa secara damai, […] guna memperkuat ruang lingkup dan daya ikatnya.”[156] Di antara instrumen-instrumen normatif ini, kesepakatan multilateral antarnegara harus diutamakan, karena –lebih baik daripada kesepakatan bilateral– kesepakatan itu menjamin perawatan kesejahteraan umum yang benar-benar universal dan perlindungan bagi negara-negara yang lebih lemah.
175. Syukur pada Allah, begitu banyak kelompok dan organisasi masyarakat sipil membantu untuk mengatasi kelemahan komunitas internasional, kurangnya koordinasi dalam situasi-situasi yang kompleks, kurangnya perhatian terhadap hak asasi manusia dan situasi yang sangat kritis dari beberapa kelompok. Di sini terungkap secara nyata prinsip subsidiaritas, yang menjamin partisipasi dan aktivitas komunitas dan organisasi di tingkat yang lebih rendah yang secara integral melengkapi aktivitas negara. Sering kali mereka melakukan upaya yang patut dipuji dengan memikirkan kebaikan bersama; dan anggota-anggotanya terkadang sampai melakukan tindakan yang benar-benar heroik, yang menunjukkan betapa indahnya kemampuan yang masih dimiliki kemanusiaan kita.
Cinta kasih sosial dan politik
176. Bagi banyak orang, politik saat ini merupakan kata yang buruk, dan tidak dapat diabaikan bahwa di balik fakta ini sering terdapat aneka kesalahan, tindakan korupsi, dan inefisiensi beberapa politisi. Tambahan lagi, adanya pelbagai upaya yang bertujuan untuk melemahkan politik, menggantinya dengan ekonomi, atau menguasainya dengan suatu ideologi. Namun, bisakah dunia berfungsi tanpa politik? Bisakah dunia menemukan suatu cara efektif menuju persaudaraan universal dan perdamaian sosial tanpa politik yang baik?[157]
Politik yang kita butuhkan
177. Saya ingin menegaskan kembali bahwa “politik tidak harus tunduk pada ekonomi dan ekonomi tidak harus tunduk pada perintah dan paradigma efisiensi teknokrasi.”[158] Meskipun kita harus menolak penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, pengabaian terhadap hukum, dan ketidakefisienan, “kita tidak bisa membenarkan ekonomi tanpa politik, karena akan membuat mustahil mengajukan pola berpikir lain untuk menanggulangi berbagai aspek krisis saat ini.”[159] Sebaliknya, “kita membutuhkan sebuah politik yang berpandangan luas dan bisa mengajukan pendekatan komprehensif, mampu mengintegrasikan berbagai aspek krisis ke dalam suatu dialog interdisipliner.”[160] Saya memikirkan “politik yang sehat, yang mampu membaharui dan mengoordinasi lembaga-lembaga serta membuatnya berfungsi dengan lebih baik sehingga dapat mengatasi pelbagai tekanan dan kelumpuhan birokrasi.”[161] Ini tidak dapat diharapkan dari ekonomi, juga tidak dapat diterima bahwa ekonomi mengambil alih kekuasaan nyata dari negara.
178. Dalam menghadapi begitu banyak bentuk politik picik yang diarahkan pada kepentingan instan, saya mengulangi bahwa “kebesaran politik terungkap ketika, di masa-masa yang sulit, orang bekerja berdasarkan prinsip-prinsip utama dan memikirkan kesejahteraan umum jangka panjang. Sangat sulit bagi kekuasaan politik untuk mengemban kewajiban ini dalam proyek pembangunan bangsa”[162] dan terlebih lagi dalam proyek bersama untuk umat manusia sekarang dan di masa depan. Memikirkan generasi mendatang tidak melayani kepentingan pemilihan, tetapi itulah yang dituntut oleh keadilan sejati, karena, seperti yang diajarkan oleh para Uskup Portugal, bumi “adalah pinjaman yang diterima setiap generasi dan harus diteruskannya kepada generasi berikutnya.”[163]
179. Masyarakat dunia memiliki kelemahan struktural serius yang tidak dapat diselesaikan dengan perbaikan tambal sulam atau solusi cepat yang hanya sesekali. Ada hal-hal yang perlu diubah melalui revisi mendasar dan perubahan besar. Hanya suatu politik yang sehat dapat memandu proses itu, dengan melibatkan berbagai sektor dan bidang pengetahuan yang paling beragam. Dengan cara ini, ekonomi yang diintegrasikan ke dalam program politik, sosial, budaya, dan kerakyatan yang ditujukan pada kesejahteraan umum, dapat membuka jalan ke “aneka-kemungkinan yang berbeda, yang tidak berarti mematikan kreativitas manusia dan cita-cita kemajuannya, tetapi mengarahkan energi itu ke jalan-jalan baru.”[164]
Cinta kasih politik
180. Mengakui setiap manusia sebagai saudara atau saudari dan mengusahakan persahabatan sosial yang menyatukan semua orang bukanlah utopia belaka. Dibutuhkan keputusan dan kemampuan untuk menemukan jalan-jalan efektif yang menjamin kemungkinan nyatanya. Komitmen apa pun ke arah ini menjadi latihan kasih yang luhur. Seorang individu dapat membantu seorang yang berkesusahan, tetapi ketika ia bergabung dengan orang lain untuk memulai suatu proses sosial persaudaraan dan keadilan bagi semua, ia memasuki “bidang kasih paling luas, yakni cinta kasih politik.”[165] Ini adalah tentang bergerak maju menuju tatanan sosial dan politik yang jiwanya adalah cinta kasih sosial.[166] Sekali lagi saya mengundang Anda untuk mengevaluasi kembali politik yang “merupakan panggilan luhur, dan salah satu bentuk paling bernilai amal kasih, sejauh mengusahakan kesejahteraan umum.”[167]
181. Setiap komitmen yang diilhami oleh ajaran sosial Gereja “berasal dari kasih yang, menurut ajaran Yesus, merupakan paduan keseluruhan hukum (lih. Mat. 22:36-40).”[168] Ini berarti mengakui bahwa “kasih, yang melimpah dengan tindakan-tindakan kecil yang bersifat saling mempedulikan, juga bersifat sipil dan politik, dan mengungkapkan diri dalam segala tindakan yang berusaha membangun sebuah dunia yang lebih baik.”[169] Oleh karena itu, kasih diungkapkan tidak hanya dalam hubungan erat dan dekat, tetapi juga dalam “relasi-makro (bidang sosial, ekonomi, dan politik).”[170]
182. Cinta kasih politik ini mengandaikan bahwa kita telah mengembangkan rasa sosial yang melampaui mentalitas individualistis: “’Cinta kasih sosial membuat kita mencintai kesejahteraan umum dan secara efektif mengikhtiarkan kebaikan semua orang, yang tidak saja terdiri dari orang perorangan atau masing-masing pribadi tetapi juga dalam matra sosial yang mempersatukan mereka semua.”[171] Setiap orang menjadi pribadi seutuhnya jika ia menjadi milik suatu bangsa, dan pada saat yang sama, itu bukan bangsa sejati bila tidak menghargai wajah setiap pribadi. Bangsa dan pribadi merupakan istilah korelatif. Namun, saat ini ada upaya untuk mereduksi pribadi menjadi individu, yang dengan mudah dikendalikan oleh kekuatan yang mengejar kepentingan ilegal. Politik yang baik mencari cara-cara untuk membangun komunitas di berbagai tingkat kehidupan sosial, untuk menyeimbangkan kembali dan mengarahkan kembali globalisasi untuk menghindari efek-efek yang mengganggu.
Kasih yang berdaya guna
183. Mulai dari “kasih sosial”[172] terbukalah kemungkinan untuk melangkah maju menuju peradaban kasih yang kepadanya kita semua merasa terpanggil. Cinta kasih, dengan dinamisme universalnya, dapat membangun suatu dunia baru,[173] karena kasih itu bukan sekadar perasaan yang steril, tetapi cara terbaik untuk mencapai jalan-jalan pembangunan yang berdaya guna bagi semua. Kasih sosial adalah “kekuatan yang mampu mengilhami cara-cara baru untuk mendekati berbagai persoalan dunia dewasa ini dan untuk secara mendalam membarui pelbagai struktur, organisasi sosial, dan sistem perundang-undangan.” [174]
184. Kasih adalah inti dari setiap kehidupan sosial yang sehat dan terbuka. Namun, saat ini kasih “dengan mudah disingkirkan sebagai sesuatu yang tidak relevan untuk menerjemahkan dan memberi arah pada tanggung jawab moral.”[175] Kasih itu jauh lebih dari sekadar sentimentalitas subjektif, jika disertai dengan suatu komitmen pada kebenaran, sehingga ia tidak mudah menjadi “korban perasaan-perasaan dan pikiran-pikiran subjektif yang berubah-ubah.”[176] Justru hubungannya dengan kebenaran yang membantu kasih menjadi universal dan, dengan demikian, menjaga agar kasih tidak “dibatasi pada bidang yang sempit dan tanpa relasi.”[177] Tanpa kebenaran, kasih akan “disingkirkan dari rencana dan proses memajukan perkembangan manusiawi dalam lingkup universal, dalam dialog antara pengetahuan dan praksis.”[178] Tanpa kebenaran, emosi dikosongkan dari isi relasional dan sosial. Oleh karena itu, keterbukaan terhadap kebenaran melindungi kasih dari kepercayaan palsu yang “merampasnya dari kehidupan manusiawi dan universal.” [179]
185. Kasih membutuhkan terang kebenaran yang terus kita cari dan “terang itu sekaligus adalah terang akal budi dan terang iman,”[180] tanpa relativisme. Ini juga mengandaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan kontribusinya yang tak tergantikan untuk menemukan jalan-jalan konkret dan paling aman untuk mencapai hasil yang diinginkan. Memang, ketika kebaikan orang lain dipertaruhkan, niat baik tidak cukup. Harus dilakukan upaya-upaya konkret untuk mewujudkan apa pun yang mereka dan negara-negara mereka perlukan demi perkembangan mereka.
Aktivitas kasih politik
186. Ada yang disebut kasih yang “ditimbulkan “, yaitu tindakan-tindakan yang secara langsung timbul dari keutamaan kasih, yang ditujukan pada orang-orang dan bangsa-bangsa. Ada juga kasih yang “diperintahkan“: tindakan-tindakan kasih yang mendorong kita untuk menciptakan institusi-institusi yang lebih sehat, tatanan yang lebih adil, struktur yang lebih mendukung.[181] Oleh karenanya, itu “merupakan sebuah tindakan kasih yang sama-sama sangat diperlukan untuk memperjuangkan pengelolaan dan penataan masyarakat agar sesamaku tidak akan menemukan dirinya terperangkap di dalam kemiskinan.”[182] Kasihlah yang berada dekat dengan orang yang menderita, dan kasih pulalah yang melakukan segala sesuatu, bahkan tanpa berhubungan langsung dengan orang itu, guna mengubah keadaan masyarakat yang menyebabkan penderitaannya. Jika seseorang membantu seorang lansia menyeberangi sungai –itu adalah tindakan kasih yang sangat indah‑, seorang politikus membangun jembatan untuknya, dan itu juga kasih. Sementara seseorang membantu orang lain dengan memberinya makanan, politikus menciptakan pekerjaan untuknya, dan mempraktikkan bentuk kasih yang sangat luhur yang memuliakan aktivitas politiknya.
Pengorbanan karena kasih
187. Cinta kasih ini, jantung dari semangat politik, selalu merupakan kasih yang mengutamakan mereka yang paling ditinggalkan, dan menjiwai setiap tindakan yang diambil demi kemajuan mereka.[183] Hanya dengan pandangan yang cakrawalanya diubah oleh cinta kasih yang memberi pemahaman akan martabat orang lain, orang-orang miskin diakui dan dihargai dalam martabat mereka yang luhur, dihormati dalam gaya dan budaya mereka sendiri, dan dengan demikian benar-benar diintegrasikan ke dalam masyarakat. Pandangan seperti itu adalah inti dari semangat autentik dari politik. Dari pandangan ini, terbukalah jalan-jalan yang berbeda dengan jalan-jalan pragmatisme tanpa jiwa. Misalnya, “skandal kemiskinan tidak dapat diatasi dengan meningkatkan strategi pengendalian yang hanya menenangkan orang miskin dan mengubah mereka menjadi makhluk yang dijinakkan dan tak berbahaya. Betapa menyedihkan melihat bahwa, di balik karya-karya yang dianggap altruistik, orang lain direndahkan menjadi pasif.”[184] Yang dibutuhkan adalah berbagai saluran ekspresi dan partisipasi dalam masyarakat. Pendidikan melayani jalan ini sehingga setiap manusia dapat menjadi pencipta nasibnya sendiri. Di sini asas subsidiaritas yang tidak dapat dipisahkan dari asas solidaritas menunjukkan nilainya.
188. Oleh karena itu, mendesak untuk menemukan solusi atas segala sesuatu yang mengancam hak-hak asasi manusia. Para politisi dipanggil untuk memperhatikan “kerapuhan, kerapuhan bangsa-bangsa dan setiap warga. Memperhatikan kerapuhan mengungkapkan kekuatan dan kelembutan, perjuangan dan keberhasilan di tengah-tengah model fungsionalis dan privatisasi yang secara tak terelakkan mengarah kepada ‘budaya membuang.’ […] Itu berarti bertanggung jawab atas saat ini dalam situasi yang paling marjinal dan menyedihkan serta mampu memberinya harga diri.”[185] Dengan demikian pasti timbul aktivitas yang intens, karena “segala sesuatu harus dilakukan untuk melindungi kondisi dan martabat pribadi manusia.”[186] Seorang politikus adalah seorang pelaksana, adalah seorang pembangun dengan tujuan-tujuan besar, dengan pandangan yang luas, realistis dan pragmatis, bahkan melampaui batas negaranya sendiri. Keprihatinan utama seorang politikus seharusnya bukan tentang turunnya jumlah suara, melainkan kegagalannya menemukan solusi yang efektif untuk “fenomena pengucilan sosial dan ekonomis, dengan banyak konsekuensi yang menyedihkan: perdagangan manusia, perdagangan organ dan sel-sel manusia, eksploitasi seksual terhadap anak-anak laki-laki dan perempuan, kerja paksa, termasuk prostitusi, perdagangan narkoba dan senjata, terorisme dan kejahatan internasional yang terorganisir. Skala besarnya situasi ini dan jumlah nyawa tak bersalah yang menjadi korban adalah sedemikian parah sehingga kita harus menghindari godaan untuk jatuh ke dalam nominalisme retorik dengan efeknya yang menenangkan hati nurani. Kita harus memastikan bahwa lembaga-lembaga kita benar-benar efektif dalam memerangi semua momok itu.”[187] Ini dilakukan dengan secara cerdas memanfaatkan sumber daya besar yang ditawarkan oleh perkembangan teknologi.
189. Kita masih jauh dari globalisasi hak-hak asasi manusia yang paling dasar. Karena itu politik dunia tidak boleh lupa untuk menempatkan pemberantasan kelaparan yang efektif di antara tujuan-tujuan utamanya yang harus dicapai. Karena, “ketika spekulasi keuangan mempengaruhi harga makanan dengan memperlakukannya sebagai komoditi seperti yang lain, jutaan orang menderita dan mati kelaparan. Di sisi lain, banyak sekali makanan yang dibuang. Ini benar-benar sebuah skandal. Membiarkan kelaparan adalah kejahatan, makanan adalah hak yang tidak dapat dicabut.”[188] Seringkali, pada saat kita tenggelam dalam diskusi semantik (arti kata) atau ideologis, kita saat ini masih membiarkan saudara-saudari sekarat karena kelaparan dan kehausan, tanpa atap atau akses ke perawatan kesehatan. Selain kebutuhan-kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi ini, juga perdagangan manusia adalah aib bagi umat manusia yang seharusnya tidak lagi ditoleransi oleh politik internasional, melampaui berbagai pernyataan dan niat baik. Itulah syarat minimal yang mutlak perlu.
Kasih yang memadukan dan menyatukan
190. Cinta kasih politik juga terungkap dalam keterbukaan untuk semua. Terutama mereka yang memikul tanggung jawab pemerintahan, dipanggil untuk berkorban demi memungkinkan perjumpaan, dan mencari titik-titik temu, setidaknya dalam beberapa masalah. Mereka tahu bagaimana mendengarkan sudut pandang orang lain dengan memberi ruang kepada setiap orang. Dengan berkorban dan bersabar, seorang pemimpin dapat membantu menciptakan realitas polihedron yang indah di mana setiap orang mendapat tempat. Dalam konteks ini, negosiasi gaya bisnis ekonomis tidak akan berhasil. Lebih dari itu, ini adalah pertukaran pemberian demi kebaikan bersama. Ini tampaknya suatu utopia yang naif, tetapi kita tidak dapat mengingkari tujuan yang sangat luhur ini.
191. Sementara kita melihat bahwa segala macam intoleransi fundamentalis merusak hubungan antar individu, kelompok dan bangsa, mari kita berkomitmen untuk menghayati dan mengajarkan nilai penghormatan, kasih yang mampu menyambut segala perbedaan, dan prioritas dari martabat setiap manusia di atas segala gagasan, perasaan, dan tindakannya, dan bahkan di atas dosa-dosanya. Sementara fanatisme, cara berpikir yang tertutup, dan fragmentasi sosial dan budaya menjamur dalam masyarakat saat ini, seorang politikus yang baik mengambil langkah pertama agar suara-suara yang berbeda terdengar. Memang benar bahwa beberapa perbedaan menimbulkan konflik, tetapi keseragaman menyebabkan kita sesak nafas dan tertelan secara budaya. Jangan kita menyerah dengan hidup terkurung dalam sepenggal realitas saja.
192. Dalam konteks ini, saya ingin mengingatkan kembali bahwa, bersama Imam Besar Ahmad Al-Tayyeb, kami meminta “para pembuat kebijakan internasional dan ekonomi dunia, untuk bekerja keras menyebarkan budaya toleransi dan hidup berdampingan dalam damai; untuk ikut campur tangan selekas mungkin untuk menghentikan pertumpahan darah dari orang-orang yang tidak bersalah.”[189] Dan ketika politik tertentu menebarkan kebencian dan ketakutan terhadap bangsa-bangsa lain atas nama kesejahteraan negaranya sendiri, orang harus waspada, menanggapinya tepat waktu, dan segera mengoreksi arah jalannya.
Kesuburan lebih daripada hasil
193. Sementara menjalankan aktivitas ini tanpa kenal lelah, setiap politikus tetaplah manusia. Ia dipanggil untuk menghayati kasih dalam hubungan interpersonal sehari-hari. Ia adalah seorang pribadi, dan ia harus memperhatikan bahwa “dunia modern, dengan kemajuan teknisnya, cenderung semakin merasionalisasi pemuasan kebutuhan manusia, yang diklasifikasikan dan dibagi di antara pelbagai layanan. Semakin jarang seseorang dipanggil dengan namanya sendiri, semakin sedikit ia akan diperlakukan sebagai pribadi yang unik di dunia ini, seorang pribadi yang memiliki hati, penderitaannya, masalahnya, kegembiraannya dan keluarganya. Kita hanya akan mengetahui penyakitnya untuk menyembuhkannya, kekurangan uangnya untuk mencukupinya, kebutuhannya akan rumah untuk memberinya akomodasi, kebutuhannya akan hiburan dan rekreasi untuk mengurusnya.” Namun, “mencintai orang terkecil di antara manusia sebagai saudara, seolah-olah tidak ada orang lain di dunia ini selain dia, tidaklah membuang-buang waktu.”[190]
194. Dalam politik pun ada ruang untuk mengasihi dengan kelembutan. “Apakah kelembutan itu? Itulah kasih yang menjadi dekat dan konkret; suatu gerakan yang keluar dari hati dan menyentuh mata, telinga, tangan. […] Kelembutan adalah jalan yang dilalui oleh laki-laki dan perempuan yang paling berani dan terkuat.”[191] Di tengah-tengah aktivitas politik, “orang-orang terkecil, terlemah, termiskin harus menyentuh hati kita: mereka memiliki ‘hak’ untuk mengambil hati dan jiwa kita. Ya, mereka adalah saudara kita dan oleh karena itu kita harus memperlakukan mereka dengan kasih.”[192]
195. Ini membantu kita menyadari bahwa aktivitas initidak selalu tentang memperoleh hasil-hasil besar, yang terkadang tidak mungkin. Dalam aktivitas politik, harus diingat bahwa “apa pun penampilannya, setiap orang adalah sangat kudus dan layak kita kasihi dan layani. Akibatnya, jika saya dapat membantu setidaknya satu orang untuk hidup lebih baik, hal itu telah membenarkan persembahan hidup saya. Sungguh mengagumkan menjadi umat Allah yang setia. Kita mencapai pemenuhan ketika kita merobohkan dinding-dinding dan hati kita dipenuhi dengan wajah-wajah dan nama-nama!”[193] Sasaran-sasaran besar yang diimpikan dalam pelbagai strategi hanya tercapai sebagiannya. Namun melebihi hal itu, orang yang menaruh kasih dan yang tidak lagi memahami politik sekadar sebagai pencarian kekuasaan, “yakin bahwa tidak akan hilang satu pun tindakan kasih kita, begitu juga dengan tindakan kepedulian tulus kita kepada orang lain. Tak akan hilang satu pun tindakan kasih bagi Allah, tidak ada upaya murah hati akan sia-sia, tidak akan hilang satu pun kesabaran yang menyakitkan. Semuanya itu mengelilingi dunia sebagai suatu daya kehidupan.”[194]
196. Di sisi lain, adalah sangat mulia untuk dapat memulai proses yang buahnya akan dipanen oleh orang lain, dengan menaruh harapan pada kekuatan rahasia yang hadir dalam kebaikan yang ditaburkan. Politik yang baik menyatukan kasih dengan harapan yang percaya pada kebaikan yang tersimpan di dalam hati orang, terlepas dari segalanya. Oleh karena itu, “kehidupan politik yang autentik, yang didasarkan pada hukum dan dialog jujur antara para pelaku, selalu dibarui dengan keyakinan bahwa setiap perempuan, setiap laki-laki, dan setiap generasi membawa dalam dirinya suatu janji yang dapat melepaskan energi relasional, intelektual, budaya dan spiritual yang baru.”[195]
197. Bila dipandang demikian, politik lebih mulia daripada penampilannya, pemasaran dirinya dan pelbagai bentuk polesannya di media. Semuanya ini tidak menebarkan apa pun selain perpecahan, permusuhan, dan skeptisisme suram yang tidak mampu menggerakkan orang untuk suatu proyek bersama. Berkenaan dengan masa depan, ada kalanya hendaknya kita bertanya: “Apa tujuan saya? Apa sasaran saya yang sebenarnya?” Sebab, beberapa tahun kemudian, dengan merenungkan masa lampau sendiri, pertanyaannya bukan: “Berapa banyak orang yang telah mendukung saya, berapa banyak yang telah memilih saya, berapa banyak yang telah memiliki citra positif tentang saya?” Pertanyaan yang mungkin menyakitkan, adalah: “Seberapa besar kasih yang telah saya taruh dalam pekerjaan saya? Dalam hal apa saya telah membawa kemajuan bagi bangsa? Jejak apa yang telah saya tinggalkan dalam kehidupan masyarakat? Ikatan nyata apa yang telah saya bangun? Kekuatan positif apa yang telah saya lepaskan? Berapa banyak kedamaian sosial yang telah saya tabur? Apa yang telah saya hasilkan di posisi yang dipercayakan kepada saya?”
BAB ENAM
DIALOG DAN PERSAHABATAN SOSIAL
198. Saling mendekati dan mengungkapkan diri, saling memandang dan mendengarkan, mencoba mengenal dan memahami satu sama lain, mencari titik-titik temu, semua ini terangkum dalam kata kerja “berdialog.” Untuk berjumpa dan membantu satu sama lain, kita perlu berdialog. Tidak perlu saya jelaskan manfaat dialog itu. Saya justru memikirkan akan seperti apa dunia tanpa dialog yang sabar dari begitu banyak orang yang murah hati yang telah menjaga kesatuan keluarga dan komunitasnya. Dialog yang gigih dan berani tidak menjadi berita seperti perselisihan dan konflik, namun secara diam-diam membantu dunia untuk hidup lebih baik, lebih daripada yang dapat kita bayangkan.
Dialog sosial demi budaya baru
199. Beberapa orang mencoba melarikan diri dari realitas dengan berlindung di dunia pribadi mereka, dan beberapa menghadapinya dengan menggunakan kekerasan yang merusak, tetapi “di antara ketidakpedulian egois dan protes penuh kekerasan selalu ada kemungkinan pilihan lain: berdialog. Dialog antargenerasi, dialog di antara anak bangsa, karena kita semua adalah bangsa itu, kemampuan untuk memberi dan menerima, tetap terbuka pada kebenaran. Sebuah negara tumbuh ketika kekayaan budayanya yang beragam berinteraksi secara konstruktif: budaya populer, budaya akademis, budaya orang muda, budaya seni dan teknologi, budaya ekonomi, budaya keluarga, dan budaya media.”[196]
200. Dialog sering kali dikacaukan dengan sesuatu yang sangat berbeda: pertukaran pendapat yang memanas di jejaring sosial, yang seringkali diarahkan oleh informasi media yang tidak selalu dapat diandalkan. Semua itu hanya monolog yang berjalan paralel, yang mungkin menarik perhatian orang karena nada yang tinggi dan agresif. Tetapi monolog itu tidak melibatkan siapa pun, sampai-sampai isinya seringkali oportunistis dan kontradiktif.
201. Penyebaran fakta dan opini yang gencar di media, pada kenyataannya sering menutup kemungkinan untuk berdialog, karena memungkinkan setiap orang berpegang teguh pada pendapat, kepentingan, dan pilihannya sendiri, dengan dalih bahwa semua orang lain keliru. Kebiasaan untuk dengan cepat mendiskreditkan lawannya mendominasi, dengan memberi julukan-julukan yang menghina mereka, alih-alih masuk ke dalam dialog yang terbuka dan penuh hormat dalam upaya mencapai sintesis yang lebih tinggi. Yang lebih buruk adalah bahwa bahasa seperti itu yang lazim digunakan dalam media yang menyangkut kampanye politik, telah begitu menyebar luas sehingga semua orang menggunakannya setiap hari. Perdebatan sering dimanipulasi oleh kepentingan tertentu yang memiliki kekuatan sangat besar dan secara culas berupaya membelokkan opini publik agar mendukungnya. Saya tidak hanya merujuk pada pemerintah saat ini, karena kekuatan manipulatif ini dapat juga berupa ekonomi, politik, media, agama atau dalam bentuk apa pun. Kadang-kadang kita membenarkan praktik itu atau memaafkannya ketika dinamikanya sesuai dengan kepentingan ekonomi atau ideologi kita, tetapi cepat atau lambat hal itu berbalik melawan kepentingan yang sama itu.
202. Kurangnya dialog berarti bahwa tidak ada seorang pun, di berbagai sektor individual, yang peduli dengan kebaikan bersama, tetapi hanya dengan keuntungan yang diperoleh dari kekuasaan, atau, paling banter, dengan memaksakan cara berpikirnya sendiri. Dengan demikian, pembicaraan merosot menjadi negosiasi belaka agar masing-masing dapat merebut kekuasaan dan keuntungan sebesar mungkin, tanpa pencarian bersama yang menghasilkan kebaikan bersama. Para pahlawan masa depan adalah mereka yang akan tahu bagaimana mematahkan cara berpikir yang tidak sehat ini dan bertekad untuk dengan hormat menjunjung tinggi pembicaraan yang sarat dengan kebenaran, melampaui kepentingan pribadi. Menjadi kehendak Allah bahwa para pahlawan itu diam-diam bermunculan di tengah-tengah masyarakat kita.
Membangun bersama
203. Dialog sosial yang autentik mengandaikan kemampuan untuk menghormati sudut pandang orang lain, menerima kemungkinan bahwa pandangannya itu mengandung beberapa keyakinan atau kepentingan yang sah. Dari identitasnya, orang lain memiliki sesuatu untuk diberikan, dan diharapkan bahwa ia menegaskan dan menjelaskan posisinya sehingga debat publik menjadi makin lengkap. Benarlah bahwa ketika seseorang atau kelompok konsisten dengan apa yang mereka pikirkan, berpegang teguh pada nilai-nilai dan keyakinannya, dan mengembangkan suatu gagasan, hal itu dengan satu atau lain cara akan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Namun, hal ini hanya benar-benar tercapai sejauh pengembangan gagasannya itu berlangsung dalam dialog dan keterbukaan kepada orang lain. Memang, “dalam semangat dialog sejati, kita tumbuh dalam kecakapan kita untuk menangkap makna dari apa yang dikatakan dan dibuat oleh orang lain, bahkan jika kita tidak bisa menerima itu sebagai keyakinan kita sendiri. Dengan demikian dimungkinkan bersikap jujur, tidak menutupi apa yang kita percaya, tanpa berhenti berdialog, mencari titik-titik singgung, dan terutama bekerja dan berjuang bersama.”[197] Diskusi publik, jika benar-benar memberi ruang kepada semua orang dan tidak memanipulasi atau menyembunyikan informasi, selalu menjadi dorongan yang memungkinkan untuk menggapai kebenaran secara memadai, atau setidaknya untuk mengungkapkannya dengan lebih baik. Ini mencegah bahwa berbagai sektor menempatkan diri dengan nyaman dan puas diri dalam sudut pandang mereka sendiri dan dalam kepentingan mereka yang terbatas. Mari kita ingat bahwa “perbedaan-perbedaan itu kreatif, menciptakan ketegangan; dan dalam penyelesaian ketegangan terdapat kemajuan umat manusia.”[198]
204. Saat ini ada keyakinan bahwa, selain perkembangan ilmiah yang terspesialisasi, diperlukan juga komunikasi antar-disiplin ilmu, karena realitas adalah satu, meskipun dapat didekati dari perspektif yang berbeda dan dengan metodologi yang berbeda. Hendaknya jangan diabaikan risiko bahwa kemajuan ilmiah dianggap sebagai satu-satunya pendekatan yang mungkin untuk memahami salah satu aspek kehidupan, masyarakat, dan dunia. Sebaliknya, seorang peneliti yang berhasil membuat kemajuan dalam penyelidikannya, tapi juga siap untuk mengenali dimensi lain dari realitas yang ia selidiki, dengan bantuan karya ilmu lain dan bentuk pengetahuan lain, membuka diri untuk mengetahui realitas secara lebih utuh dan lengkap.
205. Dalam dunia yang mengglobal ini, “media dapat membantu kita untuk merasa lebih dekat satu sama lain; untuk membuat kita merasakan arti baru persatuan keluarga manusia yang mendorong solidaritas dan komitmen serius untuk kehidupan yang lebih bermartabat. […] Media dapat membantu kita dalam hal ini, terutama saat ini, ketika jaringan komunikasi manusia telah mencapai perkembangan yang belum pernah ada sebelumnya. Secara khusus, internet dapat menawarkan kesempatan yang lebih besar untuk perjumpaan dan solidaritas di antara semua, dan ini adalah hal yang baik, ini adalah anugerah dari Allah.”[199] Namun, harus terus dipastikan apakah bentuk-bentuk komunikasi saat ini benar-benar mengarahkan kita pada perjumpaan yang murah hati, pada pencarian tulus akan seluruh kebenaran, pada pelayanan, pada kedekatan dengan yang paling hina, pada komitmen untuk membangun kebaikan bersama. Pada saat yang sama, seperti yang telah ditunjukkan oleh para Uskup Australia, “kita tidak dapat menerima dunia digital yang dirancang untuk mengeksploitasi kelemahan kita dan menampilkan yang terburuk dalam diri orang-orang.”[200]
Dasar setiap konsensus
206. Relativisme bukanlah solusi. Dengan kedok toleransi yang semu, relativisme akhirnya mendukung fakta bahwa nilai-nilai moral ditafsirkan oleh orang yang berkuasa menurut apa yang dianggap cocok bagi mereka saat itu. Jika pada akhirnya “tidak ada kebenaran objektif atau prinsip-prinsip yang kuat, selain realisasi proyek-proyek pribadi dan pemuasan kebutuhan mendesak, […] janganlah kita berpikir bahwa upaya politik atau kekuatan hukum akan memadai. […] Apabila budaya sudah korup dan kita tidak lagi mengakui kebenaran objektif atau prinsip-prinsip yang berlaku universal, hukum hanya dilihat sebagai pemaksaan yang sewenang-wenang dan sebagai hambatan yang perlu dihindari.”[201]
207. Apakah mungkin untuk memberi perhatian kepada kebenaran dan mencari kebenaran yang sesuai dengan realitas terdalam kita? Apakah arti hukum tanpa keyakinan, yang dicapai melalui perjalanan panjang refleksi dan hikmat, bahwa setiap manusia itu sakral dan tidak dapat diganggu gugat? Untuk memiliki masa depan, suatu masyarakat harus mengembangkan rasa hormat yang tulus terhadap kebenaran martabat manusia, yang kepadanya kita tunduk. Maka, kita tidak akan menahan diri dari membunuh seseorang hanya untuk menghindari cemooh masyarakat dan beban hukum, tetapi karena keyakinan. Inilah kebenaran hakiki yang kita kenali dengan akal budi dan terima dengan hati nurani. Suatu masyarakat adalah mulia dan terhormat juga karena memupuk pencarian kebenaran dan karena berpegang pada kebenaran yang mendasar.
208. Kita perlu belajar membongkar bagaimana kebenaran dengan berbagai cara dimanipulasi, diputarbalikkan, dan ditutupi di ruang publik dan pribadi. Apa yang kita sebut “kebenaran” bukan hanya penyampaian fakta yang dilakukan melalui jurnalisme, tetapi terutama pencarian dasar-dasar paling kokoh yang menjadi landasan dari segala pilihan kita dan hukum kita. Ini berarti menerima bahwa kecerdasan manusia dapat melampaui kenyamanan sesaat dan memahami beberapa kebenaran yang tidak berubah, yang sudah benar sebelum kita dan akan selalu demikian. Dengan menyelidiki hakikat manusia, akal budi menemukan nilai-nilai yang universal, karena diturunkan dari hakikat itu.
209. Jika tidak demikian, tidakkah dapat terjadi bahwa hak-hak asasi manusia, yang sekarang dianggap tidak bisa diganggu gugat, akan ditolak oleh mereka yang sedang berkuasa, setelah mereka memperoleh “konsensus” dari para warga yang dininabobokkan atau diintimidasi? Konsensus belaka antara berbagai bangsa, yang sama-sama bisa dimanipulasi, juga tidak akan memadai. Sudah ada bukti berlimpah tentang segala kebaikan yang mampu kita lakukan, tetapi pada saat yang sama kita harus mengakui bahwa di dalam diri kita ada juga kemampuan untuk merusak. Bukankah kejatuhan kita ke dalam individualisme yang acuh tak acuh dan kejam juga merupakan akibat dari kemalasan dalam mencari nilai-nilai yang lebih tinggi yang melampaui kebutuhan sesaat? Relativisme membawa risiko tambahan bahwa yang berkuasa atau paling licik akan mampu memaksakan apa yang mereka anggap sebagai kebenaran. Sebaliknya, “berhadapan dengan norma-norma moral yang melarang kejahatan intrinsik, tidak ada hak istimewa atau pengecualian bagi siapa pun. Tidak ada bedanya menjadi penguasa dunia atau “orang yang paling malang” di muka bumi ini: menghadapi tuntutan-tuntutan moral kita semua secara mutlak sama.”[202]
210. Apa yang sedang terjadi pada kita saat ini, dan menyeret kita ke dalam cara berpikir yang sesat dan kosong, adalah bahwa etika dan politik disejajarkan dengan fisika. Tidak ada yang baik atau yang jahat dalam dirinya sendiri, tetapi hanya perhitungan keuntungan dan kerugian. Tergesernya penalaran moral membawa konsekuensi bahwa hukum tidak dapat merujuk pada paham dasar tentang keadilan, tetapi menjadi cerminan dari gagasan dominan. Di sini kita memasuki suatu kemerosotan: suatu “penurunan level” secara progresif melalui konsensus yang dangkal dan kompromistis. Jadi, pada akhirnya, logika kekuatan menang.
Konsensus dan kebenaran
211. Dalam masyarakat majemuk, dialog adalah cara paling tepat untuk mengenali apa yang harus selalu ditegaskan dan dihormati, dan melampaui setiap konsensus insidental. Kita berbicara tentang suatu dialog yang perlu diperkaya dan diterangi dengan alasan-alasan, dengan argumen-argumen rasional, dengan berbagai perspektif, dengan kontribusi dari berbagai bidang pengetahuan dan sudut pandang, dan yang tidak mengesampingkan keyakinan bahwa adalah mungkin untuk mencapai beberapa kebenaran hakiki yang harus dan akan selalu harus didukung. Menerima bahwa ada nilai-nilai tetap, meskipun tidak selalu mudah dikenali, memberikan soliditas dan stabilitas pada etika sosial. Bahkan bila kita telah mengakui dan menerimanya melalui dialog dan konsensus, kita melihat bahwa nilai-nilai dasar ini melampaui konsensus apa pun, dan kita mengakuinya sebagai nilai-nilai yang melampaui konteks kita dan tidak pernah dapat dinegosiasi. Pemahaman kita tentang makna dan pentingnya mungkin tumbuh –dan dalam arti itu konsensus adalah suatu realitas dinamis–, tetapi dalam dirinya sendiri nilai-nilai dasar ini dianggap tetap bertahan karena makna intrinsiknya.
212. Jika hal tertentu selalu bermanfaat untuk berfungsinya masyarakat dengan baik, bukankah mungkin karena di baliknya ada kebenaran abadi, yang dapat dipahami oleh akal budi? Dalam realitas manusia dan masyarakat, di dalam hakikatnya yang terdalam, terdapat serangkaian struktur dasar yang mendukung perkembangan dan kelangsungan hidup mereka. Dari situ muncul persyaratan-persyaratan tertentu yang dapat ditemukan berkat dialog, meskipun tidak dibuat secara tegas dengan konsensus. Fakta bahwa norma-norma tertentu sangat diperlukan untuk kehidupan sosial itu sendiri adalah petunjuk eksternal bahwa norma-norma itu pada hakikatnya baik. Karena itu, tidak perlu mempertentangkan kemanfaatan sosial, konsensus, dan realitas kebenaran objektif. Ketiganya bisa bersatu secara harmonis ketika, melalui dialog, orang memiliki keberanian untuk mencapai inti suatu permasalahan.
213. Jika martabat orang-orang lain harus dihormati dalam setiap situasi, itu bukan karena kita menemukan atau mengandaikan martabat itu, tetapi karena di dalam diri manusia memang ada nilai yang melebihi benda-benda materiil dan keadaan-keadaan yang tak tentu; dan itu menuntut agar mereka diperlakukan secara berbeda. Bahwa setiap manusia memiliki martabat yang tak terganggu gugat adalah kebenaran yang sesuai dengan kodrat manusia melampaui perubahan budaya apa pun. Oleh karena itu, manusia memiliki martabat sama yang tidak dapat diganggu gugat dalam masa sejarah mana pun; dan tidak seorang pun dapat merasa diberi wewenang oleh situasi tertentu untuk menyangkal keyakinan ini atau tidak bertindak sesuai dengannya. Karena itu, akal budi dapat meneliti realitas segala hal, melalui refleksi, pengalaman, dan dialog, untuk mengenali di dalam realitas yang melampaui dirinya, dasar dari tuntutan-tuntutan moral universal tertentu.
214. Landasan ini mungkin tampak cukup bagi kaum agnostik untuk memberikan validitas universal yang kuat dan stabil pada prinsip-prinsip etika dasar yang tidak dapat dinegosiasi, untuk dapat mencegah tragedi baru. Bagi orang beriman, kodrat manusia, sumber dari prinsip-prinsip etika, diciptakan oleh Allah, hal mana pada akhirnya memberikan landasan kuat pada prinsip-prinsip tersebut.[203] Ini tidak mengakibatkan etika yang kaku dan juga tidak membuka jalan bagi pemaksaan sistem moral apa pun, karena prinsip-prinsip moral dasar yang berlaku secara universal dapat menghasilkan peraturan-peraturan praktis yang berbeda. Oleh karena itu, selalu ada ruang untuk berdialog.
Suatu budaya baru
215. “Hidup adalah seni perjumpaan, meskipun ada banyak bentrokan dalam hidup.”[204] Saya sudah sering mengajak orang untuk mengembangkan budaya perjumpaan, yang melampaui dialektika yang mengadu domba. Inilah gaya hidup yang cenderung membentuk polihedron, benda yang memiliki banyak segi, sangat banyak sisinya, tetapi semuanya membentuk satu kesatuan yang kaya akan nuansa, karena “keseluruhan lebih besar daripada bagian.”[205] Polihedron menggambarkan sebuah masyarakat di mana perbedaan-perbedaan hidup berdampingan dengan saling melengkapi, saling memperkaya, dan saling menerangi, meskipun disertai ketidaksepakatan dan ketidakpercayaan. Sesungguhnya, kita bisa belajar sesuatu dari semua orang. Tak seorang pun tidak berguna, tak seorang pun tidak diperlukan. Artinya, mereka yang ada di pinggiran juga harus dilibatkan. Mereka yang berada di pinggiran memiliki sudut pandang berbeda, mereka melihat aspek-aspek realitas yang tidak dikenali oleh mereka yang berada di pusat kekuasaan di mana diambil keputusan-keputusan paling menentukan.
Perjumpaan yang menjadi budaya
216. Kata “budaya” menunjukkan sesuatu yang meresap ke dalam bangsa, ke dalam keyakinan-keyakinannya yang terdalam dan gaya hidupnya. Jika kita berbicara tentang “budaya” bangsa, itu lebih dari sekadar ide atau abstraksi. Budaya mencakup keinginan-keinginan, antusiasme, dan akhirnya cara hidup yang menjadi ciri khas kelompok manusia itu. Maka, berbicara tentang “budaya perjumpaan” berarti bahwa sebagai bangsa kita bersemangat untuk bertemu, mencari titik temu, membangun jembatan, merencanakan sesuatu yang melibatkan semua orang. Hal itu sudah menjadi aspirasi dan gaya hidup. Subjek budaya ini adalah bangsa, dan bukan satu bagian masyarakat yang bertujuan menjaga ketenangan bagian yang lain dengan sarana profesional dan media.
217. Perdamaian sosial menuntut kerja keras dan keterampilan. Akan lebih mudah untuk menjaga kebebasan dan aneka perbedaan dengan sedikit kelihaian dan sumber daya lain. Namun, perdamaian itu akan dangkal dan rapuh, bukan buah dari budaya perjumpaan yang menopangnya. Memadukan aneka realitas yang berbeda adalah jauh lebih sulit dan lambat, namun menjadi jaminan perdamaian yang nyata dan kokoh. Ini tidak bisa dicapai dengan mempertemukan orang-orang yang “bersih” saja, karena “bahkan orang-orang yang dianggap meragukan karena kesalahan-kesalahan mereka memiliki sesuatu untuk disumbangkan yang tidak boleh diabaikan.”[206] Ini juga bukan tentang perdamaian yang muncul dengan membungkam tuntutan sosial atau menghalangi orang membuat terlalu banyak keributan karena perdamaian bukanlah “konsensus di atas kertas atau perdamaian sementara bagi minoritas yang sudah puas.”[207] Yang penting adalah memulai proses perjumpaan, proses yang bisa membangun bangsa yang mampu menerima perbedaan-perbedaan. Mari kita mempersenjatai anak-anak kita dengan senjata dialog! Mari kita ajari mereka perjuangan yang baik untuk perjumpaan!
Sukacita mengakui orang lain
218. Ini meminta sikap yang mampu mengakui hak orang lain untuk menjadi dirinya sendiri dan menjadi berbeda. Mulai dari pengakuan yang membudaya ini, akan mungkin untuk menciptakan pakta sosial. Tanpa pengakuan itu, akan muncul cara-cara halus untuk membuat orang lain kehilangan segala makna, menjadi tidak relevan, tidak lagi diakui memiliki nilai apa pun dalam masyarakat. Di balik penolakan terhadap bentuk-bentuk kekerasan tertentu, sering kali disembunyikan kekerasan lain yang lebih halus: yaitu kekerasan mereka yang merendahkan orang yang berbeda, terutama ketika tuntutannya dengan cara apa pun merugikan kepentingan mereka.
219. Apabila sebagian masyarakat menuntut untuk menikmati segala yang ditawarkan dunia, seolah-olah orang miskin tidak ada, hal itu pada akhirnya akan menimbulkan konsekuensi. Mengabaikan keberadaan dan hak-hak orang-orang lain cepat atau lambat akan memicu beberapa bentuk kekerasan, seringkali pada saat yang tidak terduga. Impian-impian tentang kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan dapat tetap berada pada tataran formalitas belaka, karena tidak berlaku untuk semua. Oleh karena itu, ini bukan sekadar tentang mengusahakan pertemuan antara mereka yang memegang berbagai bentuk kekuasaan ekonomi, politik atau akademis. Dalam perjumpaan sosial yang nyata, pelbagai bentuk budaya besar yang mewakili mayoritas penduduk dibawa ke dalam dialog yang benar. Seringkali saran-saran yang baik tidak diterima oleh sektor-sektor yang paling miskin karena ditampilkan dalam bungkusan budaya yang bukan milik mereka, dan mereka tidak bisa mengidentifikasi diri dengannya. Karena itu, suatu pakta sosial yang realistis dan inklusif juga harus menjadi suatu “pakta budaya”, yang menghormati dan mengakui pelbagai pandangan dunia, budaya, dan gaya hidup yang hidup berdampingan dalam masyarakat.
220. Misalnya, masyarakat adat tidak menentang kemajuan, meskipun mereka memiliki gagasan yang berbeda tentang kemajuan, seringkali lebih humanistis daripada budaya modern bangsa-bangsa maju. Budaya masyarakat adat tidak berorientasi pada keuntungan golongan yang berkuasa, yang merasa harus menciptakan semacam surga di bumi. Intoleransi dan penghinaan terhadap budaya rakyat asli adalah benar-benar bentuk kekerasan, yang khas bagi “para guru moral” tanpa kebaikan, mereka yang hidup dengan menghakimi orang lain. Tetapi tidak ada perubahan autentik, mendalam, dan stabil yang mungkin terjadi, jika tidak diusahakan mulai dari pelbagai budaya, terutama dari budaya orang miskin. Suatu pakta budaya mengandaikan bahwa orang menghindari pemahaman monolitik tentang identitas suatu tempat, dan menuntut bahwa keanekaragaman dihormati dengan menawarkan kesempatan untuk kemajuan dan integrasi sosial bagi semua.
221. Pakta ini juga menuntut untuk menerima kemungkinan menyerahkan sesuatu bagi kebaikan bersama. Tak seorang pun akan dapat memiliki seluruh kebenaran, atau memuaskan segala keinginannya, karena tuntutan itu akan menimbulkan keinginan untuk menghancurkan yang lain dengan menyangkal hak-haknya. Pencarian toleransi palsu harus memberi jalan kepada realisme dialog di pihak mereka yang percaya bahwa mereka harus setia pada prinsip-prinsip mereka sendiri, namun dengan menyadari bahwa yang lain juga memiliki hak untuk mencoba setia pada prinsipnya sendiri. Inilah pengakuan sejati terhadap yang lain, yang hanya dimungkinkan oleh kasih, dan yang berarti menempatkan diri dalam posisi orang lain untuk menemukan apa yang otentik, atau setidaknya masuk akal di antara berbagai motivasi dan minatnya.
Memulihkan kebaikan hati
222. Individualisme konsumeris menyebabkan banyak ketidakadilan. Orang-orang lain hanya menjadi penghalang bagi ketenangan pribadi yang mengasyikkan. Akhirnya, kita memperlakukan mereka sebagai gangguan, dan agresi meningkat. Ini makin garang dan mencapai tingkat yang tidak tertahankan di saat-saat krisis, dalam situasi malapetaka, di saat-saat sulit, ketika muncul mentalitas “menyelamatkan diri sendiri.” Namun demikian, masih mungkin untuk memilih melakukan kebaikan. Ada orang-orang yang melakukannya dan menjadi bintang-bintang di tengah kegelapan.
223. Santo Paulus menyebutkan salah satu buah Roh Kudus dengan istilah Yunani chrestotes (Gal. 5:22), yang mengungkapkan sikap yang tidak keras, kasar, bengis, tetapi baik hati, lembut, menopang dan menghibur. Orang yang memiliki kualitas ini membantu orang lain agar hidup mereka lebih tertahankan, terutama ketika mereka memikul beban aneka masalah, kebutuhan mendesak, dan kecemasan. Ini adalah cara memperlakukan orang lain yang menyatakan diri dalam berbagai bentuk: seperti tindakan kebaikan dalam memperlakukan orang, kehati-hatian untuk tidak melukainya dengan perkataan atau perbuatan, dan upaya untuk meringankan beban orang lain. Termasuk “mengucapkan kata-kata penyemangat, yang menghibur, menguatkan, menjadi pelipur, dan memberi dorongan”, bukan “kata-kata yang merendahkan, yang membuat sedih, marah, dan menghina.”[208]
224. Kebaikan hati membebaskan kita dari kekejaman yang terkadang merasuki hubungan antarmanusia, dari kecemasan yang menghalangi kita memikirkan orang lain, dari kesibukan mengganggu yang mengabaikan bahwa orang lain juga berhak untuk bahagia. Saat ini jarang ditemukan waktu dan energi untuk berhenti sejenak dan memperlakukan orang lain dengan baik, untuk mengatakan “permisi”, “maaf,”, “terima kasih.” Namun terkadang muncul keajaiban seseorang yang baik hati, yang mengesampingkan segala kecemasan dan kesibukannya untuk memberikan perhatian dan senyuman, mengucapkan kata-kata yang memberi dorongan, menyediakan ruang untuk mendengarkan di tengah begitu banyak ketidakpedulian. Upaya yang dijalani setiap hari ini mampu menciptakan hidup berdampingan yang sehat, yang mengatasi kesalahpahaman dan mencegah konflik. Praktik kebaikan hati bukanlah hal kecil yang sekunder atau pun sikap yang dangkal atau borjuis. Karena kebaikan hati itu mengandaikan penghargaan dan rasa hormat, bila itu menjadi budaya dalam masyarakat, secara mendalam dapat mengubah gaya hidup, hubungan sosial, cara membahas dan membandingkan gagasan-gagasan. Ini mempermudah pencarian konsensus dan membuka jalan-jalan di tempat kemarahan akan menghancurkan segala jembatan.
BAB TUJUH
JALAN-JALAN PERJUMPAAN BARU
225. Di banyak bagian dunia dibutuhkan jalan-jalan perdamaian yang menuntun pada penyembuhan luka-luka; dibutuhkan para pendamai yang dengan cerdas dan berani siap memulai proses-proses penyembuhan dan perjumpaan baru.
Mulai dari kebenaran
226. Perjumpaan baru tidak berarti kembali ke masa sebelum konflik. Seiring waktu, kita semua telah berubah. Rasa sakit dan konflik telah mengubah kita. Selain itu, tidak ada lagi ruang untuk diplomasi kosong, untuk berpura-pura, untuk berbicara samar-samar, untuk menyelubungi maksud, untuk tata krama basa-basi yang menyembunyikan realitas. Semua yang telah saling berkonfrontasi dengan keras, harus berbicara satu sama lain mulai dari kebenaran, dengan jelas dan terus terang. Mereka harus belajar melatih ingatan penyesalan, mampu menerima masa lalu untuk membebaskan masa depan dari berbagai ketidakpuasan, kebingungan, dan proyeksi mereka sendiri. Hanya dari kebenaran historis atas fakta-fakta akan lahir upaya-upaya gigih dan berkelanjutan untuk saling memahami dan mengusahakan suatu sintesis baru untuk kebaikan semua. Kenyataannya adalah bahwa “proses perdamaian membutuhkan komitmen berkelanjutan. Ini merupakan pekerjaan yang sabar untuk mengusahakan kebenaran dan keadilan, yang menghormati memori para korban, dan yang selangkah demi selangkah membuka harapan bersama, yang lebih kuat daripada balas dendam.”[209] Seperti yang telah ditegaskan para Uskup Kongo tentang suatu konflik yang berulang, “perjanjian perdamaian di atas kertas tidak akan cukup. Kita harus melangkah lebih jauh, dengan menghormati tuntutan akan kebenaran tentang asal mula krisis yang berulang ini. Rakyat berhak tahu apa yang terjadi.”[210]
227. Sungguh, “kebenaran adalah pendamping tak terpisahkan dari keadilan dan belas kasihan. Ketiganya bersama-sama penting untuk membangun perdamaian dan, di sisi lain, masing-masing mencegah yang lain dibelokkan. […] Kebenaran seharusnya, pada kenyataannya, tidak mengarah pada balas dendam, tetapi pada rekonsiliasi dan pengampunan. Kebenaran berarti memberi tahu keluarga yang dilanda kesedihan tentang apa yang terjadi dengan kerabat mereka yang hilang. Kebenaran berarti mengakui apa yang terjadi pada anak-anak di bawah umur yang direkrut oleh para pelaku kekerasan. Kebenaran mengakui rasa sakit perempuan yang menjadi korban kekerasan dan pelecehan. […] Setiap kekerasan yang dilakukan terhadap seorang manusia adalah luka dalam daging umat manusia; setiap kematian dengan kekerasan “merendahkan” kita sebagai manusia. […] Kekerasan menghasilkan kekerasan, kebencian melahirkan lebih banyak kebencian dan kematian lebih banyak kematian. Kita harus memutus rantai yang tampaknya tak terelakkan ini.”[211]
Arsitektur dan kerja tangan perdamaian
228. Jalan menuju perdamaian tidak membutuhkan penyeragaman masyarakat, tetapi tentu mengizinkan kita untuk bekerjasama. Banyak orang bisa disatukan dalam mengusahakan pencarian bersama yang menguntungkan semua. Dihadapkan pada tujuan bersama yang tertentu, dimungkinkan untuk menawarkan berbagai usulan teknis dan berbagai pengalaman, lalu bekerja untuk kebaikan bersama. Kita harus berusaha mengidentifikasi dengan baik masalah-masalah yang dialami masyarakat, untuk menerima bahwa ada berbagai cara untuk melihat kesulitan-kesulitan dan menyelesaikannya. Jalan menuju hidup berdampingan yang lebih baik selalu menuntut untuk mengakui kemungkinan bahwa pihak lain membawa perspektif yang sah –setidaknya sebagian–, sesuatu yang dapat dipertimbangkan lagi, bahkan bila ia mungkin pernah salah atau telah melakukan hal yang buruk. Sungguh, “orang lain tidak pernah boleh dikurungkan dalam apa yang mungkin pernah ia katakan atau lakukan, tetapi harus dipertimbangkan karena janji yang ia bawa dalam dirinya,”[212] janji yang selalu menyisakan secercah harapan.
229. Seperti yang diajarkan oleh para Uskup Afrika Selatan, rekonsiliasi sejati dicapai secara proaktif, “dengan membentuk masyarakat baru berdasarkan pelayanan kepada orang lain, bukannya keinginan untuk mendominasi; sebuah masyarakat yang didasarkan pada upaya berbagi dengan orang lain apa yang dimilikinya, bukan pada perjuangan egois masing-masing untuk mengumpulkan kekayaan sebanyak mungkin; sebuah masyarakat di mana nilai kebersamaan sebagai manusia jelas lebih penting daripada kelompok kecil mana pun, entah itu keluarga, bangsa, ras, atau budaya.”[213] Para Uskup Korea Selatan telah menunjukkan bahwa perdamaian sejati “hanya dapat dicapai jika kita memperjuangkan keadilan melalui dialog, dengan mengupayakan rekonsiliasi dan pengembangan bersama.” [214]
230. Komitmen yang sulit untuk mengatasi apa yang memisahkan kita tanpa kehilangan identitas masing-masing mengandaikan bahwa rasa memiliki yang mendasar tetap hidup dalam diri setiap orang. Memang, “masyarakat kita menang ketika setiap orang, setiap kelompok sosial, benar-benar merasa di rumah sendiri. Dalam sebuah keluarga, orang tua, kakek nenek, dan anak-anak semuanya berada di rumah; tidak ada yang dikecualikan. Jika seseorang mengalami kesulitan, bahkan yang berat, bahkan ketika dia sendiri yang menyebabkan kesulitannya, yang lain datang membantunya, mendukungnya; rasa sakitnya menjadi milik mereka semua. […] Dalam keluarga, semua berkontribusi pada proyek bersama, semuanya bekerja untuk kebaikan bersama, tetapi tanpa meniadakan setiap individu; sebaliknya, mereka mendukungnya, mereka memajukannya. Mereka bertengkar, tetapi ada sesuatu yang tidak berubah: ikatan keluarga itu. Pertengkaran keluarga kemudian menjadi rekonsiliasi. Suka dan duka masing-masing ikut dirasakan oleh semua. Itulah arti menjadi sebuah keluarga! Jika saja kita mampu melihat lawan politik atau tetangga kita dengan mata yang sama seperti kita melihat anak, istri, suami, ayah dan ibu kita, betapa indahnya! Apakah kita mencintai masyarakat kita, atau itu tetap sesuatu yang jauh, sesuatu yang anonim, yang tidak melibatkan kita, tidak menyentuh kita, tidak mengikat kita?”[215]
231. Banyak kali sangat perlu untuk bernegosiasi dan dengan demikian mengembangkan jalan-jalan konkret menuju perdamaian. Namun, proses-proses efektif perdamaian yang bertahan lama terletak terutama dalam perubahan-perubahan yang merupakan kerja tangan masyarakat, di mana setiap orang dapat menjadi ragi yang efektif dengan gaya hidupnya sehari-hari. Perubahan-perubahan besar tidak dihasilkan di belakang meja atau di kantor. Oleh karena itu, “setiap orang memainkan peran mendasar dalam satu-satunya proyek kreatif, untuk menulis halaman sejarah yang baru, halaman penuh harapan, penuh perdamaian, penuh rekonsiliasi.”[216] Ada sebuah “arsitektur” perdamaian, di mana berbagai institusi masyarakat berkontribusi, masing-masing sesuai dengan kompetensinya sendiri, tetapi ada juga sebuah “kerja tangan” perdamaian yang melibatkan kita semua. Dari berbagai proses perdamaian yang berkembang di berbagai belahan dunia, “kita telah belajar bahwa jalan-jalan dari perdamaian, keutamaan akal budi di atas balas dendam, keselarasan yang halus antara politik dan hukum itu, tidak dapat mengabaikan jalan-jalan rakyat. Tidaklah cukup untuk merancang kerangka hukum dan pengaturan kelembagaan antara kelompok politik atau ekonomi yang berkehendak baik. […] Selain itu, selalu berharga bila pengalaman dari sektor-sektor yang dalam banyak kesempatan telah dibuat tidak terlihat, dimasukkan ke dalam proses perdamaian, sehingga masyarakat sendiri dapat mewarnai proses ingatan kolektif .”[217]
232. Tidak ada titik akhir dalam membangun perdamaian sosial di sebuah negara. Ini menyangkut “suatu tugas yang tidak memberikan waktu jeda dan yang membutuhkan komitmen dari semua. Pekerjaan ini meminta kita untuk tidak menyerah dalam upaya membangun persatuan bangsa. Meskipun ada banyak hambatan, perbedaan-perbedaan dan berbagai pendekatan untuk mencapai hidup berdampingan dalam damai, kita diminta bertekun dalam perjuangan untuk memajukan budaya perjumpaan. Hal ini menuntut agar pribadi manusia, dengan martabatnya yang tertinggi, dan hormat untuk kebaikan bersama ditempatkan di pusat segala tindakan politik, sosial, dan ekonomi. Semoga upaya ini membuat kita terhindar dari setiap godaan balas dendam dan pengejaran kepentingan pribadi jangka pendek saja.”[218] Berbagai demonstrasi umum dengan kekerasan, dari satu sisi atau sisi lain, tidak membantu untuk menemukan jalan keluar. Terutama karena, seperti yang diamati dengan baik oleh para Uskup Kolombia, di saat ajakan “mobilisasi warga, asal dan tujuannya tidak selalu jelas; ada berbagai bentuk manipulasi politik dan pemanfaatan untuk kepentingan tertentu.”[219]
Terutama bersama yang terkecil
233. Memajukan persahabatan sosial tidak hanya memerlukan pemulihan hubungan antara kelompok-kelompok sosial yang renggang karena konflik selama suatu periode sejarah, tetapi juga upaya untuk perjumpaan baru dengan sektor-sektor yang paling miskin dan rentan. Perdamaian “bukan hanya tidak adanya perang, melainkan komitmen yang tak kenal lelah – khususnya dari pihak mereka yang memegang jabatan dengan tanggung jawab lebih besar– untuk mengakui, menjamin dan secara konkret memulihkan martabat, yang sering dilupakan atau diabaikan, dari saudara-saudara kita itu, agar mereka dapat merasa diri sebagai pelaku utama dari peruntungan bangsa mereka sendiri.[220]
234. Orang-orang terkecil dalam masyarakat sering kali tersinggung karena berbagai penyamarataan yang tidak adil. Bila yang termiskin dan paling terbuang terkadang bereaksi dengan sikap yang tampak antisosial, kita harus menyadari bahwa dalam banyak kasus reaksi ini muncul dari suatu sejarah penuh penghinaan dan kurangnya inklusi sosial. Seperti yang diajarkan oleh para Uskup Amerika Latin, “hanya kedekatan yang membuat kita menjadi sahabat, dapat memampukan kita untuk sungguh menghargai nilai-nilai orang miskin masa kini, kerinduan mereka yang sah dan cara khas mereka dalam menghayati iman. Opsi bagi orang miskin harus membawa kita pada persahabatan dengan orang miskin.”[221]
235. Mereka yang ingin membawa damai pada suatu masyarakat, tidak boleh lupa bahwa ketimpangan dan kurangnya pengembangan manusia seutuhnya tidak memungkinkan terciptanya perdamaian. Memang, “selama tak ada kesempatan yang merata, berbagai bentuk agresi dan peperangan akan mendapatkan lahan subur untuk berkembang dan akhirnya meledak. Selama masyarakat –baik lokal, nasional maupun global– membiarkan sebagian dari dirinya disingkirkan, tak ada program politik atau penegakan hukum atau sistem keamanan yang dapat selamanya menjamin ketenangan.”[222] Jika harus memulai kembali, kita harus selalu memulainya dari mereka yang terkecil.
Nilai dan makna pengampunan
236. Beberapa orang memilih untuk tidak berbicara tentang rekonsiliasi karena mereka berpikir bahwa konflik, kekerasan dan perpecahan adalah bagian dari cara kerja yang normal dari masyarakat. Kenyataannya, dalam kelompok manusia mana pun ada perebutan kekuasaan –sering hampir tidak kentara– antara berbagai sektor. Orang lain berpendapat bahwa membolehkan pengampunan sama dengan menyerahkan ruang kepada orang lain untuk menguasai situasi. Oleh karena itu, mereka berpikir bahwa lebih baik tetap mempertahankan permainan kekuasaan yang memungkinkan untuk menjaga keseimbangan kekuatan antara pelbagai kelompok. Orang lain percaya bahwa rekonsiliasi adalah cara orang-orang lemah, yang tidak mampu mengadakan dialog yang sungguh-sungguh dan karena itu memilih untuk lari dari masalah-masalah dengan menyembunyikan ketidakadilan: tidak mampu menghadapi masalah, mereka memilih perdamaian yang semu.
Konflik yang tak terhindarkan
237. Pengampunan dan rekonsiliasi merupakan tema-tema yang sangat penting dalam agama Kristen dan, dengan berbagai cara, dalam agama-agama lain. Ada risiko bahwa pelbagai keyakinan orang-orang beriman tidak cukup dipahami, lalu ditampilkan sedemikian rupa sehingga pada akhirnya memicu fatalisme, kelesuan, atau ketidakadilan, atau, di sisi lain, intoleransi dan kekerasan.
238. Yesus Kristus tidak pernah mengajak untuk memicu kekerasan atau intoleransi. Ia sendiri secara terbuka mengutuk penggunaan kekerasan yang memaksakan diri kepada orang lain: “Kamu tahu, bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu” (Mat. 20:25-26). Di sisi lain, Injil meminta untuk mengampuni “tujuh puluh kali tujuh kali” (Mat. 18:22) dan memberikan ilustrasi tentang seorang hamba yang tak berbelas kasihan, yang telah diampuni tetapi pada gilirannya tidak mampu mengampuni orang lain (lih. Mat. 18:23-35).
239. Bila kita membaca teks-teks lain dari Perjanjian Baru, kita dapat melihat bahwa Gereja perdana, yang hidup di tengah-tengah dunia kafir yang sarat korupsi dan penyimpangan, berusaha menunjukkan kesabaran, toleransi, dan pengertian. Beberapa teks sangat jelas dalam hal ini: ada ajakan untuk menegur lawan dengan lemah-lembut (lih. 2Tim. 2:25). Ada anjuran, “Janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan” (Tit. 3:2-3). Kisah Para Rasul menegaskan bahwa para murid, yang dianiaya oleh beberapa penguasa, “disukai semua orang” (lih. 2:47; 4:21, 33; 5:13).
240. Namun, ketika kita merenungkan pengampunan, perdamaian, dan harmoni sosial, kita menemukan perkataan Kristus yang mengejutkan kita: “Jangan kamu menyangka, bahwa Aku datang untuk membawa damai di atas bumi; Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab Aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya“ (Mat. 10:34-36). Penting untuk memahaminya dalam konteks bab di mana kata-kata itu ditemukan. Di situ jelas bahwa tema yang dibahas adalah kesetiaan pada pilihannya, tanpa malu, meskipun itu menyebabkan pertentangan, bahkan bila orang-orang yang dikasihi menentang pilihan itu. Maka, perkataan tersebut tidak mengajak untuk mencari konflik, tetapi hanya untuk menanggung konflik yang tak terhindarkan; jangan sampai penghormatan manusiawi, demi menjaga perdamaian tertentu dalam keluarga atau masyarakat, menyebabkan hilangnya kesetiaan kita. Santo Yohanes Paulus II menegaskan bahwa Gereja “tidak bermaksud untuk mengecam semua dan setiap bentuk konflik sosial. Sebab Gereja menyadari juga bahwa di antara pelbagai golongan sosial pasti akan timbul konflik-konflik kepentingan tertentu; dan dalam menghadapi itu orang kristiani harus seringkali menentukan pendiriannya, dengan terus terang dan tepat.”[223]
Perjuangan yang sah dan pengampunan
241. Ini tidak berarti menawarkan pengampunan dengan melepaskan hak-haknya sendiri di hadapan seorang penguasa yang korup, seorang penjahat, atau seseorang yang merendahkan martabat kita. Kita dipanggil untuk mengasihi setiap orang, tanpa kecuali. Tetapi mengasihi seorang penindas tidak berarti membiarkannya terus bertindak demikian; juga tidak membiarkannya berpikir bahwa apa yang dilakukannya dapat diterima. Sebaliknya, cara yang baik untuk mengasihinya adalah berusaha dengan berbagai cara untuk membuatnya berhenti menindas, melucuti kekuatannya yang cara penggunaannya tidak ia ketahui dan yang merusaknya sebagai manusia. Pengampunan tidak berarti membiarkannya terus menginjak-injak martabatnya sendiri dan martabat orang lain, atau membiarkan seorang penjahat terus melakukan kejahatan. Mereka yang menderita ketidakadilan harus dengan gigih membela hak-hak mereka dan hak-hak keluarga mereka, justru karena mereka harus menjaga martabat yang telah mereka terima sebagai anugerah penuh kasih dari Allah. Bila seorang penjahat telah merugikan saya atau salah seorang yang saya kasihi, tidak ada yang melarang saya untuk menuntut keadilan dan memastikan bahwa orang itu –atau orang lain– tidak merugikan saya lagi atau melakukan hal yang sama terhadap orang lain. Saya berhak melakukannya, dan pengampunan tidak hanya tidak melarangnya, tetapi bahkan menuntutnya.
242. Yang penting adalah tidak melakukannya untuk memicu kemarahan yang menyakiti jiwa manusia dan jiwa bangsa kita, atau karena keinginan tidak sehat untuk menghancurkan orang lain dengan melampiaskan serangkaian tindakan balas dendam. Dengan cara itu tak seorang pun mencapai kedamaian batin atau berdamai dengan kehidupan. Yang benar adalah bahwa “tidak ada keluarga, tidak ada rukun tetangga, tidak ada kelompok etnis dan bahkan negara yang memiliki masa depan, jika daya dorong yang menyatukan mereka, mengumpulkan mereka, dan menutupi pelbagai perbedaan adalah balas dendam dan kebencian. Kita tidak dapat bersepakat dan bersatu demi balas dendam, membalas mereka yang telah melakukan kekerasan dengan hal yang sama seperti yang telah mereka lakukan kepada kita; atau merencanakan kesempatan pembalasan dalam bentuk yang tampaknya legal.”[224] Dengan cara itu tidak ada yang diperoleh dan dalam jangka panjang semuanya hilang.
243. Tentu saja, “bukanlah tugas yang mudah untuk mengatasi warisan pahit dari ketidakadilan, permusuhan, dan ketidakpercayaan yang ditinggalkan oleh konflik. Ini hanya dapat dilakukan dengan mengalahkan kejahatan dengan kebaikan (lih. Rom. 12:21) dan memupuk kebajikan yang mendorong rekonsiliasi, solidaritas, dan perdamaian.”[225] Dengan cara ini, “mereka yang memupuk kebaikan di dalam hatinya, memperoleh hati nurani yang damai dan sukacita yang mendalam, bahkan di tengah berbagai kesulitan dan kesalahpahaman. Bahkan ketika menderita penghinaan, kebaikan bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan sejati yang mampu melepaskan dendam.”[226] Setiap orang perlu mengakui dalam hidupnya sendiri bahwa “penghakiman keras yang saya simpan dalam hati terhadap saudara atau saudariku, luka yang belum disembuhkan, kejahatan yang tidak diampuni, dendam yang hanya akan menyakiti saya, adalah sepotong perang yang saya bawa di dalam diri saya; adalah percikan api di dalam hati saya, yang perlu dipadamkan supaya tidak menjadi kobaran api.”[227]
Cara mengatasi yang benar
244. Ketika konflik-konflik tidak diselesaikan tetapi disembunyikan atau dikubur di masa lalu, terjadi kebisuan yang bisa berarti menyebabkan diri terlibat dalam kesalahan dan dosa berat. Sebaliknya, rekonsiliasi sejati tidak lari dari konflik, tetapi dicapai dalam konflik, dengan mengatasinya melalui dialog dan negosiasi yang transparan, tulus dan sabar. Pertarungan antara berbagai kelompok, “bila menahan diri dari tindakan permusuhan dan kebencian satu sama lain, berangsur-angsur berubah menjadi diskusi jujur, yang berlandaskan pada pencarian keadilan.”[228]
245. Saya telah berulang kali mengusulkan “sebuah prinsip yang sangat diperlukan untuk membangun persahabatan dalam masyarakat; yakni, bahwa persatuan lebih unggul daripada pertentangan. […] Hal ini tidak berarti mendorong ke arah sinkretisme, atau ke penyerapan yang satu ke dalam yang lain, tetapi merupakan suatu pemecahan yang terjadi pada tataran lebih tinggi yang mempertahankan apa yang sah dan bermanfaat pada kedua belah pihak.”[229] Kita tahu betul bahwa “kapan pun, sebagai pribadi dan komunitas, kita belajar untuk mengejar tujuan yang melampaui diri kita sendiri dan kepentingan pribadi kita, maka pengertian dan komitmen timbal balik pun berubah […] menjadi ruang lingkup di mana berbagai konflik, ketegangan, dan bahkan apa yang di masa lalu mungkin dianggap bertentangan, bisa mencapai suatu kesatuan pluriform yang melahirkan kehidupan baru.”[230]
Memori
246. Tidak seharusnya dituntut semacam “pengampunan sosial” dari seseorang yang telah banyak menderita secara tak adil dan kejam. Rekonsiliasi adalah perbuatan pribadi, dan tidak seorang pun dapat memaksakannya kepada masyarakat secara keseluruhan, meskipun mereka bertugas mempromosikannya. Dalam konteks yang sangat pribadi, dengan keputusan yang bebas dan murah hati, seseorang dapat melepaskan tuntutan hukuman (lih. Mat. 5:44-46), meskipun masyarakat dan pengadilannya secara sah menuntutnya. Namun, tidak mungkin untuk menetapkan “rekonsiliasi umum”, dengan mengira bisa menutup luka dengan keputusan atau menutupi ketidakadilan dengan jubah pelupaan. Siapa yang bisa mengklaim hak untuk memaafkan atas nama orang lain? Sungguh mengharukan melihat kemampuan untuk mengampuni dari beberapa orang yang telah tahu mengatasi kerugian yang dideritanya, tetapi juga manusiawi untuk memahami mereka yang tidak bisa melakukannya. Bagaimanapun, yang tidak pernah boleh disarankan adalah melupakan.
247. Pemusnahan warga Yahudi Eropa oleh Nazi Jerman tidak boleh dilupakan. Ini adalah “simbol sejauh mana kejahatan manusia bisa terjadi ketika, dipicu oleh ideologi palsu, ia melupakan martabat hakiki setiap manusia, yang layak mendapatkan penghormatan mutlak terlepas dari bangsa asalnya dan agama yang dianutnya.”[231] Dalam mengenangnya, saya tidak bisa tidak mengulangi doa ini: “Tuhan, ingatlah kami dalam belas kasihan-Mu. Berilah kami rahmat untuk merasa malu atas apa yang, sebagai manusia, telah kami lakukan; merasa malu atas penyembahan berhala besar-besaran ini, malu karena telah memandang rendah dan menghancurkan daging kami sendiri, yang Engkau bentuk dari debu tanah, yang Engkau hidupkan dengan nafas hidup-Mu sendiri. Tidak pernah lagi, ya Tuhan, tidak pernah lagi!.” [232]
248. Kita tidak boleh melupakan bom-bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Sekali lagi, “di sini saya mengenang semua korban dan saya menyatakan hormat saya atas kekuatan dan martabat mereka yang, setelah selamat dari saat-saat pertama itu, selama bertahun-tahun telah menanggung penderitaan yang sangat berat dalam tubuh mereka dan, dalam pikiran mereka, membawa benih kematian yang terus menggerogoti energi kehidupan mereka. […] Kita tidak bisa membiarkan generasi sekarang dan generasi baru kehilangan ingatan akan apa yang terjadi, ingatan yang memberi jaminan dan dorongan untuk membangun masa depan yang lebih adil dan bersaudara.”[233] Kita juga tidak boleh melupakan penganiayaan, perdagangan budak, dan pembantaian etnis yang telah terjadi dan sedang terjadi di berbagai negara, dan banyak fakta sejarah lainnya yang membuat kita malu sebagai manusia. Semua itu harus selalu diingat, dan dikenang kembali, tanpa kenal lelah dan tanpa menjadikan kita mati rasa.
249. Saat ini kita mudah jatuh ke dalam godaan untuk membalik halaman dengan mengatakan bahwa hal itu sudah lama berlalu dan bahwa kita harus melihat ke depan. Tidak, demi kasih Allah! Tanpa ingatan kita tidak akan pernah bergerak maju, kita tidak pernah berkembang tanpa ingatan yang utuh dan jernih. Kita perlu menjaga “nyala api hati nurani kolektif, dengan memberi kesaksian kepada generasi berikutnya tentang kengerian dari apa yang telah terjadi.” Dengan cara ini, “kenangan akan para korban dibangkitkan dan dilestarikan, sehingga hati nurani manusia terus menjadi lebih kuat dalam menghadapi setiap keinginan untuk menguasai dan menghancurkan.”[234] Para korban itu sendiri –perorangan, kelompok masyarakat, atau bangsa– membutuhkannya agar tidak menyerah pada logika yang cenderung membenarkan pembalasan dan segala kekerasan atas nama penderitaan berat yang telah dialami. Oleh karena itu, saya tidak hanya mengacu pada ingatan akan kengerian, tetapi juga pada kenangan pada mereka yang, di tengah konteks yang diracuni dan rusak, dapat memulihkan martabat mereka dan dengan gerakan-gerakan tindakan-tindakan kecil atau besar telah memilih solidaritas, pengampunan, persaudaraan. Sangatlah baik untuk mengingat yang baik.
Mengampuni tanpa melupakan
250. Pengampunan tidak berarti melupakan. Lebih baik kita mengatakan, bila ada sesuatu yang sama sekali tidak dapat disangkal, dinisbikan, atau disembunyikan, namunkita dapat mengampuni. Bila ada sesuatu yang tidak pernah boleh ditoleransi, dibenarkan, atau dimaafkan, namun kita dapat mengampuni. Ketika ada sesuatu yang dengan alasan apa pun tidak boleh kita lupakan, namun kita dapat mengampuni. Pengampunan yang bebas dan tulus merupakan sesuatu yang luhur, yang mencerminkan agungnya pengampunan ilahi. Jika pengampunan itu diberikan dengan sukarela, bahkan mereka yang menolak untuk bertobat dan tidak mampu meminta pengampunan dapat diampuni.
251. Mereka yang benar-benar mengampuni tidak melupakan, tetapi mereka menolak dikendalikan oleh kekuatan destruktif yang sama yang telah menyakiti mereka. Mereka memutus lingkaran setan, menghentikan kemajuan daya kekuatan penghancur. Mereka memutuskan untuk tidak terus mencekoki masyarakat dengan semangat balas dendam, yang cepat atau lambat akhirnya sekali lagi akan jatuh kembali pada diri mereka sendiri. Sebenarnya, balas dendam tidak pernah benar-benar memuaskan ketidakpuasan para korban. Ada kejahatan yang begitu mengerikan dan kejam sehingga menimpakan penderitaan pada pelakunya tidak dapat memberikan perasaan bahwa kejahatan itu telah diperbaiki; juga tidak akan cukup untuk membunuh penjahat, juga tidak akan dapat ditemukan penyiksaan yang sebanding dengan apa yang mungkin telah diderita korban. Balas dendam tidak menyelesaikan apa pun.
252. Kita juga tidak berbicara tentang impunitas. Namun, keadilan diupayakan secara memadai semata-mata demi cinta akan keadilan itu sendiri, untuk menghormati para korban, untuk mencegah kejahatan baru, dan untuk melindungi kebaikan bersama, bukan sebagai apa yang disebut pelampiasan amarahnya sendiri. Pengampunan justru memungkinkan untuk mengupayakan keadilan tanpa jatuh ke dalam lingkaran setan balas dendam atau dalam ketidakadilan karena melupakan.
253. Ketika ada ketidakadilan dari dua belah pihak, harus diakui dengan jelas bahwa ketidakadilan itu mungkin tidak sama beratnya atau tidak dapat dibandingkan. Kekerasan yang dilakukan oleh struktur dan kekuasaan negara tidak sepadan dengan kekerasan oleh kelompok-kelompok tertentu. Bagaimanapun, tidak boleh ada anggapan bahwa hanya penderitaan tak adil dari satu pihak saja yang harus diingat. Seperti yang telah diajarkan oleh para Uskup Kroasia, “kita berutang rasa hormat yang sama kepada setiap korban yang tidak bersalah. Tidak boleh ada pembedaan berdasarkan ras, agama, negara, atau haluan politik.”[235]
254. Saya memohon kepada Allah “untuk mempersiapkan hati kita bagi perjumpaan dengan saudara-saudara melampaui segala perbedaan pandangan, bahasa, budaya, agama; untuk mengurapi seluruh keberadaan kita dengan minyak belas kasihan-Nya yang menyembuhkan luka-luka akibat kesalahan, kesalahpahaman, perselisihan; dan memohon rahmat untuk mengutus kita dengan kerendahan hati dan kelembutan di jalan yang menuntut tetapi berbuah dalam mengupayakan perdamaian.”[236]
Perang dan hukuman mati
255. Ada dua jawaban ekstrem yang dapat muncul sebagai solusi dalam keadaan yang sangat dramatis, tanpa disadari bahwa keduanya adalah jawaban keliru, yang tidak menyelesaikan masalah yang seharusnya diatasi, dan yang pada akhirnya hanya menambah faktor-faktor baru yang merusak tatanan masyarakat nasional dan mondial. Itulah perang dan hukuman mati.
Ketidakadilan perang
256. “Tipu daya ada di dalam hati orang yang merencanakan kejahatan, tetapi orang yang menasihatkan perdamaian mendapat sukacita” (Ams. 12:20). Namun, ada orang-orang yang mencari solusi dalam perang, yang sering “disuburkan oleh memburuknya hubungan, ambisi untuk hegemoni, penyalahgunaan kekuasaan, ketakutan terhadap yang lain, dan terhadap keragaman yang dipandang sebagai penghalang.”[237] Perang bukanlah hantu masa lalu, tetapi menjadi ancaman terus-menerus. Dunia menemukan semakin banyak kesulitan di jalan lambat perdamaian yang telah diupayakan dan sudah mulai membuahkan hasil.
257. Karena kondisi-kondisi untuk proliferasi perang kini sedang diciptakan kembali, saya mengingatkan bahwa “perang merupakan pengingkaran terhadap segala hak dan serangan dramatis terhadap lingkungan. Jika kita menginginkan pengembangan manusia seutuhnya yang autentik bagi semua, kita harus tanpa lelah terus berkomitmen untuk menghindari perang antar negara dan antar bangsa. Untuk tujuan itu, kita harus memastikan supremasi hukum yang tak terbantahkan dan jalan negosiasi, mediasi, dan arbitrase yang tak kenal lelah, seperti yang diusulkan oleh Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebuah norma hukum fundamental yang benar.”[238] Saya ingin menekankan bahwa 75 tahun Perserikatan Bangsa-Bangsa dan pengalaman selama 20 tahun pertama milenium ini menunjukkan bahwa penerapan norma-norma internasional secara penuh benar-benar efektif, dan bahwa kegagalan untuk mematuhinya membahayakan. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, bila dihormati dan diterapkan dengan transparansi dan ketulusan, adalah acuan wajib untuk keadilan dan wahana perdamaian. Namun, hal ini menuntut untuk tidak menutupi niat-niat yang tidak sah dan tidak menempatkan kepentingan khusus dari suatu negara atau suatu kelompok di atas kepentingan umum global. Jika hukum dianggap sebagai instrumen yang digunakan bila menguntungkan dan dihindari bila tidak menguntungkan, timbul kekuatan-kekuatan tak terkendali yang sangat merugikan masyarakat, mereka yang paling lemah, persaudaraan, lingkungan hidup dan warisan budaya, dengan membawa kerugian tak terpulihkan bagi komunitas global.
258. Orang dengan gampang memilih perang; caranya adalah membuat segala macam alasan yang tampaknya bersifat kemanusiaan, pembelaan diri, atau pencegahan, bahkan dengan menggunakan manipulasi informasi. Nyatanya, dalam beberapa dekade terakhir, semua perang mengklaim dapat “dibenarkan.” Katekismus Gereja Katolik berbicara tentang kemungkinan pembelaan yang sah melalui kekuatan militer, dengan pengandaian bisa menunjukkan bahwa ada beberapa “persyaratan ketat” yang diperlukan untuk “legitimasi moral.”[239] Akan tetapi, orang dengan mudah jatuh ke dalam penafsiran yang terlalu luas tentang kemungkinan hak ini. Dengan demikian, mereka juga ingin membenarkan serangan-serangan “pencegahan” atau tindakan-tindakan perang yang hampir tidak dapat terhindar dari “kerugian dan kekacauan yang lebih buruk daripada kejahatan yang harus dilenyapkan.”[240] Masalahnya adalah bahwa sejak pengembangan senjata nuklir, kimia, dan biologi, serta kemungkinan-kemungkinan dahsyat lainnya yang terus berkembang yang ditawarkan oleh teknologi baru, perang telah mendapat kekuatan destruktif tak terkendali yang berdampak pada banyak warga sipil yang tak bersalah. Sebenarnya, “belum pernah umat manusia memiliki kekuasaan yang begitu besar atas dirinya sendiri; dan tidak ada jaminan bahwa itu akan selalu digunakan dengan baik.”[241] Jadi, kita tidak bisa lagi memikirkan perang sebagai solusi, mengingat bahwa risikonya barangkali akan selalu lebih besar daripada manfaat hipotetis yang dikaitkan dengannya. Berhadapan dengan kenyataan ini, sekarang sangat sulit untuk mendukung kriteria rasional yang dikembangkan di abad-abad lain untuk berbicara tentang kemungkinan “perang yang adil.” Jangan pernah lagi berperang![242]
259. Penting ditambahkan bahwa, dengan perkembangan globalisasi, apa yang tampak sebagai solusi segera atau praktis untuk wilayah tertentu, menimbulkan serangkaian faktor kekerasan –sering kali terselubung– yang akhirnya berdampak untuk seluruh planet dan membuka jalan bagi peperangan yang baru dan lebih buruk di masa depan. Di dunia kita saat ini tidak hanya ada “perang-perang sepotong” di satu dan lain negara, tetapi kita sedang mengalami “perang dunia sepotong demi sepotong,” karena nasib negara-negara sangat terkait satu sama lain di panggung dunia.
260. Seperti yang dikatakan Santo Yohanes XXIII, “sudah tidak masuk akal lagi untuk mempertahankan bahwa perang atom merupakan upaya yang cocok untuk memulihkan pelanggaran keadilan.”[243] Ia menegaskan hal ini di saat ketegangan internasional yang kuat, dan dengan demikian menyuarakan kerinduan besar akan perdamaian yang menyebar pada masa Perang Dingin. Ia memperkuat keyakinan bahwa alasan-alasan untuk perdamaian lebih kuat daripada perhitungan kepentingan tertentu dan kepercayaan pada penggunaan senjata. Namun, peluang yang ditawarkan pada akhir Perang Dingin tidak sepenuhnya dimanfaatkan, karena kurangnya visi masa depan dan kesadaran bersama tentang nasib kita bersama. Sebaliknya, orang menyerah pada pencarian kepentingannya sendiri tanpa bertanggung jawab terhadap kesejahteraan umum universal. Dengan demikian, hantu perang yang menipu telah muncul kembali.
261. Setiap perang membuat dunia menjadi lebih buruk daripada keadaan sebelumnya. Perang adalah kegagalan politik dan kemanusiaan, penyerahan yang memalukan, kekalahan terhadap kekuatan jahat. Mari kita tidak terus terjerumus dalam diskusi teoretis, mari kita bersentuhan dengan luka-luka, menyentuh daging para korban. Mari kita lihat banyaknya warga sipil yang dibantai yang dianggap sebagai “kerusakan sampingan.” Mari kita bertanya kepada para korban sendiri. Mari kita memperhatikan para pengungsi, mereka yang menderita radiasi atom atau serangan kimiawi, para perempuan yang kehilangan anak-anak mereka, anak-anak yang kehilangan anggota tubuhnya atau dirampas masa kanak-kanak mereka. Mari kita mencermati kebenaran yang diungkapkan para korban kekerasan ini, melihat kenyataan dengan mata mereka, dan mendengarkan kisah mereka dengan hati terbuka. Dengan demikian, kita akan dapat memahami jurang kejahatan yang ada di jantung peperangan; dan fakta bahwa kita dianggap naif karena telah memilih perdamaian, tidak akan mengganggu kita.
262. Juga pelbagai aturan tidak akan cukup, jika kita berpikir bahwa penyelesaian masalah-masalah saat ini terletak pada menghalangi pihak lain dengan menakut-nakutinya, dengan mengancam mereka dengan penggunaan senjata nuklir, kimia atau biologi. Memang, “jika kita mempertimbangkan ancaman-ancaman utama terhadap perdamaian dan keamanan dengan berbagai dimensinya di dunia multipolar abad ke-21 ini, seperti, misalnya, terorisme, konflik-konflik asimetris, keamanan siber, berbagai masalah lingkungan hidup, dan kemiskinan, muncullah banyak keraguan berkaitan dengan ketidakcukupan pencegahan nuklir sebagai jawaban efektif terhadap aneka tantangan tersebut. Kekhawatiran ini menjadi semakin besar ketika kita mempertimbangkan akibat-akibat katastrofal bagi umat manusia dan lingkungan hidup yang akan timbul dari penggunaan senjata nuklir apa pun dengan efeknya yang menghancurkan tanpa pandang bulu, dan tak terkendali dalam ruang dan waktu. […] Kita juga harus bertanya pada diri sendiri sejauh mana suatu stabilitas yang didasarkan pada rasa takut bisa bertahan, bilamana itu sebenarnya meningkatkan rasa takut dan menggerogoti hubungan kepercayaan antarbangsa. Perdamaian dan stabilitas internasional tidak dapat didasarkan pada rasa aman yang palsu, pada ancaman penghancuran timbal balik atau pemusnahan total, atau sekadar untuk mempertahankan keseimbangan kekuatan saja. […] Dalam konteks ini, tujuan akhir penghapusan total senjata nuklir menjadi tantangan sekaligus keharusan moral dan kemanusiaan. […] Meningkatnya saling ketergantungan dan globalisasi berarti bahwa setiap tanggapan terhadap ancaman senjata nuklir harus kolektif dan terpadu, berdasarkan rasa saling percaya. Kepercayaan timbal balik hanya dapat dibangun melalui dialog yang benar-benar ditujukan pada kebaikan bersama dan bukan pada perlindungan kepentingannya sendiri yang terselubung.”[244] Dan dengan uang yang selama ini digunakan untuk persenjataan dan pengeluaran militer lainnya, hendaknya kita membentuk Dana Dunia [245] yang pada akhirnya dapat memberantas kelaparan dan mengembangkan negara-negara termiskin, sehingga para penduduknya tidak menggunakan solusi dengan kekerasan atau ilusi, dan tidak terpaksa meninggalkan negaranya untuk mengupayakan kehidupan yang lebih bermartabat.
Hukuman mati
263. Ada cara lain untuk menghilangkan orang lain, yang tidak ditujukan untuk negara-negara, tetapi untuk pribadi-pribadi. Itu adalah hukuman mati. Santo Yohanes Paulus II menyatakan dengan jelas dan tegas bahwa hukuman mati tidak sesuai pada tingkat moral dan tidak lagi diperlukan pada tingkat hukum pidana.[246] Tak mungkin berpikir untuk mundur dari posisi ini. Hari ini kita dengan jelas menegaskan bahwa “hukuman mati tidak dapat diterima”[247] dan Gereja berkomitmen teguh untuk menyerukan penghapusannya di seluruh dunia.[248]
264. Dalam Perjanjian Baru, sementara orang diminta untuk tidak melakukan pembalasan sendiri (lih. Rom 12:17.19), diakui perlunya pihak berwenang untuk menjatuhkan hukuman kepada para pelaku kejahatan (lih. Rm. 13:4; 1Ptr. 2:14). Sesungguhnya, “kehidupan bersama yang terstruktur dalam bentuk komunitas yang terorganisasi, membutuhkan aturan hukum untuk hidup berdampingan; dan pelanggaran yang sengaja menuntut tanggapan yang sesuai.”[249] Ini berarti bahwa “otoritas publik yang sah berhak dan berkewajiban menjatuhkan hukuman sesuai dengan beratnya kejahatan”[250] dan bahwa kekuasaan yudisial dijamin memiliki “independensi yang diperlukan di bidang hukum.”[251]
265. Sejak abad-abad awal Gereja, ada beberapa orang yang dengan jelas menentang hukuman mati. Misalnya, Laktansius berpendapat bahwa “tidak boleh ada pembedaan: membunuh seseorang selalu merupakan kejahatan.”[252] Paus Nikolas I menasihati: “Berusahalah untuk membebaskan tidak hanya setiap orang yang tak bersalah, tetapi juga semua orang yang bersalah dari hukuman mati.”[253] Pada kesempatan persidangan terhadap beberapa pembunuh yang telah menewaskan dua imam, Santo Agustinus meminta hakim untuk tidak mengambil nyawa para pembunuh, dan ia membenarkannya dengan cara ini: “Bukan kami ingin menghalangi bahwa orang-orang jahat diambil kebebasannya untuk melakukan kejahatan, melainkan kami ingin mereka dibiarkan hidup dan tidak dimutilasi di bagian tubuh mana pun. Untuk tujuan ini, cukuplah dengan penerapan hukum represif, mereka diubah dari agitasi mereka yang tidak sehat untuk dituntun kembali ke hidup yang sehat dan damai, atau dijauhkan dari tindakan-tindakan jahat mereka dengan diberi suatu pekerjaan yang bermanfaat. Itu juga merupakan penghukuman, tetapi siapa yang tidak akan mengerti bahwa itu lebih bermanfaat daripada siksaan, ketika tidak diberi ruang bagi keberanian untuk melakukan kejahatan, maupun tidak dihapuskanobat untuk pertobatan? […] Marahlah terhadap kejahatan, tetapi tanpa melupakan kemanusiaan; jangan melampiaskan hasrat balas dendam terhadap kekejaman orang-orang berdosa, sebaliknya inginkanlah untuk menyembuhkan luka-luka mereka.”[254]
266. Ketakutan dan dendam dengan mudah mengarah untuk memahami hukuman dengan cara mendendam, jika tidak kejam, alih-alih memahaminya sebagai bagian dari suatu proses penyembuhan dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Saat ini, “baik beberapa sektor politik dan beberapa media komunikasi, kadang-kadang menghasut kekerasan dan balas dendam, publik dan pribadi, tidak hanya terhadap mereka yang bertanggung jawab telah melakukan kejahatan, tetapi juga terhadap mereka yang dicurigai, berdasar atau tidak, telah melanggar hukum. […] Ada kecenderungan untuk sengaja membangun citra musuh: figur stereotip yang menyatukan dalam dirinya semua karakteristik yang oleh masyarakat dianggap atau ditafsirkan sebagai ancaman. Mekanisme-mekanisme yang membentuk gambaran-gambaran itu sama denganapa yang pada saatnya memungkinkan penyebaran gagasan-gagasan rasis.”[255] Hal ini sangat berisiko terhadap meningkatnya kebiasaan di beberapa negara untuk menerapkan penahanan preventif, pemenjaraan tanpa pengadilan, dan terutama hukuman mati.
267. Saya ingin menekankan bahwa “mustahil membayangkan bahwa negara-negara saat ini tidak memiliki cara lain selain hukuman mati untuk melindungi kehidupan orang lain dari penyerang yang tidak adil.” Yang sangat mengkhawatirkan adalah apa yang disebut eksekusi di luar pengadilan atau di luar hukum, yang “merupakan pembunuhan yang disengaja yang dilakukan oleh beberapa Negara dan agen-agen mereka, dan yang sering kali dianggap sebagai bentrok dengan para penjahat atau ditampilkan sebagai konsekuensi yang tidak diinginkan dari penggunaan kekerasan yang wajar, perlu, dan proporsional untuk menegakkan hukum.” [256]
268. “Argumen-argumen yang menentang hukuman mati, ada banyak dan sudah dikenal. Gereja dengan tepat telah menggarisbawahi beberapa di antaranya, seperti kemungkinan adanya kekeliruan peradilan, dan penggunaan hukuman mati oleh rezim totaliter dan diktator, yang menggunakannya sebagai sarana untuk menekan pembangkangan politik atau sebagai sarana penganiayaan terhadap minoritas agama dan budaya, semua korban yang menurut hukum negara mereka masing-masing dianggap sebagai “penjahat.” Oleh karena itu, semua orang Kristen dan orang yang berkehendak baik saat ini dipanggil untuk berjuang tidak hanya untuk penghapusan hukuman mati dalam segala bentuknya, baik yang legal maupun yang ilegal, tetapi juga untuk memperbaiki kondisi penjara-penjara, demi menghormati martabat manusiawi dari orang-orang yang dirampas kebebasannya. Dan ini saya hubungkan dengan hukuman penjara seumur hidup. […] Hukuman penjara seumur hidup adalah hukuman mati tersembunyi.”[257]
269. Mari kita ingat bahwa “bahkan seorang pembunuh pun tidak kehilangan martabat pribadinya dan Allah sendiri berjanji untuk menjamin itu.”[258] Penolakan tegas terhadap hukuman mati menunjukkan sejauh mana dimungkinkan mengakui bahwa martabat setiap manusia tak terganggu gugat, dan mengakui bahwa penjahat pun memiliki tempatnya di dunia ini. Jika saya tidak mengingkari martabat dari penjahat terburuk sekalipun, saya juga tidak akan mengingkarinya dari siapa pun. Saya akan memberikan semua orang kesempatan untuk berbagi planet ini dengan saya, terlepas dari apa yang mungkin memisahkan kita.
270. Saya mengajak orang-orang Kristen yang ragu-ragu dan tergoda untuk menyerah pada segala bentuk kekerasan, untuk mengingat pernyataan ini dari kitab Yesaya: “mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak” (2:4). Bagi kita nubuat ini menjadi daging dalam Yesus Kristus, yang berhadapan dengan seorang murid yang terhasut melakukan kekerasan, dengan tegas berkata: “Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barangsiapa menggunakan pedang, akan binasa oleh pedang” (Mat. 26:52). Itulah gema dari peringatan kuno ini: “dari setiap manusia Aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia” (Kej. 9:5-6). Reaksi Yesus ini, yang keluar secara spontan dari hatinya, mengatasi jarak yang berabad-abad dan menjadi peringatan abadi sampai hari ini.
BAB DELAPAN
AGAMA-AGAMA HENDAKNYA MELAYANI PERSAUDARAAN DI DUNIA
271. Pelbagai agama, berdasarkan rasa hormat kepada setiap pribadi manusia sebagai makhluk yang dipanggil untuk menjadi anak Allah, memberikan sumbangan berharga untuk membangun persaudaraan dan membela keadilan dalam masyarakat. Dialog antar pemeluk agama yang berbeda tidak dilakukan semata-mata atas dasar diplomasi, kesopansantunan, atau toleransi. Seperti yang diajarkan oleh para Uskup India, “tujuan dialog adalah membangun persahabatan, perdamaian, harmoni dan berbagi aneka nilai serta pengalaman moral dan spiritual dalam semangat kebenaran dan kasih.”[259]
Landasan yang terdalam
272. Sebagai orang beriman kita meyakini bahwa, tanpa keterbukaan kepada Bapa dari semua, tidak akan ada alasan yang kuat dan mantap untuk panggilan kepada persaudaraan. Kita yakin bahwa “hanya dengan kesadaran sebagai anak-anak yang bukan yatim piatu ini, kita bisa hidup dalam damai satu sama lain.”[260] Karena “akal budi sendiri mampu memahami kesetaraan antar manusia dan membangun kehidupan sipil bersama antar mereka, tetapi tidak berhasil membangun persaudaraan.”[261]
273. Dalam perspektif ini, saya ingin mengutip suatu teks yang patut diingat: “Bila tidak ada kebenaran yang mengatasi segalanya, dan bagi manusia menjadi norma untuk mewujudkan jati dirinya sepenuhnya, sama sekali juga tidak ada prinsip yang pasti untuk menjamin adilnya hubungan-hubungan antar-manusia. Sebab kepentingan khas suatu kelas, golongan atau negara mau tak mau akan menimbulkan pertentangan antara pelbagai pihak. Kalau tidak diakui adanya kebenaran yang melampaui segalanya, kekuatan kekuasaan menjadi unggul, dan setiap orang berusaha mengerahkan segala upaya yang ada padanya untuk memaksakan kepentingan dan pandangannya sendiri dengan mengesampingkan hak-hak sesamanya. […] Maka akar totalitarianisme modern terletak pada penolakan terhadap keluhuran martabat pribadi manusia, yang sebagai citra kelihatan Allah yang tidak kelihatan, menurut hakikatnya menjadi pengemban hak-hak, yang tidak boleh dilanggar oleh siapa pun, entah itu perorangan atau kelompok tertentu, kelas tertentu, bangsa atau negara sendiri. Bahkan mayoritas badan sosial mana pun tidak boleh melanggar hak-hak itu dengan menentang minoritas.”[262]
274. Dari pengalaman iman kita dan dari hikmat yang telah terhimpun selama berabad-abad, juga dengan belajar dari banyak kelemahan dan kegagalan kita, sebagai para penganut agama-agama yang berbeda kita tahu bahwa menghadirkan kesaksian tentang Allah itu baik untuk masyarakat kita. Mencari Allah dengan hati yang tulus, asalkan kita tidak mengaburkan-Nya dengan kepentingan ideologis atau praktis kita, membantu kita mengakui satu sama lain sebagai teman seperjalanan, saudara sejati. Kita percaya bahwa “ketika, atas nama sebuah ideologi, kita ingin mengusir Allah dari masyarakat, kita akhirnya menyembah berhala-berhala, dan segera manusia kehilangan dirinya, martabatnya diinjak-injak, hak-haknya dilanggar. Kalian tahu betul kekejaman apa yang dapat ditimbulkan karena dirampasnya kebebasan hati nurani dan kebebasan beragama, dan bagaimana luka ini menghasilkan kemanusiaan yang sungguh miskin, karena kehilangan harapan dan acuan cita-cita.”[263]
275. Harus diakui bahwa “di antara penyebab utama krisis dunia modern adalah ketidakpekaan hati nurani manusia, penjauhan dari nilai-nilai agama dan individualisme yang tersebar luas disertai dengan filsafat materialistis yang mendewakan manusia dan memperkenalkan nilai-nilai duniawi dan materiil sebagai pengganti prinsip-prinsip tertinggi dan transendental.”[264] Tidaklah dapat diterima bahwa dalam debat publik hanya orang-orang yang berkuasa dan para ilmuwan boleh memiliki suara. Harus ada ruang untuk refleksi yang berasal dari latar belakang religius yang mengumpulkan pengalaman dan hikmat selama berabad-abad. “Naskah-naskah keagamaan klasik dapat memberikan makna bagi segala zaman; memiliki kekuatan penggerak”, tetapi pada kenyataannya “naskah-naskah ini tidak dihargai karena kepicikan paham rasionalisme.”[265]
276. Oleh karena itu, meskipun menghormati otonomi politik, Gereja tidak membatasi misinya ke ranah privat. Sebaliknya, “ia tidak bisa dan bahkan tidak boleh tinggal terpinggir” dalam membangun dunia yang lebih baik, juga tidak berhenti “membangkitkan kekuatan spiritual” [266] yang dapat menyuburkan seluruh kehidupan masyarakat. Memang benar bahwa para pejabat agama tidak boleh terlibat dalam politik partai, yang adalah bidang khas kaum awam, tetapi mereka juga tidak dapat melepaskan dimensi politik keberadaan kita.[267] Ini meminta perhatian terus-menerus kepada kesejahteraan umum dan kepedulian terhadap pengembangan manusia seutuhnya. Gereja “mempunyai peran publik selain kegiatan-kegiatan amal kasih dan pendidikan”, dan bekerja untuk “kemajuan umat manusia dan persaudaraan universal.”[268] Gereja tidak berkeinginan untuk bersaing demi kekuasaan duniawi, melainkan untuk menawarkan dirinya sebagai “sebuah keluarga di antara banyak keluarga –ini adalah Gereja–, terbuka untuk memberi kesaksian […] kepada dunia sekarang ini tentang iman, harapan dan kasih bagi Tuhan dan bagi mereka yang dikasihi-Nya secara lebih. Gereja adalah sebuah rumah dengan pintu terbuka, karena dia adalah seorang ibu.”[269] Seperti Maria, Bunda Yesus, “kita ingin menjadi sebuah Gereja yang melayani, yang keluar dari rumahnya, bergerak keluar dari bait-bait sucinya, dari sakristinya, untuk mendampingi kehidupan, menopang harapan, menjadi tanda kesatuan […] untuk membangun jembatan-jembatan, merobohkan tembok-tembok, menabur benih-benih rekonsiliasi.”[270]
Identitas Kristiani
277. Gereja menghargai tindakan Allah dalam agama-agama lain, dan “tidak menolak apa pun, yang dalam agama-agama itu serba benar dan suci. Dengan sikap hormat yang tulus Gereja merenungkan cara-cara bertindak dan hidup, kaidah-kaidah serta ajaran-ajaran yang […] tidak jarang memantulkan sinar kebenaran yang menerangi semua orang.”[271] Namun, sebagai orang Kristen kita tidak dapat menyembunyikan bahwa “jika musik Injil berhenti bergetar di dalam batin kita, kita akan kehilangan kegembiraan yang mengalir dari bela rasa, kelembutan yang berasal dari kepercayaan, kemampuan untuk rekonsiliasi yang menemukan sumbernya dalam pengetahuan bahwa kita selalu diampuni serta diutus. Jika musik Injil tidak lagi didengar di rumah kita, di alun-alun kita, di tempat kerja, dalam politik dan dalam ekonomi, kita akan mematikan melodi yang menggugah kita untuk membela martabat setiap laki-laki dan perempuan.”[272] Yang lainnya minum dari sumber-sumber lain. Bagi kita, sumber martabat dan persaudaraan manusiawi ini ditemukan dalam Injil Yesus Kristus. Dari situ “muncul bagi pemikiran Kristiani dan bagi tindakan Gereja, keutamaan yang diberikan pada hubungan, pada perjumpaan dengan misteri suci orang lain, pada persekutuan universal dengan seluruh umat manusia sebagai panggilan untuk semua.”[273]
278. Gereja dipanggil untuk berinkarnasi dalam setiap situasi dan hadir selama berabad-abad di setiap tempat di bumi – ini berarti “katolik”. Mulai dari pengalamannya sendiri akan rahmat dan dosa, Gereja dapat memahami keindahan undangan kepada kasih universal. Sesungguhnya, “segala sesuatu yang manusiawi menjadi perhatian kita. […] Di mana pun dewan bangsa-bangsa berkumpul untuk menetapkan hak dan kewajiban manusia kita merasa terhormat, jika mereka mengizinkan kita duduk di antara mereka.”[274] Bagi banyak orang Kristiani, perjalanan persaudaraan ini juga memiliki seorang Ibu yang bernama Maria. Setelah menerima keibuan universal di kaki Salib (lih. Yoh. 19:26), perhatiannya tidak hanya diarahkan kepada Yesus, tetapi juga kepada “keturunannya yang lain” (Why. 12:17). Dengan dikuatkan oleh Tuhan Yang Bangkit, Maria ingin melahirkan dunia baru, di mana kita semua adalah saudara, di mana ada tempat untuk setiap orang yang terbuang dari masyarakat kita, di mana keadilan dan perdamaian bersinar.
279. Sebagai orang Kristiani kami meminta agar, di negara-negara di mana kami adalah minoritas, kebebasan kami dijamin, sama seperti kami mendukung kebebasan mereka yang bukan Kristen di mana mereka adalah minoritas. Ada hak asasi manusia yang tidak boleh dilupakan di jalan persaudaraan dan perdamaian, yaitu kebebasan beragama bagi pemeluk semua agama. Kebebasan ini menunjukkan bahwa kita dapat “membangun harmoni dan pemahaman antarbudaya dan agama yang berbeda. Itu juga memberi kesaksian bahwa hal-hal yang kita miliki bersama begitu banyak dan penting sehingga memungkinkan untuk menemukan jalan hidup berdampingan yang tenang, teratur dan damai, dengan menerima perbedaan-perbedaan dan bersukacita sebagai saudara karena menjadi anak-anak dari satu Allah.”[275]
280. Pada saat yang sama, mari kita memohon kepada Allah untuk memperkuat kesatuan di dalam Gereja, kesatuan yang diperkaya oleh keragaman yang didamaikan oleh karya Roh Kudus. Memang, “dalam satu Roh kita semua telah dibaptis menjadi satu tubuh” (1Kor. 12:13), di mana masing-masing memberikan sumbangan khusus. Seperti yang dikatakan Santo Agustinus, “telinga melihat melalui mata, dan mata mendengar melalui telinga.”[276] Penting juga untuk terus memberikan kesaksian tentang perjalanan perjumpaan antara berbagai denominasi Kristen. Kita tidak boleh melupakan keinginan yang diungkapkan oleh Yesus: “supaya mereka semua menjadi satu,” (Yoh. 17:21). Mendengarkan ajakan-Nya itu, dengan sedih kami mengakui bahwa dalam proses globalisasi masih kurang adanya sumbangan profetis dan spiritual dari kesatuan di antara semua umat Kristen. Meskipun demikian, “sementara kita masih dalam perjalanan menuju persekutuan penuh, kita sekarang sudah memiliki kewajiban untuk memberikan kesaksian bersama tentang kasih Allah kepada semua manusia, dengan bekerja sama dalam pelayanan kemanusiaan.”[277]
Agama dan kekerasan
281. Jalan perdamaian antar agama adalah mungkin. Titik awalnya haruslah cara pandang Allah, karena “Allah tidak melihat dengan mata-Nya, Allah melihat dengan hati-Nya. Dan kasih Allah adalah sama untuk setiap orang, apa pun agamanya. Dan jika orang itu ateis, kasih-Nya sama juga. Ketika hari terakhir tiba, dan akan ada cukup terang di bumi untuk dapat melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, kita akan mengalami beberapa kejutan!”[278]
282. Juga, “umat beriman perlu menemukan ruang untuk berdialog dan berkarya bersama demi kebaikan bersama dan penyejahteraan orang-orang miskin. Maksudnya bukan bahwa kita semua memperlemah atau menyembunyikan keyakinan-keyakinan kita sendiri, yang membuat kita paling bersemangat, agar bisa berjumpa dengan orang lain yang berpikir secara berbeda. […] Sebab semakin dalam, kuat dan kaya sebuah identitas, semakin ia memperkaya orang lain dengan sumbangan khasnya.”[279] Sebagai orang beriman kita merasa diri ditantang untuk kembali ke sumber-sumber kita dengan berfokus pada yang terpenting: menyembah Allah dan mengasihi sesama, agar jangan sampai beberapa aspek ajaran kita, keluar dari konteksnya, akhirnya menyulut pelbagai bentuk penghinaan, kebencian, xenofobia, dan penolakan terhadap orang lain. Kebenaran adalah bahwa kekerasan tidak memiliki dasar dalam keyakinan agama yang mendasar, tetapi hanya dalam distorsinya.
283. Beribadat kepada Allah, dengan tulus dan rendah hati, “menuntun kita bukan kepada diskriminasi, kebencian dan kekerasan, melainkan penghormatan pada kesucian hidup, penghormatan pada martabat dan kebebasan orang lain, dan pada komitmen penuh kasih bagi kesejahteraan semua.”[280] Sesungguhnya, “siapa yang tidak mengasihi, tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih” (1Yoh. 4:8). Oleh karena itu, “terorisme menyedihkan dan mengancam keamanan orang, baik mereka di Timur atau Barat, Utara atau Selatan, dan menyebarkan kepanikan, teror dan pesimisme, tetapi ini bukan karena agama, bahkan ketika para teroris memperalatnya. Ini lebih disebabkan oleh akumulasi penafsiran yang salah atas teks-teks agama dan oleh kebijakan yang terkait dengan kelaparan, kemiskinan, ketidakadilan, penindasan, dan kesombongan. Inilah sebabnya mengapa sangat penting menghentikan dukungan terhadap gerakan teroris dalam penyediaan dana, penyediaan senjata dan strategi, dan dengan upaya untuk membenarkan gerakan ini bahkan dengan menggunakan media. Semua ini harus dianggap sebagai kejahatan internasional yang mengancam keamanan dan perdamaian dunia. Terorisme semacam itu harus dikutuk dalam segala bentuk dan ekspresinya.”[281]Keyakinan religius tentang makna suci hidup manusia mengizinkan kita untuk “mengakui nilai-nilai mendasar kemanusiaan kita bersama. Atas nama nilai-nilai itu kita dapat dan harus bekerja sama, membangun dan berdialog, memaafkan dan bertumbuh, dengan mengizinkan suara-suara yang berbeda menciptakan lagu yang mulia dan harmonis, daripada teriakan kebencian yang fanatik.”[282]
284. Kekerasan fundamentalis di beberapa kelompok agama apa pun kadang-kadang dipicu oleh kecerobohan para pemimpinnya. Namun, “perintah perdamaian tertanam secara mendalam pada tradisi-tradisi agama yang kita wakili. […] Sebagai para pemimpin agama kita dipanggil untuk menjadi “rekan dialog” sejati, untuk bekerjasama dalam membangun perdamaian, bukan sebagai makelar, melainkan sebagai mediator yang autentik. Makelar berusaha memberikan ‘diskon’ kepada semua pihak untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Mediator, di sisi lain, adalah orang yang tidak menyimpan apa pun untuk dirinya sendiri, tetapi dengan murah hati memberikan dirinya sendiri, sampai habis, dengan mengetahui bahwa satu-satunya pendapatan adalah perdamaian. Masing-masing dari kita dipanggil untuk menjadi penenun perdamaian, dengan menyatukan bukan memecah belah, dengan memadamkan kebencian bukan memeliharanya, dengan membuka jalan-jalan dialog bukan membangun tembok baru!”[283]
Seruan
285. Dalam pertemuan persaudaraan saya dengan Imam Agung Ahmad Al-Tayyeb, suatu perjumpaan yang saya ingat dengan penuh sukacita, kami dengan tegas telah “menyatakan bahwa agama tidak boleh memprovokasi peperangan, sikap kebencian, permusuhan, dan ekstremisme, juga tidak boleh memancing kekerasan atau penumpahan darah. Realitas tragis ini merupakan akibat dari penyimpangan ajaran agama. Hal-hal tersebut adalah hasil dari manipulasi agama-agama untuk tujuan politik dan dari penafsiran yang dibuat oleh kelompok-kelompok agama yang, dalam perjalanan sejarah, telah mengambil keuntungan dari kekuatan sentimen keagamaan di hati para perempuan dan laki-laki […]. Allah, Yang Maha-kuasa, tidak perlu dibela oleh siapa pun dan tidak ingin nama-Nya digunakan untuk menteror orang-orang.”[284] Oleh karena itu saya di sini ingin mengulangi seruan untuk perdamaian, keadilan dan persaudaraan yang telah kita buat bersama: “Dalam nama Allah, yang telah menciptakan semua manusia yang setara dalam hak, kewajiban, dan martabat, dan yang telah memanggil mereka untuk hidup berdampingan sebagai saudara dan saudari, untuk memenuhi bumi dan untuk menyebarkan nilai-nilai kebaikan, cinta, dan kedamaian.
Atas nama hidup manusia yang tidak bersalah, yang telah dilarang Allah untuk dibunuh, dengan menegaskan bahwa siapa pun yang membunuh seseorang, orang itu bagaikan seseorang yang membunuh seluruh umat manusia, dan siapa pun yang menyelamatkan seseorang, orang itu bagaikan seseorang yang menyelamatkan seluruh umat manusia.
Atas nama orang miskin, orang melarat, orang yang terpinggirkan, dan mereka yang paling membutuhkan, yang bagi mereka Allah telah memerintahkan kita untuk membantu sebagai tugas yang dituntut dari semua orang, terutama orang kaya dan berkecukupan.
Atas nama anak yatim, para janda, para pengungsi dan mereka yang diasingkan dari rumah dan tanah mereka; atas nama para korban perang, penganiayaan dan ketidakadilan; atas nama mereka yang lemah, mereka yang hidup dalam ketakutan, para tawanan perang, dan mereka yang disiksa di bagian dunia mana pun, tanpa perbedaan.
Atas nama orang-orang yang telah kehilangan keamanan, kedamaian, dan kemungkinan untuk hidup berdampingan, karena menjadi korban kehancuran, malapetaka, dan perang.
Atas nama persaudaraan manusia yang merangkul semua manusia, menyatukan mereka dan menjadikan mereka setara.
Atas nama persaudaraan ini yang terkoyak oleh kebijakan-kebijakan ekstremisme dan perpecahan, oleh sistem keuntungan tak terkendali atau oleh kecenderungan ideologis penuh kebencian yang memanipulasi tindakan dan masa depan perempuan dan laki-laki;
Atas nama kebebasan, yang telah dianugerahkan Allah kepada semua manusia dengan menciptakan mereka secara bebas dan menjadikan mereka berbeda berkat rahmat ini.
Atas nama keadilan dan belas kasihan, fondasi kemakmuran dan landasan iman.
Atas nama semua orang yang berkehendak baik yang ada di setiap bagian dunia;
Dalam nama Allah dan semua ini […] kami menyatakan menerima budaya dialog sebagai jalan; kerja sama timbal balik sebagai kode etik; saling pengertian sebagai metode dan kriteria.”[285]
***
286. Dalam kerangka refleksi tentang persaudaraan universal ini, saya merasa diilhami secara khusus oleh Santo Fransiskus dari Asisi, dan juga oleh saudara-saudara lain yang bukan Katolik: Martin Luther King, Desmond Tutu, Mahatma Gandhi dan banyak lainnya. Namun, saya ingin mengakhirinya dengan mengingat seorang lain dengan imannya yang mendalam, yang, berawal dari pengalamannya yang intens akan Allah, telah melakukan perjalanan transformasi hingga merasa dirinya sebagai saudara bagi semua. Yang saya maksudkan adalah Beato Charles de Foucauld.
287. Cita-cita pengabdiannyayang total kepada Allah diarahkannya kepada identifikasi dirinya dengan mereka yang paling kecil, yang ditinggalkan di kedalaman gurun Afrika. Dalam konteks itu ia mengungkapkan kerinduannya untuk merasakan setiap manusia sebagai seorang saudara,[286] dan meminta kepada seorang teman: “Berdoalah kepada Allah agar saya benar-benar menjadi saudara dari semua orang di negeri ini.”[287] Dia ingin pada akhirnya menjadi “saudara universal.”[288] Namun, hanya dengan mengidentifikasi dirinya dengan yang paling kecil, ia berhasil menjadi saudara dari semua. Semoga Allah mengilhami kita masing-masing dengan cita-cita ini. Amin.
Doa kepada Sang Pencipta
Tuhan dan Bapa segenap umat manusia,
Engkau yang telah menciptakan semua manusia dengan martabat yang sama,
curahkanlah ke dalam hati kami semangat persaudaraan.
Ilhamilah kami dengan impian perjumpaan baru, dialog, keadilan serta perdamaian.
Doronglah kami untuk menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan dunia yang lebih layak, tanpa kelaparan, tanpa kemiskinan, tanpa kekerasan, tanpa perang.
Semoga hati kami terbuka bagi semua bangsa dan negara di bumi,
agar kami mengenali kebaikan dan keindahan
yang telah Kautaburkan pada mereka masing-masing,
untuk mempererat ikatan kesatuan, kerja sama, dan harapan bersama.
Amin.
Doa Kristiani Ekumenis
Allah kami, Tritunggal Mahakasih,
dari persekutuan teguh keintiman ilahi-Mu
curahkanlah ke tengah-tengah kami pancaran kasih persaudaraan.
Berilah kami kasih yang memancar dalam tindakan Yesus,
dalam keluarga-Nya di Nazaret, dan dalam jemaat Kristen awal.
Anugerahilah kami, umat Kristen, agar mampu menghidupi Injil
dan mengenali Kristus dalam setiap manusia;
agar dapat melihat Dia disalibkan dalam kesusahan mereka yang ditinggalkan dan dilupakan di dunia ini,
dan melihat Dia bangkit dalam setiap saudari dan saudara yang menjadi giat kembali.
Datanglah Roh Kudus,
perlihatkanlah kepada kami keindahan-Mu yang tercermin dalam segala bangsa di bumi, agar kami menemukan kembali bahwa mereka semua penting,
bahwa mereka semua diperlukan,
bahwa mereka adalah aneka wajah dari umat manusia yang satu yang dikasihi Allah. Amin.
Diberikan di Asisi, di makam Santo Fransiskus, pada 3 Oktober, pada malam Pesta “Sang Poverello”, di tahun 2020, tahun kedelapan masa kepausan saya.
Fransiskus
[1] Petuah, 6, 1: Karya-karya Fransiskus dari Asisi, Terj. Leo Laba Ladjar OFM, Kanisius, 2001, hlm. 208.
[2] Petuah, 25, 1: op. cit.,219.
[3] Fransiskus dari Asisi, Anggaran Dasar Tanpa Bulla (Regula non Bullata), 16, 3. 6: op. cit., 130
[4] Éloi Leclerc OFM, Exil et tendresse, Marova, Paris 1962, hlm. 205.
[5] Dokumen tentang Persaudaraan Manusia untuk Perdamaian Dunia dan Hidup Berdampingan, Abu Dhabi (4 Februari 2019) , L’Osservatore Romano, 4-5 Februari 2019, hlm. 6.
[6] Amanat pada Pertemuan Ekumenis dan Antaragama Bersama Orang-orang Muda, Skopje, Makedonia Utara (7 Mei 2019): L’Osservatore Romano, 9 Mei 2019, hlm. 9.
[7] Amanat kepada Parlemen Eropa, Strasbourg (25 November 2014): AAS 106 (2014), 996.
[8] Pertemuan dengan Otoritas, Masyarakat Sipil, dan Korps Diplomatik, Santiago, Chile (16 Januari 2018): AAS 110 (2018), 256.
[9] Benediktus XVI, Ensiklik Caritas In Veritate (29 Juni 2009), 19, AAS 101 (2009), 655.
[10] Seruan Apostolik Pascasinode Christus Vivit (25 Maret 2019), 181.
[11] Kardinal Raúl Silva Henríquez, Homili tentang Te Deum, Santiago de Chile (18 September 1974).
[12] Ensiklik Laudato Si’ (24 Mei 2015), 57: AAS 107 (2015), 869
[13] Amanat kepada Korps Diplomatik yang diakreditasi untuk Takhta Suci (11 Januari 2016): AAS 108 (2016), 120.
[14] Amanat kepada Korps Diplomatik yang diakreditasi untuk Takhta Suci (13 Januari 2014): AAS 106 (2014), 83-84.
[15] Bdk. Pidato kepada Yayasan “Centesimus Annus pro Pontifice” (25 Mei 2013): Insegnamenti I, 1 (2013), 238.
[16] Bdk. Santo Paulus VI, Ensiklik Populorum Progressio (26 Maret 1967): AAS 59 (1967), 264.
[17] Benediktus XVI, Ensiklik Caritas In Veritate (29 Juni 2009), 22: AAS 101 (2009), 657.
[18] Amanat kepada Otoritas Sipil, Tirana, Albania (21 September 2014): AAS 106 (2014), 773.
[19] Pesan kepada para Peserta Konferensi Internasional “Hak-hak Asasi manusia dalam Dunia Masa Kini: Pencapaian, Penghilangan, Pengingkaran” (10 Desember 2018): L’Osservatore Romano, 10-11 Desember 2018, hlm. 8.
[20] Seruan Apostolik Evangelii Gaudium (24 November 2013), 212: AAS 105 (2013), 1108.
[21] Pesan untuk Hari Perdamaian Sedunia 2015 (8 Desember 2014), 3-4: AAS 107 (2015), 69-71.
[22] Ibid., 5: AAS 107 (2015), 72.
[23] Pesan untuk Hari Perdamaian Sedunia 2016 (8 Desember 2015), 2: AAS 108 (2016), 49.
[24] Pesan untuk Hari Perdamaian Sedunia 2018 (8 Desember 2019), 1: L’Osservatore Romano, 13 Desember 2019, hlm. 8.
[25] Amanat tentang Senjata Nuklir, Nagasaki, Jepang (24 November 2019): L’Osservatore Romano, 25-26 November 2019, hlm. 6.
[26] Dialog dengan Para Pelajar dan Guru dari San Carlo College di Milan (6 April 2019): L’Osservatore Romano, 8-9 April 2019, hlm. 6.
[27] Dokumen tentang Persaudaraan Manusia untuk Perdamaian Dunia dan Hidup Berdampingan, Abu Dhabi (4 Februari 2019), L’Osservatore Romano, 4-5 Februari 2019, hlm. 6.
[28] Amanat kepada Dunia Budaya, Cagliari, Italia (22 September 2013): L’Osservatore Romano, 23-24 September 2013, hlm. 7.
[29] Humana Communitas. Surat kepada Ketua Akademi Kepausan untuk Kehidupan pada Peringatan Ulang tahun ke-25 (6 Januari 2019), 2.6: L’Osservatore Romano, 16 Januari 2019, hlm. 6-7.
[30] Pesan Video pada Konferensi TED (Technology, Entertainment, and Design) di Vancouver(26 April 2017): L’Osservatore Romano, 27 April 2017, hlm. 7.
[31] Saat Doa Luar Biasa di Masa Pandemi (27 Maret 2020): L’Osservatore Romano, 29 Maret 2020, hlm. 10.
[32] Homili pada Misa Kudus di Skopje, Makedonia Utara (7 Mei 2019): L’Osservatore Romano, 8 Mei 2019, hlm. 12.
[33] Bdk. Aeneis, I, 462: “Sunt lacrimae rerum et mentem mortalia tangunt”.
[34] “Historia … magistra vitae” (Marcus Tullius Cicero, De oratore, II, 36).
[35] Ensiklik Laudato Si’ (24 Mei 2015), 204, AAS 107 (2015), 928.
[36] Seruan Apostolik Pasca Sinode Christus Vivit (25 Maret 2019), 91.
[37] Ibid., 92.
[38] Ibid., 93.
[39] Benediktus XVI, Pesan pada Hari Migran dan Pengungsi Sedunia 2013 (12 Oktober 2012): AAS 104 (2012), 908.
[40] Seruan Apostolik Pasca Sinode Christus Vivit (25 Maret 2019), 92.
[41] Pesan pada Hari Migran dan Pengungsi Sedunia 2020 (13 Mei 2020): L’Osservatore Romano, 16 Mei 2020, hlm. 8.
[42] Amanat pada Korps Diplomatik yang diakreditasi untuk Takhta Suci (11 Januari 2016): AAS 108 (2016), 124.
[43] Amanat pada Korps Diplomatik yang diakreditasi untuk Takhta Suci (13 Januari 2014): AAS 106 (2014), 84.
[44] Amanat pada Korps Diplomatik yang diakreditasi untuk Takhta Suci (11 Januari 2016): AAS 108 (2016), 123.
[45] Pesan pada Hari Migran dan Pengungsi Sedunia 2019 (27 Mei 2019): L’Osservatore Romano, 27-28 Mei 2019, hlm. 8.
[46] Seruan Apostolik Pasca Sinode Christus Vivit (25 Maret 2019), 88.
[47] Seruan Apostolik Pasca Sinode Christus Vivit (25 Maret 2019), 89.
[48] Seruan Apostolik Gaudete et Exsultate (19 Maret 2018), 115.
[49] Dari film Pope Francis: A Man of His Word, oleh Wim Wenders (2018).
[50] Amanat pada Otoritas, Masyarakat Sipil, dan Korps Diplomatik, Tallinn, Estonia (25 September 2018): L’Osservatore Romano, 27 September 2018, hlm. 7.
[51] Bdk. Saat Doa Luar Biasa di Masa Epidemi (27 Maret 2020): L’Osservatore Romano, 29 Maret 2020, hlm. 10; Pesan untuk Hari Orang Miskin Sedunia 2020 (13 Juni 2020), 6: L’Osservatore Romano, 14 Juni 2020, hlm. 8.
[52] Sapaan kepada Orang Muda di Pusat Kebudayaan Padre Félix Varela, Havana, Cuba (20 September 2015): L’Osservatore Romano, 21-22 September 2015, hlm. 6.
[53] Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral tentang Gereja dan di Dunia Dewasa Ini, Gaudium et Spes, 1.
[54] Irenaeus, Adversus Haereses, II, 25, 2: PG7/1, 798ff.
[55] Talmud Bavli (Babylonian Talmud), Shabbat, 31a.
[56] Amanat kepada Orang-orang yang dibantu oleh Karya Amal Kasih Gereja, Tallinn, Estonia (25 September 2018): L’Osservatore Romano, 27 September 2018, hlm. 8.
[57] Pesan Video kepada Konferensi TED di Vancouver (26 April 2017): L’Osservatore Romano, 27 April 2017, hlm. 7.
[58] Homiliae in Matthaeum, 50: 3-4: PG 58, 508.
[59] Amanat pada Pertemuan Gerakan-gerakan Populer, Modesto, California, Amerika Serikat (10 Februari 2017): AAS 109 (2017), 291.
[60] Seruan Apostolik Evangelii Gaudium, (24 November 2013), 235: AAS 105 (2013), 1115.
[61] Santo Yohanes Paulus II, Pesan kepada Orang-orang Disabilitas, Angelus di Osnabrück, Jerman (16 November 1980): Insegnamenti III, 2 (1980), 1232.
[62] Konsili Vatikan II, Konstitusi Pastoral tentang Gereja di Dunia Dewasa Ini, Gaudium et Spes, 24.
[63] Gabriel Marcel, Du refus à l’invocation, ed. NRF, Paris, 1940, 50.
[64] Angelus (10 November 2019): L’Osservatore Romano, 11-12 November 2019, 8.
[65] Bdk. Santo Thomas Aquinas: Scriptum super Sententiis, lib. 3, dist. 27, q. 1, a. 1, ad 4: “Dicitur amor extasim facere et fervere, quia quod fervet extra se bullit et exhalat”.
[66] Karol Wojtyła, Love and Responsibility, London, 1982, 126.
[67] Karl Rahner, Kleines Kirchenjahr. Ein Gang durch den Festkreis, Herderbücherei 901, Freiburg, 1981, 30.
[68] Regula, 53, 15: “Pauperum et peregrinorum maxime susceptioni cura sollicite exhibeatur”.
[69] Bdk. Summa Theologiae, II-II, q. 23, a. 7; Saint Augustine, Contra Julianum, 4, 18: PL 44, 748:“How many pleasures do misers forego, either to increase their treasures or for fear of seeing them diminish!”.
[70] “Secundum acceptionem divinam” (Scriptum super Sententiis, lib. 3, dist. 27, a. 1, q. 1, concl. 4).
[71] Benediktus XVI, Ensiklik Deus Caritas Est, 15: AAS 98 (2006), 230.
[72] Summa Theologiae II-II, q. 27, art. 2, resp.
[73] Ibid., I-II, q. 26, art. 3, resp.
[74] Ibid., q. 110, art. 1, resp.
[75] Pesan untuk Hari Perdamaian Sedunia 2014 (8 Desember 2013), 1: AAS 106 (2014), 22.
[76] Bdk. Angelus (29 Desember 2013): L’Osservatore Romano, 30-31 Desember 2013, hlm. 7; Amanat kepada Korps Diplomatik yang diakreditasi untuk Takhta Suci (12 Januari 2015):AAS 107 (2015), 165.
[77] Pesan untuk Hari Penyandang Disabilitas Sedunia 2019 (3 Desember 2019): L’Osservatore Romano, 4 Desember 2019, 7.
[78] Amanat pada Pertemuan untuk Kebebasan Beragama dengan Masyarakat Hispanik dan Kelompok-kelompok Imigran, Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat (26 September 2015): AAS 107 (2015), 1050-1051.
[79] Amanat kepada Orang Muda, Tokyo, Jepang (25 November 2019): L’Osservatore Romano, 25-26 November 2019, 10.
[80] Dalam pertimbangan ini, saya terinspirasi oleh pemikiran Paul Ricoeur, “Le socius et le prochain”, in Histoire et Verité, ed. Le Seuil, Paris, 1967, 113-127.
[81] Seruan Apostolik Evangelii Gaudium(24 November 2013), 190: AAS 105 (2013), 1100.
[82] Ibid., 209: AAS 105 (2013), 1107.
[83] Ensiklik Laudato Si` (24 Mei 2015), 129: AAS 107 (2015), 899.
[84] Pesan untuk Event “Ekonomi Fransiskus” (1 Mei 2019): L’Osservatore Romano, 12 Mei 2019, 8.
[85] Amanat kepada Parlemen Eropa, Strasbourg (25 November 2014): AAS 106 (2014), 997.
[86] Ensiklik Laudato Si`(24 Mei 2015), 229: AAS 107 (2015), 937.
[87] Pesan untuk Hari Perdamaian Sedunia 2016 (8 Desember 2015), 6: AAS 108 (2016), 57-58.
[88] Soliditas secara etimologis terkait dengan “solidaritas”. Solidaritas, dalam arti etis-politik yang didapati dalam dua abad terakhir, menghasilkan suatu kesepakatan sosial yang aman dan kokoh.
[89] Homili, Havana, Kuba (20 September 2015): L’Osservatore Romano, 21-22 September 2015, 8.
[90] Amanat kepada Peserta dalam Pertemuan Gerakan-gerakan Populer (28 Oktober 2014): AAS 106 (2014), 851-852.
[91] Bdk. Santo Basilius, Homilia XXI, Quod rebus mundanis adhaerendum non sit, 3.5: PG 31, 545-549; Regulae brevius tractatae, 92: PG 31, 1145-1148; St Petrus Chrysologus, Sermo 123: PL 52, 536-540; St Ambrosius, De Nabuthe, 27.52: PL 14, 738ff.; St Augustinus, In Iohannis Evangelium, 6, 25: PL 35, 1436ff.
[92] De Lazaro Concio, II, 6: PG 48, 992D.
[93] Regula Pastoralis, III, 21: PL 77, 87.
[94] Santo Yohanes Paulus II, Ensiklik Centesimus Annus(1 Mei 1991), 31: AAS 83 (1991), 831.
[95] Ensiklik Laudato Si` (24 Mei 2015), 93: AAS 107 (2015), 884.
[96] Santo Yohanes Paulus II, Ensiklik Laborem Exercens (14 September 1981), 19: AAS 73 (1981), 626.
[97] Bdk. Dewan Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian, Kompendium Ajaran Sosial Gereja, 172.
[98] Ensiklik Populorum Progressio (26 Maret 1967): AAS 59 (1967), 268.
[99] Santo Yohanes Paulus II, Ensiklik Sollicitudo Rei Socialis(30 Desember 1987), 33: AAS 80 (1988), 557.
[100] Ensiklik Laudato Si’(24 Mei 2015), 95: AAS 107 (2015), 885.
[101] Ibid., 129: AAS 107 (2015), 899.
[102] Bdk. Santo Paulus VI, Ensiklik Populorum Progressio (26 Maret 1967): AAS 59 (1967), 265; Benediktus XVI, Ensiklik Caritas in Veritate(29 Juni 2009), 16: AAS 101 (2009), 652.
[103] Bdk. Ensiklik Laudato Si’(24 Mei 2015), 93: AAS 107 (2015), 884-885;November 2013), 189-190: AAS 105 (2013), 1099-1100.
[104] Konferensi Para Uskup Amerika Serikat, Surat Pastoral Menentang Rasisme “Open Wide Our Hearts: The Enduring Call to Love” (November 2018).
[105] Ensiklik Laudato Si’(24 Mei 2015), 51: AAS 107 (2015), 867.
[106] Bdk. Benediktus XVI, Ensiklik Caritas in Veritate(29 Juni 2009), 6: AAS 101 (2009), 644.
[107] Santo Yohanes Paulus II, Ensiklik Centesimus Annus(1 Mei 1991), 35: AAS 83 (1991), 838.
[108] Amanat tentang Senjata Nuklir, Nagasaki, Jepang (24 November 2019): L’Osservatore Romano, 25-26 November 2019, 6.
[109] Bdk. Uskup-Uskup Amerika Serikat dan Meksiko, Sebuah Surat Pastoral terkait Migrasi: “Strangers No Longer Together on the Journey of Hope” (Januari 2003).
[110] Audiensi Umum (3 April 2019): L’Osservatore Romano, 4 April 2019, hlm. 8.
[111] Bdk. Pesan untuk Hari Migran dan Pengungsi Sedunia 2018 (14 Januari 2018): AAS 109 (2017), 918-923.
[112] Dokumen tentang Persaudaraan Manusia untuk Perdamaian Dunia dan Hidup Berdampingan, Abu Dhabi (4 Februari 2019), L’Osservatore Romano, 4-5 Februari 2019, hlm. 7.
[113] Amanat kepada Korps Diplomatik yang diakreditasi untuk Takhta Suci, 11 Januari 2016: AAS 108 (2016), 124.
[115] Seruan Apostolik Pasca Sinode Christus Vivit(25 Maret 2019), 93.
[117] Amanat pada Otoritas, Sarajevo, Bosnia dan Herzegovina (6 Juni 2015): L’Osservatore Romano, 7 Juni 2015, hlm. 7.
[118] Latinoamérica. Conversaciones con Hernán Reyes Alcaide, ed. Planeta, Buenos Aires, 2017, 105.
[119] Dokumen tentang Persaudaraan Manusia untuk Perdamaian Dunia dan Hidup Berdampingan, Abu Dhabi (4 Februari 2019), L’Osservatore Romano, 4-5 Februari 2019, hlm. 7.
[120] Benediktus XVI, Ensiklik Caritas in Veritate(29 Juni 2009), 67: AAS 101 (2009), 700.
[121] Ibid., 60, AAS 101 (2009), 695.
[122] Ibid., 67, AAS 101 (2009), 700.
[123] Dewan Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian, Kompendium Ajaran Sosial Gereja, 447.
[124] Seruan Apostolik Evangelii Gaudium(24 November 2013), 234: AAS 105 (2013), 1115.
[125] Ibid., 235: AAS 105 (2013), 1115.
[127] Santo Yohanes Paulus II, Amanat kepada Perwakilan Kebudayaan Argentina, Buenos Aires, Argentina (12 April 1987), 4: L’Osservatore Romano, 14 April 1987, hlm. 7.
[128] Bdk. ID., Amanat kepada Kuria Romana (21 Desember 1984), 4: AAS 76 (1984), 506.
[129] Seruan Apostolik Pascasinode Querida Amazonia(2 Februari 2020), 37.
[130] Georg Simmel, Brücke und Tür. Essays des Philosophen zur Geschichte, Religion, Kunst und Gesellschaft, ed. Michael Landmann, Köhler-Verlag, Stuttgart, 1957, 6.
[131] Bdk. Jaime Hoyos-Vásquez, S.J., “Lógica de las relaciones sociales. Reflexión onto-lógica”, Revista Universitas Philosophica, 15-16 (Desember 1990-Juni1991), Bogotá, 95-106.
[132] Antonio Spadaro, S.J., Le orme di un pastore. Una conversazione con Papa Francesco, in Jorge Mario Bergolio – Papa Francesco, Nei tuoi occhi è la mia parola. Omelie e discorsi di Buenos Aires 1999-2013, Rizzoli, Milan 2016, XVI; Bdk. Seruan Apostolik Evangelii Gaudium(24 November 2013), 220-221: AAS 105 (2013), 1110-1111.
[133] Seruan Apostolik Evangelii Gaudium (24 November 2013), 204: AAS 105 (2013), 1106.
[134] Bdk. ibid: AAS 105 (2013), 1105-1106.
[135] Ibid., 202: AAS 105 (2013), 1105.
[136] Ensiklik Laudato Si’ (24 Mei 2015), 128: AAS107 (2015), 898.
[137] Amanat pada Korps Diplomatik yang Diakreditasi untuk Takhta Suci (12 Januari 2015):AAS 107 (2015), 165; bdk. Amanat pada Peserta dalam Pertemuan Gerakan-gerakan Populer (28 Oktober 2014): AAS 106 (2014), 851-859.
[138] Hal serupa dapat dikatakan sehubungan dengan kategori Kerajaan Allah dalam Alkitab.
[139] Paul Ricoeur, Histoire et Verité, ed. Le Seuil Paris, 1967, 122.
[140] Ensiklik Laudato Si’ (24 Mei 2015), 129: AAS107 (2015), 899.
[141] Benediktus XVI, Ensiklik Caritas in Veritate (29 Juni 2009), 35: AAS101 (2009), 670.
[142] Amanat pada Peserta dalam Pertemuan Gerakan-gerakan Populer (28 Oktober 2014): AAS106 (2014), 858.
[144] Amanat pada Peserta dalam Pertemuan Gerakan-gerakan Populer (5 November 2016): L’Osservatore Romano, 7-8 November 2016, pp. 4-5.
[147] Ensiklik Laudato Si’ (24 Mei 2015), 189: AAS107 (2015), 922.
[148] Amanat kepada para Anggota Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York (25 September 2015): AAS 107 (2015), 1037.
[149] Ensiklik Laudato Si’ (24 Mei 2015), 175: AAS107 (2015), 916-917.
[150] Bdk. Benediktus XVI, Ensiklik Caritas in Veritate (29 Juni 2009), 67: AAS 101 (2009), 700-701.
[151] Ibid.: AAS 101 (2009), 700.
[152] Dewan Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian, Kompendium Ajaran Sosial Gereja, 434.
[153] Amanat kepada para Anggota Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York (25 September 2015): AAS 107 (2015), 1037, 1041.
[154] Dewan Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian, Kompendium Ajaran Sosial Gereja, 437.
[155] Santo Yohanes Paulus II, Pesan pada Hari Perdamaian Sedunia 2004, 5: AAS 96 (2004), 117.
[156] Dewan Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian, Kompendium Ajaran Sosial Gereja, 439.
[157] Bdk. Komisi Sosial Para Uskup Prancis, Declaration Réhabiliter la Politique (17 Februari 1999).
[158] Ensiklik Laudato Si’ (24 Mei 2015), 189: AAS 107 (2015), 922.
[159] Ibid., 196: AAS 107 (2015), 925.
[160] Ibid., 197: AAS 107 (2015), 925.
[161] Ibid., 181: AAS 107 (2015), 919.
[162] Ibid., 178: AAS 107 (2015), 918.
[163] Konferensi Uskup-Uskup Portugal, Surat Pastoral Tanggung Jawab Solider untuk Kebaikan Bersama (15 September 2003), 20; bdk. Laudato Si’(24 Mei 2015), 159: AAS 107 (2015), 911.
[164] Ensiklik Laudato Si’ (24 Mei 2015), 191: AAS 107 (2015), 923.
[165] Pius XI, Kata Sambutan kepada Federasi Mahasiswa Universitas Katolik Italia (18 Desember 1927): L’Osservatore Romano, 23 Desember 1927, hlm. 3.
[166] Bdk. ID., Ensiklik Quadragesimo Anno (15 Mei 1931): AAS 23 (1931), 206-207.
[167] Seruan Apostolik Evangelii Gaudium (24 November 2013), 205: AAS 105 (2013), 1106
[168] Benediktus XVI, Ensiklik Caritas in Veritate (29 Juni 2009), 2: AAS 101 (2009), 642.
[169] Ensiklik Laudato Si’ (24 Mei 2015), 231: AAS 107 (2015), 937.
[170] Benediktus XVI, Ensiklik Caritas in Veritate (29 Juni 2009), 2: AAS 101 (2009), 642.
[171] Dewan Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian, Kompendium Ajaran Sosial Gereja, 207.
[172] Santo Yohanes Paulus II, Ensiklik Redemptor Hominis (4 Maret 1979), 15: AAS 71 (1979), 288.
[173] Bdk. Santo Paulus VI, Ensiklik Populorum Progressio (26 Maret 1967), 44: AAS 59 (1967), 279.
[174] Dewan Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian, Kompendium Ajaran Sosial Gereja, 207.
[175] Benediktus XVI, Ensiklik Caritas in Veritate (29 Juni 2009), 2: AAS 101 (2009), 642.
[176] Ibid., 3 : AAS 101 (2009), 643.
[177] Ibid., 4 : AAS 101 (2009), 643.
[179] Ibid., 3 : AAS 101 (2009), 643.
[180] Ibid. : AAS 101 (2009), 642.
[181] Ajaran moral Katolik, menuruti ajaran Santo Thomas Aquinas, membedakan antara tindakan yang “ditimbulkan” dan yang “diperintahkan” bdk. Summa Theologiae, I-II, qq. 8-17; M. Zalba, S.J., Theologiae Moralis Summa. Theologia Moralis Fundamentalis. Tractatus de Virtutibus Theologicis, ed. BAC, Madrid, 1952, vol. I, 69; A. Royo Marín, Teología de la Perfección Cristiana, ed. BAC, Madrid, 1962, 192-196.
[182] Dewan Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian, Kompendium Ajaran Sosial Gereja, 208.
[183] Bdk. Santo Yohanes Paulus II, EnsiklikSollicitudo Rei Socialis(30 Desember 1987), 42: AAS 80 (1988), 572-574; Ensiklik Centesimus Annus (1 Mei 1991), 11: AAS 83 (1991), 806-807.
[184] Amanat pada Peserta dalam Pertemuan Gerakan-gerakan Populer(28 Oktober 2014): AAS 106 (2014), 852.
[185] Amanat pada Parlemen Eropa, Strasbourg (25 November 2014): AAS 106 (2014), 999.
[186] Amanat pada Pertemuan dengan Otoritas dan Korps Diplomatik di Republik Afrika Tengah, Bangui (29 November 2015): AAS 107 (2015), 1320.
[187] Amanat kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York (25 September 2015): AAS 107 (2015), 1039.
[188] Amanat kepada Peserta pada Pertemuan Gerakan-gerakan Populer (28 Oktober 2014): AAS 106 (2014), 853.
[189] Dokumen tentang Persaudaraan Manusia untuk Perdamaian Dunia dan Hidup Berdampingan, Abu (4 Februari 2019): L’Osservatore Romano, 4-5 Februari 2019, hlm. 6.
[190] René Voillaume, Frères de tous, ed. Cerf, Paris, 1968, 12-13.
[191] Pesan Video pada Konferensi TED di Vancouver (26 April 2017): L’Osservatore Romano, 27 April 2017, hlm. 7.
[192] Audiensi Umum (18 Februari 2015): L’Osservatore Romano, 19 Februari 2015, hlm. 8.
[193] Seruan Apostolik Evangelii Gaudium(24 November 2013), 274: AAS 105 (2013), 1130.
[194] Ibid., 279: AAS 105 (2013), 1132.
[195] Pesan untuk Hari Perdamaian Sedunia 2019 (8 Desember 2018), 5: L’Osservatore Romano, 19 Desember 2018, hlm. 8.
[196] Pertemuan dengan Pemimpin Politik, Ekonomi, dan Budaya Brasil, Rio de Janeiro, Brazil (27 Juli 2013): AAS 105 (2013), 683-684.
[197] Seruan Apostolik Pascasinode Querida Amazonia (2 Februari 2020), 108.
[198] Dari film Pope Francis: A Man of His Word, oleh Wim Wenders (2018).
[199] Pesan untuk Hari Komunikasi Sedunia 2014 (24 Januari 2014): AAS 106 (2014), 113.
[200] Konferensi Para Uskup Katolik Australia, Komisi untuk Keadilan Sosial, Misi dan Pelayanan, Making It Real: Genuine Human Encounter in Our Digital World (November 2019).
[201] Ensiklik Laudato Si’ (24 Mei 2015), 123: AAS 107 (2015), 896.
[202] Santo Yohanes Paulus II, Ensiklik Veritatis Splendor (6 Agustus 1993), 96: AAS 85 (1993), 1209.
[203] Sebagai orang Kristen kita juga percaya bahwa Allah memberikan rahmat-Nya sehingga menjadi mungkin untuk bertindak sebagai saudara.
[204] Vinicius De Moraes, Samba da Benção, dalam album Um encontro no Au bon Gourmet, Rio de Janeiro (2 Agustus 1962).
[205] Seruan Apostolik Evangelii Gaudium (24 November 2013), 237: AAS 105 (2013), 1116.
[206] Ibid., 236: AAS 105 (2013), 1115.
[207] Ibid., 218: AAS 105 (2013), 1110.
[208] Seruan Apostolik Pascasinode Amoris Laetitia (19 Maret 2016), 100: AAS 108 (2016), 351.
[209] Pesan untuk Hari Perdamaian Sedunia 2020 (8 Desember 2019), 2: L’Osservatore Romano, 13 Desember 2019, hlm. 8.
[210] Konferensi Uskup-Uskup Kongo, Pesan untuk Umat Allah dan untuk para perempuan dan laki-laki yang berkehendak baik (9 Mei 2018).
[211] Amanat pada Pertemuan Besar Doa untuk Rekonsiliasi Nasional, Villavicencio, Kolombia (8 September 2017): AAS 109 (2017), 1063-1064, 1066.
[212] Pesan untuk Hari Perdamaian Sedunia 2020 (8 Desember 2019), 3: L’Osservatore Romano, 13 Desember 2019, hlm. 8.
[213] Konferensi Uskup Afrika Selatan, Surat Pastoral tentang Harapan Kristen dalam Krisis Saat Ini (Mei 1986).
[214] Konferensi Uskup Korea, Seruan Gereja Katolik di Korea untuk Perdamaian di Semenanjung Korea (15 Agustus 2017).
[215] Pertemuan dengan para Pemimpin Politik, Ekonomi, dan Sipil, Quito, Ekuador (7 Juli 2015): L’Osservatore Romano, 9 Juli 2015, hlm. 9.
[216] Perjumpaan Lintas Iman dengan Orang Muda, Maputo, Mozambik (5 September 2019): L’Osservatore Romano, 6 September 2019, hlm. 7.
[217] Homili pada Misa Kudus, Cartagena de Indias, Colombia (10 September 2017): AAS 109 (2017), 1086.
[218] Pertemuan dengan Otoritas, Korps Diplomatik, dan Perwakilan Masyarakat Sipil, Bogotá, Kolombia (7 September 2017): AAS 109 (2017), 1029.
[219] Konferensi Uskup-Uskup Kolombia, Untuk kebaikan Kolombia: dialog, rekonsiliasi, dan pembangunan integral (26 November 2019), 4.
[220] Pertemuan dengan Otoritas, Masyarakat Sipil, dan Korps Diplomatik, Maputo, Mozambik (5 September 2019): L’Osservatore Romano, 6 September 2019, hlm. 6.
[221] Konferensi Umum Kelima Uskup-Uskup Amerika Latin dan Karibia, Dokumen Aparecida (29 Juni 2007), 398.
[222] Seruan Apostolik Evangelii Gaudium (24 November 2013), 59: AAS 105 (2013), 1044.
[223] Ensiklik Centesimus Annus (1 Mei 1991), 14: AAS 83 (1991), 810.
[224] Homili pada Misa untuk Perkembangan Bangsa-Bangsa, Maputo, Mozambik (6 September 2019): L’Osservatore Romano, 7 September 2019, hlm. 8.
[225] Pidato pada Upacara Penyambutan, Kolombo, Sri Lanka (13 Januari 2015): L’Osservatore Romano, 14 Januari 2015, hlm. 7.
[226] Pertemuan dengan Anak-anak “Bethany Centre” dan Perwakilan para dampingan dari Pusat-pusat Amal Kasih lainnya di Albania, Tirana, Albania (21 September 2014): Insegnamenti II, 2 (2014), 288.
[227] Pesan video pada Konferensi TED di Vancouver (26 April 2017): L’Osservatore Romano, 27 April 2017, hlm. 7.
[228] Pius XI, Ensiklik Quadragesimo Anno (15 Mei 1931): AAS 23 (1931), 213.
[229] Seruan Apostolik Evangelii Gaudium (24 November 2013), 228: AAS 105 (2013), 1113.
[230] Pertemuan dengan Otoritas Sipil, Masyarakat Sipil, dan Korps Diplomatik, Riga, Latvia (24 September 2018): L’Osservatore Romano, 24-25 September 2018, hlm. 7.
[231] Pidato pada Upacara Penyambutan, Tel Aviv, Israel (25 May 2014): Insegnamenti II, 1 (2014), 604.
[232]Pidato pada Kunjungan ke Yad Vashem Memorial, Yerusalem (26 May 2014): AAS 106 (2014), 228.
[233] Amanat di Monumen Perdamaian, Hiroshima, Jepang (24 November 2019): L’Osservatore Romano, 25-26 November 2019, hlm. 8.
[234] Pesan untuk Hari Perdamaian Sedunia 2020 (8 Desember 2019), 2: L’Osservatore Romano, 13 Desember 2019, hlm. 8.
[235] Konferensi Uskup-Uskup Kroasia, Surat pada Peringatan Kelima Puluh Akhir Perang Dunia Kedua (1 Mei 1995).
[236] Homili pada Misa Kudus, Amman, Yordania (24 Mei 2014): Insegnamenti II, 1 (2014), 593.
[237] Bdk. Pesan untuk Hari Perdamaian Sedunia 2020 (8 Desember 2019), 1: L’Osservatore Romano, 13 Desember 2019, hlm. 8.
[238] Amanat kepada para Anggota Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York (25 September 2015): AAS 107 (2015), 1041-1042.
[239] No. 2309.
[240] Ibid.
[241] Ensiklik Laudato Si’ (24 Mei 2015), 104: AAS 107 (2015), 888.
[242] Juga Santo Agustinus, yang menciptakan gagasan “perang yang adil” yang tidak lagi kita dukung saat ini, mengatakan bahwa “mengakhiri perang dengan berbicara, dengan mengupayakan perdamaian secara damai dan bukan dengan berperang, adalah lebih mulia dari pada memberi manusia perdamaian dengan pedang” (Epistula 229, 2: PL 33, 1020).
[243] Ensiklik Pacem in Terris (11 April 1963): AAS 55 (1963), 291.
[244]Pesan kepada Konferensi PBB untuk Merundingkan Instrumen yang mengikat secara hukum untuk larangan senjata nuklir (23 Maret 2017): AAS 109 (2017), 394-396.
[245] Bdk. Santo Paulus VI, Ensiklik Populorum Progressio (26 Maret 1967): AAS 59 (1967), 282.
[246] Bdk. Ensiklik Evangelium Vitae (25 Maret 1995), 56: AAS 87 (1995), 463-464.
[247] Amanat pada Peringatan 25 Tahun Promulgasi Katekismus Gereja Katolik (11 Oktober 2017): AAS 109 (2017), 1196.
[248] Bdk. Kongregasi untuk Ajaran Iman, Surat kepada para Uskup tentang redaksi baru no. 2267 Katekismus Gereja Katolik (1 Agustus 2018): L’Osservatore Romano, 3 Agustus 2018, hlm. 8.
[249] Amanat kepada para Delegasi Asosiasi Internasional Hukum Pidana (23 Oktober 2014): AAS 106 (2014), 840.
[250] Dewan Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian, Kompendium Ajaran Sosial Gereja, 402.
[251] Santo Yohanes Paulus II, Amanat kepada Perkumpulan Nasional para Hakim (31 Maret 2000), 4: AAS 92 (2000), 633.
[252] Divinae Institutiones VI, 20, 17: PL 6, 708.
[253] Epistola 97 (Responsa ad consulta Bulgarorum), 25: PL 119, 991. “non solum innoxios quosque, verum etiam et noxios a mortis exitio satagite cunctos eruere…”; ”Hendaknya kalian berusaha untuk menyelamatkan dari hukuman mati bukan hanya siapa yang tak bersalah, tetapi juga semua yang bersalah”
[254] Epistola ad Marcellinum 133, 1.2: PL 33, 509.
[255] Amanat kepada para Delegasi Asosiasi Internasional Hukum Pidana (23 Oktober 2014): AAS 106 (2014), 840-841.
[258] Santo Yohanes Paulus II, Ensiklik Evangelium Vitae (25 Maret 1995), 9: AAS 87 (1995), 411.
[259] Konferensi Uskup-Uskup Katolik India, Tanggapan Gereja di India terhadap Tantangan-Tantangan Dewasa Ini(9 Maret 2016).
[260] Homili pada Misa Kudus,Domus Sanctae Marthae (17 May 2020).
[261] Benediktus XVI, Ensiklik Caritas in Veritate (29 Juni 2009), 19: AAS 101 (2009), 655.
[262] Santo Yohanes Paulus II, Ensiklik Centesimus Annus (1 Mei 1991), 44: AAS 83 (1991), 849.
[263] Amanat kepada Pemimpin Agama-agama lain dan Denominasi-denominasi Kristen lainnya, Tirana, Albania (21 September 2014): Insegnamenti II, 2 (2014), 277.
[264] Dokumen tentang Persaudaraan Manusia untuk Perdamaian Dunia dan Hidup Berdampingan, Abu Dhabi (4 Februari 2019): L’Osservatore Romano, 4-5 Februari 2019, hlm. 6.
[265] Seruan Apostolik Evangelii Gaudium (24 November 2013), 256: AAS 105 (2013), 1123.
[266] Benediktus XVI, Ensiklik Deus Caritas Est (25 Desember 2005), 28: AAS 98 (2006), 240.
[267] “Manusia adalah binatang politik”, Aristotle, Politics, 1253a 1-3.
[268] Benediktus XVI, Ensiklik Caritas in Veritate(29 Juni 2009), 11: AAS 101 (2009), 648.
[269] Amanat kepada Komunitas Katolik, Rakovski, Bulgaria (6 Mei 2019): L’Osservatore Romano, 8 Mei 2019, hlm. 9.
[270]Homili pada Misa Kudus, Santiago de Cuba (22 September 2015): AAS 107 (2015), 1005.
[271] Dokumen Konsili Vatikan II, Pernyataan tentang Hubungan Gereja dengan Agama-Agama Bukan Kristiani Nostra Aetate, 2, hlm. 311.
[272] Amanat pada Doa Ekumenis, Riga, Latvia (24 September 2018): L’Osservatore Romano, 24-25 September 2018, hlm. 8.
[273] Lectio Divina, Universitas Kepausan Lateran, Roma (26 Maret 2019): L’Osservatore Romano, 27 Maret 2019, hlm. 10.
[274] Santo Paulus VI, Ensiklik Ecclesiam Suam (6 Agustus 1964): AAS 56 (1964), 650.
[275] Amanat kepada Otoritas Sipil, Bethlehem, Palestina (25 Mei 2014): Insegnamenti II, 1 (2014), 597.
[276] AUGUSTINUS, Enarrationes in Psalmos, 130, 6: PL 37, 1707.
[277] Deklarasi Bersama Paus Fransiskus dan Patriark Ekumenis Bartolomeus I, Yerusalem (25 Mei 2014), 5: L’Osservatore Romano, 26-27 Mei 2014, p. 6.
[278] Dari film Pope Francis: A Man of His Word, oleh Wim Wenders (2018).
[279] Seruan Apostolik Pascasinode Querida Amazonia (2 Februari 2020), 106.
[280] Homili pada Misa Kudus, Kolombo, Sri Lanka (14 Januari 2015): AAS 107 (2015), 139.
[281]Dokumen tentang Persaudaraan Manusia untuk Perdamaian Dunia dan Hidup Berdampingan, Abu Dhabi (4 Februari 2019): L’Osservatore Romano, 4-5 Februari 2019, hlm. 7.
[282] Amanat kepada Masyarakat Sipil, Sarajevo, Bosnia-Herzegovina (6 Juni 2015): L’Osservatore Romano, 7 Juni 2015, hlm. 7.
[283] Amanat pada Pertemuan Internasional untuk Perdamaian yang diselenggarakan oleh Komunitas Sant’Egidio (30 September 2013): Insegnamenti I, 1 (2013), 301-302.
[284]Dokumen tentang Persaudaraan Manusia untuk Perdamaian Dunia dan Hidup Berdampingan, Abu Dhabi (4 Februari 2019), ): L’Osservatore Romano, 4-5 Februari 2019, hlm. 6.
[286] Bdk. Charles de Foucauld, Méditations sur le Notre Père (23 Januari 1897).
[287] Surat kepada Henry de Castries (29 November 1901).
[288] Surat kepada Nyonya de Bondy (7 Januari 1902). Santo Paulus VI menggunakan kata-kata ini ketika memuji komitmen Charles de Foucauld: Ensiklik Populorum Progressio (26 March 1967): AAS 59 (1967), 263.