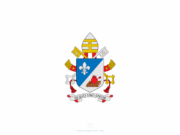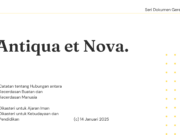| Judul | (A) MENDIDIK UNTUK DIALOG ANTARBUDAYA DI SEKOLAH-SEKOLAH KATOLIK (B) MENDIDIK UNTUK HUMANISME PERSAUDARAAN |
| Deskripsi | Dikeluarkan oleh Kongregasi untuk Pendidikan Katolik |
| Tanggal Terbit Dokumen | (A) Roma, 28 Oktober 2013 (B) Roma, 16 April 2017 |
| Harga | Rp 25.000,- |
| Tebal Buku | 94 halaman |
| Ukuran Buku | 15 x 22 cm |
MENDIDIK UNTUK DIALOG ANTARBUDAYA DI SEKOLAH-SEKOLAH KATOLIK
HIDUP DALAM KESELARASAN DEMI PERADABAN KASIH
Kongregasi untuk Pendidikan Katolik
(Untuk Lembaga-lembaga Pendidikan)
Kota Vatikan
2013
PENDAHULUAN
Telah menjadi sebuah kenyataan bahwa masyarakat masa kini terdiri dari berbagai macam budaya, yang didukung oleh globalisasi. Kehadiran tumpang tindih berbagai budaya yang berbeda menjadi sumber daya sungguh besar bilamana perjumpaan di antara berbagai budaya itu dianggap sebagai sumber untuk saling memperkaya. Namun, dapat muncul masalah-masalah mendesak jika masyarakat yang multibudaya dipandang sebagai ancaman bagi kohesi sosial, ataupun sebagai ancaman bagi perlindungan dan pelaksanaan hak-hak individu atau kelompok. Tidaklah mudah untuk menyeimbangkan dan menyelaraskan budaya yang sudah ada sebelumnya dengan budaya-budaya baru, karena kedua budaya itu sering menunjukkan kebiasaan atau adat-istiadat yang saling bertentangan. Untuk beberapa saat sekarang, masyarakat multibudaya telah menjadi sebuah objek perhatian, baik bagi pemerintah-pemerintah maupun organisasi-organisasi internasional. Demikian juga di Gereja, lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi pendidikan dan studi, baik di tingkat internasional, nasional, dan lokal, telah mulai mempelajari fenomena ini dan melakukan proyek-proyek khusus di bidang tersebut.
Pendidikan memuat tantangan utama di masa depan: untuk memungkinkan berbagai ungkapan budaya[1] hidup berdampingan dan memajukan dialog demi mengembangkan masyarakat yang damai. Tujuan-tujuan ini dicapai melalui berbagai tahap: 1. Menemukan sifat multikultur dalam situasinya sendiri; 2. Mengatasi prasangka dengan hidup dan bekerja dalam keselarasan; dan 3. Mendidik diri sendiri “melalui orang lain/liyan” menuju visi global dan makna kewarganegaraan. Dengan mengembangkan perjumpaan di antara berbagai orang yang berbeda membantu menciptakan saling pengertian, meskipun itu hendaklah tidak berarti kehilangan identitasnya sendiri.
Sekolah memiliki tanggung jawab besar di bidang ini karena mereka dipanggil mengembangkan dialog antarbudaya dalam visi pedagogik mereka. Ini adalah tujuan yang sulit, tidak mudah dicapai, namun diperlukan. Pendidikan, menurut sifatnya, menuntut keterbukaan terhadap budaya lain, tanpa kehilangan identitasnya sendiri, dan penerimaan akan orang lain, untuk mencegah risiko budaya yang sempit, tertutup pada dirinya sendiri. Maka, melalui pengalaman sekolah dan akademis mereka, orang muda harus memperoleh sarana-sarana teoretis dan praktis untuk menghimpun pengertian yang lebih besar tentang orang lain maupun dirinya sendiri, serta pengetahuan yang lebih besar akan nilai-nilai budaya mereka sendiri dan budaya lainnya. Mereka dapat mencapai hal ini dengan membandingkan budaya-budaya dengan pikiran terbuka. Dengan cara ini, mereka akan terbantu untuk memahami perbedaan dengan cara yang tidak menimbulkan konflik, tetapi memungkinkan perbedaan itu menjadi peluang untuk pengayaan timbal balik, yang mengarah kepada keselarasan.
Dalam konteks ini sekolah-sekolah Katolik dipanggil untuk memberi sumbangan mereka melalui tradisi pedagogik dan budaya mereka, dan dalam terang visi pedagogik mereka yang sehat. Perhatian terhadap aspek kehidupan antarbudaya bukanlah hal baru dalam tradisi sekolah-sekolah Katolik, karena sudah terbiasa menerima para siswa yang berasal dari berbagai latar belakang budaya dan agama. Namun, apa yang dituntut di bidang ini adalah kesetiaan yang berani dan inovatif terhadap visi pedagogiknya sendiri.[2] Hal ini benar di mana pun sekolah-sekolah Katolik berada, baik di negara-negara di mana komunitas Katolik adalah minoritas maupun di negara-negara di mana tradisi Katolisisme lebih berakar. Di negara-negara yang disebut pertama, dibutuhkan kemampuan untuk bersaksi dan berdialog, tanpa jatuh ke dalam jebakan relativisme yang nyaman, yang menyatakan bahwa semua agama sama dan hanya merupakan perwujudan dari Yang Mutlak yang tak seorang pun sungguh bisa mengetahui. Dalam kelompok negara yang disebut kemudian, apa yang penting adalah memberi jawaban kepada banyak orang muda “tanpa rumah agama,” hasil dari masyarakat yang semakin sekuler.
Kongregasi untuk Pendidikan Katolik tetap setia pada tugas yang dipercayakan kepadanya setelah Konsili Vatikan Kedua: untuk memperdalam prinsip-prinsip pendidikan Katolik. Karena itu, Kongregasi ingin menawarkan sumbangannya sendiri untuk mendorong dan membimbing pendidikan, di sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan Katolik, menuju jalan dialog antarbudaya. Maka, dokumen ini terutama ditujukan kepada: 1. Para orang tua, yang memiliki tanggung jawab pertama dan kodrati bagi pendidikan anak-anak mereka, juga organisasi-organisasi yang mewakili keluarga-keluarga di sekolah-sekolah; 2. Kepala sekolah, guru dan personel lain di sekolah Katolik yang, bersama-sama dengan para siswa, membentuk komunitas pendidikan; serta 3. Komisi-komisi episkopal nasional dan Komisi-komisi keuskupan, juga Lembaga-lembaga Religius, para Uskup, gerakan-gerakan gerejawi, perkumpulan-perkumpulan umat beriman, serta organisasi-organisasi lain yang menjalankan karya pastoral pendidikan. Kami juga dengan gembira menawarkan dokumen ini sebagai sarana dialog dan permenungan bagi semua yang peduli pada pendidikan seluruh pribadi, untuk membangun masyarakat damai yang ditandai dengan solidaritas.
BAB I
LATAR BELAKANG
Budaya dan Keberagaman Budaya
1. Budaya adalah ungkapan khas manusia, cara berada mereka yang khusus dan mengatur kehadiran mereka di dunia. Dengan menggunakan sumber-sumber daya warisan budaya mereka, yang dimiliki sejak saat kelahiran mereka, maka orang dapat berkembang secara tenang dan seimbang, dalam hubungan yang sehat dengan lingkungan mereka dan dengan orang lain. Ikatan mereka dengan budaya mereka sendiri perlu dan penting; namun, ikatan ini tidak memaksa orang menjadi menutup diri secara egois. Faktanya, pertalian budaya orang-orang selaras dengan perjumpaan dan pemahaman budaya lain. Sebenarnya, perbedaan budaya adalah kekayaan, yang dipahami sebagai ungkapan kesatuan fundamental umat manusia.
2. Globalisasi merupakan salah satu fenomena zaman kita saat ini, dan yang terutama menyentuh dunia kebudayaan. Globalisasi telah menunjukkan kemajemukan budaya yang menandai pengalaman manusia, dan mempermudah komunikasi di antara berbagai wilayah dunia, dengan melibatkan segala aspek hidup. Ini bukan hanya sesuatu yang teoretis atau umum: sesungguhnya, setiap individu senantiasa dipengaruhi oleh informasi dan berita yang sampai pada saat yang riil (real time) dari setiap sudut dunia. Orang menjumpai dalam hidup sehari-hari beragam budaya, dan dengan demikian mengalami peningkatan rasa memiliki terhadap apa yang disebut “global village” (desa global).
3. Namun, keanekaragaman budaya yang sangat banyak ini bukan sebagai bukti perpecahan leluhur yang sudah ada sebelumnya. Sebaliknya, ini merupakan hasil percampuran populasi yang terus-menerus, yang ditunjukkan sebagai faktor “ras-campuran”, atau “hibridisasi” (persilangan) keluarga manusia dalam perjalanan sejarahnya. Artinya, tidak ada sebuah budaya yang “murni.” Kondisi lingkungan, sejarah dan masyarakat yang berbeda-beda telah memperkenalkan kebinekaan yang luas dalam satu komunitas manusia, di mana, bagaimanapun “setiap orang itu pribadi yang sesungguhnya. Artinya: kodratnya dikaruniai akal budi dan kehendak bebas. Oleh karena itulah ia mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban, yang kesemuanya timbul sebagai konsekuensi langsung kodratnya. Hak-hak serta kewajiban-kewajiban itu bersifat universal dan tidak boleh dilanggar, maka dari itu sama sekali tak dapat direbut dari manusia.”[3]
4. Fenomena multikulturalisme zaman ini, yang terkait dengan munculnya globalisasi, sekarang berisiko menonjolkan “kebinekaan dalam kesatuan” yang problematis, yang menjadi ciri pandangan budaya orang. Bahkan, perjumpaan yang semakin akrab di antara beragam budaya, yang merupakan proses dinamis dalam dirinya sendiri, menimbulkan banyak ambivalensi. Di satu sisi, ada dorongan kepada berbagai bentuk keseragaman budaya yang lebih besar. Di sisi lain, sifat khas budaya yang berbeda diagung-agungkan. Orang mempertanyakan apa yang akan terjadi dengan identitas khusus setiap budaya, karena tekanan mobilitas manusia, komunikasi massa, internet, jejaring sosial, dan terutama penyebaran luar biasa adat-istiadat dan produk-produk yang mengakibatkan “westernisasi” dunia. Namun demikian, meskipun kecenderungan tak terhindarkan terhadap keseragaman tetap kuat, ada juga banyak unsur keragaman dan perbedaan, yang hidup dan aktif, di antara kelompok-kelompok. Semua ini sering membangkitkan reaksi fundamentalisme dan ketertutupan egois dalam diri sendiri. Karena itu, pluralisme dan keragaman tradisi, adat-istiadat, dan bahasa – yang dari sifatnya menghasilkan pengayaan dan pengembangan timbal balik – dapat menggiring kepada pernyataan berlebihan tentang identitas individu, yang memicu perselisihan dan konflik.
5. Namun, akan salah dengan meyakini bahwa perbedaan etnis dan budaya menjadi sebab dari banyak konflik yang mengguncang dunia. Kenyataannya, konflik-konflik ini disebabkan hal-hal politik, ekonomis, etnis, agama dan wilayah; dan tentu saja bukan secara eksklusif atau terutama karena konflik budaya. Meskipun demikian, unsur-unsur budaya, historis dan simbolis digunakan untuk menghasut orang, hingga mendorong kekerasan yang berakar pada unsur-unsur persaingan ekonomis, perbedaan sosial yang tajam dan absolutisme politik.
6. Semakin meningkatnya ciri masyarakat yang bersifat multikultural dan adanya risiko bahwa, bertentangan dengan sifat sejatinya, budaya sendiri dapat digunakan sebagai unsur-unsur pertentangan dan konflik, menjadi alasan untuk semakin mendorong terbangunnya hubungan antarbudaya yang mendalam di antara individu-individu dan kelompok-kelompok. Dalam terang ini, sekolah-sekolah menjadi tempat istimewa untuk dialog antarbudaya.
Budaya dan Agama
7. Aspek lain yang harus dipertimbangkan adalah hubungan antara budaya dan agama. “Budaya lebih luas daripada agama. Menurut salah satu konsep, agama dapat dikatakan untuk menunjukkan dimensi budaya yang transenden dan dalam cara tertentu adalah jiwanya. Agama-agama tentu saja telah menyumbang pada kemajuan budaya dan pengembangan masyarakat manusia.”[4] Agama diinkulturasikan, dan budaya menjadi lahan subur bagi kemanusiaan yang lebih kaya yang memenuhi panggilan khas dan mendalamnya agar terbuka pada sesama dan Allah. Maka, “inilah saatnya…untuk memahami secara lebih mendalam bahwa inti yang menghasilkan setiap budaya autentik didasari oleh pendekatannya terhadap misteri Allah, yang di dalam dirinya sendiri tatanan sosial yang berpusat pada martabat dan tanggung jawab pribadi manusia mendapatkan landasannya yang tak tergoyahkan.”[5]
8. Pada umumnya, agama menawarkan dirinya sebagai jawaban penuh makna atas pertanyaan-pertanyaan hakiki yang diajukan oleh manusia: “manusia mengharapkan jawaban tentang teka-teki keadaan manusiawi yang tersembunyi, yang seperti di masa silam, begitu pula sekarang menyentuh hati manusia secara mendalam.”[6] Karakteristik agama-agama menuntut untuk berdialog tidak hanya di antara mereka sendiri, tetapi juga dengan berbagai bentuk penafsiran ateistik, atau non-religius atas pribadi manusia dan sejarah, karena mereka berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sama tentang makna. Sekarang ini, negara dan masyarakat sipil juga melihat bagaimana pentingnya kebutuhan akan dialog lintas iman – artinya, pertukaran yang lebih luas di antara individu dan komunitas, masing-masing dengan cara pandang yang berbeda. Untuk menghindari penyempitan dan distorsi di bidang sensitif ini, pantaslah untuk menegaskan pertimbangan-pertimbangan berikut ini.
9. Masyarakat Barat, yang semakin ditandai dengan multikulturalisme, mengalami proses sekularisasi yang semakin cepat, dengan bahaya peminggiran ekstrem atas pengalaman religius, yang dianggap sah hanya dalam ruang lingkup pribadi. Lebih umum, dalam pola pikir yang dominan, persoalan antropologis diam-diam dihapuskan, antara lain soal martabat penuh dan ketentuan hidup umat manusia. Maka, tujuan dikejar untuk meniadakan segala ungkapan keagamaan dari budaya. Namun, kuranglah kesadaran tentang betapa berharganya dimensi keagamaan bagi dialog antarbudaya yang bermanfaat dan menjanjikan. Di samping pola pikir ini, ada fenomena yang pantas diperhatikan yang juga berisiko meremehkan pentingnya pengalaman religius bagi budaya. Orang dapat berpikir tentang tersebarnya sekte-sekte dan New Age, yang diidentikkan dengan budaya modern yang hampir tak lagi dianggap sebuah kebaruan.[7]
10. Agama menekankan kebenaran-kebenaran akhir dan definitif, dan dengan demikian, kebenaran yang menjadi dasar makna, yang membuat budaya Barat pada umumnya tampak menjauh darinya. Bagaimanapun, agama adalah sumbangan menentukan bagi pembangunan komunitas sosial, dengan menghormati kebaikan bersama dan dengan maksud memajukan setiap manusia. Maka, mereka yang memegang kekuasaan politik dipanggil untuk dengan hati-hati mempertimbangkan peluang-peluang emansipasi dan inklusi universal yang ditunjukkan dan dipengaruhi oleh setiap budaya dan setiap agama. Kriteria penting untuk penilaian ini adalah kemampuan efektif yang dimiliki agama untuk menunjukkan nilai seluruh pribadi dan semua orang. Kristianitas, agama Allah dengan wajah manusia,[8]membawa serta dalam dirinya kriteria yang sama.
11. Agama dapat memberikan sumbangannya kepada dialog antarbudaya “hanya jika Allah menemukan tempat dalam ruang publik.”[9] “Pengingkaran hak untuk memeluk agama seseorang secara publik dan hak membawa kebenaran-kebenaran iman untuk memengaruhi kehidupan publik memiliki konsekuensi-konsekuensi negatif terhadap perkembangan sejati. Penghilangan agama dari lingkungan publik, dan pada ekstrem lainnya, fundamentalisme agama, menghalangi perjumpaan antara pribadi-pribadi dan kerja sama mereka demi kemajuan umat manusia. Kehidupan publik dilemahkan motivasinya dan politik mengambil sikap mendominasi dan agresif. Hak-hak asasi manusia berisiko tidak dihormati, baik karena dasar transenden mereka dirampas, atau karena kebebasan pribadi tidak diakui.Sekularisme dan fundamentalisme meniadakan kemungkinan dialog subur dan kerja sama efektif antara akal budi dan iman kepercayaan. Akal budi selalu perlu dimurnikan oleh iman, dan ini juga berlaku untuk pikiran politik, yang tidak boleh menganggap dirinya mahakuasa. Pada gilirannya, agama selalu perlu dimurnikan oleh akal budi untuk memperlihatkan wajah kemanusiaannya yang sejati. Kerusakan apa pun dalam dialog ini mengakibatkan kerugian besar bagi perkembangan umat manusia.”[10] Iman dan akal budi, karena itu, harus mengakui satu sama lain dan saling memperkaya.
12. Dalam dialog antara budaya dan agama, harus diperhatikan diskusi antara iman dan berbagai bentuk ateisme dan perspektif humanis non-religius. Dalam inti diskusi ini perlu diupayakan apa pun yang bermanfaat bagi pengembangan integral seluruh pribadi dan semua orang, tanpa menjadi mandek dalam perselisihan mandul dari berbagai pihak. Masyarakat juga perlu mengakui hak individu atas identitasnya sendiri. Di pihaknya, Gereja dengan kasih yang ditimba dari sumber-sumber Injil, dengan mengikuti teladan misteri Inkarnasi Sabda, akan terus “mewartakan bahwa manusia layak mendapatkan penghargaan dan kasih bagi dirinya dan harus dihormati martabatnya. Dengan demikian, para saudara harus belajar lagi untuk memanggil saudara kepada satu sama lain, untuk saling menghormati, saling memahami, sehingga manusia sendiri dapat bertahan hidup dan bertumbuh dalam martabat, dalam kebebasan dan dalam penghargaan. Semakin ia menghambat dialog budaya, semakin dunia modern terperangkap dalam konflik yang berisiko mematikan masa depan peradaban manusia. Di luar prasangka, hambatan budaya, perpecahan ras, bahasa, agama dan ideologi, manusia harus saling mengakui satu sama lain sebagai saudara dan saudari, dengan saling menerima dalam kebinekaan mereka.”[11]
Agama Katolik dan Agama-agama Lain
13. Dalam konteks inilah dialog di antara berbagai agama mengambil bentuk tertentu. Dialog itu memiliki gambarannya sendiri, dan terutama menggarisbawahi kompetensi otoritas setiap agama. Tentu saja, dialog lintas agama, yang ditempatkan dalam dimensi religius kebudayaan, menyentuh beberapa aspek pendidikan antarbudaya – meskipun tidak semua, karena kedua hal tersebut tidaklah sama.
Globalisasi telah meningkatkan ketergantungan bangsa-bangsa satu sama lain, dengan tradisi dan agama mereka yang berbeda-beda. Dalam kaitan ini, ada yang menegaskan bahwa perbedaan menurut kodratnya menyebabkan perpecahan, sehingga harus sangat dimaklumi. Orang lain bahkan meyakini bahwa agama-agama sebaiknya dibungkam saja. “Sebaliknya, [perbedaan] memberi peluang luar biasa bagi orang-orang dari berbagai agama untuk hidup bersama dalam rasa hormat, penghargaan dan pengertian mendalam, dengan saling mendukung di jalan Allah.”[12]
Dalam hal ini, Gereja Katolik merasa bahwa kebutuhan dialog semakin penting. Dialog semacam itu, yang berawal dari kesadaran akan identitas imannya sendiri, dapat membantu orang untuk masuk dalam hubungan dengan agama-agama lain. Dialog bukan hanya sebatas berbicara, melainkan menyangkut segala hubungan lintas agama yang bermanfaat dan konstruktif, baik dengan individu maupun komunitas berkeyakinan lain, sehingga mencapai pemahaman timbal balik.[13]
Dialog, baik dengan pribadi-pribadi maupun komunitas-komunitas berkeyakinan lain, digerakkan oleh fakta bahwa kita semua adalah makhluk ciptaan Allah. Allah berkarya pada diri setiap manusia yang, melalui akal budi, telah memahami misteri Allah dan mengakui nilai-nilai universal. Lebih-lebih lagi, dialog memperoleh alasan utamanya (raison d’être) dalam pencarian akan warisan nilai-nilai etis bersama yang ditemukan dalam tradisi-tradisi keagamaan yang berbeda. Dengan cara ini, para penganut agama dapat membantu menegaskan kebaikan bersama, keadilan dan perdamaian. Oleh karena itu, “karena banyak yang dengan cepat menunjukkan perbedaan yang tampak jelas di antara agama-agama, maka sebagai para penganut agama atau orang-orang beragama kita dihadapkan pada tantangan untuk menyatakan secara jelas kesamaan yang kita miliki bersama.”[14]
Lebih lanjut, dialog yang dibina oleh Gereja Katolik dengan gereja-gereja lain dan dengan komunitas-komunitas Kristen tidak berhenti pada apa yang telah kita miliki bersama, tetapi cenderung menuju ke tujuan tertinggi untuk menemukan kembali kesatuan yang hilang.[15] Ekumenisme memiliki tujuannya demi terlihatnya kesatuan umat Kristen, yang untuk hal itu Yesus berdoa bagi para murid-Nya: Ut omnes unum sint, supaya mereka semua menjadi satu (Yoh 17:21).
14. Ada beragam cara yang dapat membuat orang-orang beriman berdialog: ada dialog kehidupan, dengan berbagi suka dan duka; dialog karya, dengan bekerja sama memajukan pengembangan umat manusia; dialog teologis, bilamana dimungkinkan, dengan studi warisan keagamaan satu sama lain; dan dialog pengalaman religius.
15. Namun, dialog ini bukanlah sebuah kompromi, melainkan ruang kesaksian timbal balik di antara para pemeluk agama yang berbeda. Dengan cara ini, orang mengerti agama orang lain dengan lebih mendalam dan lebih baik, juga perilaku etis yang berasal darinya. Dari pengetahuan langsung dan objektif atas pribadi lain, serta harapan religius dan etis yang berasal dari keyakinan dan praktik keyakinan agamanya, berkembanglah rasa hormat dan saling penghargaan, pemahaman, kepercayaan dan persahabatan. “Agar dialog itu benar, maka harus jelas, dengan menghindari relativisme dan sinkretisme, tetapi dijiwai oleh rasa hormat yang tulus pada orang lain dan semangat rekonsiliasi serta persaudaraan.”[16]
16. Kejelasan dalam dialog terutama berarti kesetiaan kepada identitas Kristianinya sendiri. “Kristianitas mengajukan Yesus dari Nazaret. Dia, yang kita imani, adalah Logos abadi yang menjadi manusia untuk mendamaikan manusia dengan Allah dan mewahyukan akal budi yang mendasari segala hal. Dialah yang kita bawa ke dalam forum dialog lintas agama. Keinginan kuat untuk mengikuti jejak-Nya melecut umat Kristen untuk membuka hati dan pikiran mereka untuk berdialog (bdk. Luk10:25-37; Yoh4:7-26).”[17] Gereja Katolik mewartakan bahwa “Yesus Kristus mempunyai relevansi dan nilai bagi umat manusia beserta sejarahnya, yang bersifat unik dan istimewa, khas bagi Dia satu-satunya, eksklusif, universal dan mutlak. Kenyataannya, Yesus itu Sabda Allah yang menjadi manusia demi keselamatan semua orang.”[18] Maka, jika hal ini adalah kondisi yang sangat diperlukan bagi dialog lintas agama, ini juga sangat diperlukan bagi pendidikan antarbudaya yang memadai, yang tidak terpisah dari identitas religius seseorang.
17. Sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan tinggi Katolik merupakan tempat penting bagi pendidikan ini. Apa yang menandai sebuah lembaga pendidikan sebagai “Katolik” adalah acuannya pada konsep Kristiani tentang realitas, “kualitas Katoliknya, yakni acuannya pada sebuah konsep hidup Kristiani yang berpusat pada Yesus Kristus.”[19] Karena itu, “sekolah-sekolah Katolik sekaligus adalah tempat evangelisasi, pendidikan seutuhnya, inkulturasi dan inisiasi pada dialog kehidupan di antara orang muda dari latar belakang agama dan sosial yang berbeda.”[20] Paus Fransiskus, yang berpidato pada sebuah sekolah di Albania, yang “setelah bertahun-tahun penindasan terhadap lembaga-lembaga keagamaan, telah memulai kembali aktivitasnya pada 1994, dengan menerima dan mengajar siswa-siswa Katolik, Ortodoks dan Muslim serta beberapa siswa yang lahir dalam lingkungan agnostik,” menyatakan bahwa “dengan demikian sekolah menjadi tempat dialog dan perjumpaan damai untuk mendorong sikap menghormati, mendengarkan, persahabatan dan semangat kerja sama.”[21]
18. Dalam konteks ini, “pendidikan harus membuat para siswa sadar akan akar mereka sendiri dan memberikan titik acuan yang memungkinkan mereka menjelaskan ruang pribadi mereka sendiri di dunia.”[22] Semua anak-anak dan orang muda harus memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan pemahaman atas agama mereka sendiri, juga unsur-unsur yang menjadi ciri-ciri agama-agama lain. Pengetahuan tentang cara berpikir dan berkeyakinan lain menghilangkan ketakutan dan memperkaya cara berpikir tentang orang lain dan tradisi spiritualnya. Maka, para guru bertanggung jawab untuk selalu menghormati pribadi manusia yang mencari kebenaran atas keberadaannya sendiri, dan menghargai serta menyebarluaskan tradisi budaya luhur yang terbuka kepada yang transenden dan yang mengungkapkan keinginan akan kebebasan dan kebenaran.
19. Pengetahuan ini tidaklah cukup dalam dirinya sendiri, tetapi membuka dialog. Semakin berlimpah pengetahuan itu, semakin mampu menopang dialog dan hidup berdampingan dengan orang-orang yang menganut agama lain. Dalam konteks dialog terbuka di antara budaya, agama-agama yang berbeda dapat dan harus memberikan sumbangan yang menentukan untuk membentuk kesadaran nilai-nilai bersama.
20. Sebaliknya, dialog, hasil pengetahuan, harus dikembangkan bagi orang-orang untukhidup berdampingan dan membangun sebuah peradaban kasih. Ini bukanlah soal mengurangi kebenaran, melainkan soal mewujudkan tujuan pendidikan yang “memiliki peran khusus untuk membangun dunia yang lebih bersatu dan damai. Ini bisa membantu menegaskan bahwa humanisme integral, terbuka pada dimensi kehidupan yang etis dan religius, yang menghargai pentingnya memahami dan menunjukkan penghargaan pada budaya-budaya lain dan nilai-nilai rohani yang ada di dalamnya.”[23] Dalam pendidikan antarbudaya, dialog ini bertujuan “untuk mengikis ketegangan dan konflik, serta potensi konfrontasi dengan pemahaman yang lebih baik di antara beragam budaya religius dalam wilayah tertentu mana pun. Hal ini bisa berkontribusi untuk memurnikan budaya dari unsur-sunsur apa pun yang tidak manusiawi, dan dengan demikian menjadi agen perubahan. Dialog juga bisa membantu menguatkan nilai-nilai budaya tradisional tertentu yang terancam modernitas dan perendahan nilai yang ditimbulkan oleh internasionalisasi sembarangan.”[24] “Dialog sangat penting bagi kematangan kita sendiri, karena ketika menghadapi pribadi lain, menghadapi budaya lain, dan juga menghadapi agama-agama lain secara benar, kita bertumbuh; kita berkembang dan menjadi matang… Dialog ini menciptakan perdamaian,” demikian tegas Paus Fransiskus.[25]
BAB II
PENDEKATAN TERHADAP PLURALISME
Penafsiran yang berbeda
21. Pluralisme adalah sebuah fakta nyata di dunia masa kini. Kemudian, soalnya adalah mengevaluasi potensi dialog, juga potensi dalam integrasi budaya-budaya yang berbeda. Jalan dialog menjadi mungkin dan subur bilamana didasarkan pada kesadaran akan martabat setiap individu dan kesatuan orang-orang dalam sebuah kemanusiaan bersama, dengan tujuan berbagi dan membangun bersama-sama suatu nasib bersama.[26] Terlebih lagi, situasi dunia saat ini, juga panggilan setiap budaya berarti memilih dialog antarbudaya sebagai suatu konsep yang membimbing, terbuka pada budaya itu, ketika berhadapan dengan aneka penafsiran pluralisme yang berkembang dan berlaku di masyarakat, politik dan (terkait dengan bidang perhatian kita) pendidikan.
Realitas pluralisme telah ditanggapi dengan dua pendekatan utama: relativisme dan asimilasi. Keduanya tidak lengkap, meskipun masing-masing memiliki aspek-aspek yang bermanfaat.
Pendekatan Relativistik
22. Kesadaran atas sifat budaya yang relatif dan pilihan pada relativisme merupakan dua hal yang sangat berbeda. Mengakui bahwa realitas bersifat historis dan dapat berubah tidak perlu mengarah pada pendekatan relativistik. Di sisi lain, relativisme menghormati perbedaan-perbedaan, tetapi sekaligus memisahkannya ke dalam lingkup otonom, dengan menganggapnya terisolasi dan tidak dapat ditembus sehingga tidak memungkinkan dialog. “Netralitas” relativistik sesungguhnya menyokong sifat mutlak setiap budaya dalam ruang lingkupnya sendiri dan menghalangi penggunaan penilaian kritis metakultural, yang sebaliknya akan memungkinkan penafsiran universal. Model relativistik berlandaskan pada nilai toleransi, tetapi membatasi diri untuk menerima pribadi lain, dengan meniadakan kemungkinan dialog dan pengakuan timbal balik dalam perubahan satu sama lain. Kenyataannya, ide toleransi tersebut mengarah pada makna hubungan yang pada dasarnya pasif dengan siapa pun yang mempunyai budaya lain. Ide ini tidak menuntut bahwa orang memperhatikan kebutuhan dan penderitaan sesamanya, juga bahwa orang harus mendengarkan alasan-alasan mereka; tidak ada pembandingan diri dengan nilai-nilai mereka, dan bahkan kurangnya cita rasa mengembangkan kasih bagi sesama.
23. Pendekatan semacam ini pada dasarnya adalah model multikulturalisme politik dan sosial. Model ini tidak menawarkan solusi yang tepat untuk hidup berdampingan, dan gagal mendorong dialog antarbudaya sejati. “Pertama, perlu dicatat bahwa eklektisisme budaya sering dipandang secara tidak kritis: budaya-budaya ditempatkan sejajar satu sama lain dan dipandang pada hakikatnya sama saja serta dapat dipertukarkan. Hal ini dengan mudah memunculkan relativisme yang justru tidak membantu dialog antarbudaya sejati; pada tataran sosial, relativisme budaya membuat kelompok-kelompok budaya yang berdampingan tetap terpisah, tanpa dialog autentik dan karenanya tidak ada integrasi yang sesungguhnya.”[27]
Pendekatan Asimilasi
24. Apa yang disebut pendekatan asimilasi tentu saja tidak lebih memuaskan. Alih-alih masa bodoh terhadap budaya lain, pendekatan ini ditandai dengan tuntutan agar orang lain menyesuaikan diri. Sebuah contoh adalah ketika, di suatu negara dengan imigrasi massal, kehadiran orang asing diterima hanya bila ia melepaskan identitas dan akar budayanya demi menganut identitas dan akar budaya negara penerima. Dalam model pendidikan yang berdasarkan asimilasi, orang lain/liyan harus melepaskan anutan budayanya, untuk mengenakan budaya kelompok lain atau negara penerima. Pertukaran dipersempit hanya pada penyisipan budaya minoritas ke dalam budaya mayoritas, dengan sedikit atau tanpa perhatian pada budaya asal orang lain.
25. Secara lebih umum, pendekatan asimilasi dikembangkan melalui budaya dengan ambisi universal yang berusaha memaksakan nilai-nilai budayanya sendiri melalui pengaruh ekonomis, perdagangan, militer dan budayanya. Di sinilah bahaya tampak jelas: “yakni penyeragaman budaya dan penerimaan sama rata terhadap bermacam tingkah laku dan gaya hidup.”[28]
Pendekatan Antarbudaya
26. Bahkan komunitas internasional mengakui bahwa pendekatan-pendekatan tradisional dalam menghadapi rintangan-rintangan kultural di masyarakat kita telah menunjukkan ketidakefektifannya. Namun, bagaimana mengatasi rintangan-rintangan yang ditimbulkan oleh posisi-posisi yang tidak mampu memberikan suatu penafsiran positif bagi faktor multikultural? Memilih logika dialog antarbudaya berarti tidak membatasi diri terhadap strategi-strategi untuk penyisipan fungsional para imigran ke dalam budaya mayoritas, juga tidak dalam tindakan-tindakan kompensasi yang bersifat khusus. Sesungguhnya, harus dipertimbangkan bahwa masalah tidak hanya muncul dari kedaruratan imigrasi, tetapi sebagai akibat meningkatnya mobilitas manusia.
27. Kenyataannya, dalam perspektif pendidikan yang bermakna, “sekarang ini kemungkinan interaksi antar–budaya telah berkembang secara signifikan, sehingga menimbulkan peluang baru untuk dialog antarbudaya: suatu dialog yang, jika inginmenjadi efektif, harus dimulai dari kesadaran mendalam atas identitas khusus dari bermacam-macam mitra dialog.”[29] Dari sudut pandang ini, keanekaragaman tidak lagi dipandang sebagai sebuah masalah. Sebaliknya, sebuah komunitas yang ditandai oleh pluralisme dipandang sebagai sumber daya, sebuah peluang untuk membuka seluruh sistem kepada semua perbedaan asal usul, hubungan antara laki-laki dan perempuan, status sosial dan sejarah pendidikan.
28. Pendekatan ini berdasarkan ide budaya dinamis, yang tidak tertutup dalam dirinya sendiri ataupun tidak mengungkapkan keanekaragaman dengan gambaran stereotip atau folkloristik. Strategi antarbudaya berjalan ketika itu menghindari pemisahan individu-individu ke dalam lingkup budaya yang otonom dan tertutup rapat-rapat; sebaliknya, hendaknya dikembangkan perjumpaan, dialog dan perubahan timbal balik sehingga memungkinkan orang untuk hidup berdampingan dan mengatasi kemungkinan konflik. Singkat kata, tujuannya adalah untuk membangun pendekatan antarbudaya baru, yang bertujuan mewujudkan integrasi budaya dalam pengakuan timbal balik.
BAB III
BEBERAPA LANDASAN UNTUK PENDEKATAN ANTARBUDAYA
Ajaran Gereja
29. Aspek antarbudaya tentu saja menjadi bagian dari warisan Kristianitas, yang memiliki panggilan “universal.” Bahkan, dalam sejarah Kristianitas ada jalinan dialog dengan dunia, dalam upaya mencari persaudaraan yang lebih besar di antara umat manusia. Dalam tradisi Gereja, perspektif antarbudaya tidak terbatas pada menghargai perbedaan, tetapi menolong membangun hidup berdampingan secara damai di antara umat manusia. Hal ini terutama dibutuhkan dalam masyarakat yang kompleks, di mana risiko relativisme dan penyeragaman budaya harus diatasi.
30. Banyak ajaran Gereja, terutama dalam Konsili Vatikan Kedua dan dalam Magisterium selanjutnya, telah merenungkan kebudayaan dan pengaruhnya bagi pengembangan potensi manusia yang utuh.
Konsili Vatikan Kedua, dalam mempertimbangkan pentingnya budaya menegaskan bahwa tidak ada pengalaman manusiawi sejati tanpa konteks budaya khusus. Kenyataannya, “manusia hanya dapat menuju kepenuhan kemanusiaannya yang sejati melalui kebudayaan.”[30] Setiap kebudayaan merupakan cara menyampaikan ungkapan pada aspek transendental kehidupan; hal ini mencakup permenungan tentang misteri dunia dan, terutama, tentang misteri umat manusia. Makna penting kebudayaan dibentuk “dalam kenyataan bahwa itu adalah ciri khas hidup manusia sebagaimana adanya. Manusia menjalani kehidupan manusiawi sejati berkat kebudayaan. Hidup manusia adalah kebudayaan juga dalam arti bahwa manusia dibedakan dan berbeda dari segala hal yang ada di mana pun dalam dunia yang tampak: manusia tidak dapat ada di luar budaya. Budaya adalah cara khas ‘ber-ada’ dan ‘meng-ada’ manusia. Manusia selalu hidup selaras dengan budaya yang dimilikinya dan yang pada gilirannya budaya itu menciptakan di antara manusia sebuah ikatan yang juga pantas bagi mereka, dengan menetapkan karakter antarmanusia dan sosial dari keberadaan manusia.”[31]
31. Selain itu, istilah kebudayaan menunjukkan segala sarana yang dengannya “manusia mengembangkan dan menyempurnakan pelbagai bakat-pembawaan jiwa-raganya. Ia berusaha menguasai alam semesta dengan pengetahuan maupun jerih payahnya. Ia menjadikan kehidupan sosial, dalam keluarga maupun dalam seluruh masyarakat, lebih manusiawi melalui kemajuan tata susila dan lembaga-lembaga. Akhirnya, di sepanjang masa ia mengungkapkan, menyalurkan dan melestarikan pengalaman-pengalaman rohani serta aspirasi-aspirasinya yang besar melalui karya-karyanya, supaya berfaedah bagi kemajuan banyak orang, bahkan segenap umat manusia.”[32] Oleh sebab itu, kebudayaan mencakup baik aspek subjektif – tingkah laku, nilai dan tradisi yang dimiliki setiap orang – dan aspek objektif, yaitu karya-karya individu.
32. Karena itu, “kebudayaan manusia mencakup dimensi historis dan sosial dan … seringkali mengandung arti sosiologis dan etnologis. Dalam arti itulah orang berbicara tentang kemacam-ragaman kebudayaan. Sebab dari pelbagai cara menggunakan bermacam-macam hal, menjalankan pekerjaan dan mengungkapkan diri, menghayati agama dan membina tata susila, menetapkan undang-undang dan membentuk lembaga-lembaga hukum, memajukan ilmu-pengetahuan serta kesenian, dan mengelola keindahan, muncullah pelbagai kondisi hidup yang umum serta pelbagai cara menata nilai-nilai kehidupan. Begitulah dari tata hidup yang diwariskan muncullah pusaka nilai-nilai yang khas bagi setiap masyarakat manusia. Begitu pula terwujudlah lingkungan hidup tertentu dengan corak historisnya sendiri, yang menampung manusia dari berbagai zaman manapun, dan yang menjadi sumber nilai-nilai untuk mengembangkan kebudayaan manusia serta masyarakat.”[33]
Kebudayaan-kebudayaan menunjukkan sifatnya yang sangat dinamis dan historis dan mengalami perubahan seiring waktu. Namun demikian, jauh di bawah perubahan yang bersifat dangkal, kebudayaan memperlihatkan unsur-unsur bersama yang penting. “Keragaman kebudayaan dengan demikian hendaknya dimengerti dalam wawasan yang lebih luas tentang kesatuan umat manusia,” dalam terang yang dapat dipahami orang tentang makna mendalam perbedaan, dan bukannya “radikalisasi identitas yang membuat kebudayaan resistan terhadap pengaruh positif apa pun dari luar.”[34]
33. Maka, relasi antarbudaya muncul tidak keluar dari ide budaya statis, tetapi dari keterbukaannya. Terutama ini merupakan potensi universalitas setiap budaya yang membentuk dialog di antara budaya-budaya.[35] Karena itu, “Dialog di antara kebudayaan … timbul sebagai sebuah tuntutan intrinsik kodrat manusia sendiri, juga budaya … yang berlandaskan pada pengakuan bahwa ada nilai-nilai bersama bagi semua budaya karena itu berakar dalam kodrat pribadi … Perlulah meningkatkan kesadaran orang tentang nilai-nilai bersama ini, demi merawat ‘tanah’ budaya yang pada hakikatnya universal, yang menghasilkan dialog subur dan konstruktif.”[36] Keterbukaan pada nilai-nilai bersama yang lebih tinggi bagi seluruh umat manusia – berdasarkan kebenaran dan, terlebih bersifat universal, seperti keadilan, perdamaian, martabat pribadi manusia, keterbukaan kepada yang transenden, kebebasan hati nurani dan kebebasan beragama – menyiratkan gagasan budaya sebagai sumbangan kepada kesadaran kemanusiaan yang lebih luas. Ini berlawanan dengan kecenderungan yang ada dalam sejarah kebudayaan, untuk membangun dunia-dunia kecil yang tertutup dan menutup diri.
Landasan Teologis
34. Mendefinisikan manusia melalui hubungan mereka dengan manusia lain dan dengan alam tidak memberikan jawaban lengkap terhadap pertanyaan mendasar: siapakah sesungguhnya manusia? Antropologi Kristiani menempatkan dasar bagi laki-laki dan perempuan serta kemampuan mereka untuk menghasilkan kebudayaan dalam keber-ada-an mereka yang diciptakan dalam gambar dan rupa Allah, Trinitas Pribadi-pribadi dalam persekutuan. Bahkan, pedagogi Allah yang sabar telah diwahyukan kepada kita dari sejak penciptaan dunia. Sepanjang sejarah keselamatan, Allah mendidik umat-Nya kepada perjanjian – yakni, kepada relasi yang hidup – dan membuka diri mereka sendiri kepada lebih banyak bangsa-bangsa. Perjanjian ini berpuncak pada Yesus, yang melalui wafat dan kebangkitan-Nya, telah menjadikannya “baru dan abadi.” Sejak saat itu Roh Kudus terus mengajarkan misi yang telah dipercayakan Kristus kepada Gereja-Nya: “Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku … ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu” (Mat. 28:19-20).
“Setiap manusia dipanggil kepada persekutuan karena kodratnya yang diciptakan dalam gambar dan rupa Allah (bdk. Kej. 1:26-27). Karena itu, dalam perspektif antropologi biblis, manusia bukanlah individu yang terasingkan, melainkan seorang pribadi: suatu makhluk yang pada hakikatnya relasional. Persekutuan yang menjadi panggilan manusia selalu meliputi dimensi rangkap, yakni vertikal (persekutuan dengan Allah) dan horizontal (persekutuan dengan orang-orang). Pentinglah bahwa persekutuan dipahami sebagai karunia Allah, sebagai buah inisiatif ilahi yang terpenuhi dalam misteri Paskah.”[37]
35. Dimensi vertikal persekutuan individu dengan Allah secara autentik diwujudkan dengan mengikuti Jalan yang adalah Yesus Kristus. Sesungguhnya, “hanya dalam misteri Sabda yang menjelmalah misteri manusia benar-benar menjadi jelas … Kristus … sepenuhnya menampilkan manusia bagi manusia, dan membeberkan kepadanya panggilannya yang amat luhur.”[38] Pada saat yang sama, dimensi vertikal ini berkembang dalam Gereja yang “dalam Kristus bagaikan sakramen, yakni tanda dan sarana persatuan mesra dengan Allah dan kesatuan seluruh umat manusia.”[39] “Berkat kekayaan keselamatan yang dilaksanakan oleh Kristus, tembok-tembok yang menceraikan pelbagai kebudayaan roboh. Janji Allah dalam Kristus sekarang menjadi tawaran universal… menyebarluas kepada semua sebagai pusaka, dan dari warisan itu siapa pun kiranya dapat menerima sesuatu. Dari tempat-tempat huni dan tradisi-tradisi mereka yang berbeda-beda, semua dipanggil dalam Kristus untuk ikut serta dalam kesatuan keluarga anak-anak Allah.”[40]
36. Dimensi horizontal persekutuan, yang kepadanya laki-laki dan perempuan dipanggil, diwujudkan dalam hubungan antarpribadi.[41] Identitas pribadi menjadi matang sejauh bahwa orang menjalani hubungan tersebut secara autentik. Maka, hubungan dengan orang lain dan dengan Allah sangat penting karena melalui mereka laki-laki dan perempuan meningkatkan nilai diri mereka sendiri. Hubungan di antara bangsa-bangsa, juga di antara budaya-budaya dan di antara negara-negara memperkuat dan mengembangkan mereka yang memasuki hubungan. Bahkan, “komunitas manusiawi tidak meleburkan individu, dengan menghilangkan otonominya, seperti yang terjadi pada aneka ragam bentuk totalitarianisme, tetapi lebih menghargainya karena relasi antara individu dan komunitas adalah relasi antara totalitas yang satu dengan totalitas yang lain. Seperti suatu keluarga tidak menenggelamkan identitas para individu anggotanya, seperti halnya Gereja bersukacita dalam setiap “ciptaan baru” (Gal. 6:15; 2Kor. 5:17) yang disatukan dengan Baptisan ke dalam Tubuhnya yang hidup, demikian juga kesatuan keluarga manusia tidak menenggelamkan identitas individu-individu, bangsa-bangsa dan budaya-budaya, tetapi menjadikannya lebih terlihat jelas satu sama lain dan menghubungkan mereka secara lebih dekat dalam keberagaman mereka yang sah.”[42]
37. Pengalaman hubungan antarbudaya, seperti halnya perkembangan manusia, dipahami secara mendalam hanya dalam terang inklusi individu-individu dan bangsa-bangsa dalam satu keluarga manusia, yang berlandaskan solidaritas dan nilai-nilai keadilan dan perdamaian yang fundamental. “Perspektif ini diterangi dengan sangat jelas dalam hubungan antara Pribadi-pribadi Trinitas dalam satu Hakikat ilahi. Trinitas adalah kesatuan mutlak karena ketiga Pribadi Ilahi itu merupakan relasionalitas murni. Transparansi timbal balik antara ketiga Pribadi ilahi itu total dan ikatan satu sama lain sempurna, karena Mereka adalah satu kesatuan yang unik dan mutlak. Allah juga berkehendak mempersatukan kita ke dalam realitas persekutuan ini: ‘Supaya menjadi satu sama seperti Kita adalah satu’ (Yoh. 17:22). Gereja adalah tanda dan sarana dari persekutuan ini. Demikian juga, relasi antara manusia sepanjang sejarah tidak dapat tidak diperkaya dengan mengacu pada model ilahi ini. Terutama, dalam terang misteri pewahyuan Trinitas, kita mengerti bahwa keterbukaan sejati bukan berarti kehilangan identitas pribadi, tetapi saling menyatu secara mendalam.”[43] Dasar yang diberikan tradisi Kristen untuk kesatuan umat manusia terutama ditemukan dalam penafsiran metafisika dan teologis “humanum” di mana relasionalitas menjadi unsur hakikinya.[44]
Landasan Antropologis
38. Dimensi antarbudaya yang autentik dapat diraih karena landasan antropologisnya. Sebenarnya, perjumpaan dengan orang lain selalu terjadi antara dua individu yang hidup. Budaya menjadi hidup dan terus-menerus merancang ulang dirinya mulai dari perjumpaan dengan pribadi lain. Keluar dari diri sendiri dan memandang dunia dari sudut pandang yang berbeda bukanlah suatu penyangkalan terhadap diri sendiri, melainkan sebaliknya diperlukan untuk meningkatkan identitasnya sendiri. Dengan kata lain, saling ketergantungan dan globalisasi di antara bangsa-bangsa dan budaya-budaya haruslah berpusat pada pribadi manusia. Akhir ideologi abad lalu, seperti halnya penyebaran ideologi masa kini yang tertutup bagi realitas transenden dan religius menunjukkan betapa kuat perlunya kembali ke pokok persoalan tentang manusia dan budaya. Tak dapat dipungkiri bahwa laki-laki dan perempuan zaman kita, meskipun mengalami kemajuan di banyak bidang, menemui kesulitan besar dalam menjelaskan siapa mereka sesungguhnya. Konsili Vatikan Kedua dengan jelas menggambarkan situasi ini: “tentang dirinya, pendapat-pendapat yang beraneka pun bertentangan: sering kali ia menyanjung-nyanjung dirinya sebagai tolok ukur yang mutlak, atau merendahkan diri hingga putus asa; maka, ia serba bimbang dan gelisah.”[45] Indikator paling jelas dari kebingungan identitas ini adalah rasa kesepian orang-orang zaman sekarang. “Salah satu bentuk kemiskinan paling dalam yang dialami seseorang adalah keterasingan. Jika kita melihat lebih dekat bentuk lain dari kemiskinan, termasuk bentuk-bentuk material, kita tahu bahwa bentuk-bentuk itu muncul dari keterasingan, dari tidak dicintai atau sulit untuk mengasihi. Kemiskinan sering ditimbulkan oleh penolakan akan kasih Allah, berasal dari kecenderungan tragis menutup diri, karena menganggap diri sudah mampu mencukupi kebutuhan sendiri, atau sekadar sebuah kenyataan yang tidak penting dan hanya sekejap mata, ‘seorang asing’ di alam semesta yang tercipta begitu saja. Manusia terasing ketika ia sendirian, ketika ia terpisah dari kenyataan, ketika ia berhenti berpikir dan berhenti percaya pada sebuah dasar. Seluruh kemanusiaan terasing ketika sangat percaya hanya pada proyek-proyek manusia, ideologi-ideologi dan utopia-utopia palsu. Dewasa ini umat manusia tampak lebih interaktif daripada di masa lalu: rasa kedekatan terhadap satu sama lain ini harus diubah menjadi persekutuan sejati. Pengembangan bangsa-bangsa terutama tergantung pada pengakuan bahwa bangsa manusia adalah satu keluarga yang bekerja bersama dalam persekutuan sejati, bukan sekelompok orang yang semata-mata hidup saling berdampingan.”[46]
39. Oleh sebab itu, untuk membentuk hubungan antarbudaya dengan benar, diperlukan landasan antropologis yang sehat. Ini harus berangkat dari fakta bahwa manusia, menurut kodratnya yang paling dalam, adalah makhluk relasional, yang tidak dapat hidup atau mengembangkan potensi mereka tanpa berelasi dengan sesamanya. Laki-laki dan perempuan, bukan hanya individu-individu belaka, seperti makhluk bersel satu yang bisa mencukupi diri sendiri, melainkan terbuka dan berkembang menuju orang yang berbeda dari dirinya. Manusia adalah seorang pribadi, makhluk hidup yang berelasi, yang memahami dirinya dalam relasi dengan sesamanya. Terlebih lagi, hubungannya mencapai tingkat terdalam jika itu berlandaskan kasih. Setiap individu ingin mengasihi sehingga merasa terpenuhi sepenuhnya, baik dalam kasih yang diterima maupun kemampuan untuk memberikan kasih sebagai balasan. “Manusia tidak dapat hidup tanpa cinta. Ia tetap makhluk yang tidak dapat dimengerti bagi dirinya. Hidupnya tiada maknanya, kalau cinta tidak dinyatakan kepadanya, kalau ia tidak menjumpai cinta, kalau ia tidak mengalaminya dan menjadikannya miliknya, kalau ia tidak secara mendalam berperan serta di dalamnya… Dalam dimensi itu manusia menemukan lagi keagungan, martabat dan nilai kemanusiaannya.”[47]
40. Gagasan cinta, dalam pelbagai bentuk, telah menyertai sejarah berbagai budaya. Di Yunani kuno istilah yang paling sering digunakan adalah eros, cinta sebagai hasrat, yang pada umumnya diasosiasikan dengan hasrat sensual. Juga dipakai istilah philia, yang sering dimengerti sebagai kasih persahabatan, dan agape, yang menunjukkan penghargaan tinggi kepada sesuatu atau seseorang yang dicintai. Tradisi Kitab Suci dan Kristen menggarisbawahi aspek oblatif (berkurban) kasih. Namun, di atas dan di luar perbedaan ini ada suatu kesatuan mendalam dalam keragaman di dalam realitas kasih, yang memaksa orang kepada “jalan tetap dari kungkungan diri sendiri ke penganugerahan diri, untuk penyerahan dan justru karena itu penemuan diri, ya, sampai menemukan Allah.”[48]
41. Kasih, ketika dibebaskan dari egoisme, merupakan cara par excellence (terbaik) kepada persaudaraan dan saling membantu menuju kesempurnaan antara orang-orang. Kasih adalah kerinduan tak tertahan, yang tertulis dalam kodrat setiap laki-laki dan perempuan di dunia. Tidak menerima kasih menyebabkan kehilangan makna dan keputusasaan, serta menimbulkan tingkah laku destruktif. Kasih adalah keagungan sejati individu, melebihi dan melampaui budaya, kelompok etnis, strata sosial atau posisi apa pun yang dimilikinya. Kasih adalah ikatan terkuat, paling autentik, dan paling diinginkan, yang menyatukan orang satu sama lain dan membuat mereka mampu saling mendengarkan, saling memperhatikan, dan saling memberikan penghargaan yang layak mereka terima. Dapat dikatakan bahwa kasih adalah metode dan tujuan hidup itu sendiri. Kasih adalah harta yang benar, yang dicari dan diberikan kesaksian, dalam berbagai cara dan pelbagai konteks, oleh para pemikir, orang-orang kudus, umat beriman, dan tokoh berkarisma yang, selama berabad-abad telah menjadi teladan hidup pengorbanan diri sebagai jalan yang luhur dan penting menuju perubahan dan pembaruan spiritual dan sosial.
Landasan Pedagogik
42. Landasan teologis dan antropologis di atas meletakkan dasar-dasar yang sehat bagi pedagogi antarbudaya autentik, yang pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari pengertian manusia sebagai pribadi. Oleh sebab itu, bukanlah terutama kebudayaan melainkan pribadilah yang saling berhubungan satu sama lain – pribadi-pribadi yang berakar dalam sejarah dan hubungan mereka sendiri. Karenanya, memahami hubungan antarpribadi menjadi paradigma pedagogik dasar, baik sarana maupun tujuan untuk mengembangkan identitas pribadi itu sendiri. Paradigma ini mengarah ke gagasan dialog, dengan menjamin bahwa itu bukan ide abstrak atau ideologis, melainkan ditandai oleh rasa hormat, pengertian dan pelayanan timbal balik. Kemudian, ide ini dikembangkan dengan ide budaya yang menyejarah dan dinamis, yang menolak untuk mendorong orang lain ke dalam semacam penjara budaya. Akhirnya, disadari bahwa sifat budaya yang relatif tidak sama dengan relativisme; relativisme, sambil menghargai perbedaan, serentak memisahkannya ke dalam kosmos otonom, dengan menganggapnya terasing dan tak tertembus. Sebaliknya, paradigma kita berusaha dengan segala cara untuk mengembangkan budaya dialog, budaya pengertian dan saling membarui untuk mencapai kebaikan bersama.
43. Dari perspektif ini, pengertian hubungan antarbudaya tidak bersifat diferensialistik pun bukan relativistik. Sebaliknya, pandangan ini menganggap budaya termasuk dalam tatanan moral, yang nilai fundamentalnya terutama adalah pribadi manusia. Mengenali fakta dasar ini memungkinkan orang dari pelbagai dunia budaya saling berhubungan untuk mengatasi perasaan-perasaan keterasingan awal mereka. Oleh karena itu, hal ini bukan hanya soal saling menghormati: proses ini mengandaikan bahwa orang-orang mempertanyakan pra-pemahaman mereka, dan bahwa setiap orang mengerti dan mendiskusikan sudut pandang orang lain.
44. Dari sudut pandang pedagogis, untuk mengembangkan tema sulit ini dibutuhkan keberanian dan upaya untuk semakin menyadari realitas yang kompleks dan pada hakikatnya multikultural ini. Khususnya, pembahasan perlu dilakukan dengan cara yang berbeda, untuk mendapatkan ide umum pendidikan secara lebih dalam dan lebih luas. Sesungguhnya, perlu dicari ide pendidikan untuk dialog antarbudaya, yang dimengerti sebagai perjalanan individu menuju harus menjadi apa, dalam perspektif dialog dan saling belajar seumur hidup.
BAB IV
PENDIDIKAN KATOLIK DALAM PERSPEKTIF DIALOG ANTARBUDAYA
Sumbangan Pendidikan Katolik
45. Gagasan budaya-budaya dalam dialog merupakan terang yang membimbing upaya bersama yang diperlukan untuk mengatasi pemisahan. Dalam kerangka saling belajar, harus diketahui cara masuk ke dalam detail praktis dialektika yang ditimbulkan oleh beberapa kategori dasar hidup dan budaya (“pertentangan/perjumpaan”, “ketertutupan/keterbukaan”, “monolog/dialog”, dan sebagainya).
Dalam proses pendidikan ini, pencarian akan koeksistensi damai dan memperkaya harus didasarkan pada pengertian yang paling luas tentang manusia. Hal ini harus ditandai dengan pencarian berkelanjutan akan transendensi diri, yang dipandang tidak hanya sebagai upaya psikologis dan kultural untuk mengatasi segala egosentrisme dan etnosentrisme, tetapi juga sebagai dorongan spiritual dan religius, selaras dengan pengertian akan pengembangan integral dan transenden dari individu dan masyarakat.
46. Dengan demikian, komunitas-komunitas yang mengambil inspirasi mereka dari nilai-nilai iman Katolik (keluarga, sekolah, kelompok, organisasi orang muda, dan sebagainya) harus memberikan suara dan realitas kepada pendidikan yang sungguh didasarkan pada pribadi manusia, sejalan dengan budaya dan tradisi Kristen yang humanistik. Harus ada komitmen baru kepada individu yang dipandang sebagai “pribadi dalam persekutuan” dan makna baru dari keterlibatannya dalam masyarakat. Jika tidak, masyarakat yang dikenal dengan individu-individu yang bebas dan setara tentu saja menyembunyikan risiko konflik dan penyalahgunaan kekuasaan yang tanpa batas dan tak terkendali.
Lebih lanjut, kaitan penting antara individu-individu yang bersama-sama membentuk masyarakat atau komunitas “membutuhkan evaluasi kritis lebih dalam atas kategori relasi. Ini adalah tugas yang tidak dapat dilakukan oleh ilmu-ilmu sosial saja, sebab kontribusi dari ilmu-ilmu seperti metafisika dan teologi dibutuhkan apabila martabat transenden manusia itu sungguh-sungguh hendak dipahami secara tepat.”[49]
Dalam terang misteri ke-Tritunggal-an Allah, hubungan antarpribadi harus dipandang bukan hanya dalam proses komunikasi mereka; justru, seperti Kasih, hubungan itu adalah hukum hakiki Keberadaan. Kasih ini tidak biasa, samar-samar, dan terikat pada perasaan belaka; pun tidak semata-mata terikat pada kenyamanan atau aturan memberi-menerima. Sebaliknya, kasih ini “bebas”, kuat dan murah hati sebagaimana kasih yang dengannya Yesus Kristus mengasihi. Dalam arti ini, kasih adalah kehendak untuk “memajukan”; inilah kepercayaan kepada orang lain dan, karenanya, menjadi tindakan yang pada dasarnya bersifat mendidik.
47. Konsep “kasih” dalam pendidikan secara langsung menunjukkan konsep “anugerah” dan “ketimbal-balikan”, yang menjadi aspek mendasar pendidikan itu sendiri. Sekolah, baik pendidik maupun peserta didik, keluarga dan komunitas yang lebih luas harus mengembangkan gerakan dua arah, kepada-dan-dari, yang adalah kasih. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan dua gerakan: dari kasih yang diterima kepada kasih yang diberikan. Di sini ketimbal-balikan (resiprositas) dimengerti bukan semata-mata sebagai hasil akhir, sebagai kesetaraan hasil, melainkan terutama sebagai langkah proaktif yang diambil oleh pendidik, yang dipanggil untuk pertama-tama mengasihi.
Konsep-konsep ini harus dikaji ulang dengan berani agar dapat mengembangkan pedagogi persekutuan. Tujuannya adalah suatu cita-cita pendidikan yang menggerakkan para pendidik agar menjadi para saksi yang dapat dipercaya di mata orang-orang muda. Kemudian, harus diikuti dengan refleksi tentang hubungan yang krusial dan strategis yang mengikat “kasih akan pendidikan” dengan “pendidikan untuk mengasihi.” Dua gagasan ini sangat penting dan terkait satu sama lain secara tak terpisahkan. Di dalamnya, baik pendidik maupun peserta didik melihat kebaikan, rasa hormat dan dialog.
Kehadiran di Sekolah-sekolah
48. Yohanes Paulus II menggarisbawahi gagasan ini, dan melihat dalam spiritualitas persekutuan[50] tantangan terpenting untuk dihadapi dalam budaya, hidup keseharian, keluarga, di sekolah dan di Gereja.
Di hadapan segala prakarsa nyata lainnya, harus ada semangat persatuan yang hidup di antara individu-individu dan kelompok-kelompok. Ini adalah perspektif di mana setiap nilai memperoleh landasannya. Ini adalah unsur penting yang menjadi dasar bagi semua unsur lainnya. Ini bukan hanya sebuah tantangan rohani, melainkan juga tantangan budaya, bagi semua orang yang berkehendak baik. Karena itu, para pendidik Katolik, para guru dan para siswa yang berada di dalam jenis sekolah apa pun, yang bersatu dalam seni mengasihi yang sama, juga harus menerima ajakan ini.
49. Oleh karena itu, bukanlah hukum sendiri atau bentuk yuridis lain yang membentuk sebuah komunitas dan menjaganya tetap hidup, melainkan spirit hukum itulah yang membentuk warga negara yang aktif dan bertanggung jawab, tepat sejauh hukum itu melayani kesejahteraan umum dan menempatkan setiap orang dalam situasi ketimbal-balikan. Maka, identitas komunitas menjadi matang sejauh itu dilakukan dan terus-menerus serta dengan setia berusaha memperbarui nilai-nilai kerja sama dan solidaritas.
50. Sekolah dipercayakan dengan tanggung jawab sangat besar untuk pendidikan antarbudaya. Selama proses pembinaan mereka, para siswa berinteraksi dengan aneka budaya, dan membutuhkan alat-alat yang perlu untuk memahami budaya-budaya tersebut dan menghubungkannya dengan budaya mereka sendiri. Sekolah harus terbuka terhadap perjumpaan dengan kebudayaan-kebudayaan lain. Mereka bertugas untuk mendukung individu-individu sehingga setiap pribadi mengembangkan identitasnya sendiri dengan menyadari kekayaan dan tradisi budayanya.
Dari pandangan pedagogik dan antarbudaya, hadiah terindah yang dapat diberikan pendidikan Katolik kepada sekolah adalah kesaksian. Sekolah-sekolah Katolik dapat memberikan kesaksian kepada jejaring hubungan yang langgeng dan personal, yang dihidupi antara kutub-kutub identitas pribadi dan identitas yang berbeda. Jejaring ini ditandai dengan perpaduan dinamis, dalam beragam hubungan antara orang-orang dewasa (para guru, orang tua, pendidik, mereka yang bertanggung jawab dalam lembaga, dan sebagainya), antara guru dan siswa, di antara para siswa – tanpa prasangka terhadap budaya, jenis kelamin, kelas sosial atau agama.
Di mana Kebebasan Pendidikan Diingkari
51. Di banyak wilayah dunia, karena alasan politik atau budaya, tidak selalu dimungkinkan mempunyai sekolah Katolik. Kadang-kadang kehadiran sekolah Katolik sangat terbatas dan menghadapi permusuhan. Persoalan ini bukan semata tentang membela sebuah hak, hak kebebasan mengajar dan bersekolah, melainkan kebutuhan untuk diungkapkan terkait dengan tawaran budaya yang membuat setiap orang makin kaya. Maka, orang harus bertanya: apa yang dapat ditawarkan pendidikan Katolik dalam situasi ini?
Pada dasarnya, harus dimulai dengan mengakui pada diri orang lain keinginan yang sama yang ditemukan di banyak agama dan budaya, dalam perintah penting yang disebut aturan emas kemanusiaan: “Perbuatlah terhadap orang lain seperti yang Anda ingin mereka perbuat kepada Anda; jangan melakukan kepada orang lain apa yang Anda tidak ingin mereka lakukan kepada Anda.” Ini adalah hukum moral dan sangat hakiki untuk kehidupan bermasyarakat. Kasih harus diberikan kepada semua. Inilah sumber peradaban baru, pemanusiaan sejati (ke)manusia(an), dan kebalikan dari segala naluri egois pada kekerasan dan peperangan.[51]
52. Hal ini merupakan kebaruan pendidikan yang juga mengalir dari pedagogi Kristiani, yang pendasarannya ditemukan dalam kata-kata Yesus: “supaya mereka semua menjadi satu” (Yoh 17:21). Bahkan, hal ini menunjukkan inti segala Kristianitas, pembawa misteri Allah, yang adalah Yang Ada dalam relasi, tindakan kasih yang murni. Di sinilah ditemukan kebaruan Injil, yang penerimaan penuhnya tentu saja mencakup iman, tetapi yang pengaruhnya mengubah makna setiap perjumpaan di antara individu, kelompok, budaya dan lembaga.
53. Hanya dalam semangat menemukan persatuan ini, tatanan masyarakat dapat tetap disatukan. Ini adalah solidaritas dalam totalitasnya, dalam setiap maknanya (religius, politik, sosial, ekonomis, dan profesional). Ini merupakan alternatif bagi kondisi persaingan abadi yang menghukum orang menjadi semakin terasing, meskipun mereka hidup dalam dunia yang mengglobal – yang menghukum mereka untuk semakin tak peduli, baik kepada Allah yang diwartakan oleh Kristianitas maupun setiap bentuk Yang Absolut apa pun.
Oleh sebab itu, orang muda dirampas dari budaya dan iman, dari makna sejatinya dan tujuan yang layak untuk dikejarnya. Maka, mereka berisiko tidak memanusiawikan (mendehumanisasi) hidup itu sendiri dengan beragam cara. Justru dalam banyak situasi “perbatasan” ini, di mana iman setiap hari diuji, melawan arus –yang sekarang ini sering terjadi lebih daripada sebelumnya– adalah pilihan Injil. Puncaknya, hadiah teragung, adalah pemberian diri sendiri, dengan memberi hidup seseorang bagi orang lain ketika keadilan dan kebenaran dilanggar.
54. Oleh karenanya, dalam konteks yang sangat berbeda ini (terhadap ateisme, fundamentalisme, relativisme, sekularisme), “prioritas nilai” harus ditempatkan kembali di pusat. Hal ini pada dasarnya adalah kesaksian yang jelas; penganugerahan diri; kemampuan meminta dan memberi pengampunan, bukan untuk ekshibisionisme atau moralisme keliru, melainkan “demi kasih,” untuk berperan serta demi perkembangan dunia.
Ada “sebuah fakta antropologis penting: keinginan, yang pantas bagi pribadi manusia, untuk menjadikan orang lain berbagi harta bendanya. Penerimaan Kabar Baik dalam iman, karenanya, diarahkan secara dinamis kepada komunikasi semacam itu,” terutama dengan mereka “yang kurang memiliki manfaat besar di dunia ini: untuk mengenal wajah Allah yang benar serta persahabatan dengan Yesus Kristus, Allah-beserta-kita. Tentunya, ‘tidak ada yang lebih indah daripada dikejutkan oleh Injil, oleh perjumpaan dengan Kristus. Tak ada yang lebih indah daripada mengenal-Nya dan berbicara kepada sesama tentang persahabatan kita dengan-Nya’.”[52]
BAB V
SUMBANGAN SEKOLAH KATOLIK
Tanggung jawab Sekolah Katolik
55. Dalam konteks sosial masa kini, sekolah-sekolah Katolik dituntut untuk menawarkan sumbangan khas mereka. Namun, hal ini bukanlah tugas yang mudah: sungguh, ini menghadapi rintangan yang semakin lebih besar. Sekolah-sekolah Katolik sedang menghadapi semakin banyaknya kehadiran siswa dengan aneka ragam kebangsaan dan keyakinan keagamaan. Di banyak negara di dunia, kebanyakan siswa menganut agama non-Katolik dan tema perjumpaan lintas agama sekarang ini tak terhindarkan lagi. Untuk menghindari ketertutupan diri pada “identitas” sebagai tujuan itu sendiri, pedagogi pendidikan harus memperhitungkan berkembangnya tingkat kemajemukan agama di masyarakat, dengan akibat perlunya mengenal aneka keyakinan dan berdialog, baik dengan mereka yang memiliki keyakinan maupun yang tidak.
56. Pentinglah bagi sekolah-sekolah Katolik untuk menyadari risiko yang timbul jika mereka melupakan alasan-alasan mengapa mereka ada. Hal itu dapat terjadi, misalnya, ketika tanpa berpikir kritis mereka menyesuaikan diri dengan harapan masyarakat yang ditandai dengan nilai-nilai individualisme dan persaingan. Ini juga dapat terjadi melalui formalisme birokrasi, tuntutan konsumerisme keluarga, atau pencarian dukungan eksternal yang tak terkendali. Sekolah-sekolah Katolik dipanggil untuk memberikan kesaksian yang setia, melalui pedagogi mereka yang jelas-jelas diilhami Injil – lebih lagi (a fortiori) dalam sebuah budaya yang menuntut agar sekolah hendaklah netral dan menghapus seluruh referensi keagamaan dari lingkup pendidikan.[53] Sekolah-sekolah Katolik, dengan menjadi Katolik, tidak terbatas pada ilham Kristiani yang samar-samar atau hanya berdasarkan nilai-nilai manusiawi. Mereka memiliki tanggung jawab untuk memberi para siswa, selain pengetahuan agama yang sehat, juga kemungkinan untuk bertumbuh dalam kedekatan pribadi dengan Kristus dalam Gereja. Sebenarnya, “salah satu hak asasi manusia, juga berkaitan dengan perdamaian internasional, adalah hak individu dan komunitas atas kebebasan beragama… Menjadi semakin penting untuk memajukan hak ini bukan hanya dari sudut pandang negatif, seperti bebas dari – misalnya, kewajiban atau keterbatasan yang meliputi kebebasan untuk memilih agama – melainkan juga dari sudut pandang positif, dalam pelbagai ungkapannya, seperti bebas untuk – misalnya, memberi kesaksian untuk agamanya, membuat ajaran agamanya dikenal, terlibat di bidang pendidikan, bela rasa, dan amal kasih yang memungkinkan pelaksanaan ajaran agama, dan ada serta bertindak sebagai badan-badan sosial yang terstruktur sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran yang tepat dan tujuan kelembagaan masing-masing.”[54]
57. Tanggung jawab utama sekolah Katolik adalah memberi kesaksian.[55] Dalam aneka situasi yang diciptakan oleh kebudayaan yang beragam, kehadiran umat Kristen harus ditunjukkan dan diperjelas, yakni, harus kelihatan, nyata, dan disadari. Sekarang ini karena kemajuan proses sekularisasi, sekolah-sekolah Katolik berada dalam situasi misioner, bahkan di negara-negara dengan tradisi Kristen kuno. Sumbangan yang dapat diberikan oleh Katolisisme kepada pendidikan dan dialog antarbudaya adalah dalam rujukan mereka kepada sentralitas pribadi manusia, yang memiliki unsur konstitutifnya dalam hubungan dengan sesama. Sekolah-sekolah Katolik mendasarkan paradigma antropologis dan pedagogisnya pada Yesus Kristus, mereka harus menjalankan “tata bahasa dialog,” bukan sebagai alat teknis, melainkan sebagai cara berelasi dengan orang lain secara mendalam. Sekolah-sekolah Katolik harus merenungkan identitasnya sendiri karena apa yang dapat mereka sumbangkan terutama adalah menjadi diri mereka sebagaimana adanya.[56]
Komunitas Pendidikan sebagai Pengalaman Hubungan Antarbudaya
58. Model yang harus dipakai oleh struktur-struktur sekolah sebagai inspirasi mereka adalah komunitas yang mendidik, tempat segala perbedaan hidup bersama secara harmonis.[57] Komunitas sekolah adalah sebuah tempat perjumpaan dan memajukan peran serta. Sekolah berdialog dengan keluarga yang menjadi komunitas pertama di mana para siswa yang bersekolah menjadi bagian di dalamnya. Sekolah harus menghormati budaya keluarga. Ia harus mendengarkan dengan cermat kebutuhan-kebutuhan yang ditemukannya dan harapan yang ditujukan kepadanya. Dengan demikian, sekolah bisa dianggap sebagai suatu pengalaman hubungan antarbudaya yang sejati, yang sungguh dijalankan dan bukan hanya diomongkan.
59. Masyarakat dan sekolah netral, yang kekurangan nilai-nilai acuan dan tidak terlibat dengan pembinaan moral apa pun, tidak mengembangkan keikutsertaan. Atau dalam ekstrem lain, peran serta tidak berkembang dalam masyarakat atau sekolah-sekolah yang diresapi oleh pandangan-pandangan fundamentalis. Sebaliknya, dikembangkan iklim dialog dan hormat timbal balik, dalam lingkungan pendidikan di mana semua dijamin dapat meningkatkan kemampuan mereka sepenuhnya, dengan tujuan tetap untuk mengusahakan kebaikan bagi semua. Dengan demikian, juga dapat dikembangkan iklim saling percaya yang terus-menerus, kesiapsediaan, iklim mendengarkan serta pertukaran yang berbuah, yang harus menjadi ciri seluruh periode pembinaan. Kelas-kelas yang bertujuan memberi ungkapan, baik pada kehidupan maupun pemikiran, diarahkan untuk menciptakan dialog berkelanjutan antara guru dan siswa; meningkatkan andil pribadi para siswa dalam pencarian bersama akan pengetahuan; serta meningkatkan pengajaran interdisipliner, dengan sumbangan para guru dari pelbagai disiplin ilmu.
60. Di sekolah-sekolah, yang dimengerti sebagai komunitas pendidikan, keluarga-keluarga mempunyai tempat dan peran yang paling penting. Sekolah-sekolah Katolik menghargai nilai mereka, dan mengembangkan peran serta mereka di sekolah, di mana mereka dapat menerima berbagai bentuk tanggung jawab bersama. Bahkan ketika beberapa keluarga hidup dalam situasi sulit dan ada orang tua-orang tua yang tidak mengikuti anjuran sekolah, keluarga selalu dipandang sebagai titik acuan yang sangat diperlukan, sebagai pembawa sumber-sumber daya yang cukup berharga. “Kemitraan antara sebuah sekolah Katolik dan keluarga-keluarga para siswa harus terus berlanjut dan diperkuat; tidak semata-mata agar mampu menghadapi masalah-masalah akademis yang mungkin timbul, melainkan agar tujuan pendidikan sekolah dapat tercapai.”[58]
Program Pendidikan untuk Pendidikan Dialog Antarbudaya
61. Pendidikan yang ditawarkan oleh sekolah-sekolah Katolik mengalir dari kesaksian mereka terhadap Injil dan kasih mereka yang bebas dan terbuka bagi semua. Pendidikan ini terkait dengan pengembangan pendekatan antarbudaya di semua lingkungan sekolah: hubungan antara individu-individu, pandangan yang dipakai terhadap pengetahuan manusia dalam totalitasnya dan dalam pelbagai disiplin akademis, serta integrasi dan hak-hak semua orang.
Kondisi yang sangat diperlukan bagi kerja sama adalah keterbukaan pada pluralitas dan perbedaan. Pengalaman menunjukkan bahwa agama Katolik mengerti cara menjumpai, menghormati, dan menghargai budaya-budaya yang berbeda-beda. Kasih terhadap semua laki-laki dan perempuan tentu juga adalah kasih kepada kebudayaan mereka. Sekolah-sekolah Katolik, menurut panggilan mereka sendiri, bersifat antarbudaya.
62. Program pendidikan sekolah-sekolah Katolik mengusahakan agar studi dan kehidupan bertemu dan berpadu secara selaras satu sama lain. Hal ini memungkinkan para siswa mengalami pembinaan yang berkualitas, yang diperkaya dengan penelitian ilmiah di berbagai cabang ilmu pengetahuan, dan sekaligus, menjadi sumber kebijaksanaan karena konteksnya: hidup yang disegarkan oleh Injil. Dengan cara ini, dihindari risiko kegagalan pendidikan, terutama, untuk mengembangkan pembinaan individu yang integral. Bahkan, “sekolah adalah salah satu lingkungan pendidikan di mana kita berkembang untuk belajar bagaimana hidup, bagaimana menjadi laki-laki dan perempuan yang dewasa dan matang yang dapat berjalan, yang dapat mengikuti jalan kehidupan… Sekolah membantu Anda tidak hanya dengan mengembangkan intelektualitas Anda, tetapi juga dengan pendidikan integral seluruh aspek kepribadian Anda.”[59]
63. Bidang perhatian utama program pendidikan adalah sebagai berikut:
Kriteria identitas Katolik. Tujuan sekolah-sekolah Katolik, dalam segala bentuknya, adalah untuk menghidupi dalam kesetiaan misi pendidikan mereka, yang berpangkal pada Kristus. “Fakta bahwa menurut caranya masing-masing para anggota komunitas sekolah membagikan misi Kristianinya ini, menjadikan sekolah disebut ‘Katolik’; prinsip-prinsip Injil dalam hal ini menjadi norma-norma pendidikan karena kemudian sekolah itu menjadikan norma-norma tersebut sebagai motivasi dan tujuan akhirnya.”[60] Identitas yang jelas ini memberi makna pada tanggung jawab lain dari sekolah.
Membangun sebuah visi bersama. Pendidikan dapat membantu mengidentifikasi dalam dirinya sendiri apa pun yang hakiki dan universal, dengan menyatukan pribadi-pribadi dalam keberbedaan mereka. Peran pendidikan masa kini justru untuk memupuk dialog, dengan memungkinkan komunikasi di antara orang-orang yang berbeda, dengan membantu mereka “menerjemahkan” cara berpikir dan merasa mereka yang berbeda. Hal ini bukan hanya soal mewujudkan dialog sebagai proses atau metode. Sebaliknya, ini adalah soal membantu orang lain kembali ke kebudayaan mereka sendiri, dengan kebudayaan orang lain sebagai titik pangkal mereka: dengan kata lain, membantu orang lain berefleksi tentang dirinya sendiri dalam perspektif “keterbukaan pada kemanusiaan.”
Keterbukaan yang masuk akal terhadap globalisasi. Komunitas yang mendidik seperti sekolah seharusnya tidak mendidik orang ke arah partikularisme. Sebaliknya, ia hendaknya menawarkan kepada para siswa pengetahuan yang perlu untuk memahami kondisi manusia saat ini, sebagai warga seluruh planet, kondisi yang dicirikan dengan banyak hubungan ketergantungan timbal balik.
Perlunya membentuk identitas pribadi yang kuat, yang tidak bertentangan satu sama lain. Sesungguhnya, kesadaran atas tradisi dan kebudayaannya sendiri merupakan titik awal yang membuat seseorang mampu berdialog dan mengakui kesetaraan martabat pribadi lain.
Kesadaran diri dikembangkan dengan kebiasaan memikirkan ulang pengalaman diri sendiri; merenungkan perilakunya sendiri; dan menjadi semakin sadar diri, termasuk melalui penggunaan strategi kognitif dan pembinaan yang jauh dari egosentrisme.
Nilai-nilai budaya dan agama lain harus dihormati dan dimengerti. Sekolah harus menjadi tempat pluralisme, di mana orang bisa belajar berdialog tentang makna yang disandingkan oleh orang-orang dari pelbagai agama dengan tanda-tanda mereka masing-masing. Hal ini memungkinkan orang berbagi nilai-nilai universal, seperti solidaritas, toleransi, dan kebebasan.
Mendidik untuk berbagi dan bertanggung jawab. Sekolah tidak boleh menjadi waktu jeda dalam hidup, tempat tiruan murni yang didedikasikan hanya untuk mengembangkan dimensi kognitif. Dengan menghormati kerangka waktu individual para siswa untuk mencapai kematangan dan kebebasan pribadi mereka, sekolah harus memikul tanggung jawab untuk membantu para siswa memahami situasi sosial dan kultural kehidupan. Sekolah juga harus mendorong para siswa untuk bertanggung jawab memperbaiki situasi ini. Lebih-lebih lagi, justru karena perhatian sekolah diberikan kepada seluruh pribadi dan semua pengalaman manusiawi mereka, sekolah tidak membatasi tanggung jawab mereka hanya sebatas pengajaran. Sekolah juga harus memperhatikan banyak aspek lain dari hidup para siswa, secara informal (pesta/perayaan, saat-saat kegembiraan, dan sebagainya), secara formal (presentasi dari pembicara tamu, waktu diskusi, dan sebagainya) dan pengalaman religius (saat-saat untuk liturgi dan spiritualitas, dan sebagainya).[61]
Kurikulum sebagai Ungkapan Identitas Sekolah
64. Kurikulum adalah cara komunitas sekolah menjelaskan tujuan dan sasarannya, isi pengajarannya dan sarana-sarana penyampaiannya secara efektif. Dalam kurikulum, identitas kultural dan pedagogis sekolah ditunjukkan. Mengembangkan kurikulum merupakan salah satu tugas sekolah yang paling mendesak karena di sinilah dijelaskan nilai-nilai acuan, prioritas-prioritas mata pelajaran dan pilihan praktis sekolah.
65. Bagi sekolah Katolik, menguji kurikulumnya berarti memperkuat apa yang khas menurut sifatnya. Ini berarti memperkuat cara khususnya dalam melayani individu-individu, dengan menggunakan alat-alat yang ditawarkan oleh budaya. Maka, program sekolah dapat diselaraskan secara efektif dengan misi awal sekolah. Orang tidak boleh puas hanya dengan tawaran pendidikan yang selalu baru yang semata-mata menanggapi tuntutan-tuntutan yang datang dari situasi ekonomi yang selalu berubah. Sekolah-sekolah Katolik memikirkan kurikulum-kurikulum mereka untuk berpusat pada individu-individu dan pencarian mereka akan makna. Ini adalah nilai acuan, mengingat bahwa berbagai disiplin akademis adalah sumber daya penting dan menerima nilai yang lebih besar sejauh bahwa sumber-sumber daya itu merupakan sarana-sarana pendidikan. Dari perspektif ini, apa yang diajarkan tidaklah netral, pun pula cara mengajarnya tidak netral.
66. Telah disampaikan bahwa kita hidup dalam masyarakat berbasis ilmu pengetahuan. Namun, sekolah-sekolah Katolik didorong untuk mengembangkan suatu masyarakat berbasis kebijaksanaan, untuk melampaui ilmu pengetahuan dan mendidik orang untuk berpikir, dengan menimbang fakta-fakta berdasarkan nilai-nilai. Mereka mendidik orang untuk menerima tanggung jawab dan kewajiban, serta menjalankan kewarganegaraan aktif. Di antara hal-hal yang diajarkan secara khusus di sekolah-sekolah Katolik, perlu diberikan tempat utama pada pengetahuan tentang berbagai budaya, dengan perhatian untuk menolong para siswa menjumpai dan membandingkan banyak sudut pandang dari budaya-budaya yang berbeda. Kurikulum harus membantu para siswa merefleksikan masalah-masalah besar zaman kita, termasuk melihat secara lebih jernih situasi sulit dari sebagian besar kondisi hidup umat manusia, seperti pendistribusian sumber-sumber daya yang tidak adil, kemiskinan, ketidakadilan dan pengingkaran hak-hak asasi manusia. “Kemiskinan” menyiratkan pertimbangan cermat terhadap fenomena globalisasi, dan mengusulkan untuk memiliki visi kemiskinan yang luas dan berkembang, dengan segala macam bentuk dan penyebabnya.[62]
67. Sebuah kurikulum yang baik dapat memadukan pelajaran-pelajaran teoretis dengan presentasi para pembicara yang terpelajar, di mana pengalaman-pengalaman hidup disajikan dalam terang pandangan iman tentang dunia. Kurikulum yang baik juga memuat pengalaman-pengalaman praktis untuk berbagi dan mengemban tanggung jawab.
Dua kutub tersebut saling terarah satu sama lain: pelajaran-pelajaran disampaikan dengan mendengarkan pengalaman hidup; pengetahuan menjadi pengalaman; dan pengalaman membutuhkan daya kekuatan dari sumbangan budaya dan daya pewartaan.
Dalam mengajar berbagai disiplin ilmu, para guru menyampaikan dan mengembangkan sudut pandang metodologis yang menghubungkan pelbagai cabang ilmu pengetahuan secara dinamis dengan perspektif yang bijaksana. Kerangka epistemologis setiap cabang ilmu mempunyai identitasnya sendiri, baik pada isi maupun metodologi. Namun, kerangka kerja ini tidak hanya terkait dengan soal-soal “internal,” yang melibatkan pelaksanaan yang benar setiap disiplin ilmu. Setiap disiplin ilmu bukanlah sebuah pulau yang dihuni sebentuk pengetahuan yang terpisah dan berbatas: sebaliknya, itu merupakan hubungan dinamis dengan semua bentuk pengetahuan lainnya, yang masing-masing mengungkapkan sesuatu tentang pribadi manusia dan menyentuh beberapa kebenaran.
68. Sekolah-sekolah ditantang oleh komposisi multibudaya kelas-kelas mereka. Mereka harus mampu berpikir ulang tentang apa yang akan diajarkan; metode pembelajaran; organisasi internal mereka, peran dan hubungan dengan keluarga-keluarga; serta konteks sosial dan budaya di mana mereka berada. Sebuah kurikulum yang terbuka pada perspektif antarbudaya menunjukkan kepada para siswa studi peradaban yang belum mereka ketahui sebelumnya, atau asing bagi mereka, tetapi yang sekarang meminta perhatian mereka. Kurikulum semacam itu juga semakin “didekatkan” berkat globalisasi dan sarana komunikasi modern, yang melintasi batas-batas ruang dan pertahanan ideologis. Pengajaran yang bertujuan membantu para siswa memahami kenyataan di mana mereka tinggal tidak bisa mengabaikan aspek perjumpaan. Di sisi lain, pengajaran wajib mengembangkan dialog, juga pertukaran budaya dan spiritual.
69. Pada level didaktik, sekolah harus menunjukkan perhatian antarbudayanya sendiri dengan mengingat dua tingkat pembelajaran: kognitif dan afektif-relasional. Di tingkat kognitif, sekolah-sekolah mengembangkan isi kurikulum: bidang-bidang pengetahuan yang akan diajarkan dan keterampilan-keterampilan yang akan dikembangkan. Di tingkat afektif-relasional, sekolah membina sikap-sikap dan cara-cara berbicara mengenai orang lain, dengan mengajarkan para siswa untuk menghormati keberagaman dan mempertimbangkan sudut pandang yang berlainan, dengan meningkatkan empati dan kerja sama.
Mengajar Agama Katolik
70. Dalam konteks sekarang ini, masyarakat manusia berusaha memberikan kepada diri mereka sendiri struktur-struktur transnasional yang lebih luas, dengan bergerak menuju sebuah sistem tata pemerintahan global. Selain itu, harta warisan simbolis sangat besar yang telah dibangun oleh pelbagai bangsa, yang dipertahankan dan diteruskan selama berabad-abad melalui tradisi-tradisi budaya dan agama mereka yang khusus, tampaknya terabaikan dalam kemampuan mereka yang sebenarnya untuk memanusiakan; sebaliknya, warisan tersebut justru menjadi alasan pemisahan, dalam ketidakpercayaan timbal balik. Dengan demikian, tantangan terbesar dalam pendidikan antarbudaya terletak terutama dalam dialog antara identitas diri sendiri dan visi hidup yang lain.
71. Perubahan budaya masa kini menunjukkan tanda-tanda tegangan yang jelas antara dialog dan konflik. Terutama ketika berhadapan dengan krisis identitas ini, sumbangan orang-orang Kristen dipandang sangat diperlukan. Oleh karena itu, pentinglah bahwa agama Katolik, di pihaknya, menjadi tanda dialog yang menginspirasi. Bahkan, dapat dikatakan secara mutlak bahwa pesan Kristiani tidak pernah menjadi seuniversal dan sehakiki seperti saat ini.
72. Dengan demikian, agama meneruskan kesaksian dan pesan humanisme integral. Humanisme ini, yang diperkaya dengan identitas agama, menghargai tradisi luhur agama seperti: iman; hormat kepada hidup manusia dari sejak pembuahan hingga akhir alamiahnya; hormat kepada keluarga, masyarakat, pendidikan dan pekerjaan. Semua ini menjadi peluang dan sarana untuk tidak menutup diri, tetapi terbuka dan berdialog dengan setiap orang dan segala sesuatu, yang menuntun kepada apa yang baik dan benar. Dialog tetap menjadi satu-satunya solusi yang mungkin, bahkan ketika berhadapan dengan penolakan sentimen keagamaan, dengan ateisme dan agnotisisme.
73. Dari perspektif ini, pengajaran agama Katolik di sekolah-sekolah mengambil peran menentukan.[63] Terutama, ini merupakan masalah hak atas pendidikan, yang berlandaskan pada pengertian antropologis tentang laki-laki dan perempuan yang terbuka kepada yang transenden. Bersama-sama dengan pembinaan moral, pengajaran ini juga membantu mengembangkan tanggung jawab pribadi dan sosial, serta kebajikan kemasyarakatan lainnya, demi kebaikan bersama masyarakat. Konsili Vatikan Kedua mengingatkan kembali bahwa “orangtua berhak menentukan menurut keyakinan keagamaan mereka sendiri, pendidikan keagamaan manakah yang akan diberikan kepada anak-anak mereka… Hak orangtua dilanggar, bila anak-anak dipaksa mengikuti pelajaran-pelajaran sekolah, yang tidak cocok dengan keyakinan keagamaan orangtua mereka, atau bila hanya ada satu cara pendidikan saja yang diwajibkan, tanpa pendidikan keagamaan sama sekali.”[64] Pernyataan ini digaungkan dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia[65] juga dalam deklarasi dan konvensi komunitas internasional lainnya.[66]
74. Selain itu, harus ditunjukkan bahwa pengajaran agama Katolik di sekolah-sekolah memiliki tujuannya sendiri, yang berbeda dari tujuan katekese. Sesungguhnya, sementara katekese mengembangkan ketaatan pribadi kepada Kristus dan kematangan hidup Kristiani, pengajaran sekolah memberi para siswa pengetahuan tentang identitas Kristianitas dan kehidupan Kristiani. Maka, pengajaran sekolah bertujuan “’memperluas bidang rasionalitas kita, membukanya kembali kepada persoalan-persoalan lebih besar tentang kebenaran dan kebaikan, menghubungkan teologi, filsafat dan sains satu sama lain dengan penuh hormat atas metode mereka sendiri dan otonomi timbal balik mereka, tetapi juga dalam kesadaran akan kesatuan intrinsik yang menyatukan mereka bersama-sama.’ Dimensi religius bahkan bersifat intrinsik dengan budaya. Dimensi ini memberi kontribusi pada seluruh pembinaan pribadi dan memungkinkannya mengubah pengetahuan menjadi kebijaksanaan hidup.” Karena itu, dengan pengajaran agama Katolik, “sekolah dan masyarakat diperkaya dengan laboratorium kebudayaan dan kemanusiaan yang benar di mana, dengan menafsirkan kontribusi penting Kristianitas, pribadi dimampukan untuk menemukan kebaikan dan berkembang dalam tanggung jawab, untuk mencari perbandingan-perbandingan dan memperhalus perasaan kritisnya, untuk mengambil dari anugerah masa lalu agar dapat memahami masa kini dengan lebih baik dan agar mampu merencanakan masa depan secara bijaksana.”[67]
Akhirnya, pengajaran agama diperhitungkan sebagai salah satu bidang pelajaran di sekolah-sekolah. Ini memberinya status, dengan menempatkannya di antara mata pelajaran-mata pelajaran lain dalam kurikulum sekolah, di dalam dialog interdisipliner yang diperlukan dan bukan sekadar tambahan.
75. Karena itu, tujuan kembar untuk memperluas keterlibatan akal budi dan mendukung dialog antardisiplin dan antarbudaya secara efektif dapat dikembangkan melalui suatu pengajaran agama tertentu yang diimani. pengakuan iman pada agama tertentu. Sesungguhnya, “jika pendidikan keagamaan dibatasi pada presentasi berbagai agama, secara komparatif dan ‘netral’, itu akan menciptakan kebingungan atau menghasilkan relativisme atau ketidakpedulian agama.”[68]
Pembinaan para Guru dan para Pengelola Sekolah
76. Pembinaan para guru dan para pengelola sekolah sangatlah penting. Di sebagian besar negara, Pemerintah menyediakan pembinaan awal bagi para personel sekolah. Meskipun hal ini mungkin dianggap baik, tetapi kurang memadai. Sebenarnya, sekolah-sekolah Katolik membawa kepada mereka sesuatu yang ekstra, khas bagi mereka, yang harus selalu diakui dan dikembangkan lebih lanjut. Karena itu, sementara pembinaan wajib perlu mempertimbangkan aspek-aspek disipliner dan profesional yang khas dalam pengajaran dan tata kelola, hendaknya juga diperhatikan dasar-dasar budaya dan pedagogis yang membentuk identitas sekolah-sekolah Katolik.
77. Waktu yang dihabiskan dalam pembinaan harus digunakan untuk memperkuat gagasan sekolah Katolik sebagai komunitas hubungan persaudaraan dan tempat penelitian, yang didedikasikan untuk memperdalam dan menyampaikan kebenaran dalam pelbagai disiplin ilmu. Mereka yang mempunyai posisi kepemimpinan terikat kewajiban untuk menjamin agar semua personel menerima persiapan yang cukup untuk melayani secara efektif. Terlebih lagi, mereka harus melayani sesuai dengan iman yang mereka akui, serta mampu menafsirkan tuntutan-tuntutan masyarakat dalam situasi nyata perwujudannya saat ini.[69] Ini juga meningkatkan kerja sama sekolah dengan para orangtua dalam pendidikan,[70] seraya menghormati tanggung jawab mereka sebagai pendidik pertama dan kodrati.[71]
78. Pembinaan yang secara khusus didedikasikan untuk meningkatkan kepekaan, kesadaran, dan kompetensi di ranah antarbudaya dapat ditingkatkan dengan memperhatikan tiga penanda penting berikut ini:
1. Integrasi: hal ini berkaitan dengan kemampuan sekolah untuk secara memadai mempersiapkan dirinya untuk menerima para siswa dari beragam latar belakang budaya, dengan menanggapi kebutuhan mereka terkait prestasi akademis dan peningkatan pribadi.
2. Interaksi: hal ini berhubungan dengan memahami cara memudahkan hubungan baik di antara teman sebaya dan di antara orang-orang dewasa. Kesadaran bahwa sekadar berada dalam lingkungan fisik yang sama tidaklah cukup. Harus diberikan dorongan agar tumbuh keingintahuan tentang orang lain, keterbukaan dan persahabatan, baik di kelas maupun di tempat-tempat dan saat-saat di luar sekolah. Dengan demikian, situasi yang menjauhkan di antara orang-orang, diskriminasi dan konflik dapat dihindari dan diperbaiki.
3. Pengakuan terhadap orang lain: harus dihindari agar tidak terjebak untuk memaksakan pandangan sendiri kepada pribadi lain, dengan menegaskan gaya hidup sendiri dan cara berpikir sendiri tanpa mempertimbangkan budaya dan situasi emosional tertentu dari orang lain.
79. Di tingkat budaya, tugas memajukan kesatuan di antara berbagai cabang pengetahuan harus diupayakan terus-menerus. Ini berarti mengatasi fragmentasi dan abstraksi, dengan mencari makna dalam perspektif yang lebih luas. Tidak kurang penting, bahkan esensial, bagi komunitas pendidikan untuk menugasi dirinya dalam mengatasi perpecahan hubungan – yang bersifat antarpribadi, komunitas dan kolektif. Di mana tidak ada kesadaran akan persatuan –dalam kekayaan keberagaman, baik individu maupun masyarakat– tidak mungkin ada perkembangan pengetahuan yang sepenuhnya “manusiawi,” dan tidak fungsional belaka – pengetahuan yang menjaga tradisi sekaligus terbuka pada inovasi.
80. Sekolah-sekolah Katolik mengembangkan, dengan cara yang sepenuhnya khas bagi mereka, hipotesis dasar bahwa pendidikan mencakup seluruh rentang pengalaman profesional dan tidak terbatas pada periode pembinaan awal atau pendidikan di tahun-tahun awal. Sekolah Katolik menuntut orang-orang tidak hanya mengerti cara mengajar atau mengatur sebuah organisasi; sekolah juga menuntut mereka, dengan menggunakan keterampilan profesi mereka, untuk memahami bagaimana memberikan kesaksian autentik pada nilai-nilai sekolah serta upaya terus-menerus mereka untuk semakin menghidupinya secara mendalam, dalam pemikiran dan tindakan, cita-cita yang diungkapkan secara publik dalam kata-kata.
Oleh karena itu, pentinglah bahwa sekolah mengetahui cara menjadi komunitas pembinaan dan studi, di mana relasi di antara individu-individu mewarnai hubungan di antara disiplin akademis. Pengetahuan ditingkatkan dari dalam dengan persatuan yang diperoleh kembali ini, dalam terang Injil dan ajaran Kristiani sehingga dapat memberikan kontribusi penting pada pertumbuhan integral, baik individu maupun masyarakat global yang semakin didengung-dengungkan.
Menjadi Guru, Menjadi Pengelola Sekolah
81. Pembinaan selalu diarahkan dengan cara memaknai profesi-profesi yang terlibat dalam pendidikan. Karena itu, pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab: Apa arti menjadi pengelola di sekolah Katolik? Bidang keahlian apa yang harus menjadi ciri profesi-profesi ini?
82. Para guru sekarang ini adalah para anggota komunitas profesional. Mereka berkontribusi untuk menyusun kurikulum; dan mereka mempunyai tanggung jawab untuk berhubungan dengan beragam subjek lain, teristimewa keluarga-keluarga para siswa. Sebuah sekolah yang baik adalah sekolah di mana para guru, sebagai satu kelompok, tahu bagaimana menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar korps yang diakui, di mana para anggotanya diikat bersama oleh ikatan birokrasi belaka. Sebaliknya, mereka hendaklah menjadi sebuah komunitas, yang menghidupi relasi profesional sekaligus personal, bukan sekadar di tingkat permukaan, melainkan pada level yang lebih dalam, diikat bersama oleh kepedulian yang sama untuk pendidikan.
83. Para guru yang baik tahu bahwa tanggung jawab mereka tidak berakhir di luar kelas atau sekolah. Mereka mengetahui bahwa tanggung jawab mereka juga terkait dengan wilayah setempat mereka, dan ditunjukkan dengan pemahaman mereka terhadap aneka masalah sosial saat ini. Persiapan profesional dan kemampuan teknis menjadi prasyarat penting untuk mengajar, tetapi itu tidaklah cukup. Fungsi pendidikan dinyatakan dengan mendampingi orang-orang muda memahami zaman mereka sendiri dan menyediakan pemikiran-pemikiran yang meyakinkan untuk rencana hidup mereka. Multikulturalisme dan pluralisme merupakan ciri khas zaman kita; maka, para guru harus dapat memberikan kepada para siswa mereka alat-alat budaya yang perlu untuk mengarahkan hidup mereka. Selain itu, para guru harus memungkinkan para siswa mereka mengalami latihan mendengarkan, menghormati, dan berdialog secara nyata dan mengalami nilai keberagaman dalam kehidupan sehari-hari di kelas.
84. Dengan semakin menjadi multikultural, sekolah-sekolah memiliki tugas membantu orang-orang dengan aneka pengalaman yang berbeda untuk saling berhubungan. Sekolah juga harus bertindak sebagai mediator antara orang-orang tersebut. Pengalaman orang-orang yang beraneka warna perlu dikenali dan diakui. Para guru dan para pengelola sekolah memerlukan keterampilan profesional baru, yang bertujuan memperdamaikan perbedaan-perbedaan, dengan memungkinkannya untuk berdialog satu sama lain. Para guru dan para pengelola sekolah perlu menawarkan perspektif bersama, sambil menghargai kekhasan perkembangan dan visi dunia dari orang-orang yang berbeda.
85. Bagi mereka yang menempati posisi kepemimpinan, akan ada godaan kuat untuk menganggap sekolah seperti sebuah perusahaan atau bisnis. Namun, sekolah yang bertujuan menjadi komunitas yang mengedukasi membutuhkan orang-orang yang memimpin sekolah itu agar dapat menanamkan nilai-nilai acuan sekolah; kemudian, mereka harus mengatur semua sumber daya profesional dan manusia dari sekolah ke arah ini. Para pimpinan sekolah bertindak lebih dari sekadar manajer organisasi. Mereka adalah para pemimpin pendidikan yang sesungguhnya bilamana mereka adalah orang-orang yang pertama mengambil tanggung jawab ini, yang juga merupakan misi gerejawi dan pastoral yang berakar dalam hubungan dengan para gembala Gereja. Para pimpinan sekolah mempunyai kewajiban khas untuk menyediakan dukungan yang perlu demi menyebarluaskan budaya dialog, perjumpaan dan saling pengakuan di antara budaya-budaya yang berbeda. Baik di dalam maupun di luar sekolah, mereka meningkatkan segala bentuk kerja sama yang dimungkinkan, yang membantu mewujudkan harmoni antarbudaya.
86. Agar sekolah-sekolah dapat berkembang sebagai komunitas profesional, perlulah bagi para anggota mereka untuk belajar berefleksi dan berusaha bersama-sama. Sekolah-sekolah adalah komunitas berbagi bersama, kebersamaan gagasan dan penelitian.
Lebih lanjut, perhimpunan komunitas yang mengedukasi diteguhkan melalui ikatan-ikatan kuat dengan komunitas Kristiani. Sesungguhnya, sekolah-sekolah Katolik adalah subjek gerejawi. “Dimensi gerejawi ini bukan sekadar tambahan, melainkan ciri yang sesungguhnya dan khas, ciri pembeda yang meresapi dan membentuk setiap momen kegiatan pendidikannya, bagian fundamental dari identitasnya dan inti misinya.”[72] Oleh karena itu, “seluruh masyarakat Kristiani, dan terutama Ordinaris Keuskupan, mengemban tanggung jawab ‘untuk mengatur segala sesuatu sedemikian sehingga semua orang beriman dapat menikmati pendidikan Katolik’ (KHK kan. 794 §2), dan lebih tepatnya, memiliki ‘sekolah di mana diberikan pendidikan yang diresapi semangat Kristiani’ (KHK kan. 802; bdk. Kan 635 KKGT).”[73] Sifat gerejawi sekolah-sekolah Katolik, yang ditulis dalam inti identitasnya sebagai sekolah, menjadi alasan bagi “ikatan kelembagaan yang dipertahankannya dengan hierarki Gereja, yang menjamin bahwa pengajaran dan pendidikan berdasarkan prinsip-prinsip iman Katolik dan diajarkan oleh para pengajar ajaran yang benar dan kejujuran hidup (bdk. KHK kan. 803; bdk. Kan 632 dan 639 KKGT).”[74]
KESIMPULAN
Tradisi sekolah-sekolah Katolik terbiasa dengan aspek antarbudaya. Meskipun begitu, saat ini berhadapan dengan tantangan globalisasi serta pluralisme budaya dan agama, pentinglah mengembangkan kesadaran yang lebih besar atas maknanya. Dengan demikian, sekolah-sekolah Katolik akan mengomunikasikan dengan lebih baik – dalam kehadiran, kesaksian dan pengajaran mereka – cara istimewa keberadaan mereka sendiri, menjadi Katolik. Sekolah-sekolah Katolik itu terbuka pada keuniversalan pengetahuan dan sekaligus mempunyai sifat khas mereka sendiri, yang berasal dari keberakaran mereka dalam iman akan Kristus Sang Guru dan dari keanggotaan mereka dalam Gereja.
Sekolah-sekolah Katolik menghindari fundamentalisme maupun gagasan relativisme di mana segala sesuatu sama. Sebaliknya, mereka didorong untuk maju dalam keselarasan dengan identitas yang telah mereka terima dari inspirasi Injil. Mereka juga diajak untuk mengikuti jalan yang menuntun menuju perjumpaan dengan sesama. Mereka mendidik diri mereka sendiri dan mendidik berdialog, termasuk berbicara dengan setiap orang dan berhubungan dengan setiap orang dengan rasa hormat, penghargaan, dan sikap mendengarkan dalam ketulusan. Mereka hendaknya mengungkapkan diri secara autentik, tanpa mengaburkan atau melemahkan visi mereka sendiri agar mendapatkan permufakatan yang lebih besar. Mereka hendaknya memberi kesaksian melalui kehadiran mereka sendiri serta kecocokan antara apa yang mereka katakan dengan apa yang mereka lakukan.
Kepada semua pendidik kami ingin menyampaikan kata-kata Paus Fransiskus yang memberi dukungan dan arahan: “Jangan berputus asa dengan kesulitan-kesulitan yang dibawa oleh tantangan pendidikan! Mendidik bukanlah sebuah pekerjaan, melainkan suatu sikap, cara berada; agar dapat mendidik, orang harus keluar dari dirinya sendiri dan berada di antara orang-orang muda, mendampingi mereka dalam tahap-tahap pertumbuhan mereka dengan menempatkan diri di samping mereka. Berilah mereka harapan, optimisme bagi perjalanan mereka di dunia. Ajarlah mereka melihat keindahan dan kebaikan ciptaan dan manusia yang selalu menjaga penanda Sang Pencipta. Tetapi terutama melalui hidup Anda jadilah saksi-saksi atas apa yang Anda sampaikan. Seorang pendidik […] menyampaikan pengetahuan, nilai-nilai dengan kata-katanya, tetapi kata-kata itu akan berdampak sangat menentukan pada anak-anak dan orang-orang muda jika kata-katanya itu disertai dengan kesaksiannya, dengan cara hidupnya yang konsisten. Tanpa konsistensi tidak mungkinlah mendidik! Anda semua adalah para pendidik, tidak ada pendelegasian di bidang ini. Maka, kerja sama dalam semangat persatuan dan persekutuan antara pelbagai unsur pendidikan sangatlah penting dan harus dikembangkan dan dipupuk. Sekolah dapat dan harus bertindak sebagai katalisator, sebuah tempat perjumpaan dan perhimpunan dari segenap komunitas yang mendidik, dengan satu-satunya tujuan melatih dan menolong untuk memperkembangkan orang-orang dewasa yang sederhana, cakap dan jujur, yang tahu cara mengasihi dengan kesetiaan, yang dapat menjalani hidup sebagai jawaban atas panggilan Allah, dan profesi masa depan mereka sebagai pelayanan kepada masyarakat.”[75]
Bapa Suci Paus Fransiskus telah memberikan persetujuannya untuk penerbitan dokumen ini.
Roma, 28 Oktober 2013, ulang tahun 48 promulgasi Deklarasi Konsili Vatikan Kedua Gravissimum Educationis.
Zenon Kardinal Grocholewski
Prefek
Uskup Agung Angelo Vincenzo Zani
Sekretaris
[1] Bdk. UNESCO, Konvensi tentang Perlindungan dan Kemajuan Keragaman Ungkapan Budaya, Paris (20 Oktober 2005), art. 4.
[2] Bdk. Kongregasi untuk Pendidikan Katolik, Sekolah Katolik di Ambang Milenium Ketiga (28 Desember 1997), no. 3.
[3] Yohanes XXIII, Ensiklik Pacem in Terris (11 April 1963), no. 9.
[4] Dewan Kepausan untuk Dialog Antaragama; Kongregasi untuk Evangelisasi Bangsa-Bangsa, Instruksi Dialog dan Pewartaan: Refleksi dan Orientasi tentang Dialog Antar-agama dan Pewartaan Injil Yesus Kristus (19 Mei 1991), no. 45.
[5] Yohanes Paulus II, Pidato kepada Gereja Italia (Palermo, 23 November 1995), no. 4.
[6] Konsili Vatikan Kedua, Deklarasi tentang Hubungan Gereja dengan Agama-Agama Bukan Kristiani Nostra Aetate (28 Oktober 1965), no. 1.
[7] Bdk. Dewan Kepausan untuk Budaya; Dewan Kepausan untuk Dialog Antaragama, Yesus Kristus Pembawa Air Hidup: Suatu Refleksi Kristiani tentang “New Age” (Kota Vatikan 2003).
[8] Bdk. Benediktus XVI, Ensiklik Caritas in Veritate (29 Januari 2009), no. 55-56.
[9] Ibid., no. 56.
[10] Ibid.
[11] Yohanes Paulus II, Pidato pada Sidang Pleno Dewan Kepausan untuk Budaya (18 Januari 1983), no. 7.
[12] Benediktus XVI, Pidato kepada para Pemimpin Agama di Notre Dame Centre of Jerusalem (11 Mei 2009).
[13] Bdk. Kongregasi untuk Ajaran Iman, Deklarasi Dominus Iesus, tentang Unitas dan Universalitas Penyelamatan Yesus Kristus dan Gereja (6 Agustus 2000), no. 7. Komisi Teologi internasional menggarisbawahi bagaimana dialog antaragama bersifat “alamiah bagi panggilan Kristiani. Itu tertulis dalam dinamisme tradisi hidup dan misteri keselamatan, yang sakramen universalnya adalah Gereja.” (Christianity and the World Religions, 30 September 1997, no. 114). Sebagai sebuah ungkapan tradisi ini, dialog antaragama bukan prakarsa individu atau pribadi, karena “bukan orang-orang Kristen yang diutus, melainkan Gereja; ini bukan gagasan yang mereka sajikan, melainkan gagasan Kristus; ini tidak akan menjadi retorika mereka yang akan menyentuh hati, melainkan Roh, Parakletus. Agar setia pada ‘citarasa Gereja’, dialog antaragama memohon kerendahan hati Kristus dan kejernihan Roh Kudus” (Idem, no. 116).
[14] Benediktus XVI, Pidato kepada para Pemimpin Agama di Notre Dame Centre of Jerusalem.
[15] Bdk. Konsili Vatikan Kedua, Dekret tentang Ekumenisme Unitatis Redintegratio (24 November 1964), no. 4.
[16] Benediktus XVI, Pidato kepada Korps Diplomatik yang diakreditasi untuk Takhta Suci (7 Januari 2008).
[17] Benediktus XVI, Pidato kepada Wakil-wakil Agama-agama lain (Washington DC, 17 April 2008).
[18] Kongregasi untuk Ajaran Iman, Pernyataan Dominus tentang Unitas dan Universalitas Penyelamatan Yesus Kristus dan Gereja, no. 15.
[19] Kongregasi untuk Pendidikan Katolik, Sekolah Katolik (19 Maret 1977), no. 33.
[20] Yohanes Paulus II, Seruan Apostolik Ecclesia in Africa (14 September 1995), no. 102.
[21] Paus Fransiskus, Pidato kepada Para Siswa Sekolah-Sekolah Yesuit Italia dan Albania (7 Juni 2013).
[22] Yohanes Paulus II, Dialog antara Budaya-budaya demi Peradaban Kasih dan Perdamaian, Pesan untuk hari Perdamaian Sedunia (2001), no. 20.
[23] Yohanes Paulus II, Dialog antara Budaya-budaya demi Peradaban Kasih dan Perdamaian, no. 20.
[24] Dewan Kepausan untuk Dialog Antaragama; Kongregasi untuk Penginjilan Bangsa-Bangsa, Instruction Dialog dan Pewartaan: Refleksi dan Orientasi tentang Dialog Antar-agama dan Pewartaan Injil Yesus Kristus , no. 46.
[25] Paus Fransiskus, Pidato kepada Para Siswa dan Para Pengajar Seibu Gakuen Bunry Junior High School of Saitama, Tokyo (21 Agustus 2013).
[26] Bdk. Dewan Eropa, Buku Putih (White Paper) tentang Dialog Antar-agama “Hidup Bersama yang Setara dalam Martabat”, Strasburg (Mei 2008), p. 5: “pendekatan antarbudaya menawarkan model berwawasan ke depan untuk mengelola keragaman budaya. Pendekatan itu mengajukan suatu konsep berdasarkan martabat manusia pribadi per pribadi (dengan merangkul kemanusiaan kita bersama dan nasib bersama).”
[27] Benediktus XVI. Ensiklik Caritas in Veritate, no. 26.
[28] Ibid.
[29] Ibid.
[30] Konsili Vatikan Kedua, Konstitusi Pastoral tentang Gereja dalam Dunia Modern Gaudium et Spes (7 Desember 1965) no. 53.
[31] Yohanes Paulus II, Pidato kepada UNESCO, Paris (2 Juni 1980), no. 6.
[32] Konsili Vatikan Kedua, Konstitusi Pastoral tentang Gereja dalam Dunia Modern Gaudium et Spes, no. 53.
[33] Ibid.
[34] Yohanes Paulus II, Dialog antara Budaya-budaya demi Peradaban Kasih dan Perdamaian, no. 7 dan 9.
[35] Bdk. Komisi Teologi Internasional, Iman dan Inkulturasi (8 Oktober 1988), Bab. I – Kodrat, Budaya dan Rahmat, no. 7.
[36] Yohanes Paulus II, Dialog antara Budaya-budaya demi Peradaban Kasih dan Perdamaian, no. 10 dan 16.
[37] Kongregasi untuk Pendidikan Katolik, Mendidik Bersama-sama di Sekolah-sekolah Katolik: Sebuah Misi Bersama Antara Orang-orang Hidup Bakti dan Umat Beriman Awam (8 September 2007), no. 8.
[38] Konsili Vatikan Kedua, Konstitusi Pastoral Gaudium et Spes, no. 22.
[39] Konsili Vatikan Kedua, Konstitusi Dogmatik Lumen Gentium (21 November 1964), no. 1.
[40] Yohanes Paulus II, Ensiklik Fides et Ratio (14 September 1998), no. 70.
[41] Bdk. Benediktus XVI, Pidato kepada Sidang Umum Konferensi Waligereja Italia (27 Mei 2010): “fakta penting adalah bahwa pribadi manusia menjadi dirinya sendiri hanya bersama pribadi lain. ‘Aku’ menjadi dirinya sendiri hanya dari ‘kamu’ dan ‘kalian.’ Ini diciptakan untuk dialog, untuk persekutuan sinkronis dan diakronis. Hanya perjumpaan dengan ‘kamu’ dan dengan ‘kalian’, maka ‘aku’ terbuka kepada dirinya sendiri.”
[42] Benediktus XVI, Ensiklik Caritas in Veritate, no. 53.
[43] Ibid., no. 54.
[44] Bdk. Ibid., no. 55.
[45] Konsili Vatikan Kedua, Konstitusi Pastoral Gaudium et Spes, no. 12.
[46] Benediktus XVI, Ensiklik Caritas in Veritate, no. 53.
[47] Yohanes Paulus II, Ensiklik Redemptor Hominis (4 Maret 1979), no. 10.
[48] Benediktus XVI, Ensiklik Deus Caritas Est (25 Desember 2005), no. 6.
[49] Benediktus XVI, Ensiklik Caritas in Veritate, no. 53.
[50] Bdk. Yohanes Paulus II, Surat Apostolik Novo Millennio Ineunte (6 Januari 2001), no. 43.
[51] Bdk. Komisi Teologi Internasional, Dalam Pencarian Etika Universal: Sebuah Pandangan Baru terhadap Hukum Kodrati (2009), no. 51: “ ‘Jangan lakukan kepada orang lain apa yang kamu tidak ingin orang lain lakukan kepadamu.’ Di sini kita menemukan aturan emas, yang saat ini diposisikan sebagai prinsip moralitas ketimbal-balikan.”
[52] Kongregasi untuk Ajaran Iman, Nota Doktrinal tentang Beberapa Aspek Evangelisasi (3 Desember 2007), no. 7.
[53] Bdk. Kongregasi untuk Pendidikan Katolik, Sekolah Katolik di Ambang Milenium Ketiga, no. 3.
[54] Benediktus XVI, Berbahagialah mereka para Pembawa Damai, Pesan untuk Hari Perdamaian Sedunia (2013), no. 4.
[55] Bdk. Kongregasi untuk Pendidikan Katolik, Mendidik Bersama-sama di Sekolah-sekolah Katolik: Sebuah Misi Bersama Antara Orang-orang Hidup Bakti dan Umat Beriman Awam, no. 38.
[56] Bdk. Kongregasi untuk Pendidikan Katolik, Sekolah Katolik, no. 33-37.
[57] Bdk. Kongregasi untuk Pendidikan Katolik, Orang-orang Katolik Awam di Sekolah-sekolah: Para Saksi Iman (15 Oktober 1982), n. 22; Id., Mendidik Bersama-sama di Sekolah-sekolah Katolik: Sebuah Misi Bersama Antara Orang-orang Hidup Bakti dan Umat Beriman Awam, no. 13.
[58] Kongregasi untuk Pendidikan Katolik, Dimensi Religius Pendidikan di Sekolah Katolik (7 April 1988), no. 42.
[59] Paus Fransiskus, Pidato kepada Para Siswa Sekolah-Sekolah Yesuit Italia dan Albania.
[60] Kongregasi untuk Pendidikan Katolik, Sekolah Katolik, no. 34; bdk. Kitab Hukum Kanonik, kan. 803 § 2.
[61] Paus Fransiskus, dengan berpidato di hadapan para Yesuit yang mengelola persekolahan, mendorong mereka “untuk menemukan bentuk-bentuk baru pendidikan non-konvensional yang selaras dengan ‘kebutuhan tempat, zaman, dan orang’” (7 Juni 2013).
[62] Bdk. Benediktus XVI, Memerangi Kemiskinan untuk Membangun Perdamaian, Pesan untuk Hari Perdamaian Sedunia (2009), no. 2.
[63] Bdk. Kongregasi untuk Pendidikan Katolik, Surat Edaran kepada para Ketua Konferensi Waligereja tentang Pendidikan Agama di Sekolah-sekolah (5 Mei 2009).
[64] Konsili Vatikan Kedua, Pernyataan Dignitatis Humanae (7 Desember 1965), no. 5; bdk. KHK, kan. 799; bdk. juga Takhta Suci, Piagam Hak-Hak Keluarga (22 Oktober 1983), art. 5, c-d.
[65] Bdk. Perserikatan Bangsa-Bangsa, DeklarasiUniversal Hak-hak Asasi Manusia (1948), art. 26.
[66] Bdk., mis., Protokol Tambahan no. 1 untuk Konvensi Eropa bagi Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dan Kebebasan-kebebasan Dasar (1952), art. 2; Perserikatan Bangsa-Bangsa, DeklarasiHak-hak Asasi Anak (1959), prinsip 7, 2; UNESCO, Konvensi Menentang Diskriminasi dalam Pendidikan(1960), art. 5, b; Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konvensi tentang Hak-hak Asasi Anak (1989), art. 18, 1.
[67] Benediktus XVI, Pidato Kepada para Pengajar Agama Katolik (25 April 2009).
[68] Bdk. Kongregasi untuk Pendidikan Katolik, Surat Edaran kepada para Ketua Konferensi Waligereja tentang Pendidikan Agama di Sekolah-sekolah, no. 12.
[69] Bdk. Kongregasi untuk Pendidikan Katolik, Mendidik Bersama-sama di Sekolah-sekolah Katolik: Sebuah Misi Bersama Antara Orang-orang Hidup Bakti dan Umat Beriman Awam (8 September 2007), no. 34-37.
[70] Bdk. KHK, kan. 796 § 1.
[71] Bdk. Kongregasi untuk Pendidikan Katolik, Dimensi Religius Pendidikan di Sekolah Katolik, no. 32; Bdk. juga KHK, kan. 799.
[72] Kongregasi untuk Pendidikan Katolik, Sekolah Katolik di Ambang Milenium Ketiga, no. 11.
[73] Kongregasi untuk Pendidikan Katolik, Surat Edaran kepada para Ketua Konferensi Waligereja tentang Pendidikan Agama di Sekolah-sekolah, no. 5.
[74] Ibid., n. 6.
[75] Paus Fransiskus, Pidato kepada Para Siswa Sekolah-sekolah Yesuit Italia dan Albania.