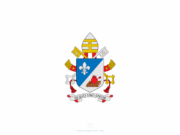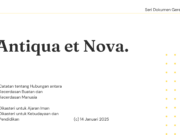PESAN PAUS FRANSISKUS
UNTUK HARI KOMUNIKASI SOSIAL SEDUNIA KE-56
“MENDENGARKAN DENGAN TELINGA HATI“
Saudara dan Saudari terkasih,
Tahun lalu, kita merenungkan perlunya “Datang dan Melihat” untuk memahami kenyataan dan dapat menceritakannya kembali, mulai dengan mengalami peristiwa-peristiwa dan bertemu orang-orang. Sejalan dengan permenungan itu, sekarang saya ingin menarik perhatian pada kata lain: “mendengarkan”, yang menentukan dalam tata bahasa komunikasi dan merupakan sebuah kondisi untuk dialog sejati.
Kenyataannya, kita sedang kehilangan kemampuan mendengarkan orang-orang di sekitar kita, baik dalam hubungan yang biasa sehari-hari maupun ketika memperdebatkan isu-isu terpenting dalam kehidupan masyarakat. Pada saat yang sama, “mendengarkan” mengalami perkembangan baru yang penting di bidang komunikasi dan informasi melalui berbagai podcast dan pesan audio yang meyakinkan kita bahwa “mendengarkan” tetap sangat esensial dalam komunikasi manusia.
Ketika ditanya tentang kebutuhan terbesar manusia, seorang dokter terkemuka, yang biasanya mengobati luka batin, menjawab: “Keinginan tak terbatas untuk didengarkan”. Sebuah keinginan yang kerap tersembunyi, tetapi menantang siapa saja yang terpanggil menjadi pendidik atau formator, atau yang memainkan peran sebagai komunikator: para orangtua dan guru, para imam dan petugas pastoral, para profesional di bidang komunikasi dan mereka yang menyediakan layanan sosial atau politik.
Mendengarkan dengan Telinga Hati
Dari tulisan-tulisan dalam Kitab Suci, kita belajar bahwa mendengarkan tidak hanya berarti menangkap/mendengar suara, tetapi pada dasarnya terhubung dengan relasi dialogis antara Allah dan umat manusia. “Shema’ Israel––Dengarlah, hai Israel” (Ul.6: 4), kata-kata pembuka dari perintah pertama Taurat, terus-menerus ditegaskan kembali dalam Kitab Suci, bahkan Santo Paulus dengan tegas mengatakan: “iman timbul dari pendengaran” (lih. Rom.10: 17). Tuhanlah yang berinisiatif, Ia berbicara kepada kita, dan kita menjawab dengan mendengarkan-Nya. Pada akhirnya, pendengaran ini pun berasal dari rahmat-Nya, sama seperti anak baru lahir yang menanggapi tatapan dan suara ibu dan ayahnya. Di antara pancaindra, tampaknya Tuhan mengistimewakan pendengaran, mungkin karena kurang invasif (bersifat menyerang), lebih bijaksana dari penglihatan, dan karena itu membuat manusia lebih bebas.
Mendengarkan sesuai dengan gaya Tuhan yang rendah hati. Mendengarkan menjadi tindakan yang memungkinkan Tuhan mewahyukan diri-Nya sebagai Dia, yang dengan berbicara, menciptakan pria dan wanita menurut gambar-Nya, dan dengan mendengarkan mengakui mereka sebagai mitra dalam dialog. Tuhan mencintai umat manusia: karena itu Dia menyampaikan firman-Nya, dan “mencondongkan telinga-Nya” untuk mendengarkan mereka.
Sebaliknya, manusia cenderung lari dari relasi, berpaling dan “menutup telinga” sehingga tidak perlu mendengar. Penolakan untuk mendengarkan sering berakhir dengan serangan terhadap yang lain, seperti terjadi pada para pendengar Diakon Stefanus yang “sambil menutup telinga serentak menyerbu dia” (lih. Kis.7: 57).
Selanjutnya, di satu sisi, Tuhan selalu mengungkapkan diri-Nya dengan berkomunikasi secara bebas; sementara di sisi lain, manusia diminta menyesuaikan diri untuk bersedia mendengarkan. Secara eksplisit, Tuhan memanggil pribadi manusia ke dalam perjanjian cinta, sehingga secara penuh dapat menjadi seperti yang seharusnya: sebagai gambar dan rupa Allah dalam kapasitasnya untuk mendengarkan, menyambut, dan memberi ruang kepada orang lain. Pada dasarnya, mendengarkan adalah sebuah dimensi cinta.
Oleh karena itu, Yesus mengajak para murid mengevaluasi kualitas pendengaran mereka. “Perhatikanlah cara kamu mendengar” (Luk. 8: 18): Inilah permintaan Yesus setelah memaparkan perumpamaan tentang penabur. Sebuah desakan untuk memahami bahwa tidakcukuplah hanya mendengar, perlu untuk mendengarkan dengan baik. Hanya mereka yang menerima Sabda Tuhan dengan hati yang “jujur dan baik” dan memelihara-Nya dengan tekun yang akan menghasilkan buah kehidupan dan keselamatan (lih. Luk. 8: 15). Hanya dengan memperhatikan siapa yang kita dengarkan, apa yang kita dengarkan, dan bagaimana kita mendengarkan, kita dapat tumbuh dalam seni berkomunikasi, yang intinya bukanlah teori atau teknik, tetapi “keterbukaan hati yang memungkinkan kedekatan” (lih. Seruan Apostolik Evangelii Gaudium art. 171).
Kita semua bertelinga, tetapi sering mereka yang memiliki pendengaran sempurna tidak dapat mendengarkan orang lain. Dalam kenyataan, ada orang yang tuli secara batiniah; keadaan ini lebih buruk dari tuli secara fisik. Mendengarkan sesungguhnya, bukan hanya berhubungan dengan indera pendengaran, tetapi keseluruhan manusia. Dan, hati menjadi tempat mendengarkan yang sebenarnya. Raja Salomo, meski masih sangat muda, membuktikan dirinya bijaksana karena meminta Tuhan memberinya “hati yang mendengarkan” (lih. 1Raj. 3: 9).
Santo Agustinus selalu mendorong orang untuk mendengarkan dengan hati (corde audire: hati mendengarkan), untuk menerima kata-kata tidak hanya secara lahiriah melalui telinga, tetapi secara rohani dalam hati kita: “Jangan menaruh hatimu di telinga, tetapi taruhlah telinga di dalam hatimu”.[1] Santo Fransiskus dari Assisi menasihati saudara-saudaranya untuk “mencondongkan telinga hati”.[2]
Oleh karena itu, mendengarkan diri sendiri menjadi cara mendengarkan yang pertama-tama harus ditemukan, pada saat orang mencari komunikasi sejati. Inilah kebutuhan terdalam, yang tertanam dalam diri setiap orang. Dan kita hanya bisa mulai dengan mendengarkan apa yang membuat kita unik dalam ciptaan: keinginan untuk berhubungan dengan orang lain dan dengan Yang Lain (Yang Ilahi). Kita tidak diciptakan untuk hidup seperti atom-atom, tetapi bersama-sama.
Mendengarkan sebagai Syarat Komunikasi yang Baik
Ada jenis pendengaran yang tidak benar-benar mendengarkan, tetapi malah kebalikannya: menguping. Dalam kenyataan, menguping dan memata-matai, yang mengeksploitasi orang lain untuk kepentingan kita sendiri, menjadi godaan yang selalu ada dan tampaknya menjadi lebih akut di era jejaring sosial sekarang ini. Sebaliknya, mendengarkan orang yang di ada depan kita, bertatap muka, dan mendengarkan orang lain yang kita dekati dengan keterbukaan tulus, percaya diri, dan jujur merupakan hal yang secara khusus membuat komunikasi menjadi baik dan sepenuhnya manusiawi.
Sangat disayangkan, kurang mendengarkan, yang banyak kali dialami dalam hidup sehari-hari, juga tampak dalam kehidupan publik, di mana bukannya saling mendengarkan satu sama lain, kita malahan kerap “saling membicarakan masa lalu satu sama lain”.
Ini merupakan gejala atas fakta, bahwa kita lebih mencari konsensus daripada menemukan yang benar dan yang baik; kita lebih senang memperhatikan audiens daripada mendengarkan. Padahal, komunikasi yang baik tidak berusaha membuat publik terkesan dengan lelucon suara, dengan tujuan mengejek lawan bicara, tetapi memperhatikan alasan orang lain dan mencoba memahami kompleksnya realitas. Sungguh menyedihkan, kalau juga dalam Gereja, keberpihakan ideologis dibentuk, mendengarkan dihilangkan, dan oposisi yang murni ditinggalkan di belakang.
Kenyataannya, kita sama sekali tidak berkomunikasi dalam banyak dialog. Kita hanya menunggu orang lain selesai bicara untuk memaksakan sudut pandang kita. Dalam situasi ini, seperti dicatat filsuf Abraham Kaplan,[3] dialog adalah duolog—sebuah monolog dalam dua suara. Padahal, dalam komunikasi sejati, “sang aku” dan “sang engkau” seharusnya sama-sama “bergerak keluar”, saling menjangkau satu sama lain.
Oleh karena itu, mendengarkan adalah unsur pertama yang sangat diperlukan dalam dialog dan komunikasi yang baik. Komunikasi tidak akan terjadi jika tidak terlebih dahulu mendengarkan, dan tidak ada jurnalisme yang baik tanpa kemampuan mendengarkan. Perlu mendengarkan dalam waktu lama, untuk dapat memberikan informasi yang padat, seimbang, dan lengkap. Demikian pula untuk dapat menceritakan suatu peristiwa atau menggambarkan sebuah realitas dalam pelaporan berita, sungguh pentinglah mengetahui cara mendengarkan, siap berubah pikiran, dan mengubah asumsi awal.
Hanya dengan keluar dari monolog, keselarasan suara yang menjadi jaminan komunikasi sejati dapat tercapai. Mendengarkan beberapa sumber: “tidak berhenti di kedai pertama”—seperti yang diajarkan oleh para ahli di lapangan—memastikan keandalan dan keseriusan informasi yang kita kirimkan. Mendengarkan beberapa suara, mendengarkan satu sama lain, bahkan di Gereja, di antara saudara dan saudari, memungkinkan kita melatih seni berdiskresi, yang selalu muncul sebagai kemampuan untuk mengarahkan diri kita pada sebuah simfoni suara.
Akan tetapi, mengapa kita harus berjuang untuk mendengarkan? Seorang diplomat besar Takhta Suci, Kardinal Agostino Casaroli, biasa bicara tentang “kemartiran atas kesabaran” yang diperlukan untuk mendengarkan dan didengarkan dalam negosiasi dengan pihak-pihak yang paling sulit, demi mendapatkan kebaikan terbesar dalam kondisi kebebasan yang terbatas.
Namun, juga dalam situasi yang tidak terlalu sulit, mendengarkan selalu butuh keutamaan kesabaran, bersama dengan kemampuan untuk membiarkan diri sendiri dikejutkan oleh kebenaran, bahkan jika hanya sebagian dari kebenaran pada orang yang sedang kita dengarkan. Hanya keheranan/kekaguman memungkinkan pengetahuan. Saya memikirkan rasa ingin tahu tak terbatas dari anak yang melihat dunia di sekitarnya dengan mata terbuka lebar. Mendengarkan dengan kerangka berpikir ini – kekaguman anak dalam kesadaran orang dewasa – selalu memperkaya karena akan selalu ada sesuatu, betapapun kecilnya, yang dapat saya pelajari dari orang lain dan berguna dalam hidup saya.
Kemampuan mendengarkan masyarakat sungguh semakin berharga pada saat ini ketika kita dilukai oleh pandemi yang panjang. Sebelumnya, begitu banyak akumulasi ketidakpercayaan atas “informasi resmi”, yang juga telah menyebabkan “infodemik”, di mana dunia informasi harus berjuang lebih keras untuk menjadi semakin kredibel dan transparan. Kita perlu mendengarkan secara penuh dan mendalam, terutama kegelisahan sosial yang diperparah oleh penurunan atau penghentian banyak kegiatan ekonomi.
Realitas migrasi paksa juga merupakan masalah yang kompleks, dan tak seorang pun memiliki resep siap pakai untuk menyelesaikannya. Saya ulangi, untuk mengatasi pelbagai prasangka atas para migran dan untuk mencairkan kekerasan hati, kita seharusnya coba mendengarkan cerita mereka. Berilah mereka masing-masing sebuah nama dan suatu cerita. Banyak jurnalis yang baik sudah melakukan ini. Dan, banyak jurnalis lain ingin melakukannya, jika saja mereka dapat.
Mari kita dorong mereka! Mari kita dengarkan cerita-cerita ini! Kemudian setiap orang akan bebas mendukung kebijakan migrasi yang mereka anggap paling tepat untuk negara mereka sendiri. Akan tetapi saat ini, bagaimanapun juga, di depan mata kita bukan angka, bukanlah para penjajah berbahaya, tetapi wajah dan cerita, tatapan, harapan, dan penderitaan pria dan wanita nyata yang harus didengarkan.
Mendengarkan Satu Sama Lain di Dalam Gereja
Di dalam Gereja juga, ada kebutuhan besar untuk mendengarkan dan saling mendengarkan satu sama lain. Inilah hadiah paling berharga dan menghidupkan yang dapat kita tawarkan satu sama lain. “Orang-orang Kristen telah lupa bahwa pelayanan mendengarkan telah dipercayakan kepada mereka oleh Dia yang adalah pendengar yang baik dan yang pekerjaannya harus mereka bagikan. Kita harus mendengarkan dengan telinga Tuhan agar kita dapat mengucapkan firman Tuhan”,[4] Demikian, teolog Protestan, Dietrich Bonhoeffer mengingatkan kita bahwa pelayanan pertama yang kita berikan kepada orang lain dalam persekutuan yaitu: mendengarkan mereka. Siapa tidak tahu mendengarkan saudara laki-laki atau perempuannya akan segera tidak mampu mendengarkan Tuhan.[5]
Tugas paling penting dalam kegiatan pastoral adalah “kerasulan telinga”—mendengarkan sebelum berbicara, seperti nasihat Rasul Yakobus: “Biarlah setiap orang cepat mendengar, lambat berbicara” (1: 19). Memberi sedikit waktu kita secara bebas untuk mendengarkan orang lain adalah tindakan pertama dari amal kasih.
Proses sinode baru saja diluncurkan. Mari kita berdoa agar menjadi kesempatan besar untuk saling mendengarkan. Persekutuan sebenarnya bukanlah hasil pelbagai strategi dan aneka program, tetapi dibangun dalam sikap saling mendengarkan antara saudara dan saudari. Sama seperti dalam paduan suara, kesatuan tidak menuntut keseragaman, kemonotonan, tetapi kemajemukan dan keragaman suara, polifonia. Pada saat yang sama, setiap suara dalam paduan suara bernyanyi sambil mendengarkan suara-suara lain dan dalam hubungannya dengan harmoni keseluruhan. Harmoni ini dirancang oleh komposer, tetapi realisasinya tergantung pada simfoni masing-masing dan setiap suara.
Dalam kesadaran bahwa kita berpartisipasi dalam persekutuan, yang sudah ada sebelumnya dan kitapun termasuk di dalamnya, kita dapat menemukan kembali Gereja yang simfonis, di mana setiap orang dapat bernyanyi dengan suaranya sendiri, sambil menyambut suara orang lain sebagai hadiah untuk mewujudkan harmoni keseluruhan yang disusun oleh Roh Kudus.
Roma, di Basilika Santo Yohanes Lateran, 24 Januari 2022, pada Peringatan Santo Fransiskus de Sales.
Fransiskus
____________________________________________
[1] “Nolite habere cor in auribus, sed aures in corde” (Sermo 380, 1: Nuova Biblioteca Agostiniana 34, hlm. 568).
[2] “Lettera a Tutto l’Ordine”: Fonti Francescane, hlm. 216.
[3] Lih. “Kehidupan Dialog”, dalam J.D. Roslansky (Ed.), Komunikasi. Sebuah Diskusi di Konferensi Nobel, Perusahaan Penerbitan Belanda Utara, Amsterdam, 1969, hlm. 89-198.
[4] D. Bonhoeffer, La Vita Comune, Queriniana, Brescia 2017, hlm. 76.