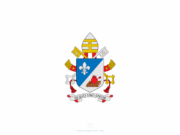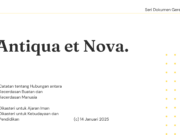Jakarta, dokpenkwi.org, Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan hukuman kebiri sebagai hukuman pemberatan bagi para pelaku kejahatan seksual dan telah menimbulkan kontroversi pada banyak kalangan kini telah bergulir ke DPR untuk menunggu pengesahannya. Mengapa hukuman kebiri yang kontroversial itu oleh Pemerintah tetap dimajukan untuk disahkan sebagai undang-undang? Hukuman kebiri dianggap tidak menyelesaikan masalah kejahatan seksual karena pokok permasalahan yang disasar tidak mencapai akarnya.
Dalam seminar yang diselenggarakan bersama oleh KKP-PMP, Komisi Keluarga dan SGPP KWI (20/6/2016), para narasumber yang diundang tampaknya juga sepakat untuk tidak menyetujui hukuman kebiri sebagai pemberatan. Mereka lebih setuju kalau hukuman kebiri dilaksanakan sebagai sarana untuk terapi atau rehabilitasi sebagaimana juga disebutkan dalam Perppu tersebut (pasal 82 (6)). (baca juga: Hukuman Kebiri, Saatnya Gereja Bicara).
 Menurut Rm. Kusmaryanto, dosen bioetika di Fakultas Kedokteran UGM dan anggota Komisi Nasional Etik Penelitian Kesehatan (KNEPK), pokok permasalahan bagi pelaku kejahatan seksual bukan terletak di dalam tubuhnya , melainkan pada ketidakmampuannya mengendalikan diri dalam menghadapi rangsangan seksual. Selain itu karena adanya alasan mendasar yang dikutipnya dari Paus Pius XII bahwa berdasarkan alasan natural dan moral Kristiani, manusia mempunyai hak dan kewajiban untuk mempertahankan hidup dan kesehatannya. “Dari sudut pandang ini, jelaslah bahwa bahwa kebiri kimiawi adalah upaya untuk menjadikan tubuh manusia tidak sehat, tidak berfungsi sebagaimana seharusnya. Apalagi ada indikasi medis yang kuat bahwa kebiri kimiawi akan menimbulkan banyak efek samping, yang berbahaya bagi tubuh (kesehatan) dan kinerja tubuh,” tegasnya.
Menurut Rm. Kusmaryanto, dosen bioetika di Fakultas Kedokteran UGM dan anggota Komisi Nasional Etik Penelitian Kesehatan (KNEPK), pokok permasalahan bagi pelaku kejahatan seksual bukan terletak di dalam tubuhnya , melainkan pada ketidakmampuannya mengendalikan diri dalam menghadapi rangsangan seksual. Selain itu karena adanya alasan mendasar yang dikutipnya dari Paus Pius XII bahwa berdasarkan alasan natural dan moral Kristiani, manusia mempunyai hak dan kewajiban untuk mempertahankan hidup dan kesehatannya. “Dari sudut pandang ini, jelaslah bahwa bahwa kebiri kimiawi adalah upaya untuk menjadikan tubuh manusia tidak sehat, tidak berfungsi sebagaimana seharusnya. Apalagi ada indikasi medis yang kuat bahwa kebiri kimiawi akan menimbulkan banyak efek samping, yang berbahaya bagi tubuh (kesehatan) dan kinerja tubuh,” tegasnya.
 Dr. E. Kristi Poerwandari juga mengamini apa yang disampaikan Rm. Kus. Selain itu, dia kurang menyetujui terminologi hukuman kebiri sebagai pemberatan karena menurutnya kalau kebiri dijadikan hukuman, hal ini justru akan menimbulkan kekerasan yang lain. Ibu Kristi, doktor filsafat UI sekaligus dosen psikologi yang kerap terlibat aktif dalam pendampingan terhadap para perempuan yang mengalami berbagai masalah, menegaskan bahwa walaupun dalam kasus-kasus tertentu kastrasi kimiawi diperlukan, tapi tetap perlu dikritisi dan dipertajam lagi tujuannya apakah sebagai hukuman pemberatan atau bentuk rehabilitasi.
Dr. E. Kristi Poerwandari juga mengamini apa yang disampaikan Rm. Kus. Selain itu, dia kurang menyetujui terminologi hukuman kebiri sebagai pemberatan karena menurutnya kalau kebiri dijadikan hukuman, hal ini justru akan menimbulkan kekerasan yang lain. Ibu Kristi, doktor filsafat UI sekaligus dosen psikologi yang kerap terlibat aktif dalam pendampingan terhadap para perempuan yang mengalami berbagai masalah, menegaskan bahwa walaupun dalam kasus-kasus tertentu kastrasi kimiawi diperlukan, tapi tetap perlu dikritisi dan dipertajam lagi tujuannya apakah sebagai hukuman pemberatan atau bentuk rehabilitasi.
Ibu Kristi menyatakan bahwa “dalam banyak kasus, sumber persoalannya adalah pada pola pikir dan praktik atau pembiasaan yang hanya memperlakukan perempuan dan anak sebagai objek sehingga hal ini bisa memicu terjadinya kekerasan seksual.” Tambahnya pula, “ kekerasan seksual tak jarang merupakan manifestasi dominasi atau perendahan, dan bukan sekedar ketidakmampuan mengendalikan gairah seksual.” Oleh sebab itu, perlu ditanamkan sejak dini pentingnya penghormatan pada perempuan/manusia lain, penanaman tanggung jawab dan sikap menghormati diri sendiri, serta pendidikan seksualitas pada anak-anak.
 Sementara itu, dr. Robert G. Sentana dari Majelis Kehormatan dan Etik Kedokteran IDI menyatakan bahwa IDI secara jelas menyatakan mendukung kebijakan pemerintah (eksekutif), legislatif, dan yudikatif untuk memberikan hukuman maksimal kepada pelaku kekerasan seksual pada anak untuk mengatasi maraknya kekerasan seksual terhadap anak yang sungguh mengancam dan membahayakan anak. Sebab, kekerasan seksual pada anak merupakan kejahatan luar biasa. Menurut dr. Sentana, IDI bahkan mendorong agar para dokter terlibat dalam upaya rehabilitasi terhadap korban dan pelaku. Hal itu harus menjadi prioritas untuk mencegah dampak buruk trauma fisik dan psikis yang dialami. Rehabilitasi terhadap pelaku dibutuhkan agar kejadian serupa tidak terulang lagi.
Sementara itu, dr. Robert G. Sentana dari Majelis Kehormatan dan Etik Kedokteran IDI menyatakan bahwa IDI secara jelas menyatakan mendukung kebijakan pemerintah (eksekutif), legislatif, dan yudikatif untuk memberikan hukuman maksimal kepada pelaku kekerasan seksual pada anak untuk mengatasi maraknya kekerasan seksual terhadap anak yang sungguh mengancam dan membahayakan anak. Sebab, kekerasan seksual pada anak merupakan kejahatan luar biasa. Menurut dr. Sentana, IDI bahkan mendorong agar para dokter terlibat dalam upaya rehabilitasi terhadap korban dan pelaku. Hal itu harus menjadi prioritas untuk mencegah dampak buruk trauma fisik dan psikis yang dialami. Rehabilitasi terhadap pelaku dibutuhkan agar kejadian serupa tidak terulang lagi.
Namun dalam kaitannya dengan hukuman kebiri, IDI berkeberatan untuk dijadikan sebagai eksekutor hukuman tersebut karena bertentangan dengan sumpah dokter dan kode etik kedokteran. “Dalam kode etik kedokteran, tugas seorang dokter itu menyembuhkan pasien, bukan melakukan penghukuman yang membuat pasien menderita. Tindakan kebiri itu bertentangan dengan kode etik kedokteran,” kata dr. Sentana. Oleh karena itu, IDI membuat fatwa yang salah satunya berbunyi “…agar profesi dokter tidak dilibatkan secara langsung sebagai eksekutor dalam pemberatan hukuman berupa kebiri kimia.”
Dalam penjelasannya, disebutkan bahwa resiko penyuntikan kebiri kimiawi bisa mengakibatkan: kadar testosteron rendah, meningkatnya resiko dm tipe 2, timbulnya gangguan kardiovaskular, otot mengecil, osteroporosis, anemia, fungsi kognitif terganggu dan payudara membesar.
 Sementara itu, Susanto MA dari KPAI menyampaikan bahwa kebiri hanya dilakukan untuk pelaku kejahatan seksual yang libidonya tinggi sehingga perlu dinormalkan. “Semangat kebiri untuk melindungi HAM orang lain. Menghilangkan hasrat seks adalah pelanggaran tetapi kalau menormalkan adalah untuk melindungi HAM orang lain,” demikian penjelasannya.
Sementara itu, Susanto MA dari KPAI menyampaikan bahwa kebiri hanya dilakukan untuk pelaku kejahatan seksual yang libidonya tinggi sehingga perlu dinormalkan. “Semangat kebiri untuk melindungi HAM orang lain. Menghilangkan hasrat seks adalah pelanggaran tetapi kalau menormalkan adalah untuk melindungi HAM orang lain,” demikian penjelasannya.
Selanjutnya, Susanto menyoroti pentingnya pendidikan seksualitas sebagai pintu masuk menuju perubahan perilaku dalam masyarakat. “Tetapi itu bukan satu-satunya. Seringkali yang terjadi adalah pada level pengetahuan kita tahu, tetapi itu tidak menyentuh perilaku, misalnya: pada kasus rokok,” demikian tandasnya. Maka, dalam hal ini perspektif hukum tetap diperlukan untuk memaksimalkan perubahan perilaku, terutama pada pelaku kejahatan seksual.
(Harini B/Dokpen KWI)
Kredit Foto: (Y. Indra/Dokpen KWI)