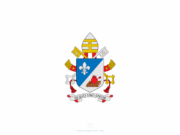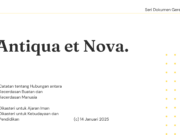TAK pernah terbayangkan sebelumnya bahwa sekali waktu dalam hidupnya, dr. Hugo dan istrinya Merlinda akan hidup di sebuah desa terpencil di tengah pedalaman dimana di situ hanya ada dua keluarga katolik di tengah masyarakat mayoritas muslim. Meski pengalaman hidup di tengah masyarakat non katolik ini terjadi 26 tahun lalu saat dirinya masih menjalani tahun pertama sebagai dokter PTT, namun pengalaman ini masih membekas kuat di hati dan pikirannya. (Baca: Cerita Hebat Keluarga Katolik di SAGKI 2015: Miskin Harta, Sumbang Tiga Anak Jadi Pastor (2)
Bukannya pengalaman jelek, melainkan justru pengalaman-pengalaman kehidupan riil yang justru membuat dirinya semakin diyakinkan, hidup ini mesti ditata agar menjadi rahmat dan berkat bagi orang lain.
Di situ, kata dr. Hugo saat melakukan sharing tentang keluarga katolik di forum SAGKI 2015 hari kedua tanggal 3 November 2015, yang ada hanya kemiskinan dan kemiskinan. Sebagai dokter PTT di pedalaman dengan tingkat penghasilan yang serba terbatas, ia sering kali terbawa oleh perasaan berbelarasa ketika mendapati banyak pasiennya tidak mampu membayar jasa medik berikut obatnya.
Tertular kemiskinan
Dengan kiasan, dr. Hugo sengaja menyebut pengalamannya melayani pasien-pasien miskin ini sebagai faktor yang telah “menjadikan dia ikut miskin”. Yang mau dia katakan sebenarnya adalah perbuatan-perbuatan baik, ketika dia dan istrinya berkomitmen mau menyediakan diri gratis dalam pelayanan medik dan –kalau perlu—“Kami juga terbuka untuk membelikan obat bagi pasien-pasien tak mampu ini,” ungkap dr. Hugo.
Selama lima tahun bekerja sebagai dokter, tambahnya, ia hanya mampu membeli sepeda motor bekas dengan harga Rp 400 ribu kala itu. “Namun, istri saya tak marah dengan kemampuan finansial kami,” ungkapnya.
Ditanyai Romo Edy Purwanto dari KWI yang bertindak sebagai moderator dalam sharing hebat keluarga katolik ini, dr. Hugo menjawab tangkas. “Kalau bukan kita, lalu siapa lagi yang harus menolong mereka yang dililit kemiskinan riil?.”
Di desa terpencil di sebuah pedalaman jauh di Kalimantan Selatan ini, hanya ada dua sarjana di situ. “Saya salah satunya dan lainnya adalah Pak Camat yang lulus sarjana muda. Selebihnya, hanya lulusan SD dan ketika umur 13-14 tahun, mereka lalu menikah,” terangnya mengenang kisah hidupnya 26 tahun lalu.
Tulus dan tanpa pamrih
Meski sering tidak mendapat bayaran atas jasa medik pelayanan kesehatan, tambahnya, “Saya tetap tulus melayani mereka tanpa pamrih.”
Atas pengabdian hidupnya ini, pada tahun 1992, dr. Hugo diganjar sebagai dokter teladan dan mendapat piagam serta hadiah naik haji. Karena dia katolik, hadiah ini tak bisa dia lakoni.
Saat menjalani kehidupan di pedesaan terpencil itu, dr. Hugo dan istirnya Merlinda hanya bisa menempati rumah kecil tanpa fasilitas listrik dengan ketersediaan air. Itu pun lokasinya di tengah pedalaman. Karena itu, setiap kali ada panggilan untuk layanan kesehatan, maka istrinya pun ikut menemani dia kemana pun dia sebagai dokter mesti menjalani pelayanan medik. “Sampai-sampai istri saya pun dikira dokter,” katanya.
Kalau pelayanan medik itu terjadi tepi gunung, maka istrinya pun ikut naik ojek, jalan mendaki bukit dan tak jarang harus menginap di lokasi.
Sakit berat dan nyaris mati
Sekali waktu dalam hidupnya, baik dr. Hugo dan istrinya Merlinda mengalami pengalaman sakit sangat serius. “Saya kena pendarahan otak dan istri saya mengidap kanker. Namun, berkat kasih Tuhan, hingga kini kami masih dikaruniai hidup panjang,” terang dr. Hugo.
Merasa bahwa Tuhan telah memberi anugerah hidup sehat dan lebih lama daripada yang semestinya ‘harus terjadi’ karena kena pendarahan otak dan kanker, baik dr. Hugo dan Merlinda semakin giat melakukan pelayanan penuh kasih dan tanpa pamrih.

Hal ini dipertegas sendiri oleh Merlinda.
Ia besar dan bekerja di Surabaya hingga sekali waktu akhirnya menikah dengan dr. Hugo; harus meninggalkan karir dan hidupnya yang mapan di Ibukota Jawa Timur ini. Ketika ditanyai Romo Edy Purwanto perihal motivasinya melayani orang miskin, Merlinda mengatakan secara tegas, “Sudah menjadi komitmen kami sejak meninggalkan Surabaya dan kemudian pindah ke Banjarmasin, hidup di pedalaman Provinsi Kalsel, untuk selalu siap sedia menolong orang lain.”
“Menolong orang, itu jangan pernah melihat materi. Kalau apa yang kita kerjakan untuk orang lain itu membuat kita menjadi lebih bahagia, maka itulah berkah dan rahmat yang kita terima walau kadang-kadang Hugo –suami saya—mesti menghabiskan separuh lebih dari gajinya sebagai dokter PNS,” terangnya.
Pengalaman berkah bagi orang lain
Hidup selama 10 tahun terakhir di Martapura di Kalsel, bagi pasangan dr. Hugo, Merlinda dan kedua anaknya, sungguh menjadi pengalaman penuh berkah. Ketika hanya ada satu-dua-tiga keluarga katolik di Martapura di tengah mayoritas masyarakat muslim, maka kehadiran mereka yang menjadi rahmat bagi masyarakat tiada lain adalah “Sukacita Injil”.
“Kami bersyukur bisa sepenuh hati melayani orang tidak berpunya dan menjadi berkah kami semua ketika kami juga dipercaya banyak orang di Martapura yang menitipkan anak dan rumahnya berbulan-bulan saat mereka bepergian ke luar negeri,” terang dr. Hugo.

Apakah masih hidup dalam kemiskinan? Demikian tanya Romo Edy Purwanto.
“Tidak juga. Kalau dulu kami hanya punya motor eglek-eglek, maka kami sekarang sudah punya rumah batu dan kendaraan,” jawab dr. Hugo.
Menerima kasih dari anonim
Seperti bunyi pepatah yang mengatakan, harimau meninggalkan jejak ,maka jejak-jejak kebaikan yang dirintis oleh dr. Hugo melayani banyak orang kini juga berbuah manis. Tak jarang, kata dia, di rumahnya tiba-tiba tergantung tas-tas plastik berisi buah-buahan atau sayuran tanpa tahu siapa yang memberinya.
Sekali waktu, kata dia, keluarganya mendapat kiriman daging sebanyak lima kilo. Pembantu rumahnya mengatakan, itu pemberian kiriman dari Pak Petrus. “Namun, ketika kami bertemu Pak Petrus, dia katakan kiriman itu bukan datang darinya. Barulah kami sadar bahwa Petrus itu banyak kali,” terang dia.
Jangan lagi ada orang tersakiti
Pasangan dr. Hugo dan Merlinda dikaruniai dua orang anak, satu laki-laki dan lainnya perempuan. Keduanya jago karate dan pernah mendapat hadiah juara pertama dan kedua dalam sebuah pertandingan karate.
Sekali waktu, terang dr. Hugo, usai sebuah kompetisi karate dimana mereka mendapat juara pertama dan kedua, kedua anaknya itu berlama-lama tinggal di kamar dan tidak mau keluar rumah. Saat akhirnya kedua anaknya keluar kamar, mereka lalu mengatakan bahwa mereka tidak mau belajar beladiri karate lagi.
Alasan mereka sederhana, beralasan, tapi sangat mengagetkan: “Jangan sampai ada orang lain kami sakiti lagi karena tendangan dan pukulan karate kami,” begitu alasan mereka hingga melepaskan sabuk kejuaraan beladiri.
Kredit foto: Romo FX Adisusanto SJ/Dokpen KWI